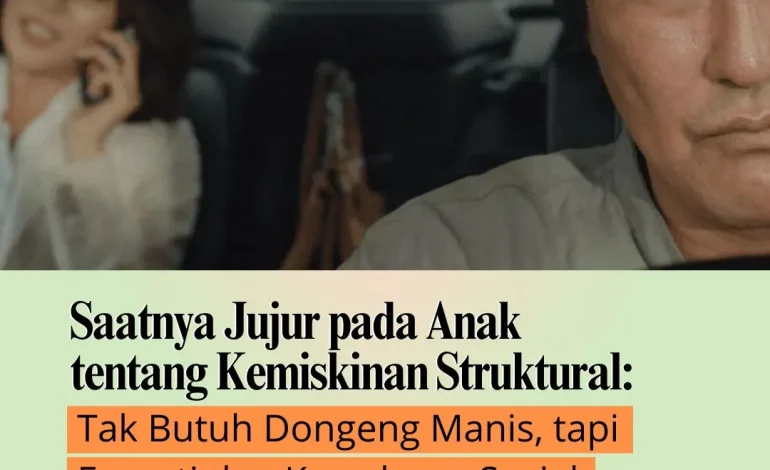‘A Poet’: Kemalangan Lulusan Humaniora yang (Sayangnya) Lucu

Ada sesuatu yang menggelikan dalam kesedihan hidup Oscar Restrepo (Ubeimar Rios), tokoh utama A Poet, arahan Simón Mesa Soto. Film ini memotret kehidupan seorang penyair paruh baya yang dulu sempat merasakan kejayaan kecil, tapi kini terdampar dalam kemiskinan dan keterasingan.
A Poet adalah sebuah dongeng pahit tentang bagaimana jurusan humaniora—spesifiknya sastra—sebagaimana agung karya yang pernah dihasilkan, sayangnya tidak mampu menyejahterakan pembuatnya; dilema yang terlalu dekat dihadapi pencari kerja dari jurusan itu hari ini.
Mesa Soto yang sebelumnya memenangkan Short Film Palme d’Or untuk Leidi (2014) dan mendapat penghargaan di Critics’ Week lewat Amparo, membawa A Poet premiere di Cannes 2025 dalam program Un Certain Regard—bagian kompetisi yang menyoroti karya dengan perspektif unik dan gaya penceritaan tak konvensional.
Dari sana, film ini merengkuh momentum besar dan melangkah ke panggung dunia sebagai submisi Kolombia untuk kategori Best International Feature Film di Oscar 2026.
Tidak sulit memahami mengapa film ini mendapat sambutan luas. Dalam 110 menit yang absurd, lucu, dan lembut di beberapa bagian, A Poet mengupas ironi tentang bagaimana dunia memuja seni dan kata-kata, tapi gagal memberi ruang hidup yang layak bagi para pembuatnya.
Baca juga: ‘It Was Just An Accident’: Saat Penyintas Tahanan Politik Tergoda Jadi Algojo
Kelas Menengah yang Disingkirkan Pasar
Oscar, si penyair gagal dari Medellín, hidup bersama ibunya yang sudah lanjut usia (Margarita Soto), bergantung pada uang saku dan mobil sang ibu untuk bertahan sehari-hari. Ia pernah menerbitkan dua buku puisi di usia 20-an. Buku-buku itu kini lusuh, seperti hidupnya. Ketika tak sedang mengajar sambilan di sekolah menengah, Oscar hobi mabuk sambil berdebat dengan teman-teman lamanya soal siapa penyair Kolombia terbaik. Ia masih memuja potret José Asunción Silva yang ia gantung di atas meja kamarnya, seolah bercermin pada versi dirinya yang lebih terhormat, kendati Silva menembak dirinya sendiri di usia 30, sementara Oscar hanya menembaki dunia dengan keluh kesah tak berkesudahan.
Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah bagaimana Mesa Soto mampu membuat kita menertawakan kemiskinan Oscar tanpa serta-merta meniadakan kepedihan di baliknya. Kita tergelak saat Oscar muncul mabuk di acara pembacaan puisi dan berorasi tentang “kebodohan mencoba hidup dari seni”.
Namun, di balik “kekonyolan” yang ditampilkan, film ini menyuguhkan luka eksistensial dari seseorang yang masih percaya bahwa hidup seharusnya punya ruang bagi idealisme, padahal dunia terus-menerus menolaknya.
Oscar bukan sosok pemalas atau pecundang. Ia adalah cermin dari banyak intelektual kelas menengah bawah yang tersingkir oleh logika pasar.
Cerita bergerak ke arah baru ketika Oscar bertemu Yurlady (Rebeca Andrade), murid SMA yang tulisan iseng-isengnya diam-diam memukau. Ia datang dari keluarga miskin di pinggiran Medellín, tinggal di rumah sempit yang penuh sesak dengan adik-adik, keponakan, nenek, dan ibunya yang bekerja serabutan. Yurlady menulis karena bosan, bukan karena ingin jadi penyair. Tapi Oscar melihat diri mudanya dalam gadis itu. Ia pun mencoba menjadikannya murid, atau lebih tepatnya, proyek ego untuk menebus kegagalannya.
Dalam beberapa adegan, hubungan mereka terasa tulus dan lucu. Oscar dengan sungguh-sungguh mengajarkan bagaimana cara menginjeksikan emosi saat membaca puisi, sementara Yurlady lebih sibuk meniup kuteks di kukunya.
Namun, kegetiran muncul di di situasi ketika Oscar memperkenalkan Yurlady ke lingkaran orang-orang sastra: sebuah dunia yang ternyata tak kalah kejam dari kemiskinan itu sendiri.
Salah satu adegan paling menohok adalah ketika para kurator dan donatur lembaga sastra mencoba “mengemas” Yurlady sebagai wajah baru puisi Kolombia, lengkap dengan narasi “anak miskin berkulit gelap yang diselamatkan oleh seni”. Mereka meminta Yurlady menulis tentang kemiskinan dan kekerasan di lingkungannya, sesuatu yang tidak pernah ingin ia tulis sebelumnya. Ia hanya ingin menulis apa yang ia rasakan sebagai remaja putri, bukan apa yang dunia ekspektasikan dari tubuh dan latar sosialnya.
Baca juga: ‘Sentimental Value’, Trauma Turun-temurun, Serta Sela di Antara Memaafkan dan Mengampuni
Jahitan Visual, Musik, dan Narasi yang Tajam
Mesa Soto menyoroti tajam dunia seni yang jadi bentuk eksploitasi baru, tempat penderitaan dipoles menjadi komoditas, dan otentisitas dijual sebagai citra “kemajuan”. Oscar, yang berharap bisa menebus diri lewat bakat Yurlady, akhirnya menyadari bahwa mereka berdua sama-sama diperas oleh sistem yang sama: satu sebagai idealis yang kelaparan, satu lagi sebagai simbol sosial yang dimanfaatkan.
Gaya visual A Poet memperkuat pesan itu. Sinematografer Juan Sarmiento G. menggunakan kamera 16mm dengan tekstur grainy yang memberi nuansa nostalgia. Dunia Oscar tampak berhenti di masa lalu, dalam warna-warna pudar, seolah waktu enggan bergerak untuknya.
Teknik handheld dan zoom cepat membuat film terasa seperti perpaduan antara dokumenter, komedi absurdis, dan drama sosial. Musik dari Trio Ramberget dan Matti Bye muncul dalam ledakan nada yang menggoda, lalu tiba-tiba melunak, mengikuti ritme batin tokohnya.
Mesa Soto berhasil menjaga keseimbangan antara komedi dan ironi tanpa kehilangan arah. Ia tahu kapan harus membuat penonton tertawa, dan kapan harus membuat tawa itu membuat tenggorokan tercekat. Pun di balik humor itu, ada simpati yang lembut terhadap mereka yang tetap bertahan hidup dengan cara yang tak efisien, tak pragmatis, tapi tetap bermartabat.
Meski kisah ini berakar di Medellín, relevansinya terasa kuat di Indonesia. Di sini pun, banyak orang di dunia humaniora menghadapi dilema serupa: mereka diajarkan untuk memahami kehidupan, tapi tak dibekali alat untuk bertahan di dalamnya.
Baca juga: ‘The Secret Agent’: Surat Cinta untuk Sinema dan Brasil dalam Cengkraman Rezim Militer
Profesi seperti penulis, dosen, penerjemah, atau seniman sering dianggap pekerjaan yang “mulia, tapi tak menghasilkan”. Situasi-situasi seperti ini acap kali memicu munculnya komentar-komentar sinis yang mempertanyakan apa gunanya jurusan-jurusan itu, kalau ujung-ujungnya lulusan mereka jadi banker semua?
Ironi itulah yang membuat film ini terasa universal. A Poet memperlihatkan kenyataan bahwa ada bentuk kebanggaan dalam bertahan, bahkan di tengah kegagalan. Dalam satu adegan kecil nan kuat, Oscar diberi panggung kecil untuk membacakan puisinya di depan audiens yang setengah mendengarkan. Ia tahu mereka tidak peduli, tetapi tetap membaca.
Puisi itu tak akan mengubah nasibnya, tapi juga tidak akan memadamkannya. Dalam momen itu, film ini menjadi refleksi tentang martabat manusia yang menolak tunduk pada ukuran ekonomi.