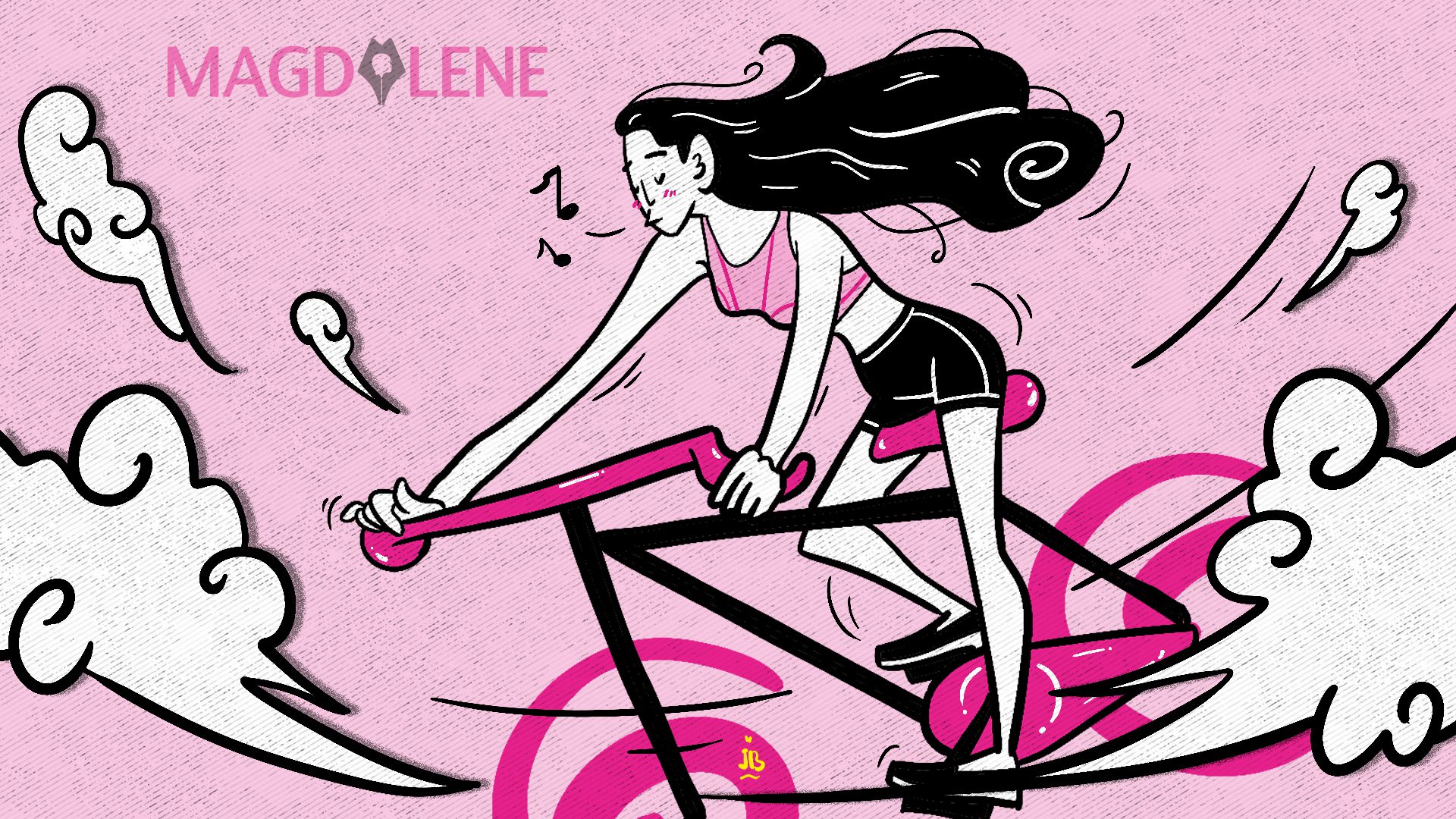‘Die My Love’: Tubuh Ibu yang Terancam Darah dan Dagingnya Sendiri

Dalam Die My Love, keganasan emosi dipertunjukkan melalui bahasa visual yang terasa tak terjinakkan. Dalam salah satu momen di awal-awal, Jennifer Lawrence dan Robert Pattinson merangkak di antara rumput tinggi bak dua makhluk liar yang didorong naluri paling dasar untuk saling mendekap dan menguasai: sebuah hasrat akan kedekatan, seks, dan kehidupan yang lebih penuh.
Namun, inti film ini bukan cuma tentang ketegangan fisik itu.
Adaptasi Lynne Ramsay atas novel Ariana Harwicz ini perlahan mengungkap bagaimana seorang perempuan dapat terkikis dari dalam: oleh tubuhnya, pikirannya, dan cintanya.
Baca juga: Apa Itu ‘Baby Blues’? Kondisi yang Masih Sering Diremehkan Keberadaannya
Ramsay, seperti dalam We Need to Talk About Kevin atau Morvern Callar, tak pernah membuat film yang ceritanya bisa diuraikan begitu saja. Ia suka membuat kita mengarungi psikis tokoh-tokohnya yang tak pernah sederhana. Dalam Die My Love, Grace (Jennifer Lawrence) adalah seorang ibu muda yang perlahan kehilangan pijakan atas realitas setelah melahirkan. Tapi Ramsay menolak menjadikan film ini sebagai drama depresi pasca-melahirkan yang konvensional.
Yang ia tawarkan justru potret batin yang lebih purba, saat keibuan, hasrat, dan kegilaan menyatu seperti binatang yang mengendus darahnya sendiri.
Ketika Grace pindah bersama suaminya, Jackson (Robert Pattinson), ke rumah tua milik pamannya yang meninggal bunuh diri, ruang pedesaan yang umumnya memberi ketenangan justru berubah jadi semacam kandang. Kamera Seamus McGarvey dengan rasio layar yang sempit, menyulap lanskap Montana yang luas menjadi semacam penjara optik: padang rumput terasa menutup, rumah kayu tampak mengawasi.
Dalam konteks itu, Die My Love terasa seperti remake Ramsey atas The Shining dengan twist feminis, membuat rumah bukan sebagai tempat domestik yang aman, melainkan sebuah entitas tersendiri yang hendak menelan hidup-hidup perempuan yang meninggalinya.
Jennifer memainkan Grace dengan level keleluasaan yang jarang ditemui pada aktris besar sekelasnya. Ia tidak sedang berakting sebagai “ibu gila”, ia menjadi tubuh yang kehilangan batas antara gairah dan kehampaan. Dalam satu adegan, ia menatap dapur kosong sambil memegang pisau. Di lain waktu, ia bermasturbasi di kamar sementara suaminya memasak di bawah. Namun, adegan ini tidak dimaksudkan menjadi erotis, melainkan tentang alienasi: betapa tubuh yang dulu ia kenal kini menjadi sesuatu yang asing, yang menakuti dirinya sendiri.
Tema post-partum depression sentral dalam film ini, tentu saja, lewat suasana suram, rasa bersalah, dan keletihan yang menyelimuti Grace terus-terusan.
Baca juga: Idealita Ismanto dan Pengalaman Postpartum Depression dalam Esai Foto
Menariknya, Grace digambarkan Ramsay bukan sebagai korban yang perlu diselamatkan. Alih-alih, Grace tampil sebagai perempuan yang tak sepenuhnya siap atau ingin merengkuh perannya sebagai ibu, yang menolak domestikasi bahkan ketika cinta pada pasangan dan anaknya adalah fondasi utama. Grace berkata sinis di satu adegan: “A real mom would’ve baked a cake,” sembari memakan kue supermarket bersama Jackson di bawah terik matahari.
Film ini nyaris tak memiliki plot yang linear. Ia menyerupai arus mimpi yang melompat antara realisme dan halusinasi. Dalam fragmen-fragmen ini, kita melihat Grace menari di dapur, melukai dirinya sendiri, terpikat oleh lelaki misterius bermotor (LaKeith Stanfield) yang mungkin saja hanya hidup dalam imajinasinya.
Semua potongan-potongan adegan itu, lagi-lagi, seperti upaya tubuh Grace mencari kembali identitas yang terserap ke dalam peran “ibu”.
Ada momen penting ketika Grace menatap kertas kosong di meja tulisnya. Ia dulu ingin menjadi penulis, tapi kini ia hanya menatap tinta yang bercampur dengan ASI. Sebuah imaji yang begitu membekas, simbol dari dua hal yang tak bisa ia rekonsiliasi: kreativitas dan keibuan.
Dalam pandangan Ramsay, keduanya lahir dari sumber yang sama: tubuh perempuan. Tapi tubuh itu sendiri selalu terancam oleh cinta yang mengikat dan dunia yang ingin menjinakkannya.
Menjelang akhir film, Grace kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit jiwa. Ia mencoba menyesuaikan diri kembali ke tatanan “normal” yang dianut kebanyakan orang di sekelilingnya, dengan cara menyesuaikan diri pada ekspektasi perempuan paling konvensional: memasak, mendekorasi, dan menyiapkan pesta kecil-kecilan. Tapi, rumah itu kini sudah bukan miliknya.
Ramsay menggiring kita pada kesadaran bahwa Grace bukan ingin mati, ia hanya ingin bebas dari kebohongan bahwa cinta rumah tangga bisa menyembuhkan segalanya.
Dan pada akhirnya, kebebasan itu datang dalam bentuk api. Grace membakar hutan di tepi rumahnya, dan bersama nyala itu, ia membakar naskah novel yang tak pernah selesai ia tulis. Di titik ini, film menjelma jadi metafora: seorang perempuan membakar dunia yang menolaknya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri.
Baca juga: Bagaimana Jika Tak Ada Surga di Telapak Kakiku?
Sebagai judul, “Die My Love” bisa memiliki makna ganda. Ia bisa terdengar seperti seruan putus asa, tapi bisa juga menjadi doa: jika memang harus mati, biarlah dalam cinta yang sungguh, bukan cinta yang menjinakkan.
Dalam kobaran api di momen-momen terakhir film, Jennifer berdiri seperti makhluk yang baru lahir, dan Ramsay menutup filmnya bukan dengan momen kematian literal, melainkan lebih pada pembebasan.
Sebagai laki-laki yang menonton film ini, saya merasa seperti tamu di rumah orang lain. Tidak semua yang terjadi di sana bisa saya pahami, tapi saya bisa merasakan panasnya. Die My Love bukan tentang menjadi ibu, melainkan tentang apa jadinya manusia ketika cinta dan identitas saling melahap. Ia adalah film tentang tubuh dan betapa sulitnya kadang hidup di dalamnya.