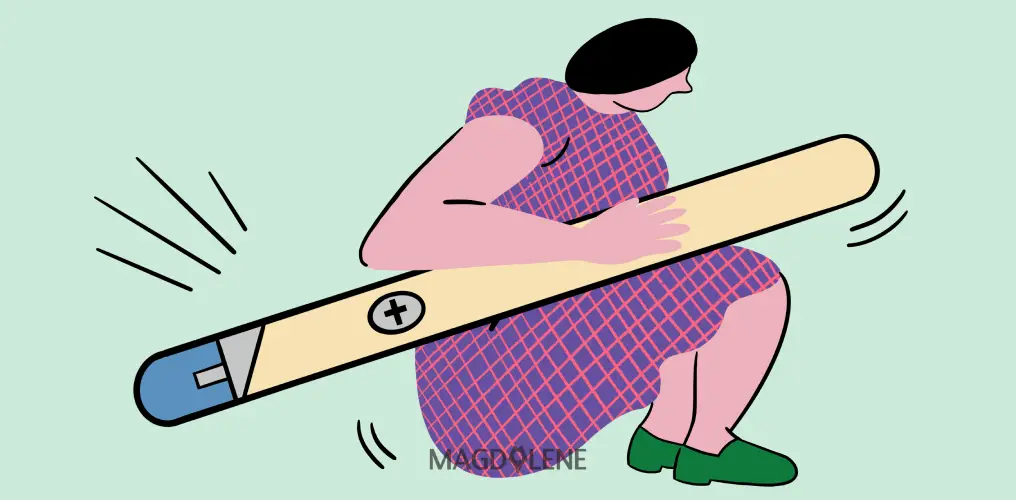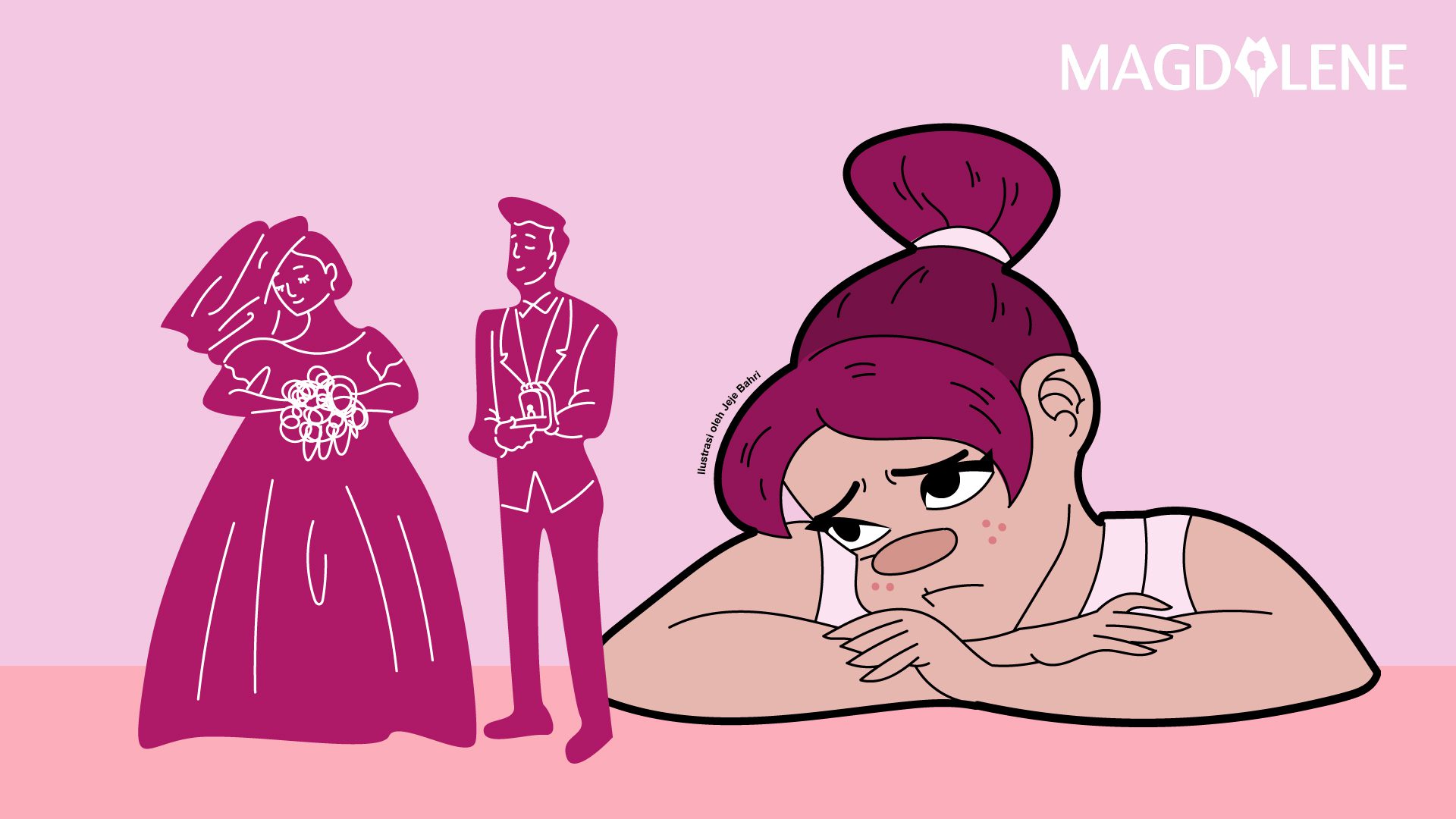Pendamping KBGO Bekerja di Ruang Bising tapi Nyaris Tanpa Dukungan

*Peringatan pemicu: Cerita kekerasan seksual berbasis gender.
Saat pertama kali bergabung dengan SAFEnet pada 2023, Shinta tidak pernah membayangkan betapa berat perjalanan yang menantinya di Divisi Kesetaraan dan Inklusi. Ditugaskan menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Shinta langsung dihadapkan pada ribuan aduan yang masuk setiap tahun melalui kanal pengaduan lembaganya.
Semua kasus datang dengan luka masing-masing. Enggak ada yang sederhana dan bisa ditangani tanpa mengguncang batin. Di awal bekerja, setiap kali membaca kronologi, emosinya akan bergejolak. Ia takut kekerasan korban bisa terjadi pada diri atau orang-orang terdekatnya.
Perlahan ia belajar menjaga batas dan menemukan ritme, tapi ternyata jalannya enggak mudah. Menangani KBGO adalah pekerjaan yang menuntut empati sekaligus keteguhan mental. Salah satu masa paling berat dalam pekerjaannya terjadi pada pertengahan 2024, ketika ia menangani korban kasus penyebaran konten intim non-konsensual.
Proses hukum yang seharusnya melindungi korban justru berjalan lamban. Laporan yang diajukan ke pihak kepolisian ditolak, dan upaya pendampingan hukum tak mendapatkan kemajuan berarti. Di tengah ketidakpastian itu, kabar buruk datang: Korban yang ia dampingi mengakhiri hidupnya.
“Dua hari atau tiga hari setelah mendapat kabar itu aku langsung ke psikolog. Aku tuh sempat ngerasa bersalah juga. Aku menyalahkan keadaan, lalu menyalahkan diri sendiri dan banyak pihak (atas apa yang terjadi),” tuturnya pada Magdalene.
Baca Juga: Magdalene Primer: UU ITE Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual
Mereka yang Mendampingi di Sela-sela Kerja Utama
Pengalaman Shinta menjadi potret keseharian mereka yang berada di garis depan penanganan dan pendampingan KBGO. Mereka bekerja dalam tekanan emosional tinggi, menghadapi cerita traumatis hampir setiap hari, dan kerap menanggung beban psikologis. Mereka mendampingi secara emosional, mengarahkan langkah hukum, hingga membantu pengamanan digital. Dalam banyak kasus, mereka juga satu-satunya pihak yang bisa diakses korban dan menjadi titik awal korban mendapatkan keadilan.
Beban ini berlipat lebih berat, mengingat lonjakan kasus KBGO. Berdasarkan laporan SAFEnet, dalam dua tahun terakhir jumlah kasus tercatat naik secara konsisten. Dari 2022 ke 2023 meningkat sebanyak 380 kasus, dan melonjak tajam dari 2023 ke 2024 sebanyak 850 kasus. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat peningkatan tajam jumlah kekerasan berbasis gender dari 226.062 kasus pada 2020 menjadi 330.097 kasus pada 2024.
Sayang, kenaikan kasus yang signifikan ini tak diiringi dengan pertumbuhan layanan penanganan dan pendampingan. Sejauh ini, Magdalene hanya mengidentifikasi tiga entitas yang secara khusus menangani dan mendampingi korban KBGO: SAFEnet, Power Hub Girl, dan TaskForce KBGO. Ketiga entitas ini beroperasi dengan sumber daya terbatas, bahkan sebagian berbasis sukarela.
Hal ini dirasakan langsung oleh Shevierra Danmadiyah alias Shevi dari TaskForce KBGO. Di luar perannya menangani dan mendampingi korban, Shevi bekerja penuh waktu sebagai peneliti di lembaga kajian dan advokasi hak asasi manusia (HAM). Hari-harinya penuh tenggat dan menyita energi. Ia tetap harus mengurus rilis pers, melakukan koordinasi, dan komunikasi advokasi di luar jam kantor formal. Di tengah beban itu, pendampingan KBGO harus tetap berjalan tanpa honor, tanpa jam kerja, sering kali tanpa jeda.
“Ada kalanya kita tuh pasti akan overlapp, satu kasus dengan kasus yang lainnya gitu. Aku beberapa kali harus menangani dua kasus berbarengan dan jalannya kasus kan juga lama. Bisa berbulan-bulan,” jelas Shevi.
Agar tetap bisa bertahan, ia mengatur waktu seketat mungkin. Ia jarang merespons korban pada jam kerja formal karena tubuh dan pikirannya sudah berada di batas. Ia baru bisa membalas di luar jam kerja, entah malam hari atau akhir pekan. “Karena kerjaan tuh sudah berat banget. Jadi kalau didobel dengan pekerjaan lain di jam 9-5, aku merasa cukup overwhelmed.”
Akhir pekan pun bukan sepenuhnya waktu rehat. Justru hari-hari itu pekerjaan TaskForce KBGO berjalan penuh, dengan pertemuan internal, pembaruan kasus, dan lokakarya edukasi.
“Itu satu-satunya waktu di mana kita bisa benar-benar terbebas dari pekerjaan formal,” imbuh Shevi.
Kelelahan serupa juga dirasakan Lusty Ro Manna Malau dari Power Hub Girl dan PHI. Ia bukan hanya pendamping, tetapi juga pendiri komunitas untuk mendampingi perempuan korban kekerasan seksual.
Di kota dengan tingkat kekerasan seksual tinggi, dalam satu hari ia bisa berpindah dari menangani korban pemerkosaan ke menyusun respons untuk kasus KBGO yang mendesak. Bersama dua teman lain, ia juga terlibat advokasi yang memperluas medan kerja jauh melampaui ruang penanganan.
“Kami mengisi lokakarya, kadang even turun aksi, dan di wilayah masing-masing ada konflik nah kita juga turun,” ujarnya.
Baca Juga: Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru
Tantangan Struktural yang Menambah Beban
Beban kerja para pendamping membengkak bukan hanya karena jumlah kasus, tetapi juga ketiadaan mekanisme negara terpadu. Shinta mengalaminya saat mendampingi korban KBGO yang mencoba menempuh jalur hukum.
Masalah pertama adalah tuntutan aparat soal identitas pelaku. Banyak korban tidak mengenal pelaku, lokasi, atau jejak digital yang memadai. Namun kondisi ini membuat laporan sering terhenti, seolah keterbatasan informasi menjadi kesalahan korban.
Dalam satu kasus, korban lebih dulu melapor ke polisi sebelum mencari bantuan ke SAFEnet. Laporan ditolak dengan alasan memproses kasus akan memperluas penyebaran konten. “Itu alasannya konyol banget,” ungkap Shinta. Korban akhirnya menyerah.
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebenarnya menjamin hak korban untuk menghapus konten dan memulihkan nama baik, tetapi implementasinya lemah.
“Aparat belum memahami mekanismenya, dan belum punya perspektif korban yang memadai untuk mengeksekusinya,” tambahnya.
Respons platform digital yang lambat juga memperparah situasi.
Shevi menambahkan, pendampingan digital terbatas pada langkah dasar, seperti pengaturan privasi akun, pemblokiran pelaku, dan pelaporan massal. Jalur hukum pun sering membingungkan karena aparat belum memahami klasifikasi kasus KBGO.
“Masuknya ke unit siber atau unit perempuan dan anak mereka tuh juga masih bingung nge-frame kasusnya mau ke mana,” katanya.
Ketidakpastian ini menimbulkan kecemasan, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi para pendamping.
“Kadang justru ketakutannya itu datang dari pendamping, karena kita tahu kalau masuk ke polisi itu bisa berujung reviktimisasi,” tambah Shevi.
Baca Juga: SKB UU ITE Bawa Kemajuan, Tapi Revisi UU Tetap Diperlukan
Harusnya Negara Hadir
Di atas kegagalan sistem, ada tantangan lain berupa budaya victim blaming. Shevi mencontohkan kasus remaja SMA di Tangerang, yang tidak bisa mengikuti ujian karena konten intimnya tersebar. Pendamping harus meyakinkan sekolah bahwa korban bukan pelaku.
“Waktu itu kami jelasin ke sekolah kalau yang dipermasalahkan itu penyebarannya. Korban enggak menyebarkan, dia enggak punya kuasa. Video itu dikirim terbatas, sekali buka, ke satu orang yang dipercaya,” ujarnya.
Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, menegaskan negara harus hadir, tidak sekadar membuat regulasi.
“Itu berarti wajib untuk memastikan aparat paham dinamika KBGO, layanan pendampingan tersedia, sistem pelaporan mudah diakses, dan korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan saat melapor dalam mencari keadilan,” jelasnya.
Negara juga harus mengatur platform digital agar akuntabel, misalnya memastikan proses penghapusan konten berbahaya cepat dan efektif. Nenden mencontohkan Australia dengan Online Safety Act dan eSafety Commission. Regulasi itu menempatkan negara sebagai penyangga psikologis, bukan sekadar pengatur teknis, sehingga korban bisa pulih martabatnya.
Kerja kolektif tidak seharusnya menjadi satu-satunya penopang. Solidaritas komunitas perlu, tetapi negara harus hadir agar pendamping tidak memikul beban sendirian dan korban tidak harus kuat di dunia yang belum aman.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan kolaborasi #SamaSamaAman dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 bersama media anggota Women News Network (WNN). Liputan ini didukung oleh International Media Support (IMS). Informasi soal WNN bisa diakses di https://womennewsnetwork.id/