Ahli: Kemiskinan Bukan Sebab Utama Terorisme
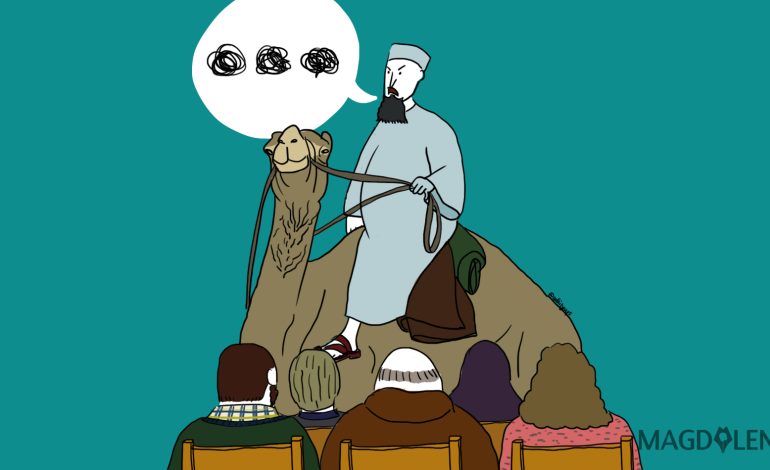
Kemiskinan acap kali dianggap sebagai penyebab utama seseorang bergabung dengan kelompok radikal, namun ahli mengatakan bahwa faktor sosio-ekonomi bukan pendorong utama seseorang ikut bergabung dengan organisasi radikal.
“Ada kesempatan yang sama antara masyarakat kelas menengah dan masyarakat urban miskin untuk bergabung dengan organisasi radikal. Bahkan faktanya, hanya sedikit teroris yang berasal dari masyarakat urban miskin,” ujar Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis Conflict (IPAC).
Ia berbicara dalam diskusi publik bertajuk Update on The Challenge of Terrorism and Radicalism in Indonesia and Southeast Asia yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kamis (12/4).
Alasan seseorang bergabung dengan kelompok radikal pun bervariasi, ujarnya. Ada yang bergabung karena sedang berada di lingkungan asing lalu mencoba mencari rasa kebersamaan melalui kelompok, dan ada juga dari sisi psikologis, yang mendorong seseorang dengan kepribadian pendiam ingin mencari ikatan atau hubungan dengan orang lain.
Cara perekrutan kelompok radikal dilakukan dalam bentuk pengajian tertutup, ungkap Jones. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia, di mana media sosial memiliki andil yang besar dalam merekrut, Indonesia lebih mengandalkan pertemuan langsung, tambahnya.
“Jadi cara kerjanya ialah seseorang akan diundang ke dalam diskusi agama atau pengajian, tapi bersifat ekstrem lalu orang tersebut diundang ke dalam pertemuan kecil yang tertutup. Hasil dari pertemuan kecil itu ialah orang tersebut akan diundang ke dalam grup diskusi di (aplikasi sosial) Telegram atau media chat kelompok lainnya. Perekrutan ini terjadi dalam pertemuan dan sebenarnya kita mampu mengidentifikasinya di beberapa masjid atau sekolah tempat pertemuan itu dilaksanakan,” papar Jones.
Perekrutan anggota organisasi teroris pun tidak hanya melalui pengajian dan media sosial saja. Penjara juga menjadi medium yang digunakan untuk mengajak tahanan lain untuk bergabung dengan organisasi ekstremis bahkan membentuk kelompok baru.
Tren dari dalam penjara adalah bagaimana organisasi teroris menyasar ketua sebuah kelompok ekstremis yang sedang dalam masa tahanan. Jika mereka bisa menggaet ketua dari kelompok tersebut, maka secara otomatis pengikutnya akan ikut serta, sehingga menghasilkan massa yang lebih banyak.
“Kadang ada perekrutan ketua sebuah kelompok dengan harapan bahwa ketua tersebut juga akan membawa pengikutnya. Jadi kelompok pro-ISIS yang berada di Nusa Kambangan berusaha untuk merekrut Abu Bakar Baasyir karena mereka tahu jika mereka bisa mendapatkan Baasyir maka akan banyak orang yang bergabung,” jelas Jones.
Keterkaitan Kelompok Intoleran dengan Kelompok Teroris
Saat ini tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya kelompok teroris dengan nama Islam yang terus melakukan perekrutan anggota saja, tetapi juga kelompok intoleran, juga dengan nama Islam, yang menginginkan adanya perubahan keadaan sosial serta politik di Indonesia.
Jones mengibaratkan kelompok intoleran tersebut dengan Forum Pembela Islam (FPI) serta orang-orang yang bergabung dalam Aksi 212 melawan Ahok. Ia menyebutkan bahwa pengikut “garis keras” yang menganggap bahwa non-Muslim tidak seharusnya memimpin masyarakat mayoritas Muslim memiliki kesalahpahaman atas makna demokrasi.
“Demokrasi diartikan sebagai semua diatur oleh kelompok mayoritas, tapi tidak melindungi minoritas dan tidak menegakkan hukum. Menurut saya demokrasi adalah semua yang telah disebutkan (perlindungan kelompok minoritas dan penegakan hukum), bukan hanya kelompok mayoritas bisa melakukan ap apun yang ia mau,” kata Jones.
“Menurut saya, Indonesia memiliki tugas besar dalam mempromosikan kesetaraan kepada seluruh masyarakat di bawah nama hukum,” lanjutnya.
Ia kemudian menambahkan bahwa kelompok intoleran dan jihadis ialah dua hal serta tantangan yang berbeda walaupun keduanya membawa nama Islam.
“Kita menghadapi dua fenomena yang berbeda. Sebagian karena Gerakan 212 merupakan kombinasi dari konservatif tradisional yang didalangi FPI dan kelompok Salafi yang ingin mengubah masyarakat Indonesia dari bawah serta tidak tertarik dengan kekerasan. Jadi tidak terdapat tumpang tindih akan ideologi antara kelompok ini dan kelompok yang berkaitan dengan terorisme,” jelasnya.
Kelompok Salafi umumnya menganggap para jihadis sebagai kelompok bidah dan sangat jarang ada teroris yang berasal dari kelompok Salafi. Secara singkat, bertambahnya kelompok Islam tidak menandakan risiko terorisme juga ikut meningkat, ujar Jones.
Meskipun tidak terdapat kesamaan dalam ideologi, kewaspadaan harus tetap dijaga karena terdapat kemungkinan-kemungkinan lain di mana keduanya bisa saling bersinggungan, tambahnya.
Ia memberikan contoh bagaimana FPI yang bercabang di Jawa Timur tidak memiliki pemimpin dengan pemahaman religi yang besar, sehingga anggota-anggotanya menghadiri kuliah agama yang dipimpin oleh ulama yang bahkan lebih ekstrem. Hal itu kemudian mendorong orang-orang tersebut menjadi kelompok pro-ISIS.
“Ada juga sebuah kelompok yang telah dilarang oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga menginginkan kekhalifahan, tapi berbeda dengan pemahaman kekhalifahan yang dimiliki ISIS,” kata Jones.
Namun, oleh karena kesamaan tujuan bahwa khalifah ialah solusi semua permasalahan, ada beberapa anggota HTI yang akhirnya ikut bergabung dengan ISIS.
“Menurut saya sangat penting untuk dipahami bahwa ada beberapa bagian yang saling bersinggungan, tapi secara garis besar kita tidak menghadapi fenomena yang sama,” ujar Sydney.
Lalu pertanyaan besarnya ialah, mana yang menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia? Apakah kelompok teroris yang melakukan pengeboman dan pro ISIS yang masih terus hidup dan melakukan perekrutan atau kelompok intoleran yang berbondong-bondong berdemo agar gubernur Jakarta di penjara dan menginginkan perubahan sosial dan politik Indonesia menjadi lebih Islami?
“Menurut saya itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang Indonesia. Meskipun begitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga lembaga demokrasi tetap kuat melawan ancaman kelompok intoleran atau perekrutan organisasi ekstremis,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ancaman tersebut dapat diatasi dengan menambah keterlibatan masyarakat dalam menolak informasi palsu, menanamkan cara berpikir kritis, memperkuat sistem peradilan negara, serta tidak mengerucutkan penyelesaian masalah dengan deradikalisasi saja.
Ia juga menambahkan bahwa korupsi menjadi fasilitator terbesar berjalannya kelompok ekstremis dan intoleran.
“Jika Anda berpikir bagaimana mudahnya orang Indonesia memeroleh dokumen perjalanan palsu, kartu identitas palsu, lalu orang di penjara dan pemerolehan senjata api, semua karena korupsi. Jadi dengan melawan korupsi kita juga melawan terorisme,” papar Jones.
“Cara terbaik untuk mengatasi isu ini ialah dengan memperkuat lembaga demokrasi di Indonesia.”
Baca juga tantangan yang dihadapi Posyandu sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak.
Tabayyun Pasinringi adalah reporter magang Magdalene, mahasiswa jurnalistik yang gemar mendengarkan musik dream pop dan menghabiskan waktunya dengan mengerjakan kuis Buzzfeed.






















