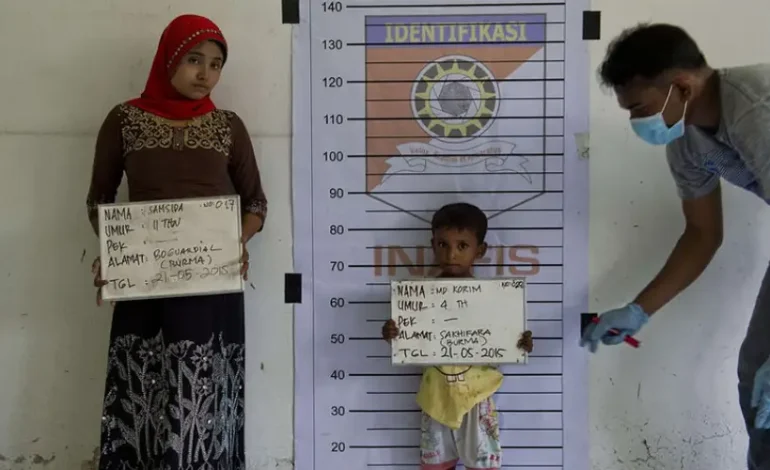Kita mungkin sering mendengar profesi jurnalis menjadi pilar demokrasi keempat di sebuah negara. Perannya penting sebagai anjing penjaga pemerintah yang katanya memang cenderung korup. Namun, profesi jurnalis kini menghadapi banyak tantangan dan risiko, termasuk kerentanan dalam hal stabilitas finansial dan keberlangsungan karier.
Sepanjang 2020-2022, saya mewawancarai 50 jurnalis dari beragam latar belakang, dari yang baru masuk industri media sampai yang sudah belasan tahun berprofesi sebagai jurnalis. Salah satu kesimpulan yang saya dapat: Profesi jurnalis menjadi semakin rentan secara finansial dan jurnalis semakin terindividualisasi.
Individualisasi berarti bahwa corak kerja yang ada semakin mengisolasi jurnalis untuk fokus pada diri sendiri, misalnya harus menguasai berbagai keterampilan sekaligus, tanpa sempat untuk memupuk solidaritas kolektif dalam serikat pekerja. Konsekuensinya, problem yang muncul hanya dianggap sebagai problem individu, alih-alih problem struktural yang membutuhkan jawaban struktural.
Tak heran, kini profesi jurnalis hanya menjadi batu loncatan bagi para kaum muda sebelum berpindah ke industri lain yang lebih menjanjikan stabilitas finansial. Dampaknya, industri media pelan-pelan kehilangan generasi jurnalis berkualitas dan terbaiknya.
Baca juga: Jurnalis di Tengah Pandemi: Upah Tertunda, PHK, sampai Ancaman Keamanan
Dilema Jurnalis
Studi terbaru tentang kondisi kerja dan kerentanan jurnalis di era digital di Indonesia menemukan bahwa perkembangan era teknologi digital, terlepas dari banyak dampak positifnya, telah membentuk pengalaman jurnalis muda sekaligus membuat kondisi kerja para jurnalis menjadi semakin rentan.
Berdasarkan temuan wawancara yang saya lakukan dengan meminjam kerangka dari studi tersebut, saat ini ada tiga dilema yang dihadapi para jurnalis.
Pertama, dilema terkait status dan hubungan kerja.
Jurnalis yang merupakan pekerja tetap menyampaikan bahwa kondisi kesejahteraan mereka masih terbatas. Keterbatasan ini di antaranya meliputi minimnya perhatian perusahaan media terhadap kesehatan mental bahkan tidak didaftarkan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Sementara, bagi jurnalis yang bekerja lepas (freelance), sebagaimana karakter pekerja prekariat, fleksibilitas dalam mengatur jam kerja memang menawarkan kebebasan. Tetapi, pandemi membuat ruang gerak mereka terbatas.
Biasanya, jurnalis freelance yang bisa bertahan adalah mereka yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan sudah memiliki jejaring yang relatif luas. Ini menjadi semacam privilese yang jarang sekali didapatkan oleh jurnalis-jurnalis muda yang sejak awal memutuskan untuk freelance.
Berdasarkan temuan wawancara yang saya lakukan, status pekerja tetap dan pekerja lepas sama-sama memiliki karakter kerentanan yang berimplikasi pada kekhawatiran akan jaminan sosial dan jenjang karier di masa depan.
Kedua, dilema terhadap kondisi dan beban kerja. Beberapa jurnalis menyebut bahwa beban kerja mereka sebagian besar dibagi menjadi dua: beban kerja dengan target kuantitas, misal harian atau mingguan; dan beban kerja yang berbasis pada isu.
Hanya media-media tertentu saja yang memiliki kemewahan membuat jurnalisnya bekerja berdasarkan isu tanpa mempertimbangkan kuantitas. Sebagian besar media digital masih menggunakan ukuran jumlah berita yang diproduksi harian. Kondisi ini dalam beberapa kasus dapat berujung pada bentuk eksploitasi jurnalis, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja.
Di Yogyakarta, misalnya, 12 mantan jurnalis media daring Akurat.co menggugat media tersebut. Penyebabnya, manajemen memecat mereka setelah para jurnalis tersebut mencoba bernegosiasi terkait dengan target produksi 200 berita/artikel per hari sementara jumlah penulisnya terbatas.
Mirisnya lagi, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi tersebut, baik terkait status maupun beban kerja, kerap “ditutup” dengan refleksi diri “daripada tidak ada pekerjaan sama sekali, kondisi ini mesti disyukuri”. Pada akhirnya semua itu mereka anggap sebagai risiko menjadi jurnalis.
Yang mengejutkan, dilema semacam ini telah dinormalisasi sejak di dunia kampus. Dalam survei yang saya lakukan bersama Remotivi (2021), saya menemukan bahwa kondisi kerentanan ini sudah dipahami oleh mahasiswa studi jurnalisme dan komunikasi. Mereka menyampaikan bahwa pekerjaan di industri media bukanlah pekerjaan yang bisa mendatangkan kesejahteraan finansial. Dan karena itu, sebagian besar responden sulit untuk membayangkan akan memiliki karier sebagai jurnalis sampai usia pensiun.
Ketiga, kesulitan-kesulitan yang dihadapi tersebut kemudian menjadikan jurnalisme sebagai profesi sementara. Profesi sebagai jurnalis menawarkan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dan berjejaring, yang kemudian digunakan sebagai ruang untuk membuka pintu pekerjaan yang baru.
Kondisi ini sangat bisa dipahami, namun dalam jangka panjang ini bisa menjadi ancaman bagi eksistensi jurnalisme di Indonesia.
Baca juga: MadgeTalk: Pemberitaan Media Makin Tak Bermakna, Kita Harus Bagaimana?
Problem Struktural
Ketidakpastian dan kerentanan akan kesejahteraan dalam profesi jurnalis bukan proses yang terjadi di ruang vakum. Pilihan yang diambil seorang jurnalis ketika memutuskan meninggalkan industri media tidak serta merta hanya persoalan pilihan individual. Ini secara tidak langsung menunjukkan adanya problem struktural dalam ekosistem media di Indonesia. Oleh karenanya, penting untuk mulai mendiskusikan upaya stuktural untuk problem yang dihadapi.
Diskusi bisa dimulai dengan memetakan kondisi yang terjadi saat ini. Upaya semacam ini sebenarnya sudah sering dilakukan, salah satunya oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) misalnya, yang sering melakukan survei upah layak.
Dari sana kita bisa melihat betapa timpangnya kondisi kesejahteraan profesi jurnalis dengan sebagian besar profesi lainnya. Namun, kita juga butuh gambaran yang lebih luas dalam skala nasional karena setiap daerah memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda.
Regulator media dan pemerintah harus segera mendorong munculnya jalan keluar yang membuat kesejahteraan jurnalis bisa terjamin dan berkelanjutan. Upaya yang mesti terus dilakukan jika tidak ingin kondisi jurnalisme semakin memburuk dan terus-menerus dalam bayang-bayang krisis.
Wisnu Prasetya Utomo, PhD student at the School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Ilustrasi oleh Karina Tungari