Menelusuri Algoritme Kecantikan di Medsos: Masih Terjebak di Standar Eurosentris
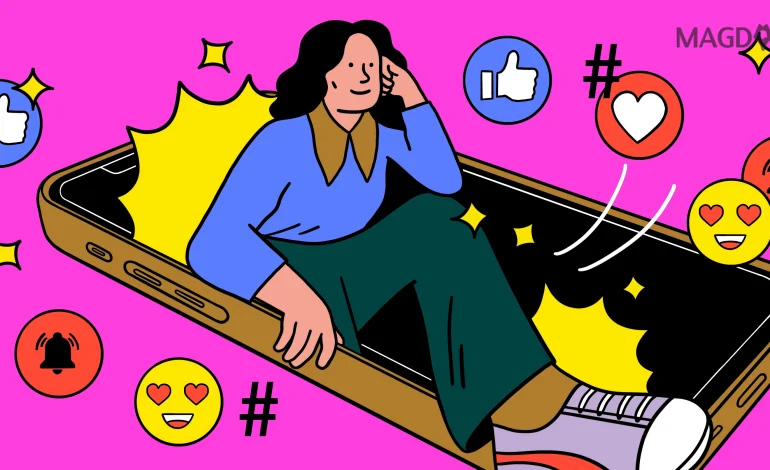
Sebagai mahasiswa, Karyn, 21, cukup memerhatikan penampilan. Hal itu membuatnya ingin mencoba perawatan di klinik kecantikan. Demi menemukan klinik yang tepat, Karyn iseng menelusuri Instagram. Namun, pencariannya belum membuahkan hasil, sampai sebuah iklan muncul di Instagram story.
Iklan tersebut menawarkan promo perawatan Intense Pulse Light (IPL)—untuk memperbaiki tekstur kulit wajah, di klinik kecantikan di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya potongan harga perawatan, promo juga termasuk konsultasi dengan dokter kulit. Saking tertariknya, Karyn langsung melihat ulasan klinik di Google, sebelum menghubungi lebih lanjut untuk treatment.
Itu bukan pertama kalinya Karyn mencari referensi kecantikan di media sosial (medsos). Ia sering memanfaatkan TikTok dan Instagram, untuk mencari rekomendasi skincare dan makeup. Kemudian melihat tutorial makeup, tren kecantikan, mempelajari kandungan bahan aktif di dalam skincare, hingga membeli produk skincare yang sering muncul di laman For Your Page (FYP) TikToknya lewat TikTok Shop.
“Aku senang cari referensi beauty products di medsos karena lebih gampang. Tinggal search bakal muncul berbagai rekomendasi, dan ada video yang nunjukkin penampilan before dan after,” ungkap Karyn.
Sejak 2019, keseharian Karyn lekat dengan Instagram dan TikTok. Di sela aktivitasnya sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, Karyn menjalankan pekerjaan sebagai Key Opinion Leader (KOL) dan spesialis media sosial di bidang kecantikan. Pekerjaan ini membuat Karyn terus mengeksplorasi tren kecantikan. Alhasil, pembahasan seputar kecantikan meramaikan algoritme Instagram maupun TikTok. Ditambah following Karyn di kedua platform tersebut, kebanyakan adalah beauty platform seperti Female Daily Network, atau para beauty influencer.
Di tengah gencarnya kampanye kecantikan inklusif oleh merek kecantikan dan beauty influencer, Karyn mendapati satu hal di algoritmenya: Standar kecantikan eurosentris—yang sebenarnya berusaha digerus kampanye tersebut.
Lewat unggahan sejumlah beauty influencer, misalnya, Karyn melihat sebagian dari mereka masih melanggengkan “cantik itu putih”. Berbeda dengan di TikTok, beauty influencer cenderung “berani” menampilkan diri apa adanya.
“Yang kulihat, di TikTok itu influencers berjerawat, bare face, redness di wajah, dan warna kulitnya gelap,” tutur Karyn. “Kalau di Instagram masih dominan perempuan kurus, kulitnya putih—kayak (orang) kaukasoid.”
Perihal standar kecantikan eurosentris bukan hanya berada di algoritme Karyn, melainkan dalam beauty filter kecantikan. Dalam laporan Magdalene pada 2022, Imam Arifin—kreator filter—mengaku filter buatannya yang banyak digunakan masih mendefinisikan “cantik itu putih”.
Masalahnya, beauty filter yang mengacu pada kecantikan eurosentris, melanggengkan standar kecantikan problematik dan enggak realistis. Terutama bagi orang-orang kulit berwarna yang menginternalisasi standar tersebut. Hal ini kemudian menggambarkan cara kerja algoritme, yang masih memiliki bias.
Baca Juga: Teknologi dan Obsesi Cantik yang Problematik
Algoritme Medsos yang Masih Eurosentris
Setidaknya sampai akhir 2019, kebijakan TikTok dalam mempromosikan konten lebih berpihak pada kreator yang berpenampilan menarik—ciri fisik maupun lingkungan pengambilan gambar. Keuntungannya, konten mereka akan lebih mudah masuk laman FYP.
Lain halnya dengan kreator yang bentuk tubuhnya dianggap “tidak normal”, berwajah tak rupawan”, perut buncit, terlalu banyak kerutan, punya penyakit mata, atau berlatar tempat di area kumuh dan wilayah rural. Mereka lebih dikesampingkan, karena dinilai tak cukup menarik pengguna baru.
Kebijakan eksklusif yang tercantum dalam dokumen itu terungkap oleh liputan The Intercept (2020). Berdasarkan keterangan TikTok, mereka memberlakukan kebijakan sedemikian rupa untuk mencegah perundungan. Namun, dalam dokumen tak disebutkan penjelasan anti-bullying, tetapi menyertakan pembenaran untuk mempertahankan pengguna baru dan mengembangkan aplikasi.
Saat diwawancara The Intercept, juru bicara TikTok Josh Gartner menyatakan, kebijakan yang dimaksud tak lagi berlaku saat The Intercept mendapatkannya. Terlepas dari penghapusannya, tindakan TikTok tak dapat dibenarkan sebagai cara mencegah perundungan. Sebagai platform digital, seharusnya TikTok melindungi pengguna, bukan mengecualikan konten agar tidak disaksikan pengguna lain.
Di samping itu, menurut riset Kristen Crawford pada 2021 yang dipublikasikan Encode Justice, TikTok menggunakan Facial Recognition Technology (FRT)—teknologi biometrik yang akan menganalisis fitur wajah seperti posisi mata, hidung, dan mulut. Teknologi tersebut diaplikasikan bersamaan dengan Facial Beauty Prediction (FBP), untuk menilai komposisi, warna, dan fitur wajah.
Lewat penggunaan FRT dan FBP, Crawford menemukan, TikTok mendukung terbatasnya keragaman konten yang populer. Artinya, konten-konten yang masuk ke laman FYP umumnya individu berkulit putih, atau orang dengan ciri fisik kaukasoid.
Crawford juga membuktikan dengan menganalisis facial landmark—titik-titik penanda di wajah untuk membedakan satu wajah dengan lainnya—partisipan survei. Ia seorang Hispanik, berkulit putih, dan berwajah kecil. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kemiripan fitur wajah antara partisipan dengan influencer TikTok, Charli D’Amelio. Faktor ini menyebabkan konten partisipan tersebut paling banyak disukai dan ditonton, dibandingkan kedua partisipan lainnya: Orang Asia dengan permukaan wajah lebih besar di area alis dan pipi, serta kaukasoid yang ukuran wajah dan alisnya lebih besar.
Di balik banyaknya likes dan views itu, pengamat data dan teknologi Utami Diah Kusumawati menjelaskan, FRT dan FBP membantu menentukan konten berkualitas tinggi, yang kemudian direkomendasikan algoritme ke FYP pengguna. Hal ini melatarbelakangi para kreator, berlomba berpenampilan menarik demi mendapatkan lebih banyak views, engagement, dan masuk dalam kategori konten berkualitas tinggi.
Namun, saat Magdalene mengonfirmasi, TikTok Indonesia mengatakan tidak menerapkan cara kerja seperti yang disebutkan Crawford. Sebab, hal itu berlawanan dengan prinsip platform terkait inklusivitas. Menurut mereka, konten yang muncul di laman FYP mencerminkan preferensi pengguna. Apabila kebanyakan konten menampilkan kecantikan eurosentris, pengguna masih menyukai standar kecantikan tersebut.
Dari keterangannya, TikTok Indonesia menekankan, keaslian konten yang menentukan jumlah views, likes, share, komentar, dan followers baru dari pengguna—sekali pun kreator berpenampilan menarik. Contohnya, kreator berkulit wajah halus mengulas produk kecantikan. Namun, ia menggunakan beauty filter. Pengguna akan bersikap kritis dan cenderung tidak percaya. Ini dikarenakan pengguna lebih mengapresiasi kreator, yang menampilkan diri apa adanya.
Sederhananya, algoritme medsos dibangun oleh sistem yang mengurasi konten dan perilaku pengguna, untuk kemudian dikonsusi. Misalnya lewat likes, komentar, postingan yang diklik, dibaca, dan dibagikan. Kemudian, algoritme akan membaca, menganalisis, dan mengoleksi data terkait perilaku pengguna, untuk menyajikan konten yang beragam. Dengan demikian, terbentuk echo chamber lantaran pengguna akan mengakses berbagai konten sesuai preferensinya.
“Semakin sering pengguna ngabisin waktu untuk lihat konten, platform media sosial dan kreator semakin banyak dapat keuntungan finansial,” ujar Utami. “Soalnya akan menarik sponsor buat mereka.”
Sayangnya, keuntungan bagi platform medsos di sisi lain melanggengkan bias dan standar kecantikan eurosentris. Sebab, algoritme dikembangkan oleh machine learning system—tipe artificial intelligence, yang pendekatannya dibangun oleh manusia. Namun, sistem tersebut tidak dilatih untuk mengenal keberagaman, ataupun bersifat inklusif. Alhasil, kecantikan yang berlaku merujuk pada ciri fisik kaukasoid.
Masalahnya, standar eurosentris itu 10-100 kali lebih mungkin menyebabkan misidentifikasi terhadap orang Asia dan kulit hitam—seperti dijelaskan dalam laporan National Institute of Standards and Technology (NIST) pada 2019, terkait penggunaan FRT. Penyebabnya adalah sebagian besar bank data, yang berisi facial landmark orang kaukasoid.
Berbeda dengan TikTok yang algoritmenya mengarah pada standar kecantikan eurosentris, Instagram justru menampilkan foto pengguna yang berpakaian minim. Dalam laporannya pada 2020, jurnalis Nicolas Kayser-Bril mengungkapkan, 54 persen foto perempuan mengenakan bikini cenderung muncul di feeds partisipan survei. Sedangkan laki-laki bertelanjang dada sebanyak 28 persen.
Saat dihubungi Kayser-Bril, Instagram menyatakan preferensi pengguna mengatur konten yang muncul di feeds mereka. Sebaliknya, paten Instagram menunjukkan, sebenarnya feeds menampilkan konten yang kemungkinan disukai semua pengguna—dalam hal ini foto berpakaian minim. Karena itu, feeds tak hanya mencerminkan perilaku berselancar pengguna, tapi ada peran Instagram yang menyajikan konten yang dianggap menarik.
Dengan berlakunya standar kecantikan di algoritme medsos, ada satu yang perlu disadari, yakni dampaknya bagi pengguna.
Baca Juga: Saat Deepfake AI Jadi Ancaman Bagi Perempuan

Dampak Algoritme
Sewaktu duduk di bangku SMP, Karyn yang lagi suka menonton drama Korea lantas mengagumi kecantikan perempuan Korea lewat Instagram. Bagi Karyn saat itu, cantik yang ideal seperti orang Korea: Kulit putih, glowing, mulus, dan bertubuh kurus. Karenanya, Karyn memutuskan diet ketat selama dua minggu, sampai jatuh sakit.
“Gara-gara kepengen, aku diet berlebihan. Awalnya ngurangin makan, bahkan sempat enggak makan sama sekali seharian. Terus aku sakit asam lambung,” cerita Karyn. “Dari situ langsung sadar, enggak boleh diet ekstrem.”
Kini ia enggak lagi menetapkan standar tersebut sebagai tolok ukur kecantikan, meski masih mendefinisikan “cantik” tercermin dalam fisik orang Korea. Artinya, masih ada bias terhadap standar kecantikan dalam sudut pandang Karyn, dan algoritme yang terinternalisasi.
Masalahnya, enggak setiap pengguna medsos mengritisi konten yang dikonsumsi, bahkan menyadari terbentuknya echo chamber dari algoritme. Hal ini membuat pengguna terekspos pada bentuk tubuh dan standar kecantikan tertentu, yang dapat berdampak negatif karena membentuk persepsi mereka terhadap body image ideal.
Lalu, apa yang dapat dilakukan supaya tidak menginternalisasi algoritme?
Baca Juga: Filter Dysmorphia: Buah Simalakama atau Kemajuan yang Perlu Diterima?
Menarik Diri dari Dampak Algoritme
Melalui pengamatannya, Utami mengatakan, sebagian orang Indonesia memahami algoritme. Setidaknya perihal faktor yang meningkatkan popularitas konten, hashtag yang perlu digunakan dalam unggahan,dan cara membuat konten yang sesuaitren. Namun, Utami tak yakin mereka memahami dampaknya.
“Rasanya pengguna belum terlalu mikirin dampak ya, karena sekarang patokannya masih gimana bisa menghasilkan uang?” ucap Utami.
Sebagai pengguna Instagram dan TikTok, Irma (51), senang berselancar di kedua platform tersebut untuk mengakses konten kecantikan. Biasanya, ibu rumah tangga sekaligus pekerja lepas ini mencari tahu tentang perawatan kulit wajah, dan beauty treatment yang perlu diwaspadai.
Irma mengungkapkan, algoritmenya diramaikan konten suntik putih, suntik vitamin C, dan filler. Ketika ditanya apakah konten tersebut mendorong keinginannya untuk melakukan treatment, Irma menjawab tidak. Ia bersikap kritis terhadap apa yang dilihat, dan sadar betul akan dampak dari konten yang dikonsumsi. Salah satunya dengan memperhatikan penjelasan dokter kulit di TikTok, terkait beauty treatment.
“Banyak ya perawatan kulit yang berbahaya, jadi aku cari tahu yang aman dari konten para dokter kulit,” ucap Irma.
Meski enggak tertarik memenuhi standar kecantikan eurosentris, Irma telah mengenalnya sejak awal karier. Bahkan sebelum menikah, ia mengaku masih berusaha untuk bertubuh langsing—mengingat adanya stereotip bahwa laki-laki enggak tertarik dengan perempuan gemuk, berambut pendek, dan berkulit gelap.
Kini Irma lebih memperhatikan pentingnya merawat kulit wajah. Baginya, definisi cantik ditentukan oleh kesehatan, kebersihan diri, dan kecerdasan sebagai nilai tambah.
Walaupun pemahaman standar kecantikan kian beragam, bagi penulis dan body positivity influencer Ririe Bogar, standar tertentu akan terus ada meski tak melulu mengacu pada eurosentris. Sebagai sosok yang juga mengepalai manajemen model plus size, Ririe ingin para model percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, tolok ukur yang ditetapkan untuk tampil di hadapan publik kerap membatasi.
“Sebenarnya, teman-teman model plus size bisa cantik dan melawan standar di masyarakat. Tapi, standar kayak tinggi badan dan besar pinggul masih berlaku,” kata Ririe. “Dan menurutku akan tetap ada.”
Ririe menambahkan, adalah tugas influencer dan siapa pun yang masih berpikir positif tentang body image, untuk berbagi tentang body positivity di medsos. Sebab, setiap pengguna medsos memiliki kapabilitas untuk sharing dan membawa dampak lewat platformnya masing-masing.
Dampak dari sharing seputar body positivity di medsos diamini oleh Karyn. Ia mengaku, perubahan pemahaman bahwa cantik tak harus ideal muncul belakangan ini. Awalnya dari TikTok, ketika sejumlah figur publik memperlihatkan penampilan fisik mereka yang sebenarnya: tanpa filter, menunjukkan bekas jerawat, bekas luka di tubuh, lekuk tubuh berlemak, dan area kulit yang menghitam. Dari situ, Karyn memahami yang sebelumnya dianggap kekurangan adalah normal. Yang penting, bagaimana seseorang menghargai dan merawat diri.
“Sekarang aku lebih melihat berbagai sisi dan mengubah mindset. Namanya di dunia maya, mungkin orang-orang lebih pengen sharing yang bagus-bagus,” tutur Karyn.
Sementara menurut Utami, kampanye seputar kecantikan inklusif perlu dilanjutkan untuk melawan sistem algoritme yang bias. Tentu dibarengi dengan pengguna yang mengubah pemahaman dan cara berpikir, bahwa beauty privilege bukan satu-satunya cara mendulang popularitas di medsos—terlebih di platform yang menggunakan FRT dan FBP. Kondisi ini sebaiknya diubah, misalnya dengan mempublikasikan konten informatif untuk mendorong keberagaman.
“Kita perlu mikir juga, dampak panjangnya apa kalau terus mendorong sistem algoritme yang melanggengkan beauty privilege?” ujar Utami.
Selain itu, menurut Discover Magazine, pengguna juga dapat mengontrol algoritme di media sosial. Contohnya mengabaikan rekomendasi konten yang ditawarkan algoritme. Dengan mengklik rekomendasi tersebut, kamu mengonfirmasi asumsi platform tentang konten yang disukai. Lebih baik mencari secara manual,sekalipun rekomendasinya tepat, daripada memperkuat profil digitalmu.
Kemudian, mematikan suggested post feeds di Instagram—sedangkan ini bukanlah opsi untuk TikTok. Terakhir, memutuskan tautan ke berbagai akun daring, supaya algoritme tidak melihat aktivitasmu di berbagai platform. Hindari menggunakan akun Facebook atau Google, untuk membuat akun baru.
Terlepas dari upaya yang dapat dilakukan sebagai pengguna, dibutuhkan kesadaran dan keterlibatan platform untuk mengubah algoritme kecantikan. Misalnya dengan melatih sistem supaya lebih inklusif, yang mana dilakukan oleh manusia sebagai pembuat sistem. Harapannya, penampilan fisik tak lagi jadi parameter dalam menentukan popularitas, maupun konten berkualitas tinggi.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari
Liputan ini merupakan bagian kerja sama dengan Meedan. Baca artikel lainnya di sini.






















