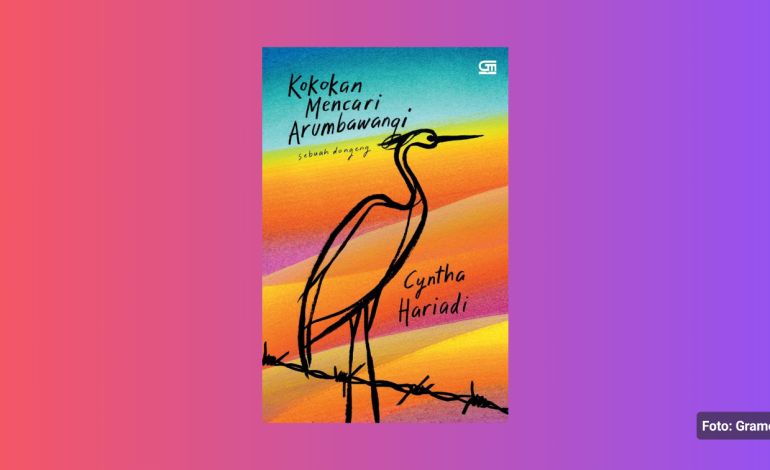‘Political Burnout’ atau Lelah Dikepung Berita Buruk, Kita Bisa Apa?

Sudah hampir empat hari aku kesulitan tidur. Tubuh terasa sangat lelah, tetapi otakku seolah tak mau diajak istirahat. Aku terus terjaga, terjebak dalam pikiranku sendiri—memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian, atau skenario-skenario terburuk tentang carut-marut kondisi Indonesia sekarang.
Jariku tak kalah aktif. Mereka punya cara sendiri untuk membuat aku tetap terjaga hingga larut malam. Rasanya seperti terjebak dalam labirin waktu yang tak berujung. Berjam-jam aku bisa terjebak di layar ponsel, bolak-balik membuka Instagram, X, dan TikTok. Semua berisi kebobrokan pemerintah, protes yang tersebar di berbagai sudut negeri, dan kebijakan yang menindas rakyat.
Marah, kesal, dan putus asa adalah perasaan yang mendominasi malam-malamku. Setiap informasi yang aku serap seolah menguatkan rasa frustrasiku. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat, perilaku para oligarki yang arogan, dan rakyat yang terus diperlakukan seperti tidak ada artinya—semua itu membanjiri pikiranku.
Yang membuatku semakin lelah adalah kenyataan bahwa banyak orang justru memilih untuk berpura-pura tidak peduli. Bukan ikut marah, mereka malah terus berada di zona nyaman. Mengunggah apa saja selain kondisi Indonesia yang memprihatinkan. Ada yang bahkan mengatakan, “Indonesia masih baik-baik saja, lah,” seakan hidup bisa dijalani tanpa perubahan meskipun terus diinjak-injak oleh para oligarki.
Dengan semua perasaan itu, setiap pagi aku terbangun seperti zombie. Kehilangan motivasi, bahkan untuk hal-hal yang biasanya aku nikmati seperti membaca buku. Rasanya, bahkan untuk duduk di depan laptop dan bekerja saja terasa sangat berat.
Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Karyawan Bisa Alami ‘Burnout’ dan Cara Atasinya
Political Burnout: Kelelahan Mental Karena Berita Politik
Ternyata, apa yang aku alami bukan cuma terjadi padaku. Banyak teman yang bahkan bukan jurnalis atau pekerja NGO, mengalami hal serupa. Kami semua terperangkap dalam lingkaran informasi buruk yang terus-menerus tentang kondisi negara ini.
Beberapa temanku mencoba mengurangi dampak ini dengan berbagi kemarahan lewat chat atau group call. Ada yang memilih langkah ekstrem, seperti memblokir akun-akun organisasi masyarakat sipil atau NGO yang berfokus pada isu politik dan HAM, agar tak terus-terusan terganggu dengan informasi politik yang menambah beban emosional. Namun, sebagai jurnalis, aku tidak bisa ikut-ikutan memblokir. Aku harus terus mengikuti perkembangan berita terkini, meskipun itu berarti aku semakin terjebak dalam lingkaran setan.
Apa yang kami alami ini disebut political burnout—kelelahan mental akibat terus-menerus mengonsumsi informasi negatif yang berkaitan dengan politik dan konflik sosial.
Menurut psikologi, political burnout dapat memicu kecemasan, depresi, dan perasaan terasing. Penelitian berjudul “Affective Intelligence and Political Judgment” (2000) misalnya menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap berita negatif dapat menurunkan kualitas hidup dan bahkan menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan rasional.
Media massa berperan besar dalam kondisi ini. Mereka menyajikan berita secara emosional dan provokatif, yang semakin memperburuk keadaan. Dalam bukunya AFRAID: Understanding the Purpose of Fear, and Harnessing the Power of Anxiety (2023), Arash Javanbakht, psikiater dan direktur Stress, Trauma, and Anxiety Research Clinic (STARC), menjelaskan bagaimana media telah menemukan cara untuk memicu rasa takut yang kuat, menarik perhatian, dan membuat kita terus mengikuti, mengklik, dan menontonnya tanpa henti.
Namun, di era digital ini, media sosial justru memperburuk segalanya. Menurut Eli Pariser dalam teorinya tentang filter bubble (2011), algoritme media sosial berfungsi dengan memberi kita konten yang hanya memperkuat pandangan dan ideologi kita. Media sosial mempersonalisasi pencarian, rekomendasi, dan konten yang kita lihat, memperkuat polarisasi dan membuat kita semakin terperangkap dalam gelembung informasi yang mengisolasi kita dari sudut pandang yang berbeda.
Akhirnya, apa yang aku terima hanyalah hal-hal yang mengonfirmasi apa yang sudah aku percayai—seakan dunia hanya berputar dalam satu perspektif saja. Itulah yang disebut ruang gema (echo chamber), lingkungan yang mengisolasi kita dari pandangan atau informasi yang berbeda.
Ruang gema ini memperkuat bias yang ada dan membuat polarisasi semakin tajam. Setiap kali aku mencoba untuk berdebat atau memperluas pandangan, aku merasa terasing dan semakin lelah secara mental. Konfrontasi ideologis yang terus muncul jadi seperti bola salju yang nggak pernah berhenti bergulir.
Baca Juga: Carut Marut Pemerintahan Prabowo: Tanggung Jawab Siapa?
Benarkah Ketidaktahuan itu Kebahagiaan?
Di tengah turbulensi informasi yang tiada henti ini, kadang aku berpikir, mungkin benar juga ya, ketidaktahuan itu berkah. Mungkin jika aku memilih untuk tidak tahu apa-apa, hidupku akan jauh lebih damai. Tidak perlu cemas tentang segala hal yang terjadi di luar sana, tidak perlu terus-menerus dipenuhi rasa frustrasi terhadap kebijakan-kebijakan yang mengubah hidup ini. Mungkin aku bisa kembali menikmati hari-hari tanpa beban, menjalani hobi, bekerja tanpa merasa cemas, bahkan makan tanpa rasa bersalah karena situasi ekonomi yang terus memanas.
Namun, ternyata ketidaktahuan itu bukan solusi. Sebaliknya, aku merasa jauh lebih tertekan dan cemas, lebih dari yang ku rasa saat aku berusaha memalingkan pandangan. Begitu aku menyadari bahwa hampir setiap keputusan yang dibuat pemerintah atau pemimpin memengaruhi hidupku dan masa depan keluarga, aku tak bisa lagi bersikap acuh. Mengabaikan kenyataan hanya akan semakin mendekatkan aku pada ketidakmampuan untuk melawan sistem yang kejam ini. Dan itu jelas berbahaya.
Lupia dan McCubbins dalam The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need to Know? (2002) menyoroti bahaya ketidaktahuan politik. Ketika orang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu penting, keputusan mereka dalam memilih bisa sangat terganggu—tidak rasional, bahkan bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri. Tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik akan berkurang, sehingga mengancam legitimasi sistem pemerintahan. Ketidaktahuan bukanlah berkah, melainkan bencana yang bisa merusak fondasi negara kita.
Baca Juga: ‘Masak Saja Babinya hingga Anjing Menggonggong’: Komunikasi Asbun Pemerintah
Menghadapi Political Burnout
Dengan segala konsekuensi dari ketidaktahuan ini, aku tahu aku tak punya pilihan selain terus mengikuti perkembangan berita politik. Namun, ada cara agar aku tidak terjebak dalam kelelahan mental atau political burnout.
Dalam artikel The Burnout Nation: Why Americans Are Tuning Out yang diterbitkan di Psychology Today, Arash Javanbakht, psikiater yang fokus pada stres dan kecemasan, memberikan saran yang relevan: kita tidak harus menghindari berita sepenuhnya, tetapi perlu menetapkan batasan dalam mengonsumsi informasi politik. Digital detox alias membatasi paparan informasi digital secara sengaja, bisa menjadi langkah pertama untuk menjaga keseimbangan mental.
Selain itu, penting juga untuk memilih sumber berita yang kredibel dan objektif. Jangan sampai kita terjebak dalam informasi yang hanya memperburuk kecemasan atau mendorong emosi negatif. Javanbakht lebih lanjut menyarankan praktik mindfulness dan perawatan diri untuk meredakan dampak stres politik. Dalam penelitiannya Navigating Political Stress in the Digital Age (2021), ia menemukan bahwa kegiatan seperti meditasi, olahraga, dan interaksi sosial yang positif dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan memperkuat ketahanan kognitif kita.
Sebagai tambahan, kombinasi kedua pendekatan ini bisa memberi kita ruang untuk tetap terlibat secara sehat dan berkelanjutan dalam politik. Karena pada akhirnya, masa depan kita di negara ini masih panjang. Kita perlu menjaga kesehatan mental dan emosional kita agar tetap bisa berjuang, terus melakukan perlawanan, dan memastikan masa depan yang lebih baik.
Ilustrasi oleh Karina Tungari