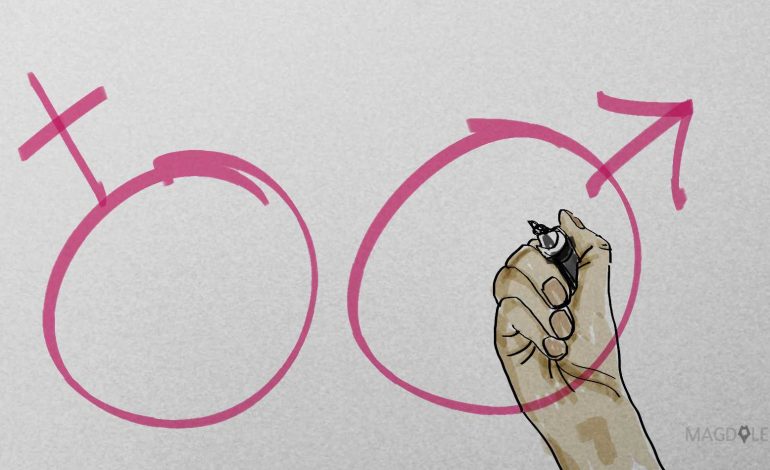Apa yang Kita Bicarakan Ketika Kita Bicara tentang Indonesia

Momen yang Mengubah Saya (Kata Devi)
Ketika kita tinggal ribuan kilometer jauhnya dari rumah, negara kita menjadi versi asing dari apa yang terlihat. Saat ini, di kediaman sementara saya di Amerika Serikat, inilah pandangan saya terhadap Indonesia: asing, membingungkan, dan konsisten ketidakpastiannya. Tetapi bukan berarti saya telah berhenti berharap.
Dua puluh tujuh tahun yang lalu, dengan usia baru 17 tahun, saya tiba di AS, dan kembali ke Indonesia tujuh tahun kemudian setelah lulus, untuk memulai karier di bidang jurnalistik. Dalam rentang waktu tujuh tahun itu saya telah melewatkan banyak hal, yang menghasilkan kesenjangan pengetahuan mengenai Indonesia pada 1990an, seperti lagu apa saja yang populer di kalangan orang Indonesia saat itu (siapa sih Tommy Page ini?), gaya rambut terkini, cerita pembunuhan mana yang paling diingat, dan konspirasi politik apa yang paling banyak diperbincangkan (karena cerita politik yang disebar dari mulut ke mulut lebih memiliki kredibilitas dibandingkan berita yang disetujui oleh Departemen Penerangan).
Terlepas dari beberapa waktu ketika saya pulang ke rumah untuk liburan, sedikit surat yang saya tulis untuk (dan terima dari) keluarga dan teman-teman, serta beberapa kali telepon jarak jauh, hubungan saya dengan Indonesia sebagian besar terputus selama tahun-tahun saya di Amerika. Dulu tentunya tidak seperti sekarang di mana kita bisa mengikuti berita di Indonesia atau tentang teman-teman di mana pun kita berada berkat internet dan media sosial. Internet komersial masih dalam masa awal pertumbuhannya pada saat itu.
Setelah kembali ke Jakarta, saya menjadi anak itik yang canggung, “terlalu Amerika,” kata teman Australia saya. Bahkan rambut saya yang dicat pirang pucat tampak menonjol (“Saya kira kamu setengah bule,” kata seorang rekan kerja). Saya tidak memiliki perilaku lemah lembut, anggun, dan kepatuhan saya lihat ada di banyak perempuan muda yang saya kenal. Saya berjalan dengan cepat, tertawa dengan keras, mengungkapkan pendapat dengan bebas, dan mengenakan pakaian yang terlalu terbuka di bagian lengan, ketiak, atau kaki. Saya tidak bisa berpura-pura tertawa sopan seperti yang diharapkan dari perempuan ketika laki-laki (yang lebih tua) menceritakan lelucon seksis. Sebaliknya, saya mengerutkan kening dan menunjukkan bahwa saya tersinggung oleh lelucon tersebut. “Seksis” bahkan belum masuk dalam kosakata banyak orang Indonesia. Padahal, saat itu sudah tahun 1996.

Di kantor, saya suka merokok di puncak anak tangga tepat di luar ruang redaksi bersama dengan para wartawan laki-laki senior lainnya, sampai seorang rekan perempuan berkomentar, “Kamu berani ya, anak baru dan perempuan merokok di sini, di tempat terbuka.” Dia telah bekerja di sana selama empat tahun dan selalu merokok di bawah anak tangga, tempat yang “lebih pantas” untuknya. Tak berapa lama, dia pun bergabung dengan saya di puncak anak tangga.
Tetapi saya cepat belajar dan beradaptasi dengan situasi baru, berkat masa kecil yang nomaden. Saya belajar untuk mengekang “Amerikanisme” saya dan menetralisir aksen Amerika saya. Saya menyerap ucapan-ucapan lokal dan bahasa sehari-hari dengan cepat. Saya belajar apa yang tidak boleh dikatakan kepada orang, dan kapan harus tutup mulut (meski sampai sekarang saya masih belajar melakukan ini).
Saya tidak langsung jatuh cinta dengan Jakarta, tetapi saya dengan cepat menemukan geng sendiri dengan sesama wartawan, campuran setengah intelek, pemberontak, dan orang-orang yang diasingkan. Dan sedikit-sedikit, saya mulai menoleransi dan mencintai Jakarta. Perlahan-lahan, saya mulai menganggap diri saya orang Indonesia.
Jika ada satu momen yang dapat mengartikulasikan perasaan ini, momen itu adalah gerakan Reformasi pada 1998 dan saat meliput peristiwa bersejarah tersebut sebagai jurnalis. Sebelumnya, saya melihat Indonesia hanya sebagai tempat kelahiran, negara yang menghasilkan saya. Sebagai seseorang yang tidak mudah terperangkap dalam nasionalisme dangkal, perasaan saya terhadap Indonesia, paling tidak, netral. Tetapi pagi itu, pada 21 Mei 1998, setelah mengikuti kerusuhan beberapa hari sebelumnya dan menyaksikan Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya secara langsung di televisi, saya duduk dan menangis, merasakan untuk pertama kalinya rasa cinta yang menyakitkan namun sungguh luar biasa bagi Indonesia. Saya membayangkannya seperti seorang istri yang akhirnya mengetahui bahwa dia mencintai suaminya setelah 20 tahun menikah lewat perjodohan.
Luapan perasaan yang kuat ini, tentu saja, tidak bertahan lama. Rasa cinta ini akan, lagi dan lagi, mengkhianati saya. Dari korupsi, kepemimpinan yang buruk, kebijakan yang buruk, godaan terhadap otoriterianisme dan militerisme, terorisme, fundamentalisme agama, politik uang, politik massa, birokrat yang tidak kompeten, sistem peradilan yang tidak adil, dan kemiskinan, semua kekecewaan ini tampaknya merupakan bagian dari menjadi orang Indonesia. Keadaan bangsa terus-menerus menjadi roller coaster harapan dan frustrasi – yang terakhir lebih dominan daripada yang pertama.
Namun saya tetap bertahan dengannya, dengan harapan bahwa saya tidak seperti istri yang putus asa dalam pernikahan yang tidak bahagia, terlalu lemah atau apatis untuk mengubah apa pun. Saya bertahan dengan keadaan itu sebagai jurnalis, sebagai penulis, dalam pekerjaan di bidang pembangunan, dalam aktivisme saya. Di mana pun saya berada, bahkan di sini, jauh dari kegilaan kerumunan manusia yaitu Jakarta, setengah hari lebih awal di ujung dunia yang lain, Indonesia sangat menonjol di benak saya.
Bagi saya, ini tidak pernah tentang “benar atau salah, negara kita”, namun ini adalah tentang memperbaiki kesalahan negara ini, dan saya senang melihat banyak orang Indonesia yang memiliki sikap yang sama dan berkontribusi dengan cara mereka sendiri, meskipun mungkin belum cukup (lihat tulisan kolega saya di bawah). Ini adalah ambisi yang besar, tetapi alternatifnya adalah tidak melakukan apa-apa, dan itu akan menjadi tragedi yang jauh lebih besar.

Sikap Materialistis yang Mengakar (Kata Hera)
Dua hari sebelum Idul Fitri bulan lalu, kami tiba di rumah ibu mertua dan menemukannya sendirian, sibuk di dapur.
“Yang lain ke mana?” tanya saya, mengacu pada adik ipar saya dan suaminya, serta dua anak mereka yang tinggal di rumah yang sama.
“Ke dealer mobil, beli mobil baru,” kata ibu mertua dengan riang.
Saya dan suami saya bertukar pandang; dia tampak kesal. Ketika kami masuk ke kamar tamu, dia berkata dengan dongkol, “Apa-apaan? Mereka enggak sanggup beli mobil!”
Memang mereka tidak mampu. Kami tahu jelas bahwa keduanya masih kesulitan dalam hal keuangan. Kami tahu berapa gaji mereka masing-masing dan kami masih membantu mereka setiap bulan. Belum ada tanda-tanda perbaikan keuangan di rumah mereka, tetapi sekarang mereka malah membeli mobil.
Selain sedikit merasa dibohongi karena telah “meminjamkan” uang dari waktu ke waktu, ini juga soal prioritas yang tidak pada tempatnya. Saya juga suka berbelanja, jadi saya bukan dalam posisi menghakimi orang-orang yang ingin menikmati sesuatu sebagai pelarian. Saya tahu bagaimana rasanya tumbuh besar dengan sedikit uang, sehingga menyenangkan rasanya memiliki uang sendiri untuk membeli barang yang kita sukai. Tetapi yang saya maksud adalah pakaian, sepatu, atau tas, bukan mobil berharga seratus juta lebih yang tidak mampu kita beli.
Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Mereka membeli mobil, dan setelah kurang dari setahun, mereka tidak dapat membayar cicilan sehingga agen harus mengambil kembali kendaraan itu. Kali ini saya merasa situasinya tidak akan berbeda, meskipun saya berharap saya salah.
Adik ipar saya kemudian mengatakan bahwa ayah mertuanya turut menyumbang uang untuk mobil itu. Namun, bukankah seharusnya uang itu dialokasikan untuk penggunaan yang lebih baik, seperti tabungan, atau asuransi, atau membayar utang kartu kredit? Dan mereka bisa membeli mobil keluarga yang murah, tapi tentu saja mereka membawa pulang mobil Jepang kelas menengah yang jauh lebih mahal.
Waktu pembelian kendaraan ini juga sedikit mencurigakan. Lebaran adalah saatnya bagi banyak orang untuk mudik, sambil memamerkan kekayaan mereka terlepas dari bagaimana mereka mendapatkannya, dan diharapkan menghujani sanak saudara dengan hadiah uang tunai. Datang ke pertemuan keluarga dengan mobil sendiri, terutama yang baru dan mengilap, pasti berbeda dibandingkan diantar taksi atau ojek.
Selama pertemuan keluarga, setelah pertanyaan-pertanyaan menjengkelkan yang biasa dilontarkan seperti kapan akan menikah, kapan memiliki anak, kapan memiliki anak kedua, dan kenapa bertambah berat badan, biasanya pertanyaan yang menyusul adalah tentang harta benda.
“Kantormu di mana? Ke kantor naik mobil?” tanya seorang paman. Saya jawab, tidak, kami tidak punya mobil – pernyataan yang membuat alisnya terangkat. Bahkan ketika saya menjelaskan bahwa kami tidak suka mengemudi dalam lalu lintas Jakarta yang gila dan bahwa membeli mobil berarti hampir tidak menyisakan uang lagi di rekening bank kami untuk hal-hal lain yang kami sukai seperti melancong, ia memandang saya dengan tatapan bingung sekaligus kasihan.
“Hai, masih kerja untuk menteri perdagangan?” tanya seorang sepupu, mengacu pada pekerjaan saya bertahun-tahun silam, satu-satunya pekerjaan saya yang dia ingat dan peduli untuk tanyakan.
Percakapan kemudian beralih ke topik kegemaran para sepuh, termasuk ayah saya, yakni kisah sepupu saya yang lain, seorang pejabat pemerintahan yang sangat kaya. Semua orang dalam keluarga besar menghormatinya dan memuja-mujanya. Tidak ada yang mempertanyakan bagaimana ia bisa menjadi sangat makmur hingga dapat membeli rumah orang tua saya dengan uang tunai hampir Rp 2 miliar.
Dari waktu ke waktu kami mendengar kabar tentang sepupu yang sangat kaya tersebut dari ayah saya, yang berseri-seri dengan bangga dan tidak dapat menyembunyikan ekspresi “mengapa anak saya tidak bisa menjadi sekaya itu” di wajahnya. Saya dan kakak saya hanya bisa mengertakkan gigi kami dan berharap dengan dengki agar sepupu tersebut diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bosan dengan dangkalnya percakapan selama pertemuan keluarga, saya beralih ke ponsel dan mendapati sahabat saya sejak SMP mengirim foto yang diambil dari grup Whatsapp alumni SMP kami (yang tidak saya ikuti karena level banalitas yang sama, tapi itu nanti saja, untuk artikel lain).
Teman-teman kami kelihatannya mengadakan reuni kecil dan mereka berpose bersama seorang wali kota yang kebetulan satu angkatan dengan kami. Dia berasal dari dinasti politik yang anggotanya memegang begitu banyak posisi publik, dan beberapa dari mereka kini berada di penjara karena menimbun kekayaan secara tidak sah. Saya bingung dan kesal. Mengapa teman-teman saya begitu bersemangat untuk berfoto bersama dengannya? Apakah mereka pikir dia adalah definisi kesuksesan? Karena dia tentu tidak mendapatkan posisi tersebut melalui meritokrasi. Apakah mereka pikir dia adalah korban yang polos tak berdosa dan tidak menyadari skandal keuangan yang keluarganya hadapi?
Ini adalah salah satu faktor mengapa korupsi tetap ada. Alih-alih memberikan sanksi sosial untuk mempermalukan para koruptor dan mencegah orang-orang menyalahgunakan kekuasaan mereka serta menggelapkan uang, kita menempatkan para pelaku pada singgasana. Alih-alih mengajarkan anak-anak mengenai kesederhanaan dan kejujuran, kita mengajarkan mereka bahwa definisi kesuksesan diukur oleh kekayaan dan kita mendorong mereka untuk membalas jasa orang tua dengan menjadi “seseorang” yang memiliki banyak uang. Alih-alih memerangi budaya feodalistis dan materialistis yang dianut generasi orang tua kita, kita sebagai kaum muda justru patuh pada norma-norma tersebut.
Kita melihat ke negara-negara maju dan sangat ingin meniru mereka, tetapi hanya pada permukaan saja. Jika kita tidak belajar menyerap nilai-nilai egalitarianisme, kerendahan hati, dan keadilan sosial, kita akan terus terjebak dalam lubang yang sama.

Bangsa dengan Keragaman yang Semu (Kata Ayunda)
Di tempat saya dibesarkan sebelum kami pindah ke kota Malang, 17 Agustusan selalu menjadi perayaan besar dan sangat ditunggu-tunggu. Sekolah dan masyarakat menggelar marching band, pertunjukan tari tradisional, dan parade kostum di jalanan yang biasanya berlangsung selama enam jam.
Saya berumur enam tahun ketika saya mengenakan kostum rumbai hijau dan ikat kepala yang hijau pula, lengkap dengan bulu burung. Itu seharusnya pakaian tradisional Papua. Beberapa teman saya mengenakan berbagai pakaian pernikahan tradisional, anak laki-laki dan perempuan duduk berpasangan dengan becak alih-alih berjalan, dan tersenyum seperti pengantin betulan.
Saat itu mungkin pertama kalinya saya diperkenalkan dengan konsep keberagaman, bahwa Indonesia terdiri dari orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional yang berbeda-beda, dan tinggal di tempat yang berbeda-beda pula.
Di sekolah dasar, saya bergabung dengan kelompok tari tradisional untuk perayaan 17 Agustus. Kami berdandan seperti orang Madura dan melakukan tarian daerah tersebut, menempuh jarak lebih dari 10 kilometer mengenakan bakiak. Saya tidak hanya belajar rutinitas tarian, saya juga menghafal lagunya (meski saya tidak pernah diberitahu apa arti lagu tersebut).
Itu mungkin pembelajaran kedua saya terhadap keberagaman: Orang-orang di Indonesia memiliki tarian dan lagu-lagu daerah yang berbeda-beda.
Namun apakah hanya ini yang kita sebut “merayakan keberagaman” di Indonesia? Mengenakan kostum pernikahan tradisional, melakukan tarian tradisional, menyanyikan lagu-lagu tradisional? Apakah “kesatuan dalam keberagaman” hanya soal mengetahui apa yang dipakai atau dipertunjukkan dalam tarian atau nyanyian masyarakat kita?
Awal tahun ini, ketika saya sedang pulang ke Malang, keluarga besar saya berencana pergi ke pantai. Percaya atau tidak, saya adalah satu-satunya perempuan dalam keluarga besar berisikan 28 anggota yang tidak memakai jilbab setiap hari. Semua bibi dan sepupu yang lebih muda (saya cucu tertua) mengenakan jilbab (beberapa di antaranya dipaksa oleh ayah mereka).
Saat saya sedang berkemas-kemas, Ibu masuk ke kamar untuk mencari tahu apa yang akan saya kenakan di pantai nanti.
Tentu saja, dia sudah tahu bahwa saya akan memakai celana pendek, jadi dia berkata, “Jangan berani-berani pakai itu! Semua keluarga kita sepenuhnya tertutup. Pakai celana panjang ini!”
Saya pun mengenakan celana panjang dan tidak bisa berenang karena bahannya terlalu tebal dan semua pasir masuk, membuat kaki saya terlihat seperti bantal kembar.
Pada kesempatan lain, saat liburan kemarin saya dan ibu saya berencana untuk memakai pakaian senada untuk menghadiri seminar ayah saya. Dia berkata, “Ayah mau kamu pakai jilbab selama seminar.” Dia tahu saya tidak akan menyukainya.
“Kenapa?” tanya saya.
“Ya dia bilang sebagian besar perempuan di universitas itu pakai jilbab, meskipun itu bukan universitas Islam.”
“Terus?”
“Yah, anggap saja ini pakaian sopan,” ujarnya mencoba meyakinkan saya.
“Aku akan pakai rok batik panjang dan kebaya kutubaru lengan panjang, itu masih kurang sopan?”
Ibu tak menjawab, tapi tetap membelikan saya jilbab.
Mungkin itulah perbedaan saya dengan generasi ibu saya. Ibu percaya dengan gagasan komunitas dan keterhubungan. Ia selalu ingin menyesuaikan diri dengan yang lain agar nampak dekat, sama, dan selaras, sementara saya tidak. Saya percaya bahwa setiap orang berbeda, dan saya menghargai orang-orang yang mempertahankan kesadaran akan diri, identitas, dan individualitas mereka. Dan yang paling penting, saya percaya bahwa saya tak harus selalu menyesuaikan diri sepanjang waktu.
Saya juga menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa ketika saya mengenakan kostum Papua untuk Pawai Hari Kemerdekaan pada waktu saya kecil.
Pada tahun 70-an pemerintah memulai operasi anti-koteka. Mereka memberikan baju dan celana panjang yang akhirnya membuat orang Papua terkena penyakit kulit, karena mereka tidak terbiasa mencuci pakaian secara teratur. Pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meratifikasi rancangan undang-undang anti-pornografi yang memiliki dampak besar pada budaya pakaian tradisional di Indonesia, termasuk koteka dan perempuan-perempuan suku asli yang bertelanjang dada.
Dan terlepas dari apa yang acara TV selalu sampaikan, bahwa kita semua hidup dalam harmoni selayaknya kita menari secara selaras di panggung yang sama, pada kenyataannya, bahkan setelah 71 perayaan Hari Kemerdekaan, kita belum benar-benar belajar untuk melindungi kelompok minoritas dan populasi yang rentan. Kita belum benar-benar belajar cara menjadi beragam.
Keberagaman bukan hanya tentang mengetahui apa yang orang pakai, bagaimana penampilan mereka, dari mana mereka berasal. Keberagaman adalah tentang menghormati keyakinan mereka, tradisi mereka dan nilai-nilai mereka. “Kesatuan dalam keberagaman” bukan tentang membuat orang lain berpakaian dengan cara yang sama, berpikir dengan cara yang sama, berdoa dengan cara yang sama. Ini soal memiliki sikap untuk menerima dan menghormati perbedaan, kesediaan untuk berbincang dan memahami kebutuhan satu sama lain.
Menjadi orang Indonesia seringkali berarti kita dipaksa masuk ke dalam kotak – apa etnis Anda, agama mana yang Anda percayai dari keenam agama resmi, apakah Anda seorang “laki-laki” atau “perempuan”. Mereka yang memercayai keyakinan tradisional adalah kafir dan dengan demikian tidak mendapat perlindungan dari negara. Mereka yang mengidentifikasi diri mereka bukan laki-laki atau perempuan, dan menyebut diri mereka bissu, calalai, atau waria, tidak layak mendapat tempat di masyarakat. Dan mereka yang tidak percaya heteronormativitas adalah ancaman serius bagi bangsa.
Jika Anda tidak cukup punya privilese, menjadi orang Indonesia sering kali berarti tidak mampu menjadi diri Anda yang sebenarnya, karena mayoritas yang tak toleran memiliki kebiasaan memaksakan nilai-nilai dan keyakinan mereka pada orang lain, bahkan tidak jarang dengan paksaan dan kekerasan.
Namun perubahan bukanlah tidak mungkin jika kita menginginkannya dengan sangat.
Tulisan-tulisan ini merupakan catatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 pada 2016, yang diterjemahkan dari versi aslinya dalam bahasa Inggris oleh Radhiyya Indra.