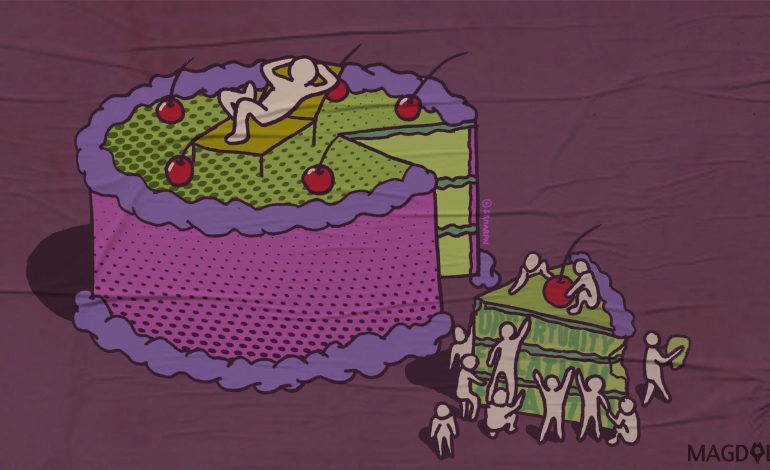Apa yang Terjadi Ketika Kamu Jadi Korban Pelecehan Seksual di Luar Negeri?

Butuh banyak waktu untuk menulis ini. Salah satu yang menghambat proses menulis itu adalah respons yang saya terima pasca-menyuarakan kejadian traumatis tersebut.
Pada Desember 2019, saya mengalami kekerasan seksual di New Delhi. Seperti mimpi buruk yang terus berulang di kepala, saya kebingungan langkah apa yang harus diambil berikutnya. Saya menceritakan hal ini pada rekan-rekan sesama mahasiswa, tapi alih-alih membuat saya aman, mereka datang hanya karena mau kepo. Seolah hendak mencari tahu, “mana, sih anaknya yang katanya dilecehkan?”
Tak ada empati terhadap penyintas seperti saya. Padahal efek yang saya rasakan setelah kejadian ini tak main-main: Saya tak bisa keluar kamar selama beberapa minggu. Saya juga tak bisa bicara pada orang lain tanpa menangis.
Selepas nama saya jadi perbincangan, berbagai notifikasi masuk melalui whatsApp namun sekedar minta saya menceritakan ulang. Lagi dan lagi, lengkap dengan beberapa komentar, “kenapa kamu tidak melawan?” atau “harusnya kamu pukul saja pelakunya!” Respons itu benar-benar membingungkan bagi saya.
Tak hanya itu, mereka juga menyalahkan cara saya berpakaian. “Ah, kalau anak-anak di sini, sih baik-baik, makanya mereka tidak pernah dilecehkan.” Sungguh bukan hal yang ingin saya dengar waktu itu. Terlebih lagi komentar itu terlontar dari pihak-pihak yang punya kapasitas untuk mendampingi warga negara Indonesia di masa krisis.
Ujung-ujungnya saya hanya jadi buah bibir, “si mahasiswa yang bermasalah” perlu untuk pendampingan yang bisa memperbaiki dia menjadi “perempuan yang baik-baik.” Saya meringkuk memeluk lutut dalam segala ketakutan ini, kenapa bisa selepas saya bercerita, segala hal semakin menjadi buruk?
India sendiri merupakan negara dengan tingkat kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender cukup tinggi. Sejujurnya ini sudah saya ketahui sejak sebelum menjadi mahasiswa di sana. Terlebih lagi di New Delhi, ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis di mana ketimpangan struktural selalu dibarengi dengan momok pemerkosaan.
Karena fakta itu, saya pernah ingin mengurungkan niat melanjutkan studi di sana dan hidup sendirian. Namun, setelah saya pikir-pikir lagi, saya harus berani.
Baca juga: Memahami ‘Consent’ Lebih Jauh untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual
Sistem yang (tidak) Berpihak pada Penyintas
Apa makna dari keberpihakan pada penyintas? Artinya dalam proses pelaporan, identitas penyintas dilindungi, pun diberi ruang aman. Dalam konteks ini, kekerasan seksual bukan aib ataupun cerita seru yang bisa jadi bahan obrolan lucu-lucuan dengan rekan-rekan. Sayangnya, tak semua rekan-rekan saya termasuk di organisasi mahasiswa luar negeri, begitu juga institusi perwakilan negara Indonesia di India, memahami ini.
Kalau sudah begini, standard operating procedure (SOP) kekerasan seksual menjadi mutlak dibutuhkan. SOP ini juga harus mampu memastikan, para korban mendapat perlindungan dan pendampingan, baik secara legal dan psikis. Apalagi mengingat penyintas akan berada di kondisi yang rentan, terasing sendiri di negeri orang tanpa kerabat atau keluarga.
Baca juga: Jangan Biarkan Korban Pelecehan Seksual Diam
Buat saya sendiri, solusi dari tingginya tingkat kekerasan seksual di India bukanlah dengan menyerukan “jangan berangkat sendirian ke luar negeri.” Sebab, jika pesan itu saja yang direpetisi, maka kita mewajarkan kekerasan seksual ini sendiri. Bahwa kekerasan adalah konsekuensi logis yang harus diterima khususnya oleh perempuan jika ia memilih belajar di luar negeri.
Baca juga: Mengenal Definisi Pencabulan, Pelecehan Seksual, dan Pemerkosaan
Sudah saatnya para penyintas seperti saya tak direviktimisasi. Ia harus dilihat sebagai subjek yang perlu dibantu supaya lebih berdaya setelah diteror para pelaku kekerasan. Akhir kata, saya menulis ini bukan untuk mengasihani diri dan pasrah akan keadaan. Ini adalah cara saya melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Artikel ini telah direvitalisasi pada 4 Maret 2024 untuk tujuan pendidikan.