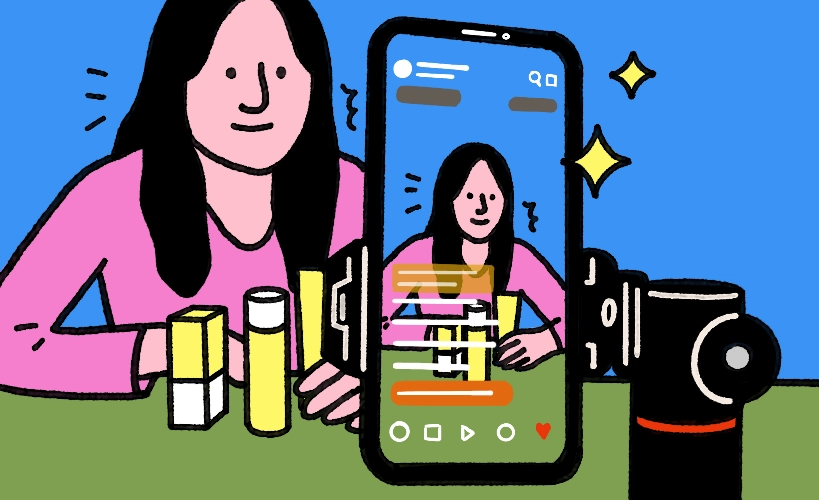Andai Lelaki Belajar dari Ayah yang Biarkan Anak Perempuannya Terbang

Saya lahir dan besar di Banda Aceh, dalam tradisi yang sarat religiusitas. Membaca Al-Qur’an selepas Magrib, jadwal belajar agama dengan mendatangkan seorang ustaz tiga kali seminggu, serta dendang pengantar tidur yang dilagukan Mama. Dalam masyarakat Aceh, seni tutur itu dikenal sebagai Do Da Idi, berisi puji pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, salawat kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, serta petuah seorang ibu kepada anaknya. Saya juga menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di madrasah.
Do Da Idi yang merekatkan hubungan saya dengan Mama tidak bertahan lama. Ketika saya tidak lagi tidur di buaian, dendang itu pun berhenti. Memasuki masa pubertas, saya menjadi sangat memberontak, keras kepala, dan hanya bisa dilunakkan dengan argumen yang masuk akal. Saya sulit menerima aturan yang ditegakkan Mama dengan alasan because I said so. Saya selalu menuntut penjelasan di balik larangan yang membatasi kebebasan, kreativitas, dan sering kali terasa tidak masuk akal.
Baca juga: Cuti Ayah Cuma 2 Hari: Bukti Nyata Bias Kita Soal Peran Orang Tua
Masa itu membuat Mama menyerahkan pengasuhan saya kepada Papa. Alasannya sederhana, ia tidak sanggup menghadapi pemberontakan remaja saya. Saat itu, saya menganggapnya sebagai anugerah. Papa dikenal sebagai sosok yang ditakuti saudara-saudara saya. Namun dengan Papa, saya bisa berdialog. Saya bisa membicarakan ambisi, pilihan, dan kegelisahan saya. Ia mendengarkan, mengamati, lalu merespons dengan tenang.
Dalam pengasuhan Papa, aktivisme saya tidak dikebiri. Ia mengikuti keterlibatan saya sejak SMA, dari organisasi sekolah hingga kerja kerja advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat La Kasspia The Institute for Social Political Studies. Ia juga mendukung keputusan saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Swiss, serta pilihan kuliah saya di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hubungan kami tidak selalu mulus. Banda Aceh pada akhir 1990-an berada dalam situasi rawan akibat konflik bersenjata. Papa sempat melarang keterlibatan saya dalam diskusi malam hari. Setelah perdebatan panjang, kami berkompromi. Saya boleh aktif dengan syarat keselamatan saya dijaga. Itu bukan kontrol, melainkan bentuk tanggung jawab.
Kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri adalah privilese langka. Papa yang mengantar dan menjemput saya ke Jakarta. Ia tidak pernah mengeluh.
Baca juga: Tujuh Bulan Berjalan, Bagaimana Peran GATI sebagai Gerakan Nasional?
Menjelang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, Papa menanyakan rencana kuliah saya. Ia tidak memaksa. Ia meminta saya berpikir, menyusun proposal, dan mempertanggungjawabkan pilihan. Ketika saya diterima di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ia menyetujuinya tanpa drama.
Kompromi itu meninggalkan jejak panjang dalam hidup saya. Papa membuktikan bahwa figur ayah tidak harus menjadi algojo patriarki. Ia hadir sebagai mitra berpikir.
Tsunami 26 Desember 2004 merenggut Papa dari hidup saya. Saya kehilangan penopang finansial sekaligus satu satunya figur yang selalu membela saya ketika keluarga bertanya kapan saya akan menikah. Jawaban Papa selalu sama, “Icha hanya ingin sekolah setinggi mungkin.”
Janji untuk lulus gemilang menjadi alasan saya bertahan hidup. Saya menyelesaikan kuliah dengan predikat cumlaude dan menjadi lulusan tercepat.
Baca juga: Dari bapak2ID Kita Belajar, Menjadi Bapak Tak Harus Kaku dan Absen di Rumah
Ayah, Patriarki, dan Hak Anak Perempuan untuk Memilih
Salah satu kenangan Papa yang tersisa adalah Honda C70 tahun 1979. Kereta itu saya temukan tertimbun reruntuhan di Gampong Jawa. Sejak 2014, motor itu resmi atas nama saya. Ia bukan sekadar benda, melainkan simbol kesederhanaan dan keteguhan Papa.
Cinta Papa tidak bersyarat. Ia mengenalkan saya pada dunia pikiran, disiplin, dan petualangan. Ia tidak mematahkan sayap saya. Ia menambahkan bulu agar saya terbang lebih tinggi.
Butuh tiga generasi bagi keluarga kami menghentikan praktik perkawinan anak. Papa menetapkan satu aturan sederhana. Anak boleh menikah setelah menyelesaikan sarjana. Di Aceh yang kerap dicap patriarkal, keputusan itu bersifat politis. Ia melawan tradisi fatherless yang sering bersembunyi di balik otoritas laki laki.
My father gave me the greatest gift anyone could give another person. He believed in me.
Setiap ingatan tentang Papa selalu datang dengan mata basah dan dada yang penuh. Ia mengajarkan bahwa ayah bukan sekadar kepala keluarga, melainkan penjaga kemungkinan. Andai lebih banyak lelaki belajar dari ayah seperti Papa, mungkin lebih banyak perempuan bisa terbang tanpa rasa bersalah.
Mirisa Hasfaria merupakan lulusan Magister Ilmu Politik dari University of Arkansas Fayetteville Amerika Serikat. Ia memiliki minat mendalam pada isu kesetaraan gender. Tulisan ini dipersembahkan untuk Papa Amir Syarifuddin bin Ben Dadeh, yang hilang dalam tsunami 26 Desember 2004.