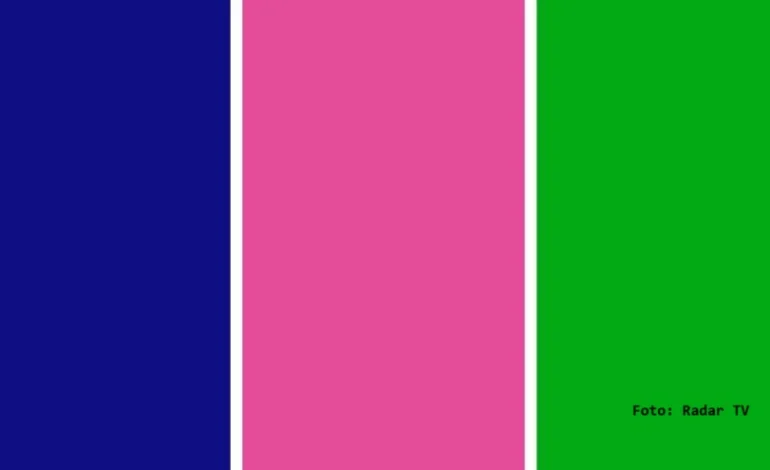Apa itu Darurat Militer dan Kenapa Bisa Ancam Masyarakat Sipil?

Belakangan, isu darurat militer kembali mencuat di tengah eskalasi demonstrasi yang terus meluas di berbagai kota sejak (25/8). Gelombang protes dipicu bukan hanya oleh kenaikan tunjangan dan pernyataan kontroversial anggota DPR, tetapi juga kematian tragis Affan Kurniawan—pengemudi ojek daring yang dilindas mobil taktis Brigade Mobil (Brimob) saat aksi berlangsung.
Darurat militer sendiri berarti militer mengambil alih sepenuhnya urusan sipil. Dalam situasi ini, militer bukan hanya mengamankan jalanan, melainkan menjadi penguasa tertinggi yang menentukan arah pemerintahan sementara. Mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Aturan lawas ini membuka ruang pemberlakuan darurat militer ketika aparat sipil dianggap tak lagi mampu menjaga ketertiban.
Konsekuensinya sangat luas. Pergerakan orang, barang, hingga komunikasi berada di bawah pengawasan militer. Keluar-masuk daerah bisa dibatasi lewat pos pemeriksaan, dan warga harus selalu membawa identitas diri agar tak dicurigai lalu ditangkap. Militer berhak memaksa seseorang tinggal di satu tempat, melarang bepergian, bahkan mengusir dari daerah tertentu. Perusahaan, hasil panen, kendaraan, hingga gedung bisa diambil alih dengan alasan mendukung operasi.
Baca Juga: Kita Adalah Affan: Potret Buram Kekerasan Negara dan Ekonomi yang Menjerat
Kebebasan informasi pun akan terpangkas habis. Surat kabar, siaran radio, hingga unggahan di media sosial wajib melewati sensor. Konten yang dianggap mengganggu ketertiban bisa langsung diblokir, media bisa dibredel sewaktu-waktu.
Yang paling mencemaskan adalah penangkapan tanpa proses pengadilan. Perppu memungkinkan seseorang ditahan 20 hari hanya atas dasar kecurigaan, lalu diperpanjang hingga 50 hari dengan izin pusat. Tanpa mekanisme kontrol sipil, siapa pun bisa kehilangan kebebasannya kapan saja, tanpa perlindungan hukum yang jelas.
Indonesia sendiri sudah punya pengalaman pahit dengan kebijakan ini. Saat itu, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan darurat militer melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003, dengan alasan mengatasi konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Namun yang terjadi, ribuan warga sipil setempat justru jadi korban. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pembatasan mobilitas. Setelahnya adalah cerita tentang penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembatasan kebebasan pers. Pengalaman Aceh menjadi peringatan keras: Ketika militer diberi wewenang absolut, masyarakat sipil jadi yang paling rentan dikorbankan.
Baca juga: Presiden Prabowo Minta TNI-Polri Ambil “Langkah Tegas Tindakan Anarkis”
Enggak cuma itu, media lokal dan nasional yang meliput Aceh selama darurat militer, beroperasi di bawah bayang-bayang sensor dan intimidasi. Menurut laporan Human Rights Watch, pemerintah saat itu menerapkan blackout informasi. Media dilarang mendistribusikan laporan kritis, jurnalis lokal bahkan ditahan atau diserang saat meliput keadaan lapangan.
Committee to Protect Journalist juga mencatat, militer memerintahkan media untuk tidak menyiarkan pernyataan pihak GAM dan mempromosikan semangat nasionalisme saja. Bahkan media seperti Metro TV dan Serambi Indonesia mendapat peringatan karena dianggap berpihak pada GAM.
Bahkan, jurnalis ditempatkan di bawah pengawasan ketat, dan dipaksa meliput bersama militer, memakai seragam, atau dilarang meliput secara bebas. Human Rights Watch juga melaporkan seorang reporter Radio Ramako dipukuli oleh Kopassus hanya karena meliput operasi militer di sebuah desa.
Dampak paling terasa adalah maraknya pelanggaran HAM, kepada mereka yang dicurigai “simpatisan” GAM. Berdasarkan laporan Komnas HAM, Tim Ad Hoc Aceh mencatat setidaknya 70 kasus pelanggaran HAM selama darurat militer. Temuan ini mencakup penahanan sewenang-wenang (9 kasus), penyiksaan (16), penghilangan paksa (6), perlakuan tidak manusiawi (30), pelecehan seksual atau pemerkosaan (9), pengusiran atau pengungsian internal (8), pembunuhan di luar hukum (19), serta tindakan kekerasan lain seperti penyerangan membabi-buta dan perusakan properti.
Sementara itu KontraS Aceh mendata, terjadi 1.326 peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat sipil, meliputi pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual hingga penghilangan paksa.
Baca juga: Dari Medan hingga Solo: Buntut Kematian Affan, Gelombang Aksi Meluas ke Berbagai Kota
Bagaimana Jika Diterapkan Hari ini?
Situasi di Aceh pada tahun 2003 memberikan gambaran jelas tentang betapa berbahayanya penerapan darurat militer bagi masyarakat sipil. Jika kondisi serupa diterapkan kembali hari ini, dampaknya bisa jauh lebih buruk. Ini mengingat eskalasi kekerasan yang semakin meningkat dalam menanggapi demonstrasi.
Apalagi dengan Pernyataan Presiden Prabowo yang meminta aparat kepolisian menindak tegas massa yang dianggap “anarkis”, dikhawatirkan semakin memudahkan aparat merepresi warga.
Data terbaru dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, selama periode 25–31 Agustus 2025, setidaknya 10 orang tewas, 1.042 terluka, dan 3.337 ditangkap dalam aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. YLBHI menilai naiknya eskalasi kekerasan dan brutalitas aparat di lapangan adalah imbas langsung dari perintah tersebut.
Karena itu, dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi pihak tertentu yang dapat mendorong penerapan kondisi darurat militer. Pengawasan ketat terhadap tindakan aparat ketika berhadapan dengan masyarakat sipil juga penting dilakukan.
Pasalnya, tidak jarang kerusuhan yang terjadi justru dipicu atau diperparah oleh oknum tertentu, dan tidak berasal dari massa aksi. Dengan pengawasan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, risiko pelanggaran HAM dapat diminimalkan, sekaligus menjaga agar hak-hak sipil tetap terlindungi.