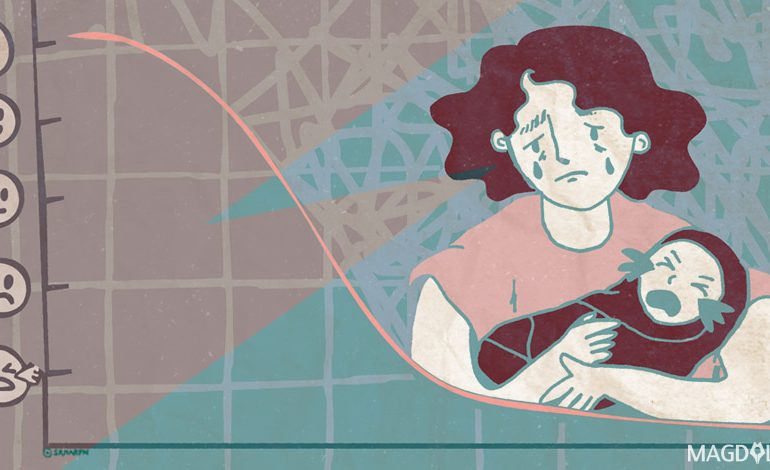Banjir di Sumatera Utara: Ketika ‘Apa Kabar?’ Datang Terlambat

Air naik sampai lutut. Listrik padam. Telepon menyala hanya untuk urusan paling mendesak: kabar soal posko, kebutuhan, jalur bantuan. Dalam banjir yang melanda sebagian Sumatera Utara ini, saya tiba-tiba berada di dua posisi sekaligus: penghubung bantuan dan korban.
Biasanya saya orang yang diminta memberi kabar—menjelaskan situasi, menghubungkan donasi, dan memastikan siapa yang sudah tertolong. Tapi kali ini saya sendiri kehabisan air bersih, membersihkan lumpur, dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Dari benturan peran itu saya belajar sesuatu yang sederhana tapi berat, bahwa “apa kabar” bisa datang terlambat—baik sebagai pesan pribadi, maupun sebagai distribusi bantuan.
Beberapa hari setelah banjir, pesan mulai masuk: “Kamu apa kabar? Apakah baik-baik saja?” Saya merasa hangat. Saya pun menanyakan hal yang sama kepada kawan-kawan yang tinggal di lokasi terdampak bencana. Dalam krisis, kita tidak hanya butuh logistik, tetapi juga satu kalimat yang membuat tubuh merasa tidak sendirian. Namun pertanyaan itu, kali ini, terasa datang setelah semuanya keburu menumpuk.
Bukan karena orang tidak peduli. Hidup hanya mendadak menyempit menjadi daftar panik: aman, air bersih, pangan, anak, obat, listrik, membersihkan lumpur. Dalam keadaan seperti itu, “tanya kabar” kalah oleh yang lebih mendesak dan oleh asumsi diam-diam: pasti sudah ada yang menanyakan.
Keterlambatan itu ternyata bukan hanya soal pesan pribadi. Ia juga terjadi pada solidaritas.
Baca Juga: Bencana Sumatera Bukan Panggung Hiburan, Setop jadi ‘Performative Government’
Ketika bantuan mengikuti peta paling parah
Saya ikut mengarahkan donasi ke wilayah yang paling parah. Secara moral terasa benar, kita melakukan semacam triase. Dari jaringan kami, kabar paling keras datang dari Kabupaten Langkat. Donatur saya hubungkan langsung dengan relawan di lapangan. Tapi keputusan itu menampar saya karena saya sempat melupakan tetangga sendiri di Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang juga terendam, hanya karena mereka tidak masuk peta “paling parah”.
Banjir mengajari saya satu hal yang pahit: solidaritas sering mengikuti peta yang paling terlihat. Yang paling parah menjadi ikon bencana dan memanggil bantuan lebih cepat. Sementara korban yang tidak “spektakuler” bisa menjadi korban yang terlambat terbaca. Rumah yang tergenang setinggi lutut sering dianggap tidak seberapa. Padahal bagi keluarga miskin, genangan setinggi itu bisa berarti hilangnya kerja harian, rusaknya stok pangan, putusnya obat rutin, dan munculnya utang kecil yang menahun.
Dalam dunia kemanusiaan, Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, mencatat adanya kesenjangan pendanaan antara keadaan darurat yang paling terlihat dan beragam “forgotten emergencies”—krisis yang tidak menarik perhatian, tetapi tetap memakan korban.
Ekonomi atensi: mengapa yang viral lebih cepat ditolong
Kita hidup di masa ketika bencana juga punya algoritma. Foto rumah ambruk dan video air bah lebih mudah menembus linimasa. Sementara kisah-kisah yang tak punya gambar dramatis cenderung tenggelam. Saya tidak sedang menyalahkan donatur atau relawan. Banyak orang memberi karena ingin cepat menolong. Yang sering bermasalah justru cara kita menata bantuan. Ketika pendataan dan distribusi lemah, bantuan bergerak mengikuti sorotan, bukan mengikuti kebutuhan. Akibatnya, ada wilayah yang kebanjiran bantuan, sementara titik lain menunggu lebih lama.
Saya baru benar-benar melihat ini ketika satu jaringan menawarkan donasi kecil khusus untuk komunitas HAPSARI, lalu kami mulai mendata siapa saja yang juga harus didukung. Dari pendataan itu, muncul kisah-kisah yang tidak viral tapi nyata. Ada yang meminta donasi sambil menggendong anak; ada yang sudah berutang pada tetangga; ada yang menyiasati hari-hari tanpa stok beras. Tidak ada yang “mencolok”, tetapi semuanya mendesak.
Di situ saya merasa malu sekaligus tercerahkan. Malu, karena saya tahu mereka ada dan saya sempat melewatkannya. Tercerahkan, karena saya melihat lebih jelas: bencana bukan hanya soal skala kerusakan, tetapi juga soal siapa yang terlihat dan siapa yang luput. Rasa malu ini, bagi saya, tidak perlu disembunyikan. Ia bisa menjadi energi untuk memperbaiki cara kita menolong: tidak hanya mengikuti peta paling parah, tetapi juga membuka telinga pada yang sunyi. Pada rumah-rumah yang tak sempat memanggil kamera, pada korban yang tak sempat menulis status.
Baca Juga: Dari Banjir ke Banjir, Kenapa Kita Masih Gagap Hadapi Bencana?
“Apa kabar?” sebagai jaring agar kita tidak jatuh terlalu jauh
Saya semakin percaya bahwa “Apa kabar?” bukan sekadar basa-basi. Ia adalah jaring sosial kecil yang menahan orang agar tidak jatuh terlalu jauh. Satu pesan singkat bisa mengingatkan kita: siapa yang perlu ditengok, siapa yang mungkin kekurangan, siapa yang sudah tidak sanggup meminta.
Masalahnya, cek kabar tidak bisa hanya mengandalkan niat baik. Ia butuh cara sederhana. Di komunitas, kita bisa membuat daftar cek kabar yang praktis: siapa lansia yang tinggal sendiri, siapa ibu menyusui, siapa keluarga tanpa kendaraan, siapa yang kehilangan kerja harian, siapa yang butuh obat rutin. Bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memastikan tidak ada yang terlambat dilihat. Cek kabar yang teratur membuat bantuan tidak selalu bergerak setelah ada unggahan yang ramai.
Di tingkat pemerintah, cek kabar seharusnya menjadi bagian dari layanan dasar saat bencana: bukan hanya membuka posko, tetapi memastikan data kebutuhan rumah tangga diperbarui dan dipakai untuk menyalurkan bantuan. Data yang baik membantu bantuan lebih tepat; data yang ceroboh bisa membahayakan. Di titik ini, “apa kabar” bukan hanya kalimat—ia perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan, sistem, dan pembagian tugas yang jelas.
Agar bantuan lebih adil, saya percaya kita perlu mengubah tiga refleks. Pertama, berhenti menunggu viral untuk bergerak dengan pendataan cepat yang tetap berjalan meski tanpa kamera. Kedua, memperlakukan organisasi akar rumput sebagai mitra sungguhan, bukan tenaga gratis yang baru dicari saat darurat. Ketiga, membiasakan distribusi berlapis. Bukan hanya ke episentrum, tetapi juga ke wilayah penyangga yang sering luput dari sorotan, agar penumpukan di satu titik tidak membuat titik lain kekurangan.
Banjir membuat saya sadar: solidaritas tidak cukup kalau hanya cepat. Ia juga harus adil. Dan mungkin, keadilan itu dimulai dari satu kalimat sederhana—“Apa kabar?”—yang tidak boleh datang terlambat.