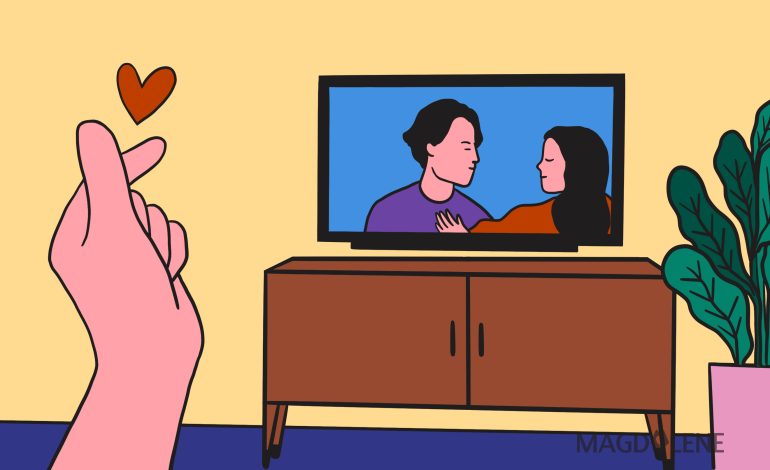Pesan-pesan Minta Bantuan dan Dilema Berbuat Baik Selama Pandemi

Assalamualaikum… Permisi, maaf melenceng, saya driver ojol yang pernah ngantarin paket ke Kakak, saya mau menjual TV saya berapa pun seikhlasnya untuk beli susu anak saya. Sudah seminggu keluarga saya hanya makan nasi dengan kecap dan Royco. Motor saya untuk mata pencaharian satu-satunya sudah ditarik oleh leasing. Saya sangat berharap di sini ada yang mau membeli TV saya…
Pesan tersebut masuk ke Whatsapp saya Juli lalu. Butuh beberapa menit bagi saya untuk menimbang-nimbang akan merespons pesan itu atau tidak. Pada akhirnya, saya membalas pesan orang itu dengan berkata saya tidak hendak membeli TV-nya, tetapi saya bisa menyumbang sedikit uang, setidaknya untuk mereka makan selama seminggu.
Kata-kata “makan nasi dengan kecap dan Royco” lah yang cukup menohok, sehingga akhirnya saya memilih tindakan tersebut. Saya lebih tergerak lagi karena membayangkan ada anak-anak kecil yang terpaksa makan sekadarnya karena keterbatasan orang tuanya. Dari situ saya menangkap jelas betapa beratnya hidup di ibu kota bagi orang-orang kelas menengah ke bawah.
Di waktu lain sebelum pandemi, ibu dengan bayi di jembatan penyeberangan daerah Kuningan, Jakarta Selatan hendak menjual sebuah gendongan kepada siapa saja yang lewat. Awalnya saya berlalu, tapi memang dasar pemilik hati marshmallow, saya yang saat itu tak membawa uang tunai di dompet, segera mencari ATM terdekat dan kembali kepada ibu itu untuk memberinya sedikit uang tanpa membeli gendongannya.
Pengalaman seperti ini saya yakin dialami juga oleh banyak orang lainnya. Setidaknya dari cerita pasangan saya, saya tahu dia pernah melakukan hal sejenis kepada orang asing yang ditemuinya di terminal bus beberapa tahun lalu. Ketika itu, orang tersebut memintanya uang untuk menyumbang ongkos pulang ke kampungnya karena ia sudah sudah tidak memegang cuan sepeser pun. Hal yang familier di telinga kita juga, bukan?
Mengapa Mau Memberi Uang ke Orang Asing?
Dalam kasus saya, tindakan memberi uang ke orang asing dilandasi beberapa “faktor X”. Jika bertemu langsung, saya menilai orang itu dulu dari bagaimana dia terlihat. Saya lebih abai pada laki-laki “berpenampilan preman” yang mengemis atau mengamen seorang diri dibanding pada orang yang membawa-bawa anak, terlebih perempuan. Bukannya saya seksis, tapi ada irisan pengalaman yang membuat saya lebih tergerak.
Dalam kasus saya, anak menjadi titik lemah saya. Dulu sebelum punya anak, saya tak secepat itu terdorong untuk memberi bantuan kepada orang-orang asing yang meminta uang dengan membawa-bawa anak. Kesamaan pengalaman yang memicu seseorang untuk membantu juga rupanya menjadi alasan pasangan saya membantu orang asing di terminal waktu itu.
“Ya karena saya pernah ada di posisi susah. Minta-minta bantuan teman dan ditolong,” kata pasangan saya. Sesederhana itu.
Namun, perbuatannya ini memang masuk akal. Sebagai manusia, sebagian orang percaya bahwa berbuat baik akan membuahkan hal baik pula di kemudian hari. Bisa juga ada semacam tanggung jawab moral atau “utang”, meski tidak berkaitan dengan si pemberi bantuan sebelumnya, untuk membantu sesama yang kesusahan atau “terlihat susah”.
Baca juga: Berburu Pahala, Mengejar Surga
Tak Selalu Mereka yang Minta Uang Dibantu
Omong-omong soal terlihat susah ini, banyak juga yang memilih tidak membantu orang asing yang meminta bantuan. Pasalnya, ada kecurigaan orang tersebut hanya menggunakan modus “terlihat susah” demi menipu targetnya.
Selain itu, di DKI Jakarta ada peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 yang memuat larangan orang menjadi pengemis dan memberi uang pada mereka. Hukuman untuk orang yang melanggar itu mulai dari 10 hingga 60 hari kurungan serta denda sebesar Rp100 ribu hingga Rp20 juta.
Soal orang yang sebenarnya tidak sesusah kelihatannya, ada satu berita menarik pada 2015 silam, di mana pengemis di Pasuruan, Jawa Timur, Ansori (77) disebutkan menjadi calon haji. Ansori sejak kecil sempat menggelandang, bekerja serabutan, hingga akhirnya pada 1980-an ia mulai mengemis. Uang hasil kerjanya itu ia kumpulkan sampai bisa melunasi ongkos naik haji.
Dari kisah Ansori ini, bisa dimengerti bila sebagian orang skeptis untuk menolong pengemis atau orang asing yang meminta-minta lewat pesan WhatsApp atau SMS. Barangkali, mereka saja masih mimpi bisa seperti Ansori dan harus banting tulang menghidupi keluarganya, sehingga terasa konyol untuk membantu orang asing.
Yang lebih membuat skeptis lagi, dalam artikel Tagar.id dibeberkan tentang sejumlah pengemis yang diketahui punya tabungan puluhan hingga ratusan juta, kartu kredit, mobil, tanah, dan rumah sampai dua lantai. Di Kalimantan Tengah, bahkan ada pengemis yang memanfaatkan kecacatan fisiknya untuk mendulang rezeki hingga akhirnya bisa mengendarai mobil sedan pribadi.
Peristiwa semacam ini membuat orang menakar ulang rasa iba terhadap kelompok tertentu. Seorang kawan saya, “Intan” menyatakan bahwa dirinya tidak akan menggubris bila ada orang asing mendatangi atau mengiriminya pesan meminta uang, sekalipun orang tersebut kelihatan perlu dikasihani.
“Pernah waktu itu ada anak kecil minta-minta di lampu merah waktu gue naik motor. Gue kasihan ngeliat dia panas-panasan, ada kayak luka-luka gitu di kakinya, enggak pakai sendal, dan dia bilang dia belum makan dari kemarin,” kisah Intan.
“Tapi beberapa hari berikutnya gue liat lagi ini anak, lagi nongkrong sama teman-temannya di bawah pohon sambil main hape. Besoknya, gue liat dia pake seragam dianter orang naik motor. Dari situ gue mulai males nanggepin anak yang ngemis.”
Intan menambahkan, kisah-kisah yang membuat iba hanyalah modus yang dipakai peminta-minta untuk menjalankan aksinya. Semakin lama, kisah-kisah itu berkembang dan makin membuat orang terenyuh.
Perkataan Intan itu sedikit banyak mempengaruhi saya sewaktu nomor yang sama pada pertengahan Agustus lalu mengirimi saya pesan sebagai berikut (yang tampaknya kali itu ditulis sang istri),
…Sekarang bayi aku sakit, badannya panas, pilek, batuk, muntah-muntah, mau periksa ke Puskesmas 5 ribu pun saya enggak pegang, jalannya jauh. Mau makan, beras abis, sampe-sampe aku minta nasi sisa dari tetangga, alesan buat bikin cireng. Padahal buat dijadiin bubur buat makan bersama keluarga. Kadang keluarga saya enggak pernah makan karena enggak punya apa-apa.
Aku keliling gendong anak buat nyari kerjaan, tapi tidak ada yang mau. Saya mau jual hp merek mito. Siapa tau di sini ada yang minat, berapa aja buat kebutuhan anak-anak soalnya pada nangis tahan laper.
Kali itu saya tidak merespons karena memang saya sedang tak punya uang lebih. Masih ada rasa iba yang muncul saat membaca pesan tersebut, tetapi kemudian tebersit pula pikiran, “Ini orang sudah dua kali minta bantuan saya [walau saya tahu pesan itu paling juga disebar ke banyak orang], bener enggak ya kalau saya nolong? Gimana kalau dia malah terus-terusan begini karena menganggap saya atau orang lain yang bantuin dia itu sumber rezeki instan?”
Baca juga: Berlomba-lomba dalam Kebaikan, Tapi Baik untuk Siapa?
Dilema Berempati Selama Pandemi
“Faktor X” lain yang mendorong saya membantu orang asing sekarang-sekarang ini adalah kondisi pandemi. Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan, alat utama dalam mata pencaharian (seperti cerita awal saya tadi), hingga akhirnya terpaksa menggunakan berbagai cara untuk mengisi perut, termasuk hal yang banyak orang anggap memalukan: meminta-minta.
Aksi solidaritas dari kawan-kawan kepada warga kurang mampu sudah menjamur di banyak daerah. Pemerintah pun sudah menggulirkan bantuan kepada warga kurang mampu. Lantas sebagai individu, ketika menghadapi langsung orang yang meminta bantuan saat pandemi ini, bagaimana kita seharusnya bereaksi? Perlukah kita menunjukkan empati dengan memberi uang langsung?
Tidak ada jawaban benar-salah secara hitam putih menurut saya. Memberi bantuan pada kondisi krisis seperti kini memang sungguh dilematis. Kita punya keterbatasan sendiri dalam memberi bantuan karena kita pun mungkin harus mempersiapkan dana darurat. Belum lagi sebagian dari kita mengalami penurunan pendapatan dan bisa saja terancam jadi pengangguran hingga akhirnya kita bisa ada di posisi orang asing yang meminta-minta tadi.
Di sisi lain, barangkali ada nyawa yang sedang di ujung tanduk saat seorang asing meminta bantuan kita. Entah karena terancam kelaparan atau terjangkit sakit, sementara bantuan dari pemerintah juga belum tentu mereka dapat karena mereka tidak punya penanda identitas. What if-what if ini yang membuat tindakan menolong sesama terasa wajar sekalipun seseorang serba pas-pasan. Walau sedikit saja bantuan yang bisa kita beri, bisa jadi itu cukup untuk mereka menyambung hidup, sehari demi sehari.