Budaya Diam Jadi Jalan Tol bagi ‘Deepfake’
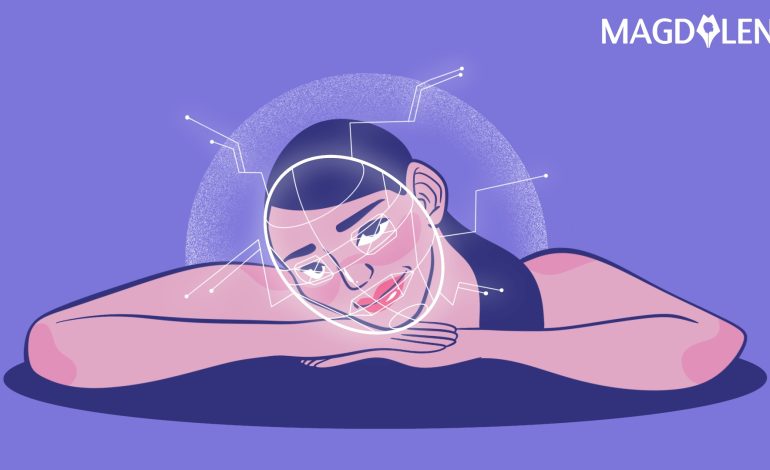
Langit sudah gelap, rumah sudah tenang. Istri saya sudah tidur di kamar. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menggulir lini masa seperti biasa, tanpa ekspektasi apa pun selain konten hiburan dan berita ringan.
Lalu sebuah berita membuat saya terhenyak. Bukan kabar dari luar negeri, bukan pula skandal selebritas. Ini dari Semarang. Seorang mahasiswa ditangkap karena membuat video deepfake pornografi.
Saya membaca judul lengkapnya. Ada satu kata yang membuat perut saya mulas: “akhirnya”. “Pelaku Deepfake Semarang Akhirnya Ditahan”.
Baca juga: Kerentanan Anak dari Ancaman Pelecehan Seksual Lewat Kecanggihan AI
Saya tidak lega. Sebaliknya, saya justru muak. Karena kata “akhirnya” itu adalah bukti terbesar dari kegagapan sistem kita. Dia tidak ditahan karena hukum proaktif melindungi korban. Dia ditahan setelah kasusnya viral. Dia ditahan setelah para siswa di sekolah itu berdemo. Dia ditahan karena kita semua berteriak.
Keadilan di negeri ini tidak datang seperti fajar. Keadilan harus dipaksa, ditarik, dan diteriakkan.
Saya teringat laporan Komnas Perempuan: mayoritas korban kekerasan digital justru mengalami reviktimisasi saat melapor. Mereka diinterogasi, diragukan, dan disudutkan. Dan malam itu saya sadar: marah saja tidak cukup. Karena kalau cukup, kita pasti sudah hidup di tempat yang lebih aman sejak lama.
Lalu saya menoleh ke arah kamar. Istri saya, wajah yang paling saya kenali di dunia, sedang tertidur pulas. Dan pikiran paling brutal itu muncul: “Bagaimana kalau ini terjadi pada dia?”
Sebagai suami, saya bisa berdiri di depannya kalau ada yang menyerang di jalan. Saya bisa pasang badan melawan preman. Tapi bagaimana melindunginya dari musuh yang terbuat dari algoritma? Musuh yang bisa mencuri wajahnya tanpa menyentuh tubuhnya? Musuh yang mungkin bukan anonim, tapi teman, tetangga, atau seseorang yang kami kenal?
Saya tak bisa mengandalkan sistem hukum yang baru bergerak setelah korban hancur dan viral.
Baca juga: Ancaman Deepfake: KBGO dan Gerak Perempuan yang Makin Rentan
Laki-laki jangan hanya diam
Sebuah teror lain muncul. Teror yang lebih dalam dan lebih menusuk. Saya muak pada sistem yang reaktif. Saya memang bukan pelaku, tapi bukankah saya juga pernah diam?
Saya pernah membiarkan stiker bertema pelecehan beredar di grup WhatsApp kantor. Saya pernah memilih tidak bersuara, padahal hati saya tidak setuju. Saya takut dibilang baperan, kaku, terlalu serius. Saya pernah tertawa kecil saat teman melontarkan lelucon seksis di warung kopi. Itu tawa basa-basi. Ketawa karier, cari aman. Tawa yang secara tidak sadar memberi restu.
Itulah solidaritas laki-laki yang diam-diam beracun: kita ingin diterima, ingin “nyambung”, tapi mengorbankan nurani.
Saya tidak menciptakan budaya itu, tapi saya menyiraminya. Mahasiswa di Semarang itu adalah bentuk paling ekstremnya. Tapi saya? Saya versi awalnya. Versi yang memilih tidak ikut campur. Versi yang diam-diam memperkuat norma yang sama.
Rasa bersalah dan rasa lumput itu berubah menjadi rasa takut. Saya masuk ke kamar anak saya. Ia tertidur pulas. Seorang anak perempuan kecil, polos, belum punya akun media sosial. Belum tahu seperti apa rasa malu yang tak bisa dihapus dari internet. Belum tahu bahwa wajahnya sendiri bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkannya suatu hari nanti.
Saya membetulkan selimutnya dan membayangkan hari ketika saya, mungkin dengan sedikit bangga, akan memberinya ponsel pertamanya. Dulu orang tua saya hanya berkata, “Jangan bicara dengan orang asing.” Musuhnya jelas. Sekarang? Nasihat apa yang cukup?
“Nak, jangan sembarangan posting foto?”
“Nak, wajahmu bisa dipalsukan dan digunakan untuk menghancurkan hidupmu?”
Baca juga: Kasus KBGO Masih Marak, Bukti Platform Medsos Belum Jadi Ruang Aman
Teknologi deepfake tidak sekadar menciptakan video palsu. Ia menciptakan generasi yang tumbuh dengan ketakutan pada wajahnya sendiri. Menciptakan trauma bahkan sebelum mereka tahu apa itu seksualitas atau harga diri. Wajah mereka, hari ini, bisa menjadi liabilitas.
Deepfake memang menakutkan. Tapi yang berbahaya juga adalah diamnya laki-laki yang merasa tidak bersalah karena tidak melakukan apa-apa.
Kita bilang peduli, tapi kita tidak bersuara. Kita mengaku bukan pelaku, tapi tidak ikut membongkar sistemnya. Kita mengaku bukan bagian dari masalah, tapi enggan jadi bagian dari solusi.
Kita tertawa saat candaan seksis dilempar. Kita diam saat pelecehan diremehkan. Kita ikut menjaga suasana, agar nyaman—bagi siapa?
Kita adalah fondasi dari bangunan yang kini kita sendiri benci.
Dan mungkin itulah dosa kita yang paling dalam: merasa baik hanya karena tidak ikut menyakiti, padahal kita juga tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya.
Akhmad Yunus Vixroni adalah pengemudi taksi online yang selalu sayang istri.






















