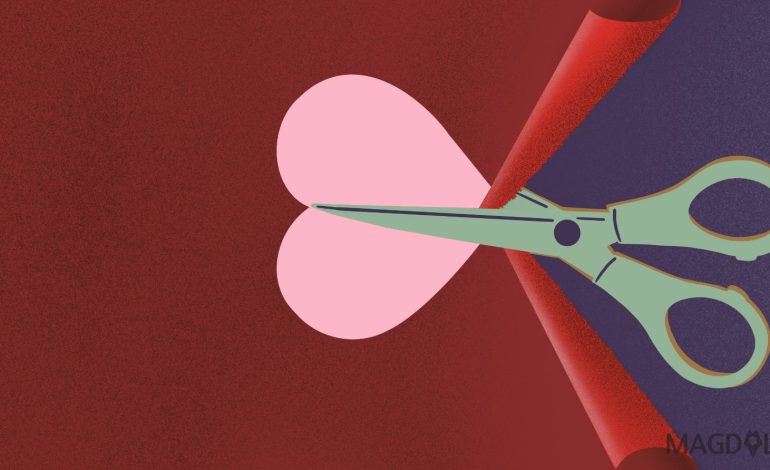Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian I)
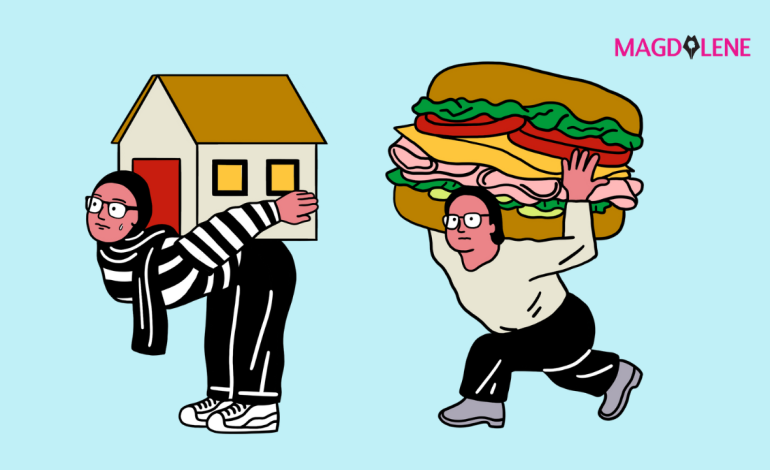
Kami mengikuti empat perempuan Milenial Jabodetabek dengan latar belakang berbeda. Ada yang generasi sandwich, tulang punggung keluarga, lajang tanpa anak, dan menikah tapi childfree. Ketika dunia mulai beralih membahas kebutuhan Generasi Z dan Alfa, masalah hidup Milenial ternyata belum selesai. Andini, Nandira, Eka, dan Caca tentu saja tidak merepresentasikan seluruh Milenial.
________
Generasi Penopang Orang Tua
“Andini” sampai di rumah pukul 9 malam. Anak bontotnya, bayi 18 bulan, langsung menghampiri minta digendong. Anak tengah yang kelas dua SD mengaduh minta makan. Sementara si sulung minta bantuan menyiapkan peralatan sekolah untuk hari ketiga ospek SMP.
Ia sempat menuju dapur, meletakan kantong kresek berisi bahan makanan yang dibeli di pasar. “Tunggu ya, aku mau makan, mandi, sama nidurin anak dulu. Nanti kita ngobrol sambil aku nyiapin bahan masakan besok,” ujar Andini pada kami.
Siang hari, anak-anak Andini dijaga ibunya. Mereka tinggal serumah di bangunan seluas 80 persegi meter: Andini, suami, ketiga anak mereka, dan kedua orang tuanya. Ia dan suami menanggung seluruh kebutuhan hidup—keperluan sehari-hari, perawatan rumah, biaya sekolah anak, uang bulanan orang tua, gaji pekerja rumah tangga (PRT), hingga cicilan kredit pemilikan rumah (KPR). Jika ditotal, pengeluarannya berkisar Rp15 juta per bulan.
Sejak menikah pada 2011, hidup begini sudah tergambar di benak Andini: Tinggal bersama anak dan orang tua sambil mencicil KPR. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, ia merasa bertanggung jawab mengurus orang tua. Terlebih, ayah Andini adalah pensiunan dan penyintas stroke.

Sebelum pensiun, ayah Andini bekerja di perusahaan swasta. Sedangkan ibunya, ibu rumah tangga. Dari Andini kecil hingga menikah, mereka menempati rumah dinas angkatan darat di bilangan Jakarta Timur, yang dipinjamkan untuk kakek dan nenek Andini. “Orang tuaku nggak punya rumah sendiri ataupun dana pensiun. Paling ibu ada sedikit (tabungan). Makanya aku dan adikku yang nopang,” tutur Andini.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), orang tua Andini termasuk 35,93 persen lansia yang tinggal dengan tiga generasi: Anak, menantu, dan cucu. Biasanya, karena kondisi lansia rentan dan perlu didampingi anggota keluarga.
Baca Juga: Bangga Jadi Milenial dengan “Cuan” yang Biasa-biasa Saja
Milenial, mereka yang menurut BPS lahir pada 1981-1996, sering disebut sebagai generasi pemalas. Media bahkan menyebutnya anak tiri masyarakat yang terbuang, generasi tertinggal, atau generasi kacau. Pasalnya, mereka dianggap melek teknologi, hak kesehatan mental, dan isu kemanusiaan, tapi malas bekerja, dan tidak pintar mengelola keuangan. Namun, narasi di media sering kali bias kelas. Cerita-cerita tentang milenial misalnya tak menangkap fenomena bahwa mereka punya tanggungan berat, semisal harus menopang orang tua, harga hunian dan inflasi biaya hidup yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, atau solusi pemerintah yang sering kali tak tepat sasaran.
Andini termasuk milenial golongan penopang orang tua, atau populer disebut generasi sandwich. Sebutan untuk orang usia produktif—15 sampai 64 tahun—yang merawat anak sekaligus orang tua mereka. Isitlah ini populer lewat sebuah studi pada 1981, yang menangkap fenomena generasi baby boomers. Setelah Perang Dunia II, angka harapan hidup membaik. Makin banyak orang yang ingin hidup lama, meski tanpa kestabilan finansial di masa tua. Alhasil, anak-anak yang sedang dalam usia produktif harus menanggung kebutuhan hidup lansia.
Hal serupa dihadapi Andini saat ini. Keadaan semakin mendesak lantaran adiknya bekerja di luar negeri, dan orang tua Andini tak memiliki rumah maupun jaminan hari tua.
Secara tradisional, anak-anak di Indonesia dianggap investasi. Terutama untuk jaminan hari tua para orang tua. Hal ini disampaikan Darmawan Prasetya lewat Caught in the middle: Unravelling motive and practice of elderly care among sandwich generation in Indonesia (2021). Menurutnya, norma ini diperkuat dengan terbatasnya ketersediaan layanan sosial bagi lansia, baik oleh negara maupun swasta.
Misalnya, saat orang rua memberikan pendidikan formal agar anak punya kehidupan lebih baik, semua itu dianggap sebagai “pinjaman” orang tua di tahap awal kehidupan anak. Sayangnya, menurut Prasetya, norma ini cenderung berdampak pada perempuan. Akibatnya, mereka terjebak dalam generasi sandwich.
Selain Andini, “Nandira”, 31, peneliti sosial, juga hidup sebagai tulang punggung keluarga. Bedanya, ia belum menikah dan memilih untuk tidak menikah, seperti Andini. Ia juga tinggal sendiri di Jakarta. Terpisah dari orang tuanya di Kuningan, Jawa Barat.
Ayah Nandira dulu seorang peternak di Lampung, yang terpaksa berhenti bekerja sejak krisis moneter 1998. Sementara ibunya pernah bekerja di bagian audit di sebuah pabrik di Tangerang, berhenti ketika Nandira masih SMP. Situasi ini membuat kedua orang tua Nandira tidak memiliki uang lebih untuk simpanan hari tua. Sejak menerima gaji pertama pada 2015, Nandira langsung menjadi tulang punggung keluarga.
Penghasilannya sekitar Rp20 juta per bulan, tapi Nandira hanya merasakan sedikit dari jerih payahnya. Setiap bulan, Nandira mengalokasikan setengah gaji untuk orang tua. Dari sisa gaji dialokasikan untuk kebutuhan dasar: Sewa apartemen sebesar Rp1,8 juta, listrik Rp400 ribu per bulan, dan uang makan.
Selebihnya, gaji Nandira masih harus dibagi, untuk membeli kebutuhan tiga kucing dan adik bungsunya yang kelas 2 SMA—berupa baju, kerudung, atau bimbel. “Dia sekolah negeri sih, tapi aku harus kasih dia les. Dulu aku gak punya kesempatan les, dan ngerasa kompetisi anak sekarang semakin susah. Jadi aku provide juga buat les adikku,” jelasnya.

Setelah dipotong berbagai kebutuhan, Nandira mengalokasikan seperempat sisa gaji untuk asuransi kesehatan. Jika dihitung, setiap bulan Nandira hanya menggunakan sekitar seperempat dari total gaji untuk kebutuhan pribadi. Soalnya, ia membutuhkan modal sekitar Rp200 ribu sehari tiap bekerja di kafe, karena ia baru ke kantor sebulan tiga kali.
Sedikitnya gaji bersih yang diterima membuat Nandira kesulitan menabung rutin. Misalnya, untuk urusan tak diduga.
“Kadang-kadang bisa bocor. Kayak tiba-tiba kucingku ketabrak itu ngeluarin Rp15 juta. Orang tuaku masuk rumah sakit, keluar lagi puluhan juta (rupiah). Kalau kayak gini, aku gak bisa nabung sama sekali,” cerita Nandira.
Realitas tersebut membuat Nandira suka kecil hati, melihat teman-teman seumurannya membeli properti. “Harusnya aku bisa kayak gini. Apalagi (lihat) teman-teman kantor yang gajinya mirip,” sambungnya.
Narasi membandingkan penghasilan dan kemampuan finansial juga sering jadi poin utama media ketika membahas Milenial. Ataupun Gen Z, generasi lebih muda, yang gelombang pertamanya juga sudah masuk usia kerja. Namun, narasi itu kadang tak sesuai realitas dan data yang ada.
Baca Juga: Beda Generasi Milenial dan Generasi Z di Dunia Kerja
Punya Rumah Bak Mimpi di Siang Bolong
Menopang keluarga bukan jadi satu-satunya permasalahan buat para milenial. Nyatanya, mereka dihadapkan dengan permasalahan berlapis. Salah satunya soal kemampuan membeli hunian.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada 2019 bilang 81 juta milenial di Indonesia belum memiliki rumah. Namun, saat diperiksa Katadata, angka itu ternyata keliru. Menurut data KPU dalam Pemilu 2024, jumlah pemilih milenial adalah 66,8 juta. Sementara hitungan BPS menyebut, ada 69,38 juta milenial di Indonesia.
Berdasarkan hitungan PUPR, jumlah rumah tangga belum memiliki rumah, biasa disebut backlog, mencapai 10,5 juta jiwa pada 2022. Rumah tangga yang tinggal di rumah kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya dianggap belum punya rumah. Dari angka itu, milenial memang generasi terbanyak jumlah backlog-nya, yaitu 4,34 juta rumah tangga. Disusul 4,3 juta rumah tangga generasi X.
Pada 2022, sebetulnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat bilang generasi muda butuh rumah, tapi tak mampu membeli. “Mereka butuh tapi tidak mampu, karena harga rumahnya lebih tinggi dibanding purchasing power (kemampuan beli) mereka,” kata Sri.
Baik di media sosial maupun artikel berita, alasan yang digadang adalah gaya hidup dan kebanyakan jajan kopi. Padahal, harga properti terus meroket dan enggak sebanding dengan kenaikan penghasilan. Rata-rata upah buruh nasional berdasarkan riset BPS per Februari 2024, sebesar Rp3.040.719.
Belum, lagi kesenjangan harga rumah di Indonesia. Pada 2019, Bank Dunia menemukan rasio harga rumah terhadap pendapatan di Jakarta adalah 10,3. Angka itu sekitar dua kali lipat rasio harga rumah terhadap pendapatan di New York (5,7). Rasionya adalah 12,1 di Bandung dan 11,9 di Denpasar.
Tahun lalu, Katadata sempat bikin simulasi kemampuan KPR berdasarkan data upah buruh nasional BPS per Februari 2023. Hasilnya, “Masalah kepemilikan rumah tidak hanya disebabkan gaya hidup konsumtif. Dengan rata-rata upah saat ini, pekerja kesulitan untuk mengakses KPR.”
Realitas itulah yang disadari Nandira. Membuatnya ogah mengambil KPR.
“Masalah kepemilikan rumah tidak hanya disebabkan gaya hidup konsumtif. Dengan rata-rata upah saat ini, pekerja kesulitan untuk mengakses KPR.”
– Cek Fakta Katadata, 2023
“Zaman sekarang lo dapat 600 juta dari mana? (Lokasi rumahnya) jauh banget di pinggir,” kata Nandira. “Buatku, di Jakarta yang stress first and for most itu adalah traffic, enggak akan kuat ngebayangin harus tinggal di pinggiran dan ngalamin kemacetan itu.”
Sepakat dengan Nandira, lokasi rumah juga menjadi pertimbangan utama Andini sebelum mengambil KPR. Dari risetnya ke beberapa wilayah seperti Parung, Jonggol, dan Cikarang, Jawa Barat, nominal cicilannya sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Tapi, enggak sebanding dengan aksesibilitas transportasi umum.
“Sebenarnya ada KRL (Kereta Rel Listrik) dan shuttle bus,” ucap Andini. Cuma kalau ongkosnya Rp100 ribu per hari, mendingan ambil (rumah) di lokasi yang lebih aksesibel. Walaupun harga rumahnya lebih tinggi.”
Butuh waktu lima tahun bagi Andini dan suami menemukan rumah di lokasi yang cocok—dengan pertimbangan aksesibilitas transportasi umum, jarak ke jalan raya, sekolah anak, dan gereja. Mereka mengambil cicilan KPR di Bekasi selama 11 tahun, terhitung dari 2021. Dengan angsuran Rp6 juta per bulan selama lima tahun pertama dan Rp7 juta setelahnya.
Meski memiliki rumah menjadi keharusan bagi Andini, kenyataannya ia terbebani secara finansial. Apalagi sambil membiayai sekolah anak-anak, serta keperluan balita dan rumah tangga. Karena itu, agar penghasilan tercukupi, Andini mencari alternatif produk yang lebih murah atau sedang promo saat belanja bulanan. Bahkan enggak menutup kemungkinan, membandingkan harga di beberapa supermarket dan minimarket.
“Ya pengeluarannya berasa banget, makanya nggak pernah jalan-jalan,” aku Andini.
Ternyata situasi serupa dihadapi Eka, 32, ibu tunggal asal Tangerang Selatan, yang bekerja sebagai karyawan swasta. Meski ia bukan generasi sandwich, penghasilan yang tak sebanding dengan pengalaman kerja tetap tak cukup untuk menghidupi anak berusia empat tahun. Ditambah sejak tinggal bersama orang tua pasca-bercerai, Eka berkontribusi untuk belanja bulanan dan mengambil KPR.
Dengan angsuran 15 tahun, rencananya rumah tersebut ditempati untuk berakhir pekan dan mengurangi gesekan dengan orang tua. Eka pun memilih lokasi di Gunung Sindur, Jawa Barat karena pemerintah menjanjikan jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja).
Baca juga: Beratnya Jadi Generasi Sandwich, Bagaimana Bicarakan Ini dengan Pasangan?
Banyaknya kebutuhan membuat Eka enggak cukup jika mengandalkan penghasilan utama. Ia kerja sampingan sebagai asisten makeup artist dan jasa titip (jastip) saat ada bazar tertentu—seperti produk kecantikan atau perlengkapan bayi dan anak-anak. Hasilnya digunakan untuk menambahkan biaya jajan anak, ongkos ke kantor, atau kado teman dan anggota keluarga anak yang berulang tahun.
Ia tak memungkiri, kebutuhan anak dirasa paling berat. Dari uang makan, susu, dan biaya pendidikan. Beruntung Eka bisa menggunakan fasilitas daycare—seharga Rp2 juta per bulan—dengan gratis, karena ibu Eka salah satu pengelolanya.
Sedangkan mantan suami Eka hanya mengirimkan Rp1 juta per bulan untuk anak, yang Eka tabung untuk biaya pendidikan. “Makanya orang tuaku sering nyuruh aku daftar CPNS. Menurut mereka, PNS itu tunjangan dan kenaikan gajinya jelas, kesejahteraan juga udah terlihat,” jelas Eka.
Baca laporan Bagian II.
______
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari
Series artikel lain bisa dibaca di sini:
Cerita #MilenialMenua: Saat Kerja Kerasmu Tak Ada Artinya (Bagian II)
Bahagia dan Kejar Mimpi Pasca-Bercerai: Cerita Tiga Perempuan
Ketika Bapak Rumah Tangga Bicara Stigma hingga Omongan Tetangga