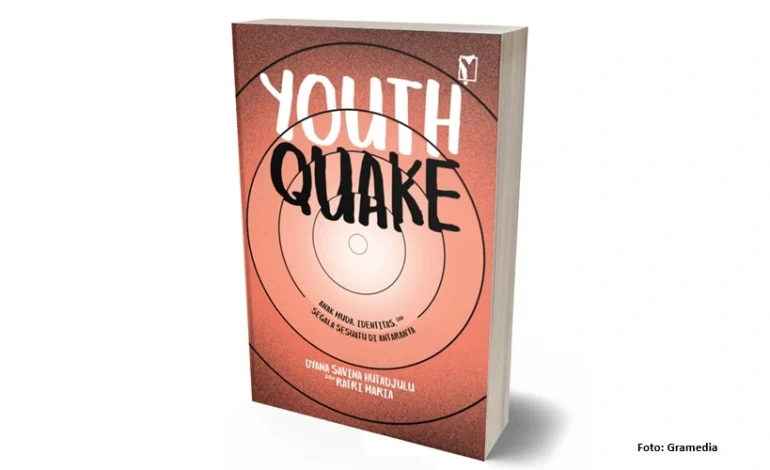‘Collective Care’ Tak Bernama tapi Anak Saya Sudah Tahu Gilirannya

Tahun ajaran baru ini, saya menyekolahkan anak di kampung, tinggal di rumah Uwaknya. Awalnya saya pikir akan gampang, tapi ternyata bikin kepala penuh hitung-hitungan. Selain urusan logistik—karena saya cuma bisa menemuinya seminggu sekali—ada satu hal yang paling bikin pusing: Seragam sekolah.
Seragam itu wajib. Ia semacam paspor sosial. Tanpa itu, anak bisa dipandang aneh, dicibir, bahkan diusir dari kelas. Sudah ada banyak kasus di negeri ini di mana anak-anak dipulangkan hanya karena tidak berseragam lengkap, seolah kain menentukan kualitas otak.
Masalahnya, di kampung saya tidak ada toko perlengkapan sekolah. Kalau mau beli, harus ke kota. Jaraknya lumayan. Transportasi umum? Jangan harap. Di desa yang berdempetan dengan perkebunan sawit asing ini, anak-anak lebih mungkin bertemu truk CPO daripada angkot.
Saya sudah siapkan strategi orang tua ala kadarnya: bujuk anak agar sabar, tunggu akhir pekan, baru saya ajak ke kota. Namun beberapa minggu lalu, anak saya santai saja bilang, “Ibun enggak usah beli baju batik sama baju Pramuka, Adek sudah punya.”
Saya tertegun. Dari mana? Saya tidak membelikan. Uwaknya juga tidak.
Baca Juga: Sekolah Anak Korban Perceraian Bermasalah? Salahkan Saja Ibunya
Seragam Sekolah yang Berputar
Rupanya ada “sistem logistik” yang lebih gesit dari saya. Bukan Gojek atau JNE. Namanya: perwiritan tetangga. Di perwiritan, para tetangga bikin pengumuman: Siapa yang punya seragam seukuran anak saya, boleh dipinjamkan. Ada yang punya lalu segera dipinjamkan.
Ya kata kuncinya: Dipinjamkan. Kalau masih bagus, baju itu akan jalan-jalan lagi. Berpindah tubuh, berpindah cerita. Seperti koper Tupperware warisan tante, cuma ini lebih merdeka.
Tahun depan, kalau masih bagus, baju itu bergilir lagi ke anak lain. Begitu terus. Seragam sekolah bukan sekadar kain. Ia simbol solidaritas yang berpindah dari satu tubuh kecil ke tubuh kecil lain.
Dan di sinilah saya terharu sekaligus geli. Anak saya malah ikut-ikutan. “Ibun, rok SD Adek bawa aja ke sini. Masih bagus. Biar dipakai orang lain.” Lah, anak saya sudah lebih cepat lulus mata kuliah solidaritas ketimbang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Baca Juga: Saat ‘Cinta’ Ibu Mencekikku: Dilarang Kerja, Hilang Percaya Diri
Collective Care dalam Bahasa Keren
Dalam kamus feminis, collective care artinya saling jaga biar hidup enggak bikin jompo sendirian. Dalam praktik kampung, ya itu tadi: Seragam, lauk, sampai anak tetangga dititipkan tanpa invoice.
Kalimat terkenal datang dari Audre Lorde, penyair dan aktivis feminis kulit hitam. Dalam bukunya A Burst of Light (1988) ia menulis: “Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.”
Merawat diri bukan kemewahan. Ia cara bertahan hidup. Sebuah bentuk perlawanan.
Dari sini, feminis generasi setelahnya mengembangkan gagasan, perawatan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga kolektif.
Namun di kampung, konsep itu tak pernah disebut. Ia tidak butuh nama. Ia hidup begitu saja—di seragam yang bergilir, di lauk yang dititipkan, di giliran menjaga anak tetangga.
Saya masih ingat, kalau ada keluarga hajatan, ibu saya otomatis bangun lebih pagi menyiapkan bawaan. Tidak ada panitia. Tidak ada grup WA. Tidak ada daftar Excel. Namun semua berjalan dengan alami.
Orang yang repot ditolong. Yang punya lebih berbagi. Semua paham giliran mereka akan tiba juga. Kalau pakai istilah keren, ini mutual aid yang organik. Kalau pakai istilah kampung? Ya “biasa aja, Mak.”
Kota yang Sibuk, Kampung yang Ingat
Di kota, orang tua sering merasa beban sekolah anak sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Semua harus dibeli sendiri. Kalau tak sanggup, rasa malu yang datang.
Sementara di kampung, ada mekanisme sosial yang membuat beban itu ringan. Meski kadang disertai gosip atau aturan sosial yang bikin pening. Ya, manusiawi. Namun tetap saja. Beban hidup lebih ringan kalau ditanggung bersama.
Mungkin yang kita butuhkan di kota bukan jargon baru bernama collective care melainkan memulihkan ingatan. Bahwa praktik saling jaga sudah lama ada. Kita saja yang terlalu sibuk, terlalu individual sampai lupa caranya.
Dalam perspektif feminis, collective care bukan sekadar berbagi beban. Ia strategi bertahan hidup. Cara agar kita tetap waras, tetap ada, tetap mampu melawan.
Di kampung, ia berlangsung tanpa nama. Di kota, barangkali harus diberi nama dulu, supaya kita ingat cara mempraktikkannya lagi.
Baca Juga: Mereka yang Tersisih dari Bangku Sekolah di Mentawai
Pertanyaan untuk Kita Semua
Pertanyaannya sederhana tapi penting. Anak saya saja sudah paham giliran, kenapa kita yang dewasa justru sering lupa? Sanggupkah semangat ini kita rawat, atau ia bakal punah, digantikan like dan komen di Instagram?
Bisakah kita belajar dari kampung? Bukan untuk romantisasi. Namun untuk mengingat bahwa saling jaga itu mungkin dan pernah jadi kebiasaan.
Bagi saya, seragam pinjaman bikin hati tenang melepas anak. Ada komunitas yang menopang. Dan mungkin, itu inti collective care: Memastikan nggak ada yang jalan sendirian—mau di kampung, mau di kota. Karena kalau anak saya saja sudah tahu gilirannya berbagi, masa saya nggak tahu diri?
Minggu depan, saya pulang kampung seperti biasa. Menjenguk anak. Selain membawa rok SD seperti permintaannya, saya juga akan membawa minyak serai untuk nenek tetangga depan. Katanya, beliau sakit gula, tak tahan gigitan nyamuk.
Minyak serai saya stoknya masih banyak. Lumayan. Bisa ikut menambah putaran kecil dalam rantai saling jaga di kampung itu.
Kalau anak saya sudah tahu gilirannya, masa saya enggak?
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini.
Ilustrasi oleh Karina Tungari