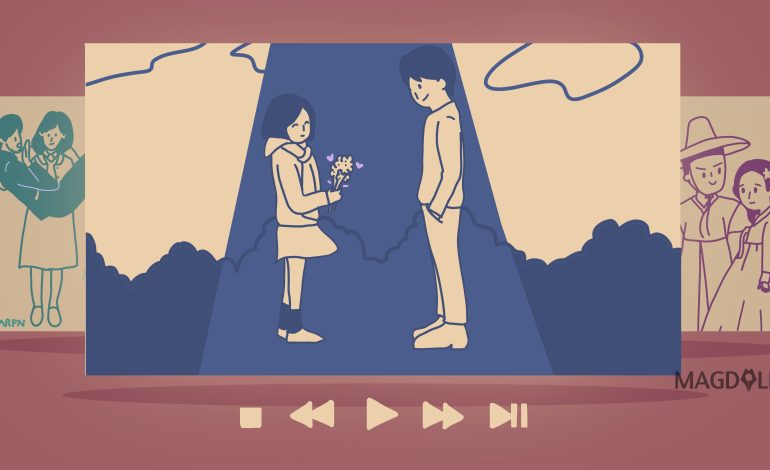Ada pemandangan berulang jika saya mengambil order taksi online dari salah satu ruma sakit ibu dan anak di pusat kota Bekasi. Seorang ibu yang baru melahirkan, berjalan susah payah untuk naik mobil, dengan bayi yang masih merah di gendongannya. Di luar pintu, suaminya mendampingi sekejap sebelum naik ojek motor ke arah yang berbeda.
“Hati-hati ya, Ma. Papa harus meeting sebentar lagi. Maaf enggak antar sampai rumah,” katanya setengah berteriak, suaranya dipenuhi rasa bersalah.
Si istri ditemani ibunya yang sudah sepuh, atau adik yang masih sekolah, atau teman yang sedang cuti. Wajahnya terlihat lelah, pandangannya kosong. Postpartum blues membayang di pelupuk mata. Saya lihat dari spion tengah, si bapak tadi sudah hilang ditelan kemacetan.
Dia baru saja punya anak tiga hari yang lalu. Tapi hari ini negara dan perusahaan sudah memaksanya kembali ke kantor.
Di media, pemerintah teriak soal “Pencegahan Stunting” dan “Ketahanan Keluarga.” Tapi nyatanya, mereka memisahkan ayah dari bayinya di masa paling kritis.
Baca Juga: Tak Semua Ayah Patut Dihormati
Apa yang bisa dilakukan ayah dalam dua hari?
Ada harapan baru ketika Undang-Undang No. 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) akan disahkan. Sayangnya, sama dengan UU Ketenagakerjaan 2003, UU KIA juga hanya memberikan hak cuti ayah dua hari, meski ada ketentuan tentang waktu tambahan tiga hari atau sesuai kesepakatan. Periode tiga hari itu adalah “sedekah” atau “kebaikan hati” tempat kerja. Jika bos bilang tidak, ya tidak. Tidak ada sanksi tegas bagi perusahaan yang menolak memberikan tambahan itu.
Bandingkan dengan cuti ayah di negara-negara lain: di Jepang 52 minggu, Swedia 90 hari, Singapura 14 hari, dan Filipina tujuh hari. Saat negara lain sudah bicara tentang kualitas pengasuhan jangka panjang, kita masih melihat cuti ayah sebagai kerugian finansial belaka.
Padahal para ayah ini harus mengurus administrasi rumah sakit, mengubur ari-ari (jika ada tradisi seperti itu), dan menerima tamu. Hari kedua mengurus akta kelahiran (antre tiga jam), daftar BPJS, lalu belanja popok untuk stok seminggu. Hari ketiga sudah back to work.
Jahitan istri masih basah, ASI belum lancar, bayi menangis tiap dua jam. Tapi suami sudah harus duduk di rapat, turun ke lapangan, atau apa pun tugasnya di tempat kerja. Sistem ini secara tidak langsung berkata: “Mengurus anak adalah tugas ibu 100 persen. Tugas Ayah cuma cari duit.”
Hal ini kontradiktif dengan apa yang dikampanyekan pemerintah. Di papan reklame, di TV, di mana pun, ada tulisan-tulisan “Cegah Stunting Sejak Dini”, “1000 Hari Pertama Menentukan Masa Depan Anak”, “Keluarga adalah Fondasi Bangsa.” Tapi di saat yang sama, negara secara sistematis memisahkan ayah dari keluarganya di masa paling kritis.
Padahal riset ilmiah memperlihatkan dampak positif keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Studi dari Dr. Ping-Jen Chen, et al. yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatric Research (2023) menunjukkan bahwa dukungan sosial, terutama keterlibatan aktif pasangan, berkorelasi signifikan dengan penurunan risiko Postpartum Depression (PPD). Studi di Puskesmas Andalas Kota Padang juga menemukan 24,3 persen ibu mengalami depresi postpartum, dengan hubungan signifikan antara rendahnya dukungan suami dan kejadian depresi.
Selain itu, sebuah hasil studi yang dimuat di Infant Mental Health Journal (2017) menemukan bahwa bayi yang ayahnya terlibat aktif dan positif pada usia tiga bulan memiliki skor perkembangan kognitif yang jauh lebih baik saat usia dua tahun. Hal serupa ditemukan dalam penelitian di Kecamatan Pacet, Indonesia yang menunjukkan keterlibatan ayah berkontribusi 18,8 persen terhadap perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun.
Ayah yang aktif merawat bayi juga mengalami lonjakan hormon oksitosin, yakni hormon kunci untuk ikatan emosional seumur hidup, menurut studi neurosains dari Prof. Ruth Feldman (Proceedings of the National Academy of Sciences/PNAS, 2014).
Jadi kenapa kita masih memberikan cuti ayah hanya dua hari?
Baca Juga: Oh, Ibu dan Ayah, Putuskan Rantai Kekerasan terhadap Anak
Patriarki juga menghukum laki-laki
Cuti ayah yang minim ini menunjukkan bahwa patriarki juga merugikan laki-laki. Sistem ini mengondisikan para ayah sebagai “mesin pencari nafkah”, bukan orang tua. Ketika karyawan laki-laki minta cuti lebih lama untuk membantu mengasuh bayi dan mendampingi istri menyusui, ia dianggap takut istri.
Padahal melarang ayah cuti sama dengan mensponsori generasi rentan stres dan ibu-ibu depresi. Ibu butuh sistem pendukung, termasuk dari suaminya. Apalagi jika ia tidak memiliki bantuan ekstra dari keluarga atau pengasuh.
Saya menulis ini sebagai seorang suami. Istri saya adalah perempuan mandiri yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri. Tapi saya tahu, sekuat-kuatnya dia, saat dia melahirkan nanti, dia butuh saya. Bukan cuma butuh transferan saya.
Sebagai pengemudi, saya mungkin beruntung punya waktu fleksibel. Tapi saya miris melihat jutaan ayah lain, seperti penumpang saya tadi yang tidak punya pilihan. Fisik mereka disandera di tempat kerja seharian, bahkan mungkin sampai malam jika lembur atau commuting. Padahal di rumah, istri mereka sedang berjuang mengurus bayi dan melawan baby blues.
Seorang istri sangat butuh tangan suami untuk memijat punggung yang pegal, telinga suami untuk meluapkan rasa lelah, dan kehadiran suami untuk mengganti popok atau memberi susu agar dia bisa tidur sejenak.
Kami, para laki-laki, juga ingin melihat anak tersenyum pertama kali, memotret makanan padat pertama yang ia lahap, dan mendengarkan kata pertama yang ia ucapkan. Kami ingin hadir. Saya yakin banyak laki-laki yang ingin sepenuhnya hadir, bukan cuma mampir.
Karena menjadi ayah itu bukan cuma soal transfer uang di akhir bulan, tapi soal transfer kasih sayang di setiap kesempatan. Tapi sistem kerja kita saat ini sedang merampok kesempatan itu dari jutaan ayah di Indonesia dan membiarkan ibu berjuang sendirian.