Hidup Gen Z dan Milenial: “Cukup Saja Sudah Mewah, Dua-Tiga Pekerjaan Enggak Cukup”
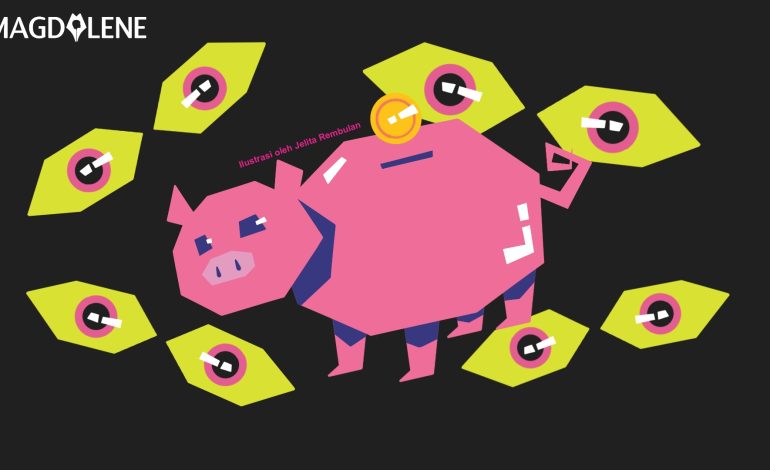
Di TikTok, ada beberapa konten soal hidup ideal yang menyita perhatian saya. Salah satunya milik @capt_jhay, yang bilang: “Being financially comfortable is enough for me. I don’t have to be the richest, I just want to always be able to eat what I want, go where I want, pay my bills on time and live a good life.“
Di kolom komentar, tak sedikit yang mengamini harapan itu. Kehidupan yang tampaknya sederhana ternyata dianggap sebuah kemewahan.
Sebenarnya, konten-konten tersebut menggambarkan krisis biaya hidup yang terjadi karena inflasi. Akibatnya, dewasa muda khawatir bisa mencukupi kebutuhan hidupnya hingga mengesampingkan keinginan berkeluarga.
Menurut laporan World Economic Forum’s Future of Jobs pada 2023 ini merupakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang dialami para pekerja muda. Ditambah serangan Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan lonjakan bahan pangan. Dampaknya, pekerja muda mengalami tekanan finansial. Mereka harus mengambil pekerjaan sampingan, demi memenuhi keperluan.
Sementara untuk bertahan hidup di Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, standar hidup layak pada 2024 mencapai Rp1,66 juta per bulan—atau Rp19,953 juta per tahun. Ada peningkatan sekitar 2,99 persen dari 2023. Dan idealnya, penghasilan pekerja berstatus lajang adalah Rp15 juta per bulan, meski kenyataannya rata-rata gaji pekerja di Jakarta berkisar Rp5,25 juta.
Kondisi ini menggambarkan keinginan dewasa muda yang mengejar kebahagiaan lewat cara-cara sederhana, seperti konten TikTok milik @capt_jhay. Hal ini juga dialami oleh Eko (26), pekerja swasta yang berdomisili di Yogyakarta, dan “Pingkan” (26), pekerja swasta asal Bekasi, Jawa Barat. Keduanya bagian dari generasi sandwich yang terpaksa menunda keinginannya, demi menghidupi keluarga.
Bagi Eko dan Pingkan, kemewahan bukanlah liburan ke luar negeri atau punya barang berharga. Mereka mendefinisikannya sebagai kestabilan finansial dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut cerita mereka.
Baca Juga: Generasi Z: Rumah Tak Terbeli Bukan karena Kebanyakan ‘Ngopi’
Q: Halo, Eko dan Pingkan. Boleh diceritakan kebutuhan hidup kalian sebagai dewasa muda?
Eko
Belum lama ini, aku pindah ke Yogyakarta. Awalnya aku mikir, mungkin biaya hidup di sini akan lebih murah. Tapi, teman-teman yang asalnya dari Yogyakarta bilang, konsep itu cara pandang outsider. Mungkin orang-orang yang datang dari area metropolitan, datang ke sini untuk berlibur. Makanya pendapatan mereka lebih tinggi. Sedangkan UMR (Upah Minimum Regional) di Yogyakarta tahun ini Rp2,1 juta.
Setelah dijalani, ternyata biaya hidup di Yogyakarta enggak jauh berbeda—dengan gaya hidup yang mirip sewaktu tinggal di Jakarta. Ditambah transportasi umum di Yogyakarta enggak mendukung, sedangkan aku belum punya kendaraan pribadi. Akhirnya enggak bisa menekan biaya transportasi karena harus naik ojek online.
Kompensasi yang diberikan perusahaan juga menyesuaikan UMR di sini. Sementara pengeluaranku cukup banyak: biaya hidup, kepentingan pribadi, dan hiburan. Belum lagi, aku termasuk generasi sandwich jadi harus membagi penghasilan dengan kebutuhan sehari-hari orang tua, dan biaya pendidikan adik.
Pingkan
Aku kerja untuk menopang kebutuhan hidup keluarga: Aku, ibu, dua saudara kandung, seorang PRT (Pekerja Rumah Tangga), dan seekor kucing. Ada juga satu mobil dan motor yang perlu perawatan. Kakakku juga bekerja sih, tapi kami punya keperluan masing-masing. Jadi enggak mau menuntut banyak ke dia untuk mengeluarkan besaran biayanya.
Mungkin kedengarannya aku berpenghasilan besar karena mempekerjakan PRT. Padahal kondisi ibu pasca stroke, mengharuskan ada yang menemani dan melakukan pekerjaan rumah tangga.
Makanya, kadang-kadang aku ambil pekerjaan tambahan kayak makeup artist atau MC. Walaupun pendapatannya enggak besar, lumayan untuk nambahin uang bensin atau kebutuhan sehari-hari—pribadi maupun keluarga. Yang jelas enggak bisa ditabung kayak Kaluna (karakter utama di Home Sweet Loan).
Q: Selain kepentingan pribadi, kamu juga menanggung biaya hidup keluarga. Kira-kira berapa persentase pengeluaranmu setiap bulan?
Eko
Untuk biaya hidup, aku lagi enggak menghitung pengeluaran per bulan secara spesifik—kira-kira ya (untuk biaya hidup) 40 persen dari pendapatan. Itu termasuk skincare dan pakaian. Sisanya dibagi untuk kebutuhan orang tua dan menabung.
Pingkan
Aku plotting 25 persen penghasilan buat tagihan rumah kayak listrik dan internet, empat sampai lima persen untuk nabung biaya perawatan mobil yang mesti dilakukan tiga bulan sekali. Kalau memungkinkan, delapan sampai 10 persen masuk tabungan. Sisanya buat belanja harian, transportasi, dan hiburan.
Q: Apakah tanggung jawab ini sebenarnya membebankan kamu?
Eko
Biaya menghidupi orang tua dan adik ini terasa ya. Soalnya, kalau dari awal kerja—di 2019—aku bukan generasi sandwich, mungkin aku punya siklus tabungan yang lebih baik. Dengan gaji sekitar lima sampai enam juta ya, setidaknya bisa fokus ke diri sendiri. Soalnya, kondisi sebagai generasi sandwich ini menahan seseorang untuk mengejar keinginan, atau kehidupan yang ideal menurutnya.
Aku pun punya pekerjaan sampingan di ranah marketing, bikin konten. Kurasa ini permasalahan di generasi milenial dan Z ya, enggak cukup kalau mengandalkan satu pemasukan—apalagi untuk memenuhi gaya hidup. Memang beda dengan generasi-generasi sebelumnya, cukup satu pekerjaan karena dulu biaya hidup lebih murah.
Pingkan
Dengan semua kebutuhan itu, sebenarnya penghasilanku yang di bawah Rp10 juta ini enggak cukup. Belanja bulanan aja mikir banget, sampai mengusahakan pakai produk yang harganya paling ekonomis, tapi punya manfaat yang sama.
Jadinya aku jarang mengajak keluarga jalan-jalan untuk refreshing—misalnya sekadar pergi ke mal. Tahun ini kayaknya enggak sampai lima kali. Soalnya apa-apa mahal, sekali pergi paling enggak ngeluarin Rp500 ribu sampai Rp1 juta.
Baca Juga: Bangga Jadi Milenial dengan “Cuan” yang Biasa-biasa Saja
Q: Terlepas dari banyaknya tanggungan yang harus dipenuhi, gimana cara kamu menikmati hasil kerja?
Eko
Biasanya aku hangout di kafe pas weekend, beli buku, liburan, sama langganan Spotify dan Netflix. Hiburan ini termasuk pengeluaran pribadi terbanyak sih.
Pingkan
Kalau aku nyobain makanan. Salah satunya makan chicken nugget tanpa nasi—impian waktu kecil yang bisa dilakukan ketika punya uang sendiri. Masa iya, udah capek kerja enggak bisa nyobain ini itu?
Q: Apakah kehidupan yang dijalani sekarang bisa disebut ideal?
Eko
Walaupun bisa menikmati hasil pekerjaan, rasanya belum termasuk kehidupan ideal versiku: Bisa memenuhi kebutuhanku sekaligus mengejar impian—melanjutkan pendidikan, sering liburan, dan keinginan-keinginan lain.
Mungkin sekarang lagi proses mencapai itu karena terjepit sebagai generasi sandwich ya, ada beberapa keinginan yang perlu ditahan. Salah satunya melanjutkan S2, karena harus menunggu adikku lulus kuliah.
Sebenarnya kehidupan yang ideal ini dipengaruhi kondisi ekonomi yang semakin sulit sih. Mau gerak ke mana pun perlu mengeluarkan uang. Apalagi di Yogyakarta yang minim third places—tempat berkumpul untuk berinteraksi atau beraktivitas dengan gratis. Ini kan berarti menambah pengeluaran. Ujung-ujungnya harus punya pekerjaan sampingan supaya mencukupi itu.
Pingkan
Kehidupan ideal buatku, ketika hidup selalu terjamin. Artinya bisa bekerja terus selama aku mampu dan mau melakukannya, bukan berdasarkan rentang usia produktif. Dan negara juga memberikan jaminan kesejahteraan, jadi (masyarakat) enggak pusing menyambung biaya hidup. Mungkin contohnya kayak di Australia.
Tapi kalau di Indonesia, definisi kehidupan ideal kayaknya tergantung seberapa kita mensyukuri hidup. Soalnya yang dilakukan pemerintah selama ini, enggak menunjukkan tanggung jawabnya menyejahterakan masyarakat.
Q: Ada orang yang menilai hidup mewah artinya mampu beli barang-barang mahal, untuk menunjukkan status sosial. Kalau buat kamu, apa definisi “hidup mewah”?
Eko
Mampu mencukupi keperluan dan keinginan, menurutku suatu kemewahan. Selain melanjutkan pendidikan, aku juga ingin punya taraf hidup yang lebih baik dan tinggal di luar negeri.
Kurasa ini dipengaruhi latar belakangku yang datang dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Dulu orang tuaku kerja sebagai petani dan seharusnya keluarga kami tergolong miskin. Tapi, kami enggak pernah mendapatkan bantuan. Alasannya karena orang tuaku bisa membiayai sekolahku sampai kuliah—enggak ngerti gimana tolok ukur (kemiskinan) pemerintah Indonesia.
Padahal untuk kuliah, aku berusaha dapat beasiswa. Begitu pun dalam berkarier, aku usaha sendiri karena keluargaku enggak kaya atau punya koneksi yang luas. Jadinya perspektif hidup ideal ini dipengaruhi oleh bagaimana aku dibesarkan.
Pingkan
Selain liburan bareng keluarga, standar hidup mewah buatku itu bisa nge-kos di dekat kantor, tanpa menanggung keperluan di rumah. Mungkin kayak konten kreator Tom Dickinson, yang suka upload konten a day in my life. Dia seorang konsultan asal Australia yang tinggal di apartemen, seminggu sekali hangout sama teman-teman, bisa olahraga, dan cuma butuh waktu 15 menit buat pergi ke kantor.
Baca Juga: Kami adalah Gen Z, Insecure dan Overthinking adalah Sahabat Kami
Q: Semakin ke sini, biaya hidup semakin mahal. Pemerintah juga berencana menaikkan pajak jadi 12 persen. Ada kekhawatiran soal itu?
Eko
Aku enggak setuju dengan kenaikan itu karena akan berdampak ke kebutuhan sehari-hari. Sekarang aja biaya hidup udah cukup menyulitkan, pajak itu akan semakin membebani seandainya nanti mau beli rumah atau kendaraan pribadi. Bahkan sewaktu tinggal di Jakarta, aku mesti kerja dengan jam lebih panjang untuk dapat penghasilan tambahan—yang berdampak ke kesehatan, waktu, dan kemampuan fokus juga.
Dulu aku pun khawatir pemasukan bulanan tetap segitu, tapi pengeluaran bulanan semakin bertambah. Untungnya sejak pindah ke Yogyakarta, aku bisa lebih menyiasati pengeluaran karena biaya hidup lebih murah.
Tapi kalau kondisi ini dibiarkan terus—sementara peluang lapangan kerja juga lebih banyak di Jakarta—kemungkinan beberapa tahun lagi, kelompok kelas pekerja di usia produktif enggak bisa memenuhi kebutuhan primer.
Pingkan
Takut biaya hidup semakin tinggi, tapi penghasilan segitu aja, kondisi karier stagnan, dan persaingan kerja semakin parah. Sebenarnya itu yang kujalani sekarang, dan aku takut enggak bisa memenuhi kebutuhan dasar karena pernah mengalami itu.
Waktu masih sekolah, aku dengar pihak bank mau menarik rumah. Sebagai anak, aku mikir, ibu bapak bisa enggak memenuhi ini? Dan apakah aku bakal putus sekolah?
Makanya sekarang lagi berusaha biar kejadian itu enggak terulang. Salah satunya enggak buru-buru berumah tangga karena harus bisa menunjang keperluan sehari-hari dulu, dan lebih stabil secara finansial.
Q: Menurutmu, siapa yang harus bertanggung jawab atas situasi ini?
Eko
Aku bingung ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab atas situasi ini, kecuali pemerintah. Sayangnya, pemerintah Indonesia cenderung enggak peka terhadap isu ini, dan enggak tanggap mengatasi permasalahannya.
Padahal, banyak perusahaan di Indonesia melakukan layoff karyawan sejak awal pandemi lalu. Mereka memang memberi dana post-layoff yang bisa diklaim melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), tapi enggak cukup karena nominalnya kecil. Lalu jumlah dan jenis layanan program pelatihan yang diberikan enggak sesuai, dengan jenis pekerjaan di Indonesia.
Pingkan
Rasanya enggak tahu mau bergantung pada nasib atau gimana. Jujur, kebijakan-kebijakan pemerintah yang aneh ini bikin ketar-ketir. Sekarang aja biaya hidup serba mahal, enggak kebayang dampak dari rencana kebijakan yang akan diterapkan nanti—salah satunya PPN 12 persen. Mungkin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sekarang aku pun enggak kepikiran caranya punya tempat tinggal, yang sebenarnya termasuk kebutuhan dasar. Belum lagi pemerintah terus menarik pajak dari kelas menengah, dan penghasilan rata-rata yang enggak meningkat signifikan. Makanya aku bangga, bisa memaksakan nabung setiap bulan. Walaupun tabungannya untuk dana darurat.
Q: Sebagai dewasa muda dari kelas menengah, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk mendorong tanggung jawab pemerintah?
Eko
Aku percaya untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, harus dilakukan secara kolektif dari berbagai lini. Misalnya sekarang ada serikat pekerja, walaupun di perusahaan teknologi—latar belakang pekerjaanku—masih kurang. Setidaknya bisa jadi awal yang baik, untuk membentuk kesadaran pentingnya berserikat dalam menyuarakan kebutuhan kelas pekerja.
Pingkan
Aku selalu update dengan isu terkini dan aktif posting di media sosial. Biar orang-orang di sekitarku juga aware, meski enggak punya platform besar yang bisa menaungi aspirasi.






















