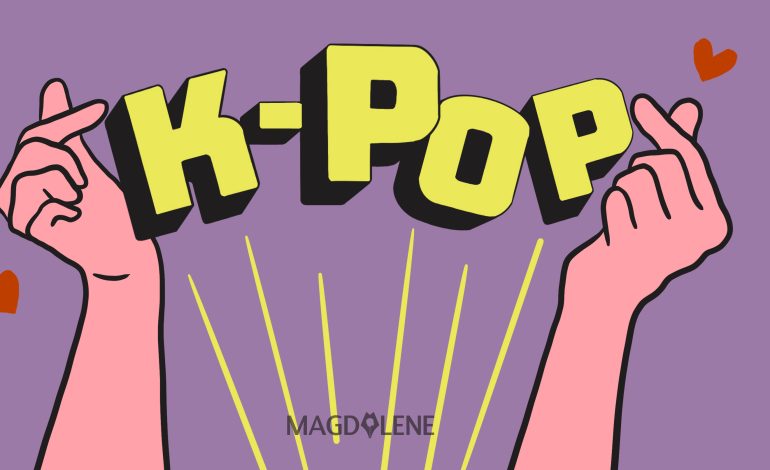Selamat Datang di ‘Alterland’: Tempat Cinta dan Perang Jadi Satu

Sebulan terakhir, saya terbiasa melihat akun alter beramai-ramai menyerang acara besar di televisi hingga media sosial. Dalam kontes olahraga pria misalnya, akun alter merajalela di Instagram. Demikian pula dalam audisi memasak di televisi yang dijadikan bulan-bulanan akun alter.
Komentarnya beragam, mulai dari “Ini kan artis alter”, “Beda banget foto sama di kamera”, hingga “Oh, jadi ini aslinya yg sering post konten rated” bertebaran. Buat mayoritas orang, fenomena akun tidak jelas yang menyerang pihak lain mungkin terdengar receh, tapi dalam konteks serius, itu bisa dikategorikan dengan doxing (penyebaran identitas) atau force outing (pemaksaan melela). Buntutnya jelas tak main-main.
Sejarah Akun Alter dan Anonimitas
Fenomena akun alter di dunia siber sebenarnya bukan hal baru. Ini muncul merata di hampir semua platform media sosial, dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Di Amerika Serikat, akun alter dan bot mulai tak asing sejak Pemilihan Presiden 2016. Kala itu, akun alter sering digunakan oleh para pendengung (buzzer) untuk mendukung kandidat presiden favorit mereka. Center for Information Policy and Governance bahkan menyimpulkan, penggunaan anonimitas untuk penggiringan opini publik lahir berbarengan dengan Twitter itu sendiri.
Baca juga: Alterland: taman Bermain di Dunia Maya
Seiring perkembangan zaman, anonimitas di media sosial ini berkembang ke arah yang lebih luas, tak melulu soal politik. Anonimitas membantu menyalurkan ekspresi seksual tanpa harus mengungkapkan identitas sebenarnya. Di Twitter, secara spesifik alter ditampilkan dengan akun avatar yang biasanya menonjolkan ekspresi sensual dan tubuh telanjang.
Akademisi Novita Ratna Wulandari dari Universitas Negeri Malang, dalam tesisnya berjudul “Finally Exposed!: Narrating Indonesian Women’s Self-exposure on Twitter” (2014) mengatakan bahwa akun alter di Twitter adalah sarana pembebasan kesenangan seksual oleh kelompok minoritas, termasuk queer, untuk memenuhi kebutuhan tanpa tujuan materialistis.
Selain itu, anonimitas juga kerap disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan slut shaming, public shaming tanpa perlu takut dibayang-bayangi risiko sosial dan hukum. Makanya kita sering melihat komentar-komentar mengganggu dari akun yang tak jelas dalam kehidupan para pesohor. Kita juga dengan mudahnya melihat sejumlah akun alter melakukan doxing kepada orang yang mereka benci.
Secara teoretis, akun alter bisa didekati dengan teori deindividuasi dari psikolog Perancis, Gustave Le Bon. Ia mengatakan, perilaku individu dapat disetir oleh nilai-nilai dan mentalitas keramaian. Contoh sederhana adalah dalam konser musik, bagaimana seseorang bisa saja melompat-lompat, menyenggol ke sana kemari, dan berteriak secara impulsif tanpa memikirkan konsekuensi lanjutan. Maka pada saat itu individu tersebut akan melupakan kewajiban personalnya.
Berangkat dari teori itu, mestinya kita tak punya pilihan lain selain memaklumi akun alter yang menyalurkan semangat anti-normatif. Pasalnya, itu adalah hal umum yang sukar dipisahkan oleh mentalitas masyarakat digital seperti sekarang karena berkaitan dengan hal-hal seperti kebebasan berekspresi dan rasa aman.
Doxing Jadi Niscaya
Akun alter bisa membantu orang mengekspresikan dirinya, tapi dalam konteks lain, ia juga bisa berdampak buruk. Dalam ranah subkultur alter Twitter, muncul beberapa akun besar yang bisa dikategorikan sebagai microinfluencer (orang-orang yang diikuti). Micro influencer dalam fenomena alter biasanya tidak hanya mengunggah konten seksual dengan sensor wajah, tetapi juga menampilkan kepribadian dan pengalaman kehidupan personalnya, sehingga lebih menarik untuk diikuti. Di sinilah fenomena deindividuasi menjadi bumerang karena para pengikut juga menjadi mudah melakukan pelacakan terhadap detail-detail implisit yang kadang dibagikan sukarela oleh si empunya akun.
Baca juga: Serangan Digital Marak: Kebebasan Berpendapat di Ujung Tanduk
Bila microinfluencer pada suatu hari muncul di media nasional sebagai persona asli, mudah bagi para pengikutnya untuk mengenali struktur wajah ataupun postur tubuh yang bersangkutan. Para pengikut akun alter juga tidak akan merasa bertanggung jawab bila mereka melakukan tindakan spill atau membeberkan fakta di luar consent pemilik akun, karena mereka sendiri adalah bagian dari budaya anti-normatif
Tak hanya spill, account alter juga bisa melakukan doxing atau membagikan informasi privat ke ranah publik dalam dunia daring. Informasi yang diberikan sangat beragam, dari nama asli, afiliasi pekerjaan, instansi, bahkan nomor telepon dan alamat rumah. Dalam konteks lebih sempit, hal ini tentu berisiko bagi kelompok queer dan minoritas lainnya yang terbiasa bebas berekspresi di balik topeng account alter.
Harusnya Bagaimana?
Idealnya, setiap pemilik akun sosial media dapat mengunggah apa saja, namun harus paham segala konsekuensinya. Di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, para jurnalis yang memiliki akun terverifikasi dengan bebas membagikan kehidupan kencan dan pandangan politiknya. Inklusivitas cenderung berjalan lurus dengan pemerintah yang tidak membatasi masyarakatnya.
Baca Juga: Hentikan Debat Kusir dan BuzzeRp: 6 Tips Berargumen di Media Sosial
Tanpa fenomena deindividuasi, masyarakat bisa menjadi inklusif di akun primer, sehingga akuntabilitas menjadi lebih jelas dipertanggungjawabkan. Pun, doxing juga bisa diminimalisasi bila masyarakat tidak mengategorikan demografi queer yang non-conforming sebagai antinormatif. Sampai entah kapan, atau suatu hari nanti, akankah demografi perempuan dan queer tidak lagi merasakan ancaman dalam bermedia sosial?