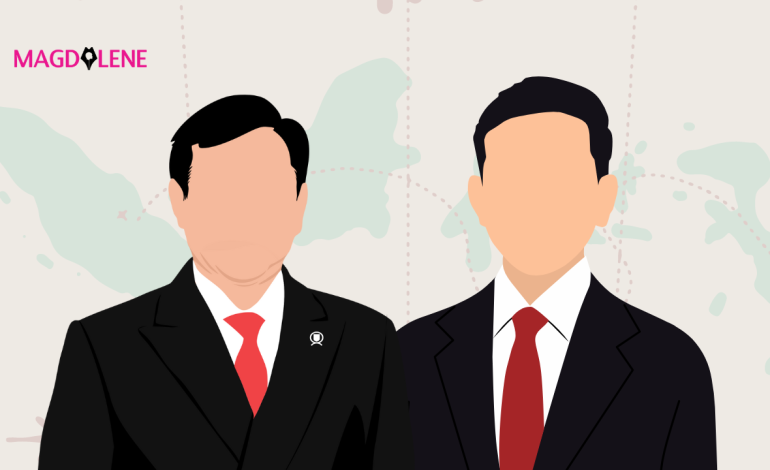Femisida Bukan Sekadar Pembunuhan Biasa, Ada Misogini di Dalamnya

Di sebuah kebun di Kampung Uning Teririt, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, seorang perempuan bernama Ayuni, 35, dibunuh oleh suaminya, Edi Andani, 31. Pada Senin (27/1), pasangan ini terlibat pertengkaran mengenai uang belanja. Namun, alih-alih menyelesaikan konflik secara dewasa, Edi memilih cara yang paling brutal untuk “mengakhiri” perdebatan tersebut.
Keesokan harinya, ia menggali lubang di kebunnya, lalu pada Rabu (29/1), mengajak Ayuni ke sana dengan alasan membantu membersihkan kebun. Begitu tiba di lokasi, Edi memukul kepala Ayuni dengan papan kayu hingga tewas, lalu menguburnya di lubang yang sudah ia siapkan.
Baca juga: Edukasi Anak Perempuan Soal Femisida, Nyalakan Alarm Sejak Dini
Kasus ini terungkap setelah seorang tetangga melaporkan Ayuni yang menghilang. Saat polisi datang ke lokasi, mereka menemukan jasad Ayuni dalam drum yang telah tertimbun tanah serta dicor dengan semen dan pasir. Setelah menginterogasi keluarga, polisi menangkap Edi pada Jumat (31/1).
“Setelah ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya dan sekarang berada di rumah tahanan Polres Bener Meriah. Masih ada pendalaman kasus, seperti rekonstruksi kejadian,” ujar Aipda Abdul Rahman dari Satreskrim Polres Bener Meriah kepada Magdalene pada Jumat (7/2).
Kejadian serupa juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Seorang ibu tunggal, Uswatun Khasanah, 29, menjadi korban pembunuhan kekasihnya, Antok (33), yang dengan kejam menghabisi nyawanya karena alasan cemburu. Antok mencekik Uswatun hingga tewas, lalu memutilasi tubuhnya. Potongan tubuhnya ditemukan dalam sebuah koper yang dibuang ke parit di Desa Dadapan, Ngawi, akhir Januari lalu.
Kasus-kasus ini mencerminkan pola femisida intim, di mana perempuan dibunuh karena gendernya oleh orang terdekatnya, baik suami, pacar, atau mantan pasangan. Data Komisi Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa dalam periode 2016–2020, terdapat 263 kasus femisida intim di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dendam atau sakit hati menjadi alasan yang paling sering dikemukakan pelaku, dengan 76 kasus.
Tidak ada kata-kata atau tindakan yang bisa membenarkan kekerasan, apalagi pembunuhan. Namun, berulang kali, kasus femisida terjadi dengan pola serupa: laki-laki membunuh perempuan karena merasa harga diri atau egonya terusik. Fenomena ini bukan sekadar kejahatan individual, tetapi bagian dari pola kekerasan berbasis gender yang terus dibiarkan terjadi.
Jika laki-laki kerap dianggap sebagai makhluk logika, mengapa begitu banyak pelaku femisida yang melakukan pembunuhan atas alasan yang tampak irasional, seperti cemburu, dendam, atau sakit hati?
Baca juga: Budaya Kehormatan Bikin Perempuan di Turki jadi Korban Femisida
Misogini yang terinternalisasi
Kriminolog Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi, menjelaskan bahwa seseorang yang telah menginternalisasi nilai-nilai misogini, atau kebencian terhadap perempuan, tidak memerlukan alasan rasional untuk melakukan femisida. Dalam pikiran mereka, dominasi atas perempuan harus tetap terjaga, dan segala bentuk perlawanan atau tindakan yang dianggap “mengancam” maskulinitas mereka bisa berujung pada kekerasan.
“Hanya karena hal-hal yang bagi kita tampak sepele dan tidak masuk akal, bagi mereka itu sudah cukup untuk menyinggung kelelakian, superioritas, dan otoritas mereka. Bisa saja mereka berpikir, ‘kok perempuan ini berani menentang saya, mempermalukan saya, atau bahkan berselingkuh,’ meskipun tuduhan itu belum tentu benar,” jelas Mamik kepada Magdalene pada Kamis (13/2).
Internalisasi misogini ini berakar dalam sistem patriarki yang mengajarkan laki-laki sejak kecil bahwa mereka harus dominan, kuat, dan mengontrol, sementara perempuan harus tunduk. Nilai ini ditanamkan sejak dalam keluarga, diperkuat dalam lingkungan sosial, dan bahkan dilegitimasi oleh kebijakan negara. Anak laki-laki diajarkan untuk menjadi maskulin, sedangkan anak perempuan diarahkan untuk menjadi feminin. Ketika mereka tumbuh dewasa, konsep superioritas laki-laki semakin mengakar.
“Sampai mati pun, kalau tidak ada kesadaran akan norma-norma maskulin yang merusak dan menindas, mereka akan terus menjadi laki-laki seperti yang dikonstruksikan secara sosial: harus maskulin, harus menguasai, harus mengontrol, dan harus lebih tinggi daripada yang dianggap feminin,” lanjut Mamik.
Ketimpangan relasi kuasa ini semakin berbahaya ketika memasuki ruang privat. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa femisida intim—pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan—adalah bentuk femisida yang paling umum terjadi. Menurut Mamik, hal ini terjadi karena pelaku memiliki keleluasaan lebih di ruang domestik, tempat kekerasan sering kali tidak terlihat oleh publik.
“Dalam kriminologi, kami melihat angka-angka kejahatan terhadap perempuan, termasuk femisida, yang tercatat oleh Komnas Perempuan, NGO, bahkan lembaga internasional, hanyalah puncak gunung es. Jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari yang tercatat,” tegasnya.
Baca juga: Cukup Sudah: Hentikan Eksploitasi Kematian Korban Kekerasan Seksual!
Femisida bukan sekadar pembunuhan berencana
Femisida bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi masalah struktural yang harus ditangani secara serius oleh negara. Saat ini, pelaku femisida seperti Edi dan Antok dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
“Karena sudah direncanakan dari awal—seperti yang dilakukan Edi yang menggali lubang sebelum membunuh istrinya—maka dia dikenakan pasal pembunuhan berencana,” ujar Aipda Abdul Rahman.
Namun, menurut Mamik, femisida tidak bisa disamakan dengan pembunuhan berencana biasa. Kejahatan ini memiliki dimensi lain yang lebih dalam, yakni kebencian terhadap perempuan, perendahan, dan misogini. Maka dari itu, femisida membutuhkan regulasi khusus, baik berupa pasal tambahan dalam KUHP maupun undang-undang tersendiri, yang mengakui kekhususan kejahatan ini.
Hukum yang ada saat ini hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan konteks dan pengalaman korban. Padahal, femisida harus diperlakukan sebagai kejahatan berbasis gender yang memiliki pola sistemik.
“Memperlakukan femisida secara khusus berarti mengakui pengalaman korban yang berbeda dari kasus pembunuhan biasa, serta memahami bahwa kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari budaya misoginis yang lebih besar,” jelas Mamik.
Selain memberikan pengakuan hukum terhadap femisida, negara juga harus memastikan bahwa masyarakat memahami akar masalahnya, yaitu misogini yang telah mengakar dalam sistem sosial. Keberhasilan menangani femisida tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender.
Sampai kapan kita akan membiarkan perempuan terus menjadi korban hanya karena ego laki-laki yang terluka?
Ilustrasi oleh Karina Tungari