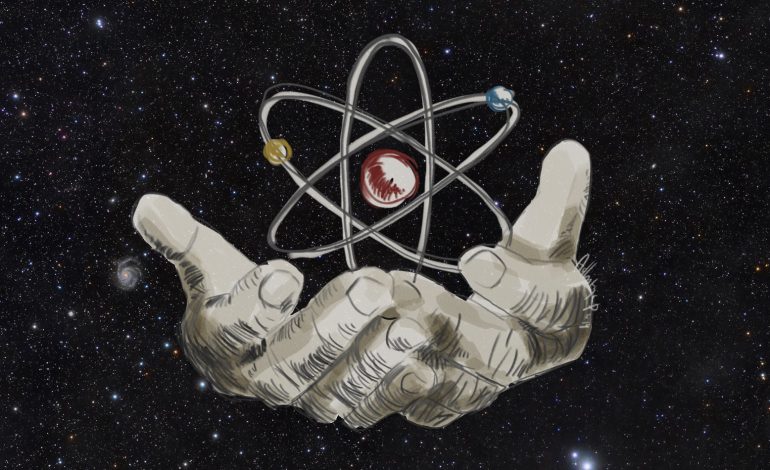Film Sebagai Katarsis Bagi Penyintas Kekerasan Seksual

Ari Aster, sutradara film horor Midsommar (2019), pernah mengatakan dalam suatu wawancara bahwa film favoritnya tahun ini adalah The Souvenir (2019). Berhubung keduanya menceritakan hubungan yang toksik, saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang ia alami? Seberapa besar sebuah karya bisa membantu luka batin untuk pulih?
Beberapa waktu lalu Magdalene menerbitkan artikel yang membahas kepahitan mengenai kemiripan tokoh di serial Hotel Del Luna dan korban kekerasan seksual di lapangan: hingga pada akhirnya pun, tak ada keadilan. Perasaan tersebut serupa dengan ketika saya membaca akhir novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dari Eka Kurniawan. Tanpa ingin terlalu spoiler, kepuasan “dendam” tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar tokoh perempuannya.
Daripada menikmati karya yang terlalu dekat dengan realitas yang sudah suram, saya cenderung memilih film yang bersifat katarsis. Sebagai orang yang pernah berada dalam hubungan yang toksik, saya menghayati Phantom Thread (2018), selain Midsommar dan The Souvenir. Tentu saja, dalam kenyataannya, saya tidak akan meracuni atau membakar (mantan) pasangan. Namun melihat hal itu terjadi di film memberikan semacam kelegaan dan keberdayaan, meskipun semu.
Sebagai penyintas kekerasan seksual, menonton film-film seperti Elle (2017), Revenge (2018), bahkan film horor Shutter (2004), cukup memberikan kepuasan. Di dalam dunia nyata yang tidak memberikan keadilan baik secara sosial maupun hukum, menonton aksi fiktif main hakim sendiri merupakan sarana khayal yang asyik.
Meski demikian, metode ini tidaklah selalu tepat bagi setiap orang. Saya tidak serta-merta menyarankan hal di atas. Itu hanya merupakan opsi bahwa ada karya-karya yang tidak selalu berbanding lurus dengan kehidupan yang menyebalkan. Tetapi tentu saja tiap pilihan memiliki konsekuensi dan kontroversinya masing-masing.
Baca juga: ‘Pengabdi Setan’: Simbol Kekerasan terhadap Perempuan
Perspektif kontroversial pertama datang dari film-film yang memiliki genre pembalasan dendam, terutama untuk kejahatan pemerkosaan. Sejak I Spit on Your Grave (1978), film dengan tema tersebut kerap dikaitkan dengan eksploitasi kekerasan dan (seksualitas) perempuan. Pembuatnya pun kebanyakan laki-laki yang dianggap tidak memahami bagaimana penyintas menghadapi masalahnya. Anne Billson, yang menulis sejumlah novel bertema horor, menegaskan pentingnya sensitivitas akan hal ini.
Perspektif pembalasan dendam dan aksi yang mengandung kekerasan kerap juga dikaitkan dengan maskulinitas semata. Hal itu dipandang tidak sejalan dengan upaya-upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan, yang sering melibatkan dialog yang ramah, pencegahan yang damai, serta tuntutan perubahan sistem yang maju amat perlahan karena dihambat di sana sini.
Dalam ranah kesehatan mental, dendam juga dianggap sebagai sesuatu yang kontra-produktif. Banyaknya opsi penanganan trauma, luka batin, dendam, dan kemarahan saat ini sebetulnya menyediakan sarana bagi penyintas untuk memiliki mekanisme penyelesaian (coping) yang lebih adaptif. Meditasi, pelatihan kesadaran, terapi trauma berbasis CBT (terapi perilaku kognitif) dan transpersonal, hanya sebagian contoh di antaranya. Tentu saja, prosesnya akan lebih panjang, mendalam, tak jarang memakan biaya, serta membutuhkan kesiapan.
Lebih lanjut, hal ini tentunya tidaklah dianjurkan jika memicu trauma. Karena mengandung konten yang sensitif, diharapkan penyintas memiliki saringan mengenai apa yang ia bisa nikmati dan apa yang tidak. Sebagai contoh, saya lebih memilih untuk tidak menonton 27 Steps of May (2018), tetapi cukup santai menonton Elle. Meski 27 Steps of May konon lebih berempati terhadap penyintas dan lebih realistis, konklusi dalam film Elle lebih memberikan rasa aman dan berdaya.
Selain itu, ada beberapa ketakutan terjadinya hal-hal yang memberikan “inspirasi” dalam kehidupan nyata. Jika jatuh ke tangan yang salah, beberapa film atau karya sastra pernah menjadi sumber motivasi orang untuk berbuat di luar batas dan kriminal. Kejadian semacam ini tentunya perlu diwaspadai.
Baca juga: ‘Surviving R. Kelly’ Sadarkan Saya Akan Kekerasan Seksual yang Saya Alami
Di sisi lain, menikmati karya yang bersifat katarsis juga memiliki manfaat secara psikologis. Norbert Wiley, dalam artikel “Emotion and Film Theory” (2003), menjelaskan bahwa menonton film dapat melepaskan emosi negatif, termasuk di antaranya agresi, tanpa harus melakukan sesuatu yang berbahaya dan mendapatkan konsekuensi di dunia nyata. Film (dan karya seni lain) secara alami dapat “memindahkan” penontonnya ke sebuah “tempat” di mana emosi yang terasa menyesakkan bisa dihadapi dengan cara yang lebih mudah, terutama jika hal itu membuat penikmatnya merasakan keterkaitan dengan tokoh di dalamnya.
Selain menjadi penikmat, seseorang juga dapat menghasilkan karya yang berhubungan dengan luka batin yang dialaminya. Beberapa penelitian menunjukkan, baik terapi seni yang sudah valid sebagai intervensi psikologis maupun contoh lain seperti menulis roman a clef (tokoh asli muncul dengan nama lain) maupun film semi-autobiografi, media seni dapat menjadi sarana pemulihan yang efektif.
The Souvenir diangkat dari kisah nyata Joanna Hogg tentang hubungannya dengan pecandu heroin yang hobi memanipulasi. Midsommar, meski ceritanya fiktif, dibuat dari pengalaman patah hati Ari Aster. Dalam ranah yang lebih luas, Shia Labeouf membuat film berjudul Honey Boy (2019) mengenai relasinya yang sulit dan cenderung penuh kekerasan dengan sang ayah.
Secara garis besar, pilihan untuk mengeluarkan emosi dengan metode menonton, membaca, atau menikmati dan membuat karya lain merupakan salah satu metode yang bisa dipilih meski dampaknya ada pada dua sisi mata uang. Tentunya luka batin dan trauma tidak akan sampai ke mana-mana jika tidak dibarengi oleh bantuan dari sekitar, misalkan adanya sistem pendukung atau mencari bantuan profesional. Jika diimbangi dengan penanganan yang tepat, metode ini bisa menjadi alat yang sejalan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi sarana eskapisme belaka.
Di luar itu, tidak perlu jugalah merasa terlalu “maskulin”, kejam, atau bersalah karena menikmati sesuatu yang beraroma dendam atau agresi. Semua orang memiliki cara dan seleranya masing-masing. Selama tidak mengganggu keseharian dan membahayakan, anggap saja itu hobi yang menyenangkan. Kemarahan dan dendam merupakan reaksi yang muncul dari banyak emosi lainnya, seperti sedih, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Hal ini amat manusiawi. Tidak perlu menyangkal keberadaannya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita menerima, merangkul, dan mengelolanya.