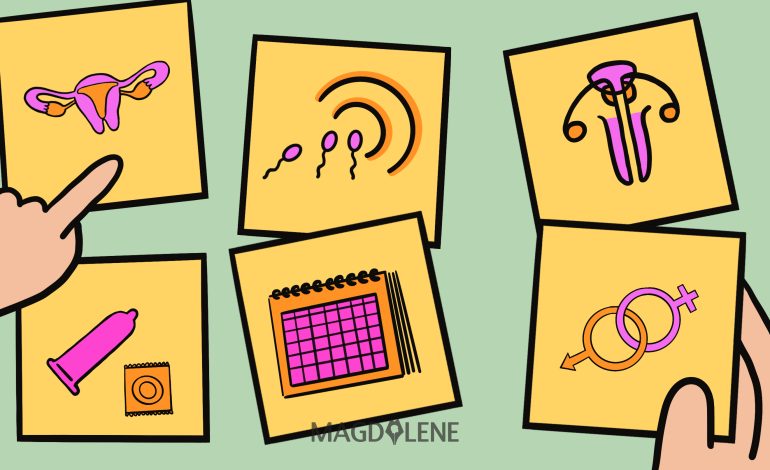Gen Z Tidak Percaya pada Sistem Korporasi dan Reformasi, Mereka Ingin Revolusi

Banyak institusi kapitalis saat ini menuai dampak buruk akibat politik kroni, keserakahan, dan pola pikir jangka pendek. Tapi, berbicara kapitalisme tak hanya tentang bobroknya saja, atau dampak negatif yang terjadi karena tindakan kelompok elite yang serakah.
Merombak kapitalisme dimulai dengan reformasi, yang berarti memberlakukan perubahan-perubahan di dalam struktur yang ada.
Baca juga: Klientelisme Politik: Ketika Untung-rugi Elite Mengorbankan Demokrasi
Menariknya, kelompok terkini yang memasuki angkatan kerja, yakni Gen Z, punya tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem korporasi. Mereka enggan “bermain” di sistem yang aturan mainnya sulit mereka percayai.
Meski riset tentang Gen Z belum banyak, kita tahu bahwa Gen Z tampak tidak terlalu melibatkan diri secara sosial (civil engagement) dan enggan bekerja sama dalam tim.
Selain itu, menurut studi terkini dari perusahaan nirlaba Ethisphere, Gen Z termasuk salah satu yang paling gencar mengadopsi komitmen-komitmen etis, namun sekaligus yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk melaporkan adanya perilaku buruk di tempat kerja. Hampir 39% responden Gen Z memilih tidak melaporkan pelanggaran yang mereka lihat – selisih 11 poin dari kolega Gen X dan Baby Boomer mereka.
Pekerja Gen Z tidak percaya bahwa melaporkan pelanggaran dan perilaku buruk di tempat kerja itu sepadan dengan potensi bahwa mereka bisa mendapatkan perlawanan balik atau bahkan hukuman. Mereka juga ragu bahwa pelanggaran tersebut akan benar-benar ditindak.
Jadi, bagaimana Gen Z bisa menjadi agen reformasi yang efektif di tengah sistem yang tidak mereka percayai?
Kehilangan Kepercayaan
Studi dari Ethisphere tersebut menemukan bahwa semakin muda seorang pegawai, semakin rendah kepercayaannya terhadap kebijakan korporasi yang dirancang untuk mencegah perlawanan balik ketika ada laporan. Temuan ini pun selaras dengan data lebih luas yang menunjukkan bahwa Gen Z memang cenderung tak percaya dengan institusi secara umum.
Kenapa ini penting?
Studi akademik menjelaskan bahwa korporasi didorong oleh logika-logika institusi – yakni pola praktik, nilai, dan aturan historis yang dikonstruksikan secara sosial, yang memandu kegiatan sehari-hari dalam lingkungan korporat.
Beragam logika institusional ini berkaitan dengan dampak historis dari lingkungan kerja terdahulu (imprinting). Proses ini pun melampaui sejarah itu sendiri – dampak dari imprinting organisasi bervariasi seiring waktu, merefleksikan keterikatan antara masa lalu dan masa kini, mengingat ia terus bertahan meski lingkungan sosial berubah.
Baca juga: Gen Z Manfaatkan TikTok sebagai Ruang Berekspresi dan Negosiasi Identitas Lokal
Organisasi berpatokan pada logika-logika yang telah mengakar ini untuk menunjang citra mereka dan membantu kita memahami lingukungan sosial, serta sebagai panduan kita berperilaku dalam organisasi.
Perlawanan dan kritik terhadap logika institusional yang sudah usang ini, kini telah berujung pada lingkungan yang mampu berubah. Misalnya, ada masanya ketika logika institusional yang dominan, terutama yang terkait tujuan perusahaan, hanya berfokus pada peningkatan profit.
Akibat perlawanan dan kritik selama beberapa dekade, kini kita menyaksikan adanya logika institusional baru. Tujuan dari korporasi kini telah didefinisikan ulang untuk melibatkan seluruh pemegang kepentingan (stakeholder) – bukan hanya pemegang saham (shareholders) – dari kegiatan korporasi.
Pergeseran dari logika shareholder ke stakeholder ini merepresentasikan perubahan 180 derajat dari pola pikir institusional terdahulu. Cara-cara lama, meski telah mendarah daging, kini menjadi ditantang ketika para pemimpin korporasi dihadapkan dengan cara-cara baru untuk menjalani dan melihat berbagai hal.
Tidak Ada Jalan Pintas untuk Transformasi
Meski kepercayaan-kepercayaan yang terinternalisasi serta kebiasaan-kebiasaan lama kini akhirnya mulai dipertanyakan, perubahannya cukup lambat. Riset terkait teori institusi menunjukkan bahwa konflik antara nilai lama dan baru akan terselesaikan melalui perubahan-perubahan yang bersifat episodik atau bertahap.
Perubahan semacam ini melibatkan periode-periode ketika organisasi menjadi terbuka bagi orang-orang untuk menerapkan perubahan bermakna, tapi juga diselangi periode-periode stabil ketika tidak ada perubahan yang terjadi.
Bisa dipahami kenapa kaum muda bisa jadi memandang bahwa revolusi itu lebih menarik ketimbang reformasi. Akan tetapi, kita butuh pemimpin masa depan yang terbuka terhadap realitas bahwa perubahan yang bermakna dan tahan lama itu sifatnya inkremental (sedikit demi sedikit). Perlu kesabaran dan komitmen.
Baca juga: 4 Isu yang Perlu Diutamakan di Pemilu 2024 Menurut Generasi Z
Perubahan akan datang, misalnya, dari para milenial yang menuntut para bisnis kapitalis untuk memprioritaskan produk dan pekerjaan berkualitas di atas profit, dan juga seluruh pekerja yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik dari organisasi mereka.
Apalagi, kini semakin menjamur beragam standar dan produk yang menambah kompleksitas etika bisnis – namun banyak korporasi tak benar-benar menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Perubahan juga akan terjadi ketika orang-orang menolak untuk melanggengkannya.
Keraguan Gen Z Bukan Tak Beralasan, Sistem Harus Berubah
Gen Z benar untuk tidak percaya sistem yang ada saat ini. Penulis dan komentator politik David Frum menjelaskan kepada saya beberapa tahun lalu, bahwa “koalisi apa pun yang mengupayakan reformasi perlu memperhatikan masalah kaum muda dengan serius.”
Frum mengamati bahwa, selama kelompok elit menggambarkan bahwa “‘kapitalisme’ itu ciri-cirinya adalah standar hidup yang stagnan, hutang pendidikan yang menggunung, biaya perawatan anak yang mahal, hingga ancaman bencana lingkungan,” mereka akan terus mencari alternatif.
Selain itu, tak hanya Gen Z yang kehilangan rasa kepercayaan. Survei tahun 2022 di Amerika Serikat (AS) menemukan bahwa kepercayaan publik pada pemimpin bisnis dan politikus mencapai titik terendah dalam sejarah. Survei di Kanada setahun sebelumnya menyoroti tren yang mirip.
Mungkin, lebih mengkhawatirkan lagi, adalah suatu survei yang menemukan bahwa hanya sepertiga orang Kanada yang yakin bahwa sesama warga negara lainnya dapat dipercaya, terlepas dari identitasnya.
Kepercayaan (“trust”) telah didefinisikan sebagai “rasa saling percaya bahwa tidak ada pihak dalam suatu hubungan yang akan mengeksploitasi kerentanan pihak lainnya.” Sebaliknya, seberapa suatu pihak dapat dipercaya (“trustworthiness”) bisa dipahami sebagai “sifat layak dipercaya oleh orang lain untuk tidak mengeksploitasi ketiadaan transparansi informasi (adverse selection), risiko moral (moral hazard), keterbatasan kontrak (holdup), atau bentuk kerentanan lainnya dalam transaksi.”
Dalam pemikiran kapitalisme konvensional, menjadi pihak yang dapat dipercaya itu biasanya dilakukan jika bisa menghemat biaya. Kita perlu beranjak dari pandangan yang cenderung terlalu sempit ini.
Ketika kaum muda tidak percaya pada sistem, prioritas tertinggi dari rezim kekuasaan dan korporat adalah membangun kembali kepercayaan itu. Upaya untuk bisa dipercaya dan meraih predikat trustworthiness tersebut adalah hal yang akan meyakinkan generasi selanjutnya yang skeptis akan institusi yang ada, untuk bekerja sama dengan kita melakukan reformasi.![]()
David Weitzner, Assistant professor, Administrative Studies, York University, Canada
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.