Lelah, Lugu, Hampir Jadi Korban: Catatan Perempuan dari Tepi Kekerasan Digital
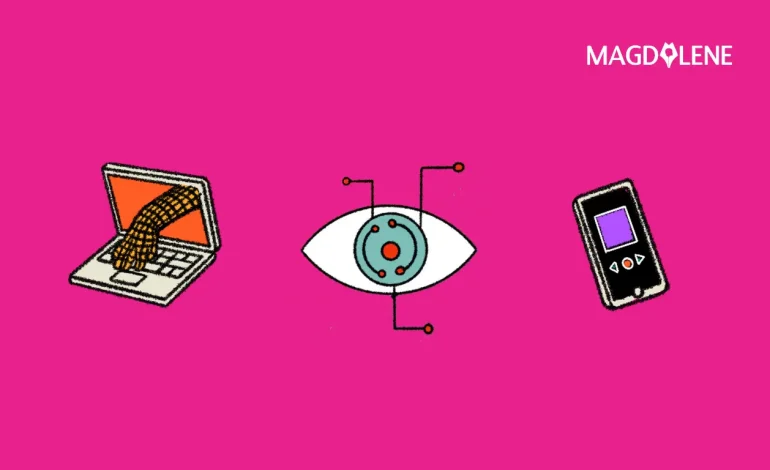
Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa rapuh. Saya baru lulus kuliah, kehilangan pekerjaan, dan harus bertahan di kota besar yang bergerak jauh lebih cepat daripada tenaga yang saya punya. Orang-orang di sekitar saya tampak berjalan dengan arah yang jelas, sementara saya masih bingung memikirkan cara membayar sewa bulan depan. Bangun pagi saja rasanya sudah seperti pekerjaan penuh waktu.
Di tengah kelelahan itu, malam-malam saya dihabiskan dengan menggulir media sosial tanpa tujuan. Bukan mencari informasi, hanya mencari jeda dari kecemasan. Sampai suatu malam, sebuah reel lowongan kerja muncul di beranda Instagram. Nama perusahaannya familiar: sebuah badan usaha besar milik pemerintah Sulawesi Selatan. Posisi yang ditawarkan beragam, dari admin sampai management trainee. Syaratnya sederhana, cukup kirim CV dan dokumen lewat alamat email yang tertera.
Alamat emailnya memakai Gmail, bukan domain resmi institusi. Ada sesuatu dalam diri saya yang berbisik bahwa ini aneh, tapi suara itu pelan sekali. Satu hal tentang kelelahan, kondisi itu membuat kita longgar pada hal-hal yang biasanya kita curigai. Di momen itu, saya memilih mendengarkan harapan, bukan kewaspadaan. Saya ingin percaya bahwa kali ini semesta sedang memberi saya kesempatan.
Maka saya kirimkan semuanya: CV, fotokopi ijazah, KTP, dan beberapa sertifikat. Seluruh identitas saya meluncur dalam satu klik.
Keesokan, sebuah email masuk yang menyatakan saya “lulus seleksi administrasi”. Di tengah lorong gelap yang saya jalani, kalimat itu terasa seperti cahaya kecil. Mereka mengabarkan bahwa saya harus mengikuti tes psikologi di kantor pusat di Jakarta dan meminta saya segera menghubungi “agen perjalanan” yang bekerja sama dengan mereka.
Tak lama kemudian, agen itu menelepon. Suaranya ramah, tegas, dan terdengar sangat profesional. Ia meminta saya segera mengecek harga tiket pesawat dari Makassar ke Jakarta dan membandingkan beberapa aplikasi. Katanya, proses ini harus cepat karena jadwal tes padat dan kuota terbatas. Semua terdengar genting, mendesak, dan meyakinkan.
Di sela-sela urgensi itu, pertanyaan-pertanyaan pelan mulai muncul di kepala: kapan lowongan ini sebenarnya dibuka? Mengapa tidak ada pengumuman di situs resmi? Apakah semua kandidat benar-benar diterbangkan ke Jakarta? Mengapa semua informasi penting hanya lewat telepon?
Setiap kali saya bertanya, jawabannya sama: “Kami hanya agen, Mbak. Semua wewenang dari BUMD.”
Kecurigaan saya tumbuh, tapi rasa lelah dan terdesak membuatnya mudah saya tekan. Sampai akhirnya, seorang teman kuliah yang sedang main ke rumah ikut mendengar percakapan kami. Ketika di ujung telepon mereka mulai meminta saya melakukan transfer uang via ATM, teman saya langsung memberi isyarat agar saya menutup telepon.
Ia mencoba menelepon balik untuk memastikan. Nada suara di seberang langsung berubah. Topeng keramahtamahan hilang, aksen asli mereka keluar, dan dalam hitungan detik kami paham: mereka bukan BUMD, bukan agen profesional. Mereka sindikat penipuan yang memanfaatkan keputusasaan orang-orang seperti saya.
Saat itu juga saya merasa seperti baru saja ditarik paksa dari tepi jurang. Tidak ada uang yang berpindah, tapi saya sudah telanjur menyerahkan sesuatu yang berharga: data pribadi, rasa percaya, dan keyakinan saya pada naluri sendiri.
Baca Juga: Tips Cegah Kekerasan Verbal di Ruang Digital
Kekerasan digital yang menyamar sebagai harapan
Pengalaman itu mengubah cara saya memandang kekerasan digital. Selama ini saya mengira kekerasan berbasis teknologi hanya berupa ancaman terbuka, doxing, atau pelecehan vulgar di kolom komentar. Nyatanya, ia juga bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih halus: kesempatan palsu, lowongan kerja impian, simpati yang direkayasa dengan rapi. Bukan hanya menakuti, tapi memikat.
Kejahatan digital bekerja paling efektif ketika kita sedang lelah dan butuh pegangan. Saat ekonomi sedang sulit, ketika rasa percaya diri menurun, waktu hari-hari terasa seperti rangkaian kegagalan. Di momen seperti itulah “tawaran baik” terasa terlalu sayang untuk dilewatkan, meski ada alarm kecil yang berbunyi di belakang kepala.
Karena itu, menyebut kasus seperti yang saya alami sebagai sekadar “kurang hati-hati” rasanya tidak adil. Kekerasan digital harus dilihat sebagai kekerasan yang menyasar kerentanan manusia. Kita tidak hanya diserang sebagai pengguna internet, tetapi sebagai manusia yang sedang berjuang menyambung hidup.
Tidak semua perempuan punya akses ke literasi digital yang memadai dan ruang aman untuk bertanya tanpa dihakimi. Tidak selalu kita punya teman yang siap mengintervensi seperti yang dilakukan teman saya hari itu. Banyak yang baru menyadari jebakan ketika uang sudah hilang, foto sudah tersebar, dan identitas sudah dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah mereka setujui.
Baca Juga: Rentan jadi Korban Kejahatan, Alasan Perempuan Suka ‘True Crime’
Karena itu, kita membutuhkan lebih dari sekadar imbauan “jangan sembarang klik”. Kita butuh komunitas yang saling menguatkan, media yang berani mengangkat cerita-cerita seperti ini tanpa menyalahkan korban, dan ruang belajar yang mengakui bahwa rasa lelah dan putus asa adalah celah yang nyata, bukan kelemahan pribadi.
Saya menulis pengalaman ini dengan jujur, meski malu, karena saya ingin perempuan lain tahu: kita tidak bodoh, tidak juga sekadar ceroboh. Kita sedang mencoba bertahan di dunia yang sering kali tidak ramah, dan para pelaku kekerasan digital memang ahli membaca celah di antara lelah dan harapan kita.
Jika kamu pernah berada di posisi serupa, izinkan saya mengatakan ini: kerapuhanmu bukan dosa. Percayamu yang tulus atau cacat karakter. Dan perjalananmu untuk menemukan kembali rasa aman tidak perlu kamu jalani sendirian.
Mari kita saling jaga, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Kekerasan digital mungkin tidak akan hilang dalam semalam, tapi setiap cerita yang berani kita bagi adalah satu langkah kecil untuk membuat para pelaku kehilangan tempat bersembunyi.
Dan bagi saya, malam itu menjadi pengingat penting. Di era serba digital, belajar curiga bukan berarti berhenti berharap, melainkan belajar melindungi diri sendiri dan satu sama lain.






















