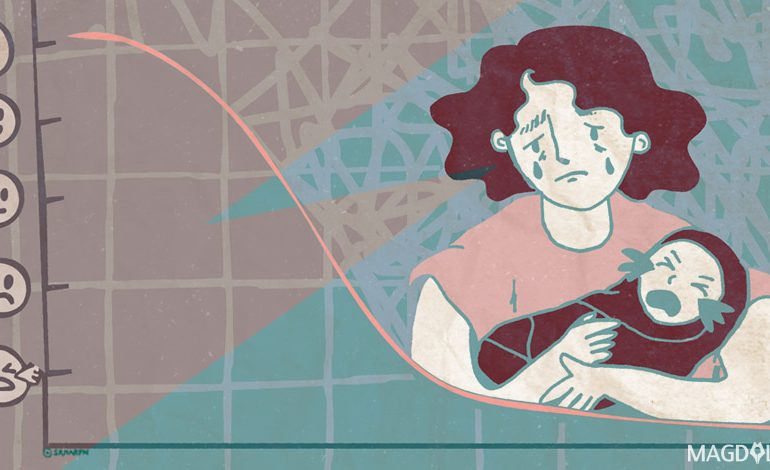
Desember kali ini datang seperti jeda yang dipaksakan. Di kalender, kita sampai pada 22 Desember 2025, Hari Ibu. Tapi di ruang publik, 2025 terasa jauh dari suasana perayaan. Terutama bagi ibu-ibu korban banjir di Sumatra, yang merayakan Hari Ibu dari posko-posko pengungsian.
Tahun ini ditandai oleh tagar #IndonesiaGelap dan gumam “#KaburAjaDulu”, humor getir yang mengubah putus asa menjadi kalimat ringan. Ketika masa depan terasa makin sempit, “pergi” terdengar lebih realistis daripada “berjuang.” Kegelisahan itu seperti penanda bahwa banyak anak muda merasa jaring pengaman sosial dan peluang hidup kian rapuh.
Gelombang protes memuncak pada akhir Agustus 2025. Sejumlah media melaporkan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang tewas setelah tertabrak kendaraan polisi saat demonstrasi di Jakarta. Amnesty International Indonesia juga mencatat penangkapan massal, kekerasan aparat terhadap demonstran, serta kriminalisasi ekspresi damai yang terus berulang bahkan setelah aksi mereda.
Lalu, seolah belum cukup, Sumatra memasuki November–Desember dengan air yang tidak berhenti. Banjir besar melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam rangkaian bencana hidrometeorologi. Menjelang pertengahan Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal telah melampaui seribu orang, dengan ratusan lainnya dilaporkan hilang, terutama di tiga provinsi tersebut.
Di sela kabar duka itu, rasa “Indonesia gelap” juga dipicu oleh cara sebagian pejabat merespons krisis. Alih-alih bahasa empati, yang muncul justru nada meremehkan, seolah penderitaan warga hanyalah angka, bukan tubuh yang kehilangan rumah dan rasa aman. Bahkan saat solidaritas publik bergerak—dari dapur umum, donasi warga, sampai bantuan dari negara tetangga—respons yang keluar kadang terdengar sinis atau merendahkan, seperti gengsi lebih penting daripada nyawa. Yang membuat gelap bukan hanya air yang naik, tetapi juga jarak emosi antara kekuasaan dan warga—ketika bahasa negara tidak memeluk duka warganya.
Baca Juga: Hari Ibu di Indonesia: Sejarah, Perjuangan, dan Maknanya
Hari Ibu: “Berdaya” di negara yang membatasi suara
Di tengah latar seperti ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menetapkan tema Hari Ibu 2025: “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Saya ingin memperlakukan tema itu sebagai titik diskusi, bukan slogan seremonial. Berdaya seperti apa, dan berkarya yang mana, ketika banyak orang justru merasa tidak berdaya? “Indonesia Emas” itu menyala untuk siapa, bila begitu banyak keluarga memadamkan mimpi mereka sendiri agar bisa bertahan sampai besok?
Rasa berdaya, sesederhana apa pun, butuh ruang yang aman untuk bicara. Tetapi ketika, seperti dicatat Amnesty International Indonesia, orang ditangkap karena menyampaikan aspirasi dan kekerasan terhadap demonstran dipertontonkan lalu dianggap biasa, pesan yang sampai ke rumah-rumah sederhana adalah, diam lebih aman daripada bicara. Bagi banyak ibu, “berdaya” bukan soal pencapaian diri, melainkan soal bertahan. Apakah anaknya pulang dengan selamat selepas aksi atau justru ditangkap dan diproses hukum. Besok anak makan apa. Obat demam masih ada. Air bersih dapat dari mana. Saat banjir datang, daftar itu berubah menjadi daftar darurat.
Lalu ada kata “berkarya” yang sering dimaknai sempit, seolah karya hanya yang bisa dijual, dipamerkan, atau dicatat dalam laporan. Sementara kerja-kerja perawatan—memasak, merawat orang sakit, memastikan keluarga selamat saat bencana, mengelola air, sampah, dan ketahanan pangan rumah tangga—masih disebut “kodrat” atau “pengorbanan.” Padahal itu kerja, butuh pengetahuan, waktu, tenaga, juga biaya. Kerja semacam ini menopang aktivitas orang lain dan menjaga keluarga tetap berjalan. Perempuan bukan “petugas perawatan” gratis.
Baca Juga: 22 Desember adalah Hari Pemberdayaan Perempuan, Bukan Hari Ibu
Jika tema Hari Ibu 2025 serius, ukurannya harus berubah
Dalam bencana, pembagian beban terlihat jelas. Negara hadir lewat posko, data, dan rapat koordinasi—sering terlambat. Pasar hadir lewat harga yang naik dan logistik yang macet. Sementara rumah, tempat perempuan paling sering “dititipkan,” menjadi lokasi semua krisis diselesaikan. Perempuan paling lama bertahan di wilayah terdampak, paling lama mengurus kebutuhan harian, paling sering mengakses layanan kesehatan untuk anak, dan paling jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kita menyebut mereka “kelompok rentan,” padahal mereka juga penyokong utama agar keluarga tidak ambruk total.
Di tengah tahun yang gelap, saya melihat kerja-kerja kecil yang sering luput dianggap “karya.” Sejak pandemi 2020, kami mengembangkan Rumah Nutrisi Keluarga (Rumah Nusa): menanam dengan pengetahuan agar pekarangan menjadi cadangan pangan dan obat keluarga. Ketika banjir menutup akses pasar, cadangan “kecil” ini menyelamatkan keluarga pada dua-tiga hari pertama—fase paling rawan dalam bencana.
Jika “berdaya” mau jujur, ia harus berarti ruang bicara yang aman dan pertanggungjawaban ketika terjadi kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat. Ia juga harus berarti penanganan bencana yang memusatkan kebutuhan sehari-hari—air bersih, layanan kesehatan, perlindungan—bukan menganggap kerja perawatan sebagai urusan domestik “nanti diatur ibu-ibu.”
Dan jika “berkarya” mau adil, ia perlu memberi tempat yang layak bagi kerja perawatan. Pada cara negara menyusun anggaran, layanan, dan perlindungan sosial. Bukan sebagai catatan kaki, apalagi sekadar jargon.
Hari Ibu seharusnya bisa jadi momen menilai apakah negara benar-benar membuat hidup keluarga lebih aman dan lebih mungkin dijalani dengan tenang. Tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” akan bermakna jika ia turun ke hal-hal yang bisa dirasakan sehari-hari: rasa aman, kebutuhan dasar saat krisis, dan penghargaan yang nyata pada kerja yang selama ini menopang rumah.
Dengan begitu, “Indonesia Emas” tidak dibangun di atas kerja perempuan yang tak terlihat—dan pertanyaan “berdaya dan berkarya untuk siapa?” tidak berhenti sebagai hiasan pidato, tetapi mendapat jawaban yang bisa diuji.






















