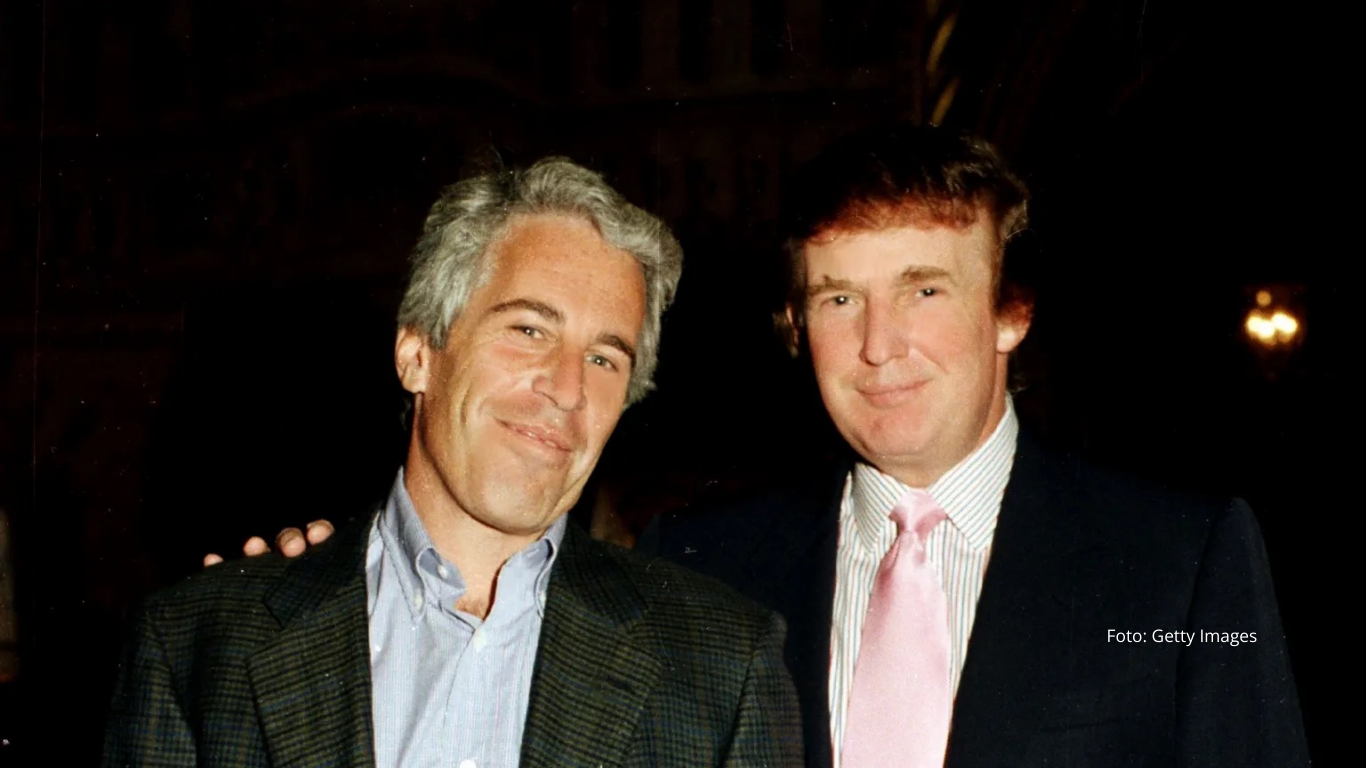Kenapa Pemecatan Massal VICE dan Masa Depan Buruk Jurnalisme Tak Mengejutkan?

Pekerjaan jurnalis, kalau boleh jujur, sebetulnya tak pernah seksi dan “menjanjikan”.
Tahun 2011, ibu mengomel ketika saya masuk organisasi pers mahasiswa di kampus. Buatnya, wartawan bukan profesi yang punya masa depan. Di kantor ibu, sebuah BUMD, wartawan suka ngetem di kantin. Menunggu siapa saja—terutama pejabat atau tamu pejabat—untuk dimintai amplop. “Enggak ada harga diri, enggak ada duitnya,” kata Ibu waktu itu.
Tahun 2013, Ibu sempat mengubah pikirannya saat saya dapat upah Rp1 juta per satu tulisan feature di koran bahasa Inggris, The Jakarta Post. Uang segitu cukup tinggi buat mahasiswa semester tiga di Medan. Dia pikir, upah jadi jurnalis kontributor lumayanlah buat uang saku tambahan anak kuliahan. “Tapi, kalau bisa, ya jangan jadi jurnalis. Nanti cari kerjaan lain,” katanya.
Tahun ini, genap sepuluh tahun saya jadi jurnalis, sudah di tahap mafhum kalau masalah upah tak layak bukan satu-satunya momok di industri jurnalisme kita.
Baca juga: Jauh Panggang dari Api: Idealisme vs Realitas Jadi Wartawan Daerah
Ada masalah Jakarta-sentrisme, ketidaksetaraan gender di dapur redaksi, model bisnis yang goncang, kebebasan pers yang terancam, pemerintah represif, serangan digital dan fisik pada jurnalis, perang dengan hoaks, sampai senjakala jurnalisme alias matinya jurnalisme. Itu semua adalah tumpukan horor yang terjadi di saat bersamaan hari ini. Efek horornya terasa lebih kalau ditumpuk jadi satu paragraf begini.
Hampir dua pekan lalu, saat segerombolan jurnalis VICE kawasan Asia-Pasific ramai muncul di Twitter, mengumumkan pemecatan massal yang dilakukan perusahaan media mereka, pertanyaan ini muncul lagi di pikiran saya:
Akankah jurnalisme betulan mati, kali ini?
Dari Senjakala Media Cetak Sampai Perang dengan Content Creator
Sejak masuk pers mahasiswa dan belajar jurnalisme di sana, isu senjakala media cetak sudah berhembus. Media-media online mulai jadi primadona. Detik jadi salah satu influencer sekaligus penggerak pertama jurnalisme online di Indonesia. Peralihan dari media cetak ke online ini dipengaruhi perubahan cara kita mengonsumsi berita. Internet dan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Tumblr, dan Instagram mulai hadir dan jadi faktor terbesar perubahan itu.
Kami di pers mahasiswa juga berani-beranian bikin media online sendiri, dan mempraktikkan pengorganisasian media ala mahasiswa. Meski dana utama disokong rektorat, SUARA USU, pers mahasiswa tempat saya belajar mewajibkan anggotanya mencari iklan. Bukan cuma belajar tentang cara menulis yang baik, kode etik jurnalisme, dan praktik memproduksi karya jurnalistik lainnya, kami juga belajar tentang usaha memutar roda organisasi media alias cari cuan sembari menjaga idealisme.
Ketika terjun ke industri jurnalisme betulan, tentu saja praktik seimbang itu lebih sulit. Jauh lebih sulit.
Iklan, sebagai pendapatan utama media cetak mulai berkurang. Pada 2004, Pew Research Center mencatat jumlah koran harian di Amerika Serikat terus turun hingga 100 koran. Menurut proyeksi Statista, pendapatan iklan media koran terus turun sejak 2009 (84 miliar dolar) sampai 2014 (73 miliar dolar).
Di Indonesia, data Nielsen 2015 menyebut ada penurunan jumlah koran yang besar dalam rentang 2012-2016. Isu senjakala media cetak makin ramai pada ujung 2016, ketika Sinar Harapan, Harian Bola, Jakarta Globe, dan Koran Tempo Minggu menghentikan penerbitan mereka.
Baca juga: MadgeTalk: Pemberitaan Media Makin Tak Bermakna, Kita Harus Bagaimana?
Pada 2017, belanja iklan di media masih dikuasai TV, diikuti media cetak di posisi kedua. Menurut data Nielsen, ada Rp145 triliun belanja iklan pada tahun itu. Sekitar Rp116 triliun atau 80 persen dibelanjakan ke media TV. Sementara porsi belanja iklan di media cetak turun dari tahun sebelumnya jadi 12 persen, karena berkurangnya media cetak yang beroperasi. Sisa uang belanja iklan itu pindah ke media online.
Di tahun yang sama, saya membuat laporan mendalam (Benarkah Bisnis Media Online Tak Secerah Masa Depan Internet?, 2017) tentang cara media-media cetak besar beradaptasi shifting ke media online. Hasilnya, semua masih kewalahan.
Waktu itu, The Jakarta Post bilang, 75 persen pemasukan utamanya masih datang dari koran. Bisnis Indonesia bilang 65 persen. Cuma Tempo, yang optimis pada model bisnis online mereka karena kenaikan jumlah subscribers pada tahun itu. Meski di saat bersamaan mengakui kalau iklan di media online belum bisa jadi sumber pemasukan utama.
Pada masa itu, banyak media percaya bahwa mengumpulkan pelanggan (subcribers) dan memasang paywall bisa jadi jalan ninja menyelamatkan finansial mereka. Media arus utama macam New York Times dan The Guardian jadi pelopor gerakan itu. Sayangnya, pertaruhan tersebut tak berlangsung lama. Masalahnya, masyarakat kita belum terlalu terikat dengan kebutuhan jurnalisme yang baik. Karya jurnalistik baik-dan-gratis saja tak banyak yang baca, apalagi mereka yang dipasangi pagar dan harus dibayar baru bisa dinikmati.
Belum lagi, memasang paywall berarti membatasi akses menikmati jurnalisme baik hanya untuk kalangan berduit. Dilema itu tak diambil sebagian besar media yang percaya bahwa berita dan karya jurnalistik baik adalah hak semua orang. Namun, bukan berarti mereka tak kewalahan mengumpulkan pembaca loyal yang mau bersedekah buat media mereka.
Jika ingin bertahan, menerima tawaran investor dan uang oligarki jadi cara tak terhindarkan. Pada 2018, saya menulis laporan mendalam tentang peta kepemilikan media di Indonesia. Hasilnya, perusahaan-perusahaan media di Indonesia dikuasai 8 orang konglomerat (8 Konglomerat Media di Indonesia Via Jalur Media TV & Cetak, 2018). Model bisnis media yang dikuasai oligarki bukan hal baru di Indonesia. Merlyna Lim lewat “Mapping Media Concentration in Indonesia” (2011), sudah memetakan 13 kelompok media yang mengontrol semua saham televisi komersial nasional di Indonesia.
Disertasi Ross Tapsell, Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution (2017) memperbarui peta itu. Digitalisasi di media terjadi di bawah kuasa delapan nama konglomerat berikut: Chairul Tanjung (CT Corp), Hary Tanoesoedibjo (Global Mediacom), Eddy Kusnadi Sariaatmadja (EMTEK), Bakrie Group (Visi Media Asia), Surya Paloh (Media Group), Keluarga Riady (Berita Satu Media Holding), Dahlan Iskan (Jawa Pos), dan Jakoeb Oetama (Kompas Gramedia).
Dalam alam oligopoli ini, media-media kecil tak akan punya kuasa melawan media-media besar, apalagi jika tak masuk dalam jaringan mereka. Kemampuan untuk kritis dan menciptakan karya jurnalistik yang menggugat kekuasaan bukan pekerjaan mudah dan murah.
Membuat karya jurnalistik baik memang mahal. Ada ongkos menggaji jurnalis, tenaga desain, manajer website, tenaga pemasaran, tenaga pencari iklan, biaya asuransi mereka, sewa kantor, listrik, internet, dan kebutuhan lainnya. Sementara, sekali lagi, tak semua orang—atau belum—merasa butuh mengonsumsi berita yang baik.
Di era digital, cara mengonsumsi berita betul-betul berubah. Artikel panjang dan tulisan-tulisan mendalam makin kehilangan tempat di media. Alasannya, attention span atau rentang perhatian seseorang saat membaca makin berkurang. Tumblr dan Tiktok mengubah cara kita memperhatikan konten. Orang-orang lebih suka dan gampang tergaet meme atau video pendek berdurasi kurang dari semenit.
Perubahan ini bikin dapur redaksi putar otak. Di sanalah ceruk media seperti VICE dan Buzzfeed News hadir. Mereka dikenal sebagai pelopor penggunaan konten “viral” dalam praktik jurnalisme. Peralihan cara baca dan mengonsumsi media ke digital dimanfaatkan dua media ini untuk mengadaptasi karya jurnalisme.
Sayangnya, Vice, perusahaan berita global dan TV yang valuasinya mencapai 5,7 miliar dollar pada 2017, terancam bangkrut. Perusahaan yang memiliki aset Vice News, Motherboard, Refinery29, dan Vice TV ini bahkan sudah lebih dulu menutup program populer mereka, Vice News Tonight, dan memecat 100 orang staf.
Buzzfeed juga menutup Buzzfeed News, kanal berita mereka yang terkenal karena kredibilitas karya jurnalistiknya. Di sebuah penelitian dari Nanyang Technological University, Singapura, berita Buzzfeed News dinilai setara The New York Times. Bahkan, saat kebanyakan berita NYT diisi oleh terorisme dan kriminalitas, berita Buzzfeed News dinilai lebih banyak mengangkat protes dan isu sosial.
Dua perusahaan media itu konon akan lebih fokus pada pembuatan konten, ketimbang jurnalisme.
Sejak media sosial jadi ladang pembuat konten (content creators), profesi jurnalis makin terancam. Kepemilikan media yang dikuasai pedagang alias pebisnis mempermudah ancaman itu. Dengan alasan biaya produksi yang tinggi dan pemasukan yang menurun, perusahaan-perusahaan media dengan santai mengurangi—kalau tak mau dibilang memangkas habis—lini dapur redaksinya.
Sejak iklan media cetak pindah perlahan ke ranah digital, saingan media berita memang bukan lagi sesamanya. Melainkan dengan perusahaan-perusahaan iklan (adverstising) raksasa macam Google, Facebook, Amazon, dan sepantarannya. Mereka mampu memproduksi konten-konten yang dianggap bisa menggantikan berita atau produk jurnalistik. Data Nielsen terbaru (2022), menyebut ada 64 persen kenaikan pemasukan iklan untuk media digital di Asia (Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan).
Tsunami informasi—yang diprediksi jurnalis dedengkot Bill Kovach dan Tom Rosenstiel akan jadi tantangan jurnalisme, dalam buku mereka Blur—kemudian hadir lewat timbunan konten itu. Orang-orang yang tidak mengerti proses dan pentingnya jurnalisme akan tenggelam dalam gelembungnya sendiri.
Sejumlah media sempat beradaptasi, dan menjadikan jurnalis mereka pembuat konten. Vox misalnya hadir dengan series Glad You Asked, dan mencoba mengoptimalkan Youtube mereka dengan konten-konten berkualitas jurnalisme baik, tapi tetap menarik buat viewers muda.
Kenyataannya, produksi jurnalisme baik memang mahal. Mereka masih memproduksi video-video indepth dengan durasi lama, tapi lebih fokus menghasilkan video-video grafis pendek demi kuantitas yang disyaratkan algoritma Youtube. Sejumlah jurnalisnya juga keluar dan beralih profesi jadi content creator.dengan label bekas jurnalis yang mereka kantongi.
Bagi yang mengikuti Vox, Buzzfeed, atau Vice, pasti tak asing melihat mantan-mantan karyawan mereka yang akhirnya keluar dan bikin channel/brand sendiri di Youtube atau TikTok.
Buat orang-orang ini, bisa jadi pilihan tersebut baik untuk finansial mereka. Namun, satu hal yang perlu disorot dari fenomena ini adalah hilangnya proses kurasi dan koreksi yang terjadi dalam pembuatan karya jurnalistik. Content creator mengeliminasi proses editing atau proofreading yang biasanya dilakukan editor dalam hierarki dapur redaksi. Sehingga output yang hadir sulit disebut karya jurnalistik yang baik.
Lantas, Bagaimana Masa Depan Jurnalisme?
Banjir konten dan ketidakpercayaan masyarakat pada media yang ada memang jadi musuh tambahan jurnalisme hari ini. Tentu saja selain model bisnis yang mengerikan tadi.
Lalu, apakah jurnalisme akan betul-betul mati? Jika iya, apa dampaknya buat kita?
Melihat bisnis media yang dikuasai pedagang, dan terjadi hampir di seluruh dunia, jadi pesimis rasanya tak salah-salah amat. Memang ada upaya-upaya yang sedang dan sudah dilakukan jurnalis, akademisi, dan mereka yang masih percaya bisa memperpanjang usia jurnalisme. Misalnya dengan mengampanyekan pentingnya media-media kecil dan mengelola mereka dengan sumber urunan warga. Metode ini bisa memelihara idealisme media dan membiayai ongkos redaksi yang lebih “terukur”, sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang perlu dan dibutuhkan.
Masalahnya, tantangan jurnalisme yang bertumpuk seperti dijelaskan di atas, akan tetap sulit dihadapi media-media kecil.
Belakangan, ada upaya untuk melibatkan pemerintah mengatasi masalah besar ini. Beberapa negara mulai berusaha memajaki perusahaan-perusahaan iklan global untuk membagi kue iklan yang mereka punya pada perusahaan-perusahaan media. Terutama mereka yang memproduksi karya jurnalistik baik. Di Indonesia sendiri, upaya ini belum terlalu terdengar. Pemerintah sendiri sempat kesulitan untuk bikin Google, Facebook, dan Netflix patuh pajak sini, meski kini sudah ditetapkan harus membayar 15 persen.
Mekanisme pembagian kue iklan ini sudah dijalankan Australia. Mereka berhasil menarik 200 juta dolar Australia dari Google dengan aturan bernama New Media Bargaining Code. Hasilnya, sejumlah media lokal berhasil menambah staf dan menaikkan gaji mereka.
Di Kanada, mekanismenya agak berbeda. Pemerintah mereka memaksa perusahaan media sosial, termasuk Google, untuk membayar perusahaan media lokal jika ada user mereka yang mem-posting berita dari media tersebut. Aturan yang disebut “link tax” ini sempat dipermasalahkan Google. Sebagian orang juga menganggapnya belum terlalu kuat, karena perusahaan raksasa macam Google tetap bisa menyiasati aturan itu dengan mendirikan media-media kecilnya sendiri dan menguasai lanskap media lokal.
Namun, upaya-upaya ini bisa jadi pedoman buat organisasi-organisasi serikat jurnalis di Indonesia. Distribusi kue iklan dari Google misalnya, bukan cuma baik untuk keberlangsungan media-media kecil, tapi juga napas panjang jurnalisme sendiri.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari