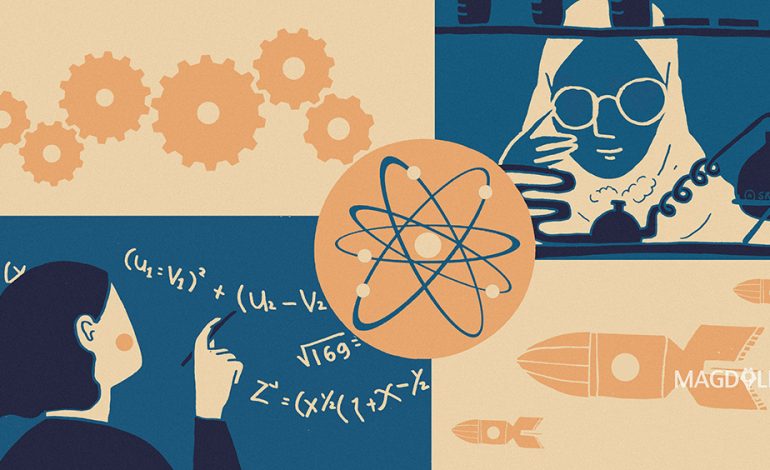Maudy Ayunda Tak Akan Kuliah di USU
Kampus di Indonesia, termasuk USU, seperti berlomba-lomba untuk membuat peraturan diskriminatif dan membiarkan persekusi terhadap minoritas semakin meluas.

Penyanyi Maudy Ayunda sangat suka belajar dan bingung menentukan kuliah di Stanford University atau di Harvard Universitas—yang ia nyatakan di media sosial dan sempat viral. Mengapa Maudy tidak mau berkuliah di kampus negeri di negara sendiri? Jawabannya mudah. Kualitas universitas negeri di Indonesia masih jauh di bawah dua kampus AS pilihan Maudy tadi. Setidaknya kampus pilihan Maudy Ayunda kelihatannya progresif untuk menggunakan keilmuan mereka membantu kelompok minoritas yang tertindas seperti imigran, kelompok Muslim dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). Sedangkan kampus di dalam negeri, konon katanya hendak menaiklan level menjadi “World Class University” tapi slogan tersebut seperti jauh tertinggal di angan-angan. Di bawah lima tahun kepemimpinan Mohamad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi, kampus-kampus di Indonesia jauh dari kata progresif, sebaliknya justru sangat konservatif.
Birokratisasi kampus
Di bawah kepemimpinan Menristek Mohamad Nasir, perguruan tinggi negeri menjadi semakin birokratis ketimbang akademis. Tingkat intelektualitas bangsa Indonesia masih termasuk yang paling rendah di Asia Tenggara dan bahkan di seluruh dunia karena kurangnya literasi masyarakatnya. Hal ini setali tiga uang dengan produktivitas akademisi untuk menerbitkan penelitian. Pak Menristek sebetulnya mempunyai semangat untuk memperbaiki lemahnya tingkat intelektualitas bangsa ini, namun cara yang digunakan justru membuat intelektualitas para akademisi semakin terperosok. Alih-alih membudidayakan kampus untuk kembali ke kodrat sebagai ruang untuk melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan mandiri, warga kampus malah berbelok menjadi birokrat dengan setumpuk kewajiban akreditasi.
Akademisi yang menjadi ujung tombak perguruan tinggi sedang didorong menjadi birokrat melalui sistem. Para dosen dituntut mengejar kum (kumulatif) demi jabatan dan gelar. Mereka dibebankan ekspetasi yang tidak wajar untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian yang harus dikerjaan bersamaan dan proporsi yang tumpang tindih satu sama lain. Kampus juga memproduksi budaya kompetisi yang tidak sehat karena semua berebut untuk meraih gelar profesor bukan melalui karya tetapi melalui hasil kumulatif tersebut. Hasilnya, para akademisi yang harusnya menjadi intelektual justru menjadi birokrat dan intelektualitasnya tumpul akibat target akreditasi perguruan tinggi negeri. Gelar profesor atau guru besar bukan lagi menjamin kemampuan dalam menguasai bidang studi atau spesialisasi keilmuan, melainkan jabatan birokratis. Guru besar adalah posisi puncak dari piramida karier akademik, namun tidak berarti apa pun.
Kampus bukan lagi tempat untuk berpikir kritis
Pada hari Senin, 25 Maret 2019, 17 pengurus pers mahasiswa SUARA USU dipanggil oleh pihak rektorat dan diturunkan paksa dari organisasi tersebut akibat menerbitkan sebuah cerpen bertema lesbianisme. Perilaku rektor USU ini membuktikan bahwa akademisi telah gagal menjadi intelektual. Kampus sebagai ruang berpikir kritis telah diberangus.
Apa yang dilakukan oleh rektor USU ini adalah wujud dari pengejawantahan ujaran kebencian yang telah dilakukan Menristek terhadap LGBT. Pak Menristek sangat homofobik karena terang-terangan menolak keberadaan minoritas seksual di kampus. SGRC UI (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies untuk Indonesia) merangkum sikap homofobia Menristek dan perguruan tinggi dalam publikasinya yang terbaru “Homofobia Perguruan Tinggi di Bawah Menristek Mohamad Nasir”.
Pada tahun 2016, Menristek menyatakan bahwa LGBT dilarang masuk kampus dan pada 2018, ia lagi- melarang LGBT beraktivitas di seluruh kampus. Warga kampus yang kehilangan intelektualitasnya langsung menelan ujaran tersebut bulat-bulat dan menghasilkan berbagai kebijakan diskriminatif dan mempersempit topik kajian penelitian. Perguruan tinggi bukan membuka seluas-luasnya akses untuk berkuliah bagi siapa pun, malah mendiskriminasi minoritas berdasarkan gender dan orientasi seksualnya.
Bandingkan dengan dua kampus pilihan Maudy Ayunda, Stanford dan Harvard. Stanford memiliki program LGBT Executive Leadership alias progam untuk menguatkan kapasitas teman-teman LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks dan queer) menjadi pemimpin dan berbisnis. Sementara itu, Harvard memiliki Harvard Gender and Sexuality Caucus yang terang-terangan mendukung gerakan LGBTIQ di kampus.
Di belahan bumi selain Indonesia, banyak universitas sedang berlomba-lomba untuk mempelajari seksualitas dan gender sebagai kajian ilmiah. Jangan jauh-jauh ke Amerika Serikat, kampus tetangga sebelah, yaitu National University of Singapore (NUS) memiliki Inter-University LGBT Network. Universitas ternama membuka seluas-luasnya kajian ilmiah dan akses terhadap pendidikan tinggi untuk siapa pun sebagai wujud kebebasan berpikir kampus. Karena dengan berpikiran terbuka dan kritis, lembaga pendidikan tinggi bisa meningkatkan kualitasnya. Bukan melalui birokratisasi.
Sementara itu, kampus di Indonesia berlomba-lomba untuk membuat peraturan diskriminatif dan membiarkan persekusi terhadap minoritas semakin meluas. Ungkapan filsuf Inggris Francis Bacon, “Knowledge is the Power” kemudian disebut kembali oleh filsuf Perancis Michael Foucault dalam bukunya The Archeology of Knowledge, yang menyatakan andil akademisi dalam membentuk norma. Ilmu pengetahuan adalah otoritas sehingga ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab etis untuk membela yang tertindas. Diskriminasi yang dilakukan oleh para akademisi di lingkungan kampus berdampak pada masyarakat yang lebih luas. Kebencian terhadap LGBT yang menjadi kebijakan kampus akan membuat lebih banyak lagi waria yang menghadapi persekusi dan ini adalah tanggung jawab mereka.
Konservatisme telah nyata menggerogoti intelektualitas dan warga kampus. Ujaran kebencian terhadap minoritas seksual yang dilontarkan Menristek Nasir dicerna bulat-bulat dan tanpa kritik ilmiah karena para dosen dan mahasiswa sudah dipaksa untuk menjadi birokrat bukan intelektual. Kampus di Indonesia semakin jauh dari cita-cita pembukaan UUD 1945 “bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa…”. Pendidikan di Indonesia semakin eksklusif, mahal dan tidak membebaskan. Jika banyak anak bangsa memilih pergi ke luar negeri untuk kuliah dan berkarier maka jangan salahkan mereka. Salahkanlah bagaimana bobroknya kualitas pendidikan kita dan kita enggan buat beranjak dari durjana itu.
Baca juga mengenai penyangkalan kasus kekerasan seksual demi nama baik kampus.
Ilustrasi oleh Sarah Arifin