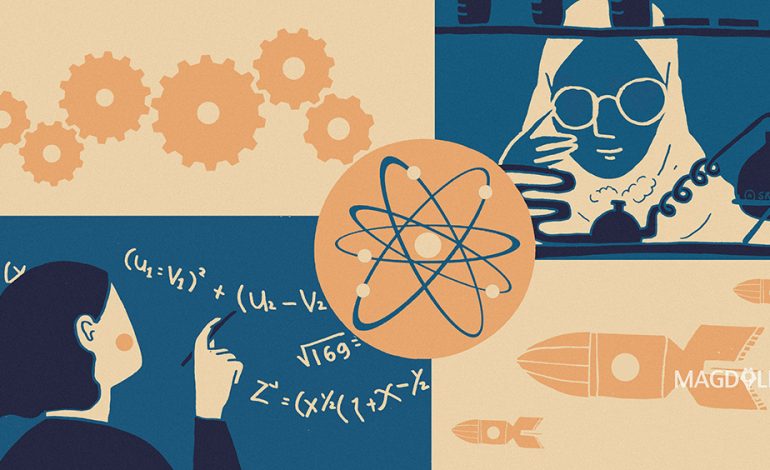Teori Linguistik Terkini: Kata Tidaklah Netral

Dua tokoh intelektual Indonesia terlibat polemik tentang netralitas kata. Pengamat bahasa Indonesia Ivan Lanin mengatakan bahwa kata itu netral. Pendapat itu ditangkis oleh novelis Eka Kurniawan yang menyatakan pendapat sebaliknya: kata tidaklah netral. Perdebatan ini segera menjadi besar bukan hanya di kalangan ilmuwan bahasa, tapi juga menyita perhatian publik lebih luas karena bahasa adalah alat komunikasi seluruh anggota masyarakat.
Dari sudut pandang keilmuan, saya sepakat dengan Eka bahwa kata tidaklah netral; mereka bersifat politis dan ideologis. Teori-teori bahasa mutakhir terkait hakikat, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari mendukung argumen tersebut.
Kronologi keilmuan
Dalam dunia kebahasaan, polemik netralitas kata bukanlah hal baru. Secara tak langsung, perdebatan ini telah hadir sejak awal ke-19 dan sejauh ini argumen bahwa kata tidak netral lebih meyakinkan.
Pemikiran bahwa bahasa itu hanya lambang dan penanda yang bersifat netral umumnya didukung kelompok linguis struktural, yaitu kelompok ahli bahasa yang memfokuskan kajiannya pada aspek struktur bahasa. Salah satu tokohnya yang paling berpengaruh adalah filsuf dari Swiss Ferdinand de Saussure yang membuat pembedaan-pembedaan antara tanda dan penanda.
Pandangan kelompok linguis struktural dikritik oleh aliran linguistik fungsional yang memandang struktur formal bahasa ditentukan oleh fungsi-fungsi sosialnya. Kelompok yang mulai berkembang tahun 1960-an ini berusaha melihat pentingnya ikatan antara bahasa dengan masyarakat yang justru diabaikan oleh kelompok struktural.
Tokoh linguistik fungsional dari Inggris MAK Halliday menunjukkan bahwa fungsi sosial bahasa sangat mempengaruhi bentuk formal bahasa. Ketika ikatan antara bahasa dengan fungsi sosialnya terungkap, ikatan bahasa dengan gejala lain di luar bahasa diketahui semakin banyak. Kelompok ini juga mengatakan bahwa bahasa ternyata juga memiliki ikatan dengan ide, keyakinan, nilai-nilai, dan praktik sosial.
Berkembangnya kelompok linguistik fungsional ini kemudian diikuti oleh lahirnya aliran kritis dalam ilmu kebahasaan pada awal 1990-an. Salah satu pelopor aliran ini adalah linguis dari Lancaster University, Inggris, Ruth Wodak. Dia mengatakan bahwa orientasi studi ini adalah menyelidiki tanda-tanda di masyarakat, termasuk tanda berupa bahasa untuk melihat kepentingan ideologi dan kekuasaan dalam penggunaan kata.
Berdasarkan kronologi aliran linguistik di atas, saya percaya aliran yang lebih mutakhir cenderung memperkuat argumen yang membantah kenetralan kata.
Baca juga: Seksisme dalam Bahasa Indonesia dan Cara Mengatasinya
Penggunaan bahasa dalam keseharian
Teori bahasa juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-sehari juga bersifat politis. Bahasa yang dipakai dalam keseharian manusia selalu bersifat politis karena terikat dengan kondisi mental, sosial, dan budaya konkret saat bahasa diproduksi.
Dalam buku klasik The Meaning of Meaning, dua filsuf Inggris CK Ogden dan IA Richard mengungkapkan kata tercipta berkat hubungan segitiga antara simbol (berupa bunyi), konsep (imaji dalam pikiran), dan referensi (sesuatu yang dirujuk). Sebuah kata bermakna hanya mungkin tercipta jika tiga unsur tersebut lengkap.
Penjelasan tersebut menunjukkan salah satu unsur pembentuk kata adalah ide. Dengan demikian, kata sudah memuat ide-ide bahkan sejak ia berupa konsep.
Di sisi lain, fakta bahwa kata-kata tertentu lahir pada ruang sosial dan budaya tertentu, bukan di ruang sosial budaya lain, menunjukkan adanya ikatan antara kata tersebut dengan kebudayaan penuturnya.
Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan ideologi dalam kata-kata, yaitu morfosemantik dan etimologi. Pendekatan morfosemantik menaruh perhatian pada makna kata-kata dengan mempertimbangkan unsur morfem penyusunnya. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menunjukkan makna kata dipengaruhi oleh makna kata lain yang menjadi unsur pembentuknya.
Dalam bahasa Indonesia contohnya, kata “karyawati” merupakan perubahan bentuk dari kata “karyawan”. Ide bahwa karyawan berjenis kelamin perempuan memerlukan kata khusus merupakan ide yang politis. Pola serupa dapat ditemukan pada kata wartawati, peragawati, siswi, mahasiswi, dan sebagainya.
Dalam bahasa Inggris, pola itu dapat ditemukan pada kata woman dan female yang memiliki ikatan morfosemantis dengan kata man dan male.
Baca juga: 9 Kata untuk Perempuan, 1 Kata untuk Laki-Laki
Pendekatan etimologi menaruh perhatian terhadap hubungan antara peristiwa, waktu, dan ide yang melatarbelakangi lahirnya kata-kata. Pendekatan ini penting karena kata adalah objek yang menyejarah.
Kata boikot, contohnya, memiliki muatan perlawanan sejak awal karena lahir dari perlawanan petani Irlandia County Mayo terhadap agen tanah bernama Charles C. Boycott. Contoh lainnya, kata nigga memiliki muatan rasialis sejak awal karena muncul sebagai olok-olok bagi orang kulit hitam Amerika. Kata itu diperkirakan muncul pertama kali di Amerika Serikat bagian selatan, daerah subur bagi kelompok antikulit hitam.
Kentalnya ideologi dalam bahasa membuatnya menjadi piranti penting untuk melawan marginalisasi kelompok minoritas pada 1980-an terutama di Amerika dan Inggris. Linguis Lancaster University Inggris Norman Fairclough mengungkapkan pemilihan kata berkaitan dengan upaya mengubah wacana yang akhirnya dapat mengubah praktik sosial terhadap objek tertentu yang dirugikan.
Contohnya, dulu penggunaan kata cacat dianggap normal. Kini istilah tersebut cenderung dihindari karena menimbulkan kesan buruk. Sebagai gantinya, kata difabel digunakan untuk dapat mengubah persepsi dan praktik sosial terhadap masyarakat difabel.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.