Perspektif Gender dan Minoritas Masih Jarang Dipakai dalam Riset
Di berbagai komunitas peneliti, norma-norma patriarkal masih sering mendominasi.
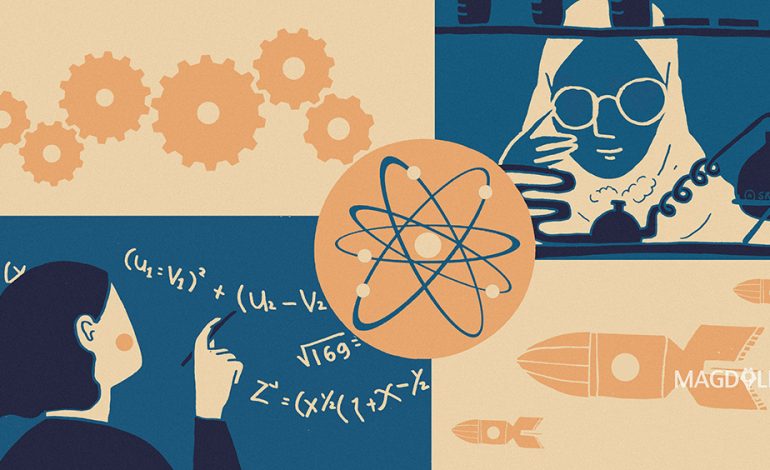
Peneliti mengakui bahwa kurangnya kesadaran untuk menggunakan perspektif yang sensitif gender dan kelompok minoritas dalam riset menghambat upaya dalam membuat kebijakan yang inklusif. Menggunakan perspektif tersebut dalam riset artinya melihat masalah juga dari aspek ketidaksetaraan perlakuan sosial atau keterbatasan akses terhadap hak dasar yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat.
Mereka menyampaikan ini dalam sebuah webinar yang diadakan pada 19 Agustus lalu oleh Knowledge Sector Initiative (KSI), berjudul “Mengapa Pendekatan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Penting dalam Penelitian?”.
Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan oleh MAMPU – program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia – bersama dengan American University di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perspektif gender dan minoritas dalam riset dan gerakan sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.
“Berbagai advokasi seperti ini pada akhirnya akan berkontribusi kepada peningkatan akses terhadap kebijakan dan program pemerintahan yang dicanangkan untuk perempuan Indonesia, terutama jika advokasi tersebut dipimpin oleh perempuan itu sendiri,” kata Stewart Norup, seorang spesialis di MAMPU.
Namun, berdasarkan data dari tim peneliti di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur hanya 7 persen dari total penelitian yang menggunakan perspektif gender and minoritas pada 2013 hingga 2017.
Baca juga: Menghancurkan ‘Tembok Kaca’ yang Hambat Perempuan di Dunia Sains Internasional
Natalia Warat, seorang anggota tim program ‘Peduli’ di The Asia Foundation, yang berupaya meningkatkan inklusi sosial di Indonesia, mengatakan bahwa akibat kurangnya kesadaran ini, penelitian di Indonesia menggunakan perspektif gender dan minoritas hanya sebagai formalitas.
“Sebagian besar peneliti hanya sekedar memenuhi tuntutan untuk memasukkan perspektif gender, tanpa memperhatikan apakah perspektif tersebut akan memiliki implikasi yang luas dan bermanfaat bagi kelompok-kelompok rentan atau tidak,” ujarnya.
Minimnya kesadaran ini juga berakar pada beberapa tantangan sistemik yang telah lama ada dalam ekosistem riset di Indonesia. Di antaranya, adanya ego di antara berbagai sektor penelitian, dan juga komunitas peneliti yang masih dipengaruhi norma-norma patriarkal.
Tantangan ini mengakibatkan rendahnya posisi Indonesia dalam Indeks Kesenjangan Gender 2019 keluaran Forum Ekonomi Dunia (peringkat ke-85). Indonesia tertinggal dari Ethiopia (peringkat ke-82) dan Botswana (peringkat ke-73).
Lingkungan yang tidak ideal
Sebuah studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang pengarusutamaan gender dalam lembaga-lembaga riset di Indonesia menemukan bahwa nilai-nilai dan peraturan organisasi seringkali menghambat terjadinya kolaborasi lintas lembaga.
Peneliti sering kali mengalami kesulitan dalam menggunakan perspektif gender saat bermitra dengan lembaga yang belum menerapkan prinsip tersebut dalam nilai, peraturan, dan misi organisasi mereka.
“Hal ini menjadi sebuah tantangan, karena dapat menghalangi peneliti untuk berdiskusi atau berkolaborasi dengan peneliti lain dari berbagai bidang studi lainya,” kata Lidwina Inge Nurtjahyo, seorang dosen hukum di Universitas Indonesia.
Pada akhirnya, tambah Lidwina, isu-isu gender sering kali tidak terjawab secara interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan suatu hal yang penting dalam studi gender karena setiap individu memiliki pengalaman masing-masing yang spesifik dan unik dalam isu tertentu. Riset yang melibatkan sudut pandang berbagai bidang ilmiah lainnya akan membantu menjawab kompleksitas dari ketidaksetaraan gender yang tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi saja.
Studi dari LIPI tersebut menemukan juga bahwa kurangnya lembaga-lembaga yang ramah perempuan di Indonesia semakin menghambat kolaborasi penelitian berbasis gender. Sebagai gambaran, pada tahun 2014, lebih dari dua-pertiga staf penelitian di beberapa institusi merupakan laki-laki. Di antaranya adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (70,8 persen), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (86,1 persen), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (74,9 persen), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat (84,2 persen).
Baca juga: Semangat Aktivisme Sita Aripurnami, Meneliti untuk Berdayakan Perempuan
Komunitas riset yang masih dipengaruhi norma patriarkal
Peneliti di Indonesia sering kali dihadapkan dengan tantangan terkait dengan fundamentalisme agama yang seringkali bertolak belakang dengan konsep kesetaraan gender. Sebuah studi tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri (UIN) di Bandung, Jawa Barat mengemukakan bagaimana tafsiran yang ‘tekstual’ dan ‘doktrinal’ dari agama berujung pada minimnya riset yang mengangkat topik progresif. Di antaranya, adalah berbagai tema yang terkait dengan kesetaraan gender.
Medelina Hendytio, peneliti di Center of Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa nilai-nilai ini mengakibatkan pengarusutamaan gender seolah-olah hanya tanggung jawab dari peneliti perempuan saja.
Pada studi Universitas Airlangga, peneliti laki-laki terlibat hanya di sekitar 40 persen penelitian yang menggunakan perspektif gender and inklusi sosial pada tahun 2013 hingga 2017.
“Di organisasi saya, misalnya, kami telah banyak melakukan penelitian yang berperspektif gender. Namun, nyatanya, hanya 20-25 persen peneliti laki-laki yang tertarik dengan isu gender,” kata Medelina.
Solusi yang mungkin diterapkan
Melihat berbagai tantangan tersebut, para ahli yang menghadiri webinar ini menawarkan dua solusi utama. Pertama, profesor studi gender di Universitas Airlangga, Emy Susanti, merekomendasikan bahwa paradigma dan metodologi penelitian sensitif terhadap isu gender harus diajarkan di berbagai universitas maupun komunitas sains.
Saat ini, konsep-konsep tersebut hanya diajarkan di beberapa institusi di Indonesia. Misalnya, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya di Jawa Timur, Universitas Indonesia di Jakarta, dan Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
“Dalam melakukan penelitian isu gender, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu menentukan pertanyaan penelitian yang jelas. Artinya, peneliti harus memahami metodologi penelitian yang sensitif terhadap gender,” katanya.
“Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap cara peneliti mengambil dan menganalisis data berbasis gender, serta untuk memastikan validitas dan kualitas dari data tersebut.”
Kedua, guru besar psikologi Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, Irwanto menyampaikan perlunya menyajikan data berbasis gender. Ia mengusulkan KSI sebagai penyelenggaranya.
KSI sendiri telah lama terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga penelitian lokal. Mereka juga saat ini terlibat dalam upaya pengarusutamaan gender pada komunitas sains Indonesia.
“Saya ingin merekomendasikan semacam clearing house [lembaga yang memfasilitasi pertukaran informasi tertentu]. Jadi, peneliti yang ingin menggunakan data berbasis gender cukup merujuk ke satu database saja,” katanya.
“Berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan informasi dan data yang relevan ataupun yang terbaru seringkali terpencar di mana-mana. Saya kira untuk dalam hal ini KSI dapat bekerja sama dengan perpustakaan di berbagai universitas.”
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.












