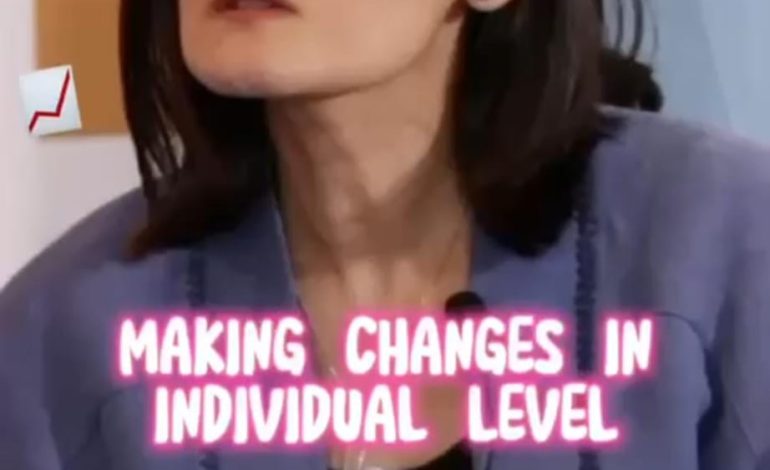#DaruratKekerasanAparat: Usut Tuntas Kekerasan Polisi pada Jurnalis

F, anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Jawa Tengah, siuman satu jam setelah polisi menembakkan gas air mata di Taman Indonesia Kaya, Semarang. Tenggorokannya perih dan kering. Sambil terbaring di rumah sakit, ia berusaha mengingat peristiwa beberapa jam terakhir yang terjadi begitu cepat.
Dari penglihatan F, ribuan massa berada di depan Gedung DPRD Kota Semarang pada (22/8). Mereka menuntut agar DPR membatalkan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Sekitar pukul 13.30 WIB, suasana mulai tak kondusif. Polisi mulai memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon.
F yang bertugas memotret di barisan depan mulai lemas, selepas polisi mengeloskan tembakan pertama. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke Taman Indonesia Kaya untuk mengamankan diri. Kemudian ia hilang kesadaran, setibanya di taman.
Baca Juga: Sejarah Kekerasan Polisi yang Terjadi di Indonesia
F bukan satu-satunya korban yang tergeletak di Taman Indonesia Kaya. Laporan Kompas.com pun menyebutkan, sejumlah mahasiswa lain dalam keadaan serupa. Mereka membantu satu sama lain yang terkena gas air mata.
Melihat situasi itu, idealnya polisi berhenti melakukan kekerasan dan membantu mengevakuasi masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Namun, mereka justru kembali menembakkan gas air mata dan lakukan kekerasan berulang.
“Pas aku pingsan, temanku bilang, polisi nembakin (gas air mata) lagi ke tengah taman. Padahal massa lagi berkerumun dan taman itu lokasi mitigasi kalau terjadi represi,” cerita F pada Magdalene.
Dari kejadian itu, F mengalami luka di bibir karena berdesakan dengan massa yang berusaha menyelamatkan diri. Ponselnya retak dan tak berfungsi optimal, sedangkan kamera yang dipakai untuk memotret aksi berhasil diselamatkan oleh teman F.
F hanyalah satu dari sejumlah jurnalis yang jadi korban kekerasan aparat selama aksi tolak revisi UU Pilkada. Per (24/8), Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mencatat, ada 11 orang jurnalis di Jakarta, enam orang jurnalis di Bandung, tiga anggota LPM di Semarang, dan seorang jurnalis di Banjarmasin yang menerima kekerasan aparat.
J, reporter di salah satu perusahaan media di Jakarta, adalah satu dari 11 jurnalis itu. Saat ingin menunjukkan cara polisi membubarkan massa di Kompleks DPR/ MPR RI, lewat live di media sosial, (22/8) malam, J dan rekan video journalist-nya didorong keluar dari barisan polisi. Kemudian polisi mengikuti mereka, dan mendorong sampai jatuh. Akhirnya J dan rekannya tidak dapat mengungkap fakta secara utuh kepada publik, terkait dugaan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran.
“Saya bilang ke polisi yang mendorong, ‘Kami sedang menjalankan kerja jurnalistik, kenapa dihalangi?’ Lalu dia buang muka dan pergi,” tutur J.
Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis—maupun masyarakat sipil—mencerminkan bahwa Indonesia dalam kondisi #DaruratKekerasanAparat. Masalahnya, aksi ini bukan pertama kalinya jurnalis jadi korban kekerasan.
Baca Juga: Deretan Aksi Kekerasan Polisi di Berbagai Negara, Prancis Bukan Satu-satunya
Kekerasan Berulang Polisi terhadap Jurnalis
Sepanjang 2019, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang di antaranya dilakukan oleh personel kepolisian dan TNI. Sedangkan saat aksi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, 28 jurnalis kembali jadi korban kekerasan. Namun, dari setiap kekerasan yang dilaporkan ke jalur hukum, tak ada satu kasus pun yang diproses.
“Sejauh ini cuma berujung laporan. Belum ada yang naik ke pengadilan,” ujar Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pratiwi Febry.
Kalau pun ditangani, prosesnya sering kali tak sesuai ekspektasi. Alih-alih diproses secara pidana seperti diatur dalam UU Pers, kebanyakan kasus yang masuk ditangani lewat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Demikian pula sanksinya lebih banyak bersifat etik.
Selain bermasalahnya penanganan kasus, aparat polisi juga kerap tak kooperatif. Misalnya, dari aksi tolak revisi UU Pilkada, (22/8), polisi tak mengakui juga memberikan keterangan pada perusahaan pers soal kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini dikonfirmasi oleh Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, saat dihubungi Magdalene.
“Kami (pemimpin redaksi media yang jurnalisnya jadi korban kekerasan) mengadukan kejadian itu ke Kepala Divisi Humas Polri, lewat group chat dengan beliau, tapi enggak ditanggapi,” terang Setri.
Ada beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh jurnalis: Penggunaan gas air mata, intimidasi, penghalang-halangan dalam bekerja, ancaman pembunuhan, hingga kekerasan psikis dan fisik yang menyebabkan luka berat.
Kekerasan ini merupakan ancaman terhadap kebebasan pers, yang menjalankan fungsi menyampaikan informasi ke publik dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebab, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jelas tertulis: Kemerdekaan pers dijamin sebagai HAM, tidak dikenakan sensor penyiaran, dan yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers harus dituntut secara pidana.
Dengan membungkam dan menghalangi proses kerja jurnalistik, polisi menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga termasuk pelanggaran HAM. Bahkan polisi juga melanggar hak konstitusional warga negara, yang seharusnya bebas menyatakan pikiran dan pendapat—seperti tercatat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Pratiwi, kekerasan ini hanya puncak gunung es dari rusaknya institusi kepolisian. Yang mereka lakukan adalah bentuk brutalitas dan penyalahgunaan jabatan. Bukan melindungi, menghormati, ataupun menjamin HAM. Ia menilai, kekerasan terhadap pers sifatnya terstruktur dan sistematis. Soalnya, polisi pun mempelajari HAM dalam pendidikannya.
“Enggak ada alasan mereka (polisi) enggak tahu soal hak pers meliput di lapangan,” kata Pratiwi.
Untuk mendapat keterangan Polri terkait alasan polisi masih melakukan kekerasan terhadap jurnalis, Magdalene telah menghubungi Komisaris Besar Polisi Erdi Chaniago. Namun, tidak ada tanggapan sampai artikel ini ditulis.
Baca Juga: Kekerasan Polisi: Slogan Mengayomi Cuma di Atas Kertas?
Desakan Pers Pada Aparat
Saat meliput aksi pekan lalu, J memakai atribut keamanan: Seragam dari kantor dan kartu pers sebagai tanda pengenal, helm untuk melindungi kepala dari lemparan barang, sampai safety goggle untuk menghindari gas air mata.
Bagi J, persiapan itu lebih dari cukup. Namun, ia tetap merasa tidak aman—baik fisik maupun psikis. Apalagi setelah mendapat kekerasan, J khawatir mengalami intimidasi lanjutan. Ditambah ia melakukan live report, di mana wajah dan identitasnya bisa dikenali dengan mudah.
“Harusnya tanpa persiapan berlebihan pun, aparat sadar untuk enggak melakukan kekerasan terhadap jurnalis,” ucap J.
Setelah konferensi pers pada (24/8), redaksi mengabarkan J untuk bersiap membuat laporan ke kepolisian. Nantinya akan didampingi oleh AJI, atau KKJ.
Sementara bagi Setri, kondisi darurat ini adalah pelajaran untuk mengutamakan keselamatan jurnalis dalam peliputan. Karena itu, berkaca dari aksi kemarin, redaksi Tempo akan menuntut kejelasan pelaku kekerasan, sekaligus perbaikan mekanisme sistem liputan di area yang berpotensi mencederai jurnalis. Salah satunya lewat evaluasi kurikulum pelatihan.
Jika Tempo relatif punya mitigasi risiko, bagaimana dengan media-media kecil di luar sana yang jurnalisnya jadi korban kekerasan? Sebenarnya jurnalis yang menjadi korban, bisa mengajukan pelaporan pula.
Idealnya, proses pelaporan kekerasan terhadap jurnalis punya alur sama dengan kasus kekerasan pada umumnya: Datang ke polisi, kemudian polisi memberikan surat tanda terima laporan, diikuti penyerahan bukti-bukti untuk kepolisian supaya kasusnya diproses. Bedanya, jurnalis akan didampingi AJI atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mana pun, dan laporan sekaligus ditujukan ke Dewan Pers. Tujuannya agar terdokumentasi, dan Dewan Pers bisa memberikan tekanan pada kepolisian—sekaligus pembelaan terhadap kerja pers.
AJI di masing-masing kota akan mendata dan mendampingi jurnalis yang jadi korban kekerasan. Namun, menurut Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung, sejumlah jurnalis punya pertimbangan yang membuat mereka enggan melaporkan kasus ke kepolisian.
“Ada yang nggak percaya polisi akan memproses kasus. Soalnya, kasus sebelumnya banyak yang mandek,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti proses pengungkapan kasus kekerasan yang mandek, AJI mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Sayangnya, kepolisian enggak begitu responsif karena ada yang menanggapi dan tidak. Yang menanggapi pun beralasan kesulitan mengidentifikasi pelaku, lantaran anggota Polri tersebar di seluruh Indonesia.
Menurut Erick, aparat penegak hukum belum serius dalam melakukan pekerjaannya, karena pelakunya adalah anggota mereka sendiri.
“Ini artinya masih ada impunitas pelaku kekerasan terhadap jurnalis, yang diusut aparat kepolisian,” tegas Erick.
Maka itu, supaya aparat berhenti melakukan kekerasan terhadap jurnalis, KKJ memberikan desakan lewat poin-poin berikut: Pertama, kepolisian memproses aparat yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis secara hukum pidana dan kode etik. Kedua, Kapolri dan jajarannya menghentikan berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas.
Ketiga, Panglima TNI dan jajarannya menarik anggotanya yang bertugas mengamankan aksi sipil, lantaran tak sesuai dengan amanat Undang-undang. Keempat, meminta Kapolri, TNI, dan jajarannya untuk menginvestigasi dan mengusut kekerasan terhadap jurnalis yang sedang meliput. Kelima, mengimbau korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami saat peliputan.
Artikel ini diperbarui pada 30 Agustus 2024 terkait jumlah jurnalis di Bandung yang jadi korban kekerasan, dan pernyataan Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung.