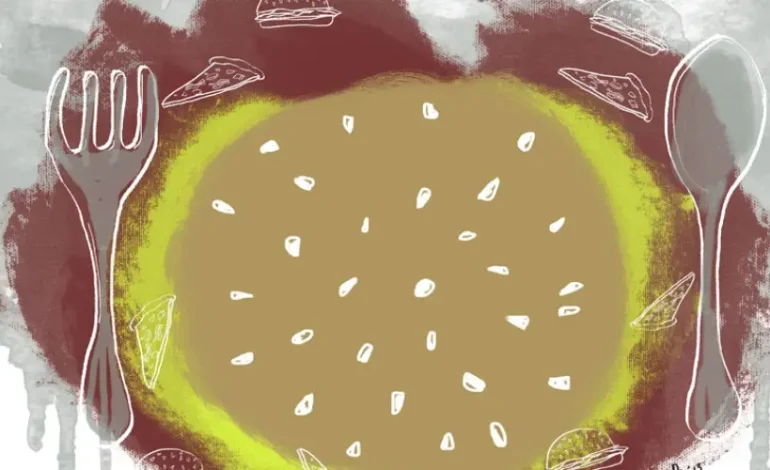Kekerasan Seksual di NGO dan Organisasi Nirlaba: SOP Penanganan Saja Tak Cukup

Kasus kekerasan seksual kembali jadi perbincangan ketika Project Multatuli merilis laporan “Mendobrak Sirkel Sendiri: Saat Penyintas Melaporkan Kekerasan Seksual di NGO”, 17 Mei lalu. Laporan ini mengangkat cerita seorang penyintas yang mengalami kekerasan seksual di tempatnya bekerja, Yayasan Plan Indonesia.
Berdasarkan liputan Project Multatuli, kasus itu tak pernah diusut secara komprehensif Plan Indonesia. Meski pelaku dikeluarkan, ia tetap dapat surat rekomendasi dari atasannya di Plan Indonesia dan direkrut oleh NGO lain, yakni Yayasan Tifa.
Kasus ini tentu saja mengundang percakapan. Pasalnya, Plan dan Tifa dikenal sebagai organisasi yang mendukung hak asasi manusia, dan turut mengampanyekan pesan-pesan anti-kekerasan seksual. Kasus ini kembali menyadarkan kita bahwa penanganan kasus kekerasan seksual bukan hal mudah dan harus terus dipantau.
Tunggal Pawestri, aktivis dan konsultan gender yang aktif sejak tahun 2000-an, menyebut pelecehan dan kekerasan seksual di NGO bukanlah hal baru. Sejak dulu, ia kerap mendengar kasus-kasus tersebut dengan derajat berbeda di sejumlah organisasi. Namun, memang jarang sekali mendengar kasus-kasus ini diusut dengan penanganan yang baik, atau sampai dilaporkan ke polisi.
“Biasanya (ditangani) pakai mekanisme organisasi. Yang paling sering saya tahu itu korban tuh enggak mau kasusnya diperpanjang dan memilih mengundurkan diri,” cerita Tunggal pada Magdalene.
Menurutnya, kesadaran penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di NGO sendiri, dari dulu hingga sekarang masih lemah. Kendati keberanian korban dan penyitas untuk melapor sudah meningkat, Tunggal masih menyayangkan mekanisme organisasi-organisasi nirlaba—terutama yang bergerak di isu perjuangan HAM—masih belum komprehensif dan berperspektif korban.
“Berbeda dengan komunitas, harusnya NGO lebih advance untuk menangani hal ini. Tapi nyatanya tidak,” kata Tunggal.
“Kita berani berbicara, demand keadilan kalau ada supporting system yang baik. Nah ini baru disadari sekarang, bahwa ya selama ini nyatanya belum ada supporting system yang baik untuk korban. Inilah momen untuk berefleksi,” lanjutnya.
Senada dengan Tunggal, Eva Danayanti, Program Manager International Media Support (IMS) Indonesia mengungkapkan ia beberapa kali mendapatkan curhatan dari para korban atau peyintas pelecehan atau kekerasan seksual di NGO. Baik korban atau penyintas mayoritas enggan melapor. Hal ini karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengusut kasusnya lebih jauh. Tidak yakin akan mendapatkan keadilan.
Menurutnya keenganan untuk melapor itu dipengaruhi faktor lingkungan.
“Kalau lingkungannya enggak mendukung, tidak paham bahwa itu kekerasan seksual, ya maka tidak heran Standar Operasional Prosedur (SOP) pelecehan seksual atau kekerasan seksual belum ada. Kalau pun udah ada SOP-nya tapi masih bersifat penanganan kasus,” jelasnya.
“Ada keterbatasan orang-orang (yang bekerja di NGO) untuk memahami kekerasan atau pelecehan seksual. Keberadaan SOP internal itu minim sekali. Kalau pun ada hanya terbatas pada proses penanganan kasus, jadi sifatnya preventif masih sangat jarang,” tambah Eva.
Baca Juga: Kekerasan Seksual Aktivis Kiri, Saatnya Bersih-bersih Gerakan Sendiri
NGO yang Tak Selamanya Progresif, Apalagi Kalau Ada Laporan Kekerasan Seksual
Kasus yang dilaporkan oleh Project Multatuli sebenarnya bukan satu-satunya kasus kekerasan seksual di NGO yang masuk media.
Dalam bulletin Januari-April 2002 di halaman website Women Crisis Center misalnya terdapat sebuah laporan tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di The Public Interest Legal Support and Research Centre (PILSARC), NGO yang memberikan nasihat hukum, litigasi dan dukungan penelitian untuk para aktivis dan kelompok aksi sosial di India.
Tara (nama samaran) adalah pengacara yang bekerja di PILSARC. Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya pada Mei 2000 karena mengalami pelecehan seksual dan intimidasi berulang oleh Dr Rajeev Dhavan, Direktur dari PILSARC dan Advokat Senior Mahkamah Agung yang terkenal selalu mendukung HAM.
Sebelum memutuskan meninggalkan pekerjaannya, Tara sempat datang ke Saheli (organisasi perempuan) untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dia alami sekaligus memperingatkan perempuan lain dengan harapan mereka dapat diselamatkan dari trauma yang dia alami di tempat kerja. Namun, segera setelah Tara menghubungi Saheli, dia didekati oleh berbagai orang yang terafiliasi dengan PILSARC.
Sepanjang proses pengusutan kasus berjalan, ada tekanan dari berbagai pihak untuk tidak mengekspos kasus ini ke publik yang lebih luas. Tara dan Saheli berulang kali diminta untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan apa pun terhadap PILSARC dan pekerjaan berharga yang dilakukannya. Sebuah alasan yang selalu diharapkan dari perempuan dan kelompok perempuan.
Cara Dewan PILSARC dan Yayasan Plan Indonesia bertindak adalah cerminan dari bagaimana NGO ternyata bergerak di luar kerangka akuntabilitas mereka sendiri ketika menghadapi laporan kasus kekerasan seksual. NGO tak selamanya progresif. Sehingga NGO yang bekerja di isu kesetaraan gender dan HAM tak secara otomatis memiliki pekerja dan mampu menciptakan lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pelecehan dan kekerasan seksual.
Baca Juga: Mempertanyakan Kesiapan Polisi Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia
Urgensi SOP Khusus Pelecehan dan Kekerasan Seksual di NGO
Eva melihat fungsi dan urgensi SOP penanganan dan pencegahan kekerasan seksual belum maksimal diterapkan mayoritas NGO. Kebanyakan menggunakannya sebagai pelarian ketika menghadapi laporan kasus. Beberapa bahkan baru membuat ketika ada laporan masuk.
Minimnya SOP ini menurut Eva jelas membuat pola kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kerja terjadi berulang, tanpa adanya itikad dari NGO untuk berbenah. Jelas ini jadi masalah, karena ketika NGO tak mampu berpihak pada korban dan penyintas, maka mereka dijauhkan dari keadilan dan dibiarkan dalam lingkar trauma berkepanjangan di masa depan.
“Penanganannya jangan untuk punishment aja, dengan dia (pelaku) mengundurkan diri maka udah selesai dianggap. Itu kan mikirnya, ‘Oh yaudah pelaku mendapatkan sanksi’, tapi enggak memikirkan korbannya gimana, ke depannya mereka gimana,” kata Eva.
Padahal SOP yang baik juga turut mencegah terjadinya kasus baru dengan memberikan pengetahuan isu kekerasan seksual bagi pekerja. Serta menyediakan tempat pengaduan yang lebih inklusif dan betul-betul aman buat korban.
Senada dengan Eva, Tunggal pun menegaskan bahwa SOP ini seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh NGO. Ini adalah langkah minimal yang bisa ditawarkan NGO dalam mencegah, menangani, dan mereduksi kasus pelecehan dan kekerasan seksual di organisasinya sendiri. Lebih lanjut, dengan adanya SOP yang jelas, NGO bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.
“Dengan tidak adanya SOP internal, penanganan yang tidak baik terkait kekerasan atau pelecehan seksual pasti akan berdampak langsung pada aktivisme NGO. Pertama, hal ini tentu akan membuat staf tidak nyaman dan aman bekerja di organisasi. Kedua, misalnya organisasi ini sangat terdepan tapi ternyata rapuh di dalamnya, seperti tidak menjalankan nilai-nilai mereka, maka tentu akan berdampak buruk pada kampanye yang ada. Publik enggak percaya lagi,” ungkap Tunggal.
Baca Juga: Glorifikasi Sifat Maskulin: Bumerang Penanganan Kekerasan Seksual pada Laki-laki
NGO dan Organisasi Serupa Harus Berbenah
Kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual sejatinya bukan hal baru di mana pun lingkup terjadinya. Mereka makin marak terdengar karena keberanian korban yang bercerita dan mengangkat kasusnya juga makin banyak. Hal ini harusnya tidak dipandang sebagai hal buruk, sebab keberanian itu tumbuh seiring dengan kesadaran tentang pentingnya membangun ruang aman yang kokoh buat para korban dan penyintas.
Membuat SOP internal terkait penanganan pelecehan dan kekerasan seksual saja tak cukup. Masih dibutuhkan banyak upaya lanjutan yang harus dilakukan NGO dalam mendobrak sirkelnya sendiri dan memberikan ruang aman bagi setiap individu yang ada.
Berikut adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan organisasi, tempat kerja, dan terutama NGO ketika sudah punya SOP penanganan dan pencegahan KS.
- Evaluasi SOP Secara Berkala
Meski sudah punya SOP, NGO atau organisasi serupa tetap harus melakukan evaluasi SOP secara berkala. Hal ini penting, menurut Tunggal, terutama untuk melibatkan pandangan dan opini tiap karyawan dan pihak eksternal dalam membangun prosedur penanganan yang lebih baik.
Memeriksa SOP secara berkala berarti memastikan semua karyawan, baik yang mau masuk ke dalam organisasi atau yang sudah bekerja, mengetahui informasi terbaru soal kebijakan organisasi.
- Makin Sering Pelatihan, Makin Baik
Pelatihan terkait isu pelecehan dan kekerasan seksual baiknya juga dilakukan secara terus-menerus.
“Training misalnya tiap tahun. Jadikan ini refresher training, jadi staff yang udah dapet sebelumnya, bisa dapet lagi. Pemahaman mereka terkait hal ini terbangun lagi, kesadarannya terpupuk lagi dan SOP enggak jadi dokumen yang dilupakan,” tambah Tunggal.
- Safe Space adalah tentang Kepercayaan
Salah satu poin yang biasanya harus hadir dalam SOP pencegahan dan penanganan KS adalah ketersediaan kanal pengaduan yang aman dan berperspektif korban. Di atas kertas, hal ini mudah dituangkan. Di kehidupan nyata, ia sulit ditemui.
Eva bilang, kanal pengaduan yang betul-betul aman amatlah penting. Kepercayaan dan keberanian korban tidak mungkin timbul di tempat yang intimidatif dan toxic. Itu sebabnya, NGO harus berupaya keras membangun kepercayaan tersebut dengan menyediakan ruang aman yang betul-betul inklusif buat semua orang.
- Ini yang Paling Penting: Utamakan Hak Korban
Ketika menghadapi pelaporan kasus KS yang diterima rekan kerja sendiri, apalagi yang sudah jadi teman, kebanyakan orang akan gelagapan—kalau tidak kaget dan bingung harus melakukan apa. Apalagi jika rekan kerja itu terlapor sebagai pelaku.
Ketika menghadapi kasus begini, jangan lupa bahwa kebutuhan utama dan paling utama dalam penanganan kasus KS adalah kebutuhan korban.
- Bergabung dengan Organisasi Lain untuk Menyediakan Ruang Aman
Jika sekiranya, berbagai PR tambahan ini terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) yang masih sedikit dan belum mumpuni, Eva pun memberikan solusi alternatif.
“Kalau organisasi kecil mungkin rada susah ya, mungkin bisa dengan joint task force antar organisasi untuk menangani kasus seperti ini. Jadi walau resource–nya masih minim, hak korban tetap diusahakan terpenuhi.”