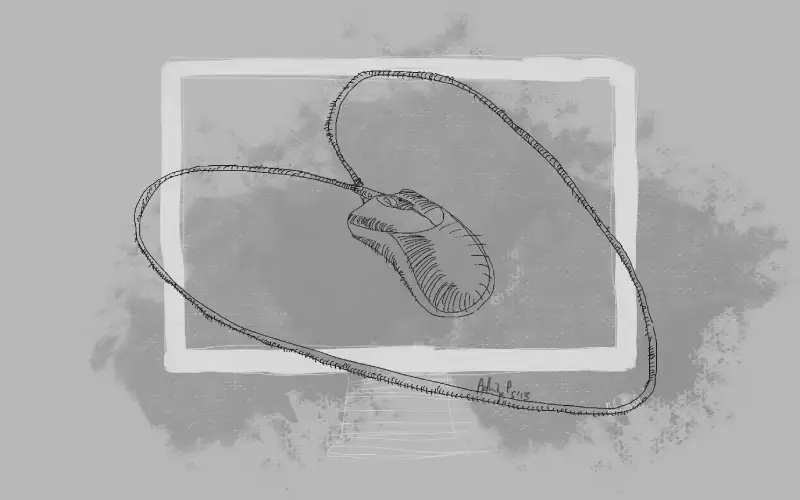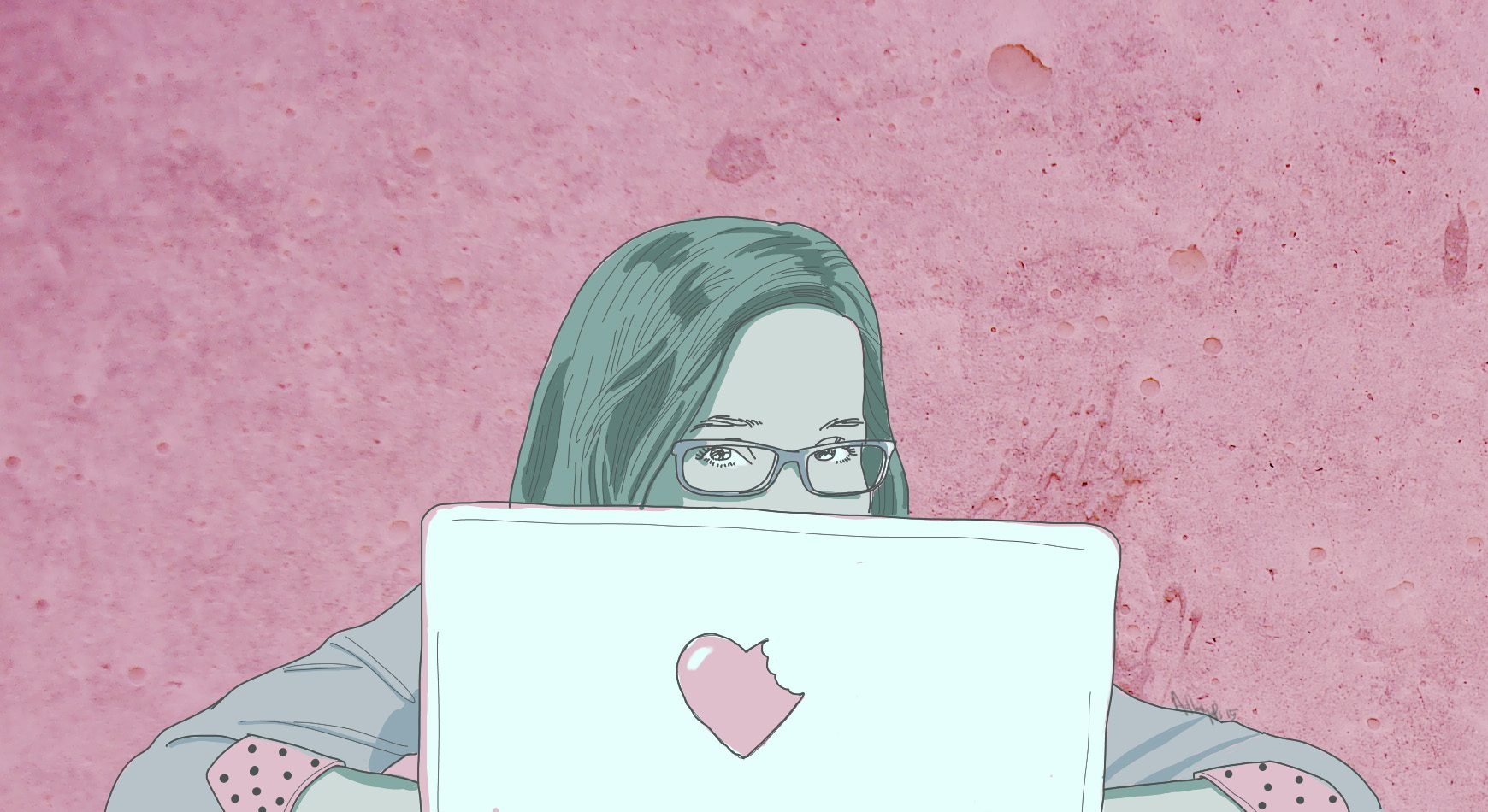Kenapa Ayahku Tak Ada di Langit-langit Kamar?
Udara pagi ini segar, tidak ada bekas hujan karena semalaman langit tidak menumpahkan apa-apa seperti beberapa malam sebelumnya. Aku keluar dari rumah, membawa serta segala benda ajaib yang ditugaskan bagi mahasiswa baru dalam rangkaian ospek universitas. Awal September 2011, aku memulai hari-hariku sebagai mahasiswi Hukum di sebuah kampus negeri di kotaku.
“Jadi mahasiswa itu hebat loh,” kata Mama. Karena bukan sembarang siswa atau siswi, melainkan ditambah kata “maha” di depannya, katanya lagi.
Aku kira yang berhak menyandang gelar Maha hanya Tuhan semata, ternyata anak yang baru lepas seragam putih abu-abu juga boleh. Membayangkannya saja membuat aku tersenyum sendiri. Aku sudah besar, bisikku.
Aku memandang rumahku beberapa saat sebelum akhirnya berangkat. Rumahku masih muram, seakan ada kabut gelap di atasnya yang menghalangi matahari memancarkan sinarnya. Ayahku baru pergi. Bukan, bukan pergi yang akan kembali. Ayahku benar-benar pergi, meninggal. Aku termangu sambil memperhatikan langkah menuju pagar.
Hari pertama ospek, aku diantar Mama ke kampus, naik motor, saling diam. Pepohonan rata di kanan kiri jalan, membentuk barisan rapi serupa itik yang digiring Pak Tani ke sawah seperti yang kulihat di rumah nenekku dulu. Rapi, tapi berisik, tapi tetap lucu.
Hari-hari perploncoan itu berakhir juga. Tidak ada lagi tas keresek, pita warna-warni, atau bekal roti bernyanyi hari ini. Aku resmi menyandang gelar mahasiswi. Segalanya masih baru, tidak ada lagi teman-teman sebangkuku di SMA yang suka menyelundupkan snack saat pelajaran.
Ah, belum-belum aku sudah rindu sekolah. Susah memang bagiku yang pemalu ini untuk memulai perkenalan walaupun akhirnya lancar. Temanku banyak, ada tiga. Menurutku, banyak itu kalo lebih dari satu, jadi 3 banyak kan? Pasti nanti bertambah, satu atau dua, bisa tiga sih. Berapa saja boleh. Aku senang banyak teman.
Menyesuaikan diri tidak sesulit yang aku bayangkan, memahami materi hukum yang banyak itu juga tidak begitu menyiksa, lebih susah bergaul dengan teman-temanku yang kaya. Uangku tidak banyak, jadi kalau mereka mengajak nongkrong di tempat yang mahal, dompetku seketika megap-megap kehabisan uang.
Baca juga: Ibu dan Setan Bernama Skizofrenia
Belajar hukum adalah keinginan ayahku dulu. Cita-cita yang tidak kesampaian itu diwariskan ke aku, karena Ayah kemudian belajar ekonomi dan menjadi dosen hingga hari terakhirnya. Aku menghela nafas berat setiap kali ingat Ayah. Aku dekat sekali dengan Ayah, karena dia sabar, beda dengan Mama yang suka marahin aku.
Ayah yang suka menari salsa ketika aku cemberut, dan memasakkanku nasi goreng terenak di dunia ketika aku sedang murung. Pipiku basah, aku belum siap kehilangan Ayah. Tapi manusia mana sih yang siap kehilangan orang terkasihnya dalam waktu sekejap?
Kehilangan ayah tidak sama rasanya dibanding kehilangan pacar, atau kucing. Kehilangan ayah itu kehilangan setengah dunia. Serius ini, bukan mengada-ada. Sedihku dalam sekali. Sedikit-sedikit menangis, meringik seperti embikan anak kambing di tengah malam.
Ayah yang selalu ingin melihatku menjadi mahasiswi hukum, pernah berjanji untuk mengantarkanku di hari pertama ospek. Perkataan sederhana yang nyatanya tidak pernah dipenuhi. Ayah selalu yakin aku bisa menjadi lawyer yang hebat, yang bisa menganalisis kasus-kasus hukum dengan cermat. Tinggi juga kepercayaan ayah padaku ya, padahal aku tidak yakin.
Hidupku, hidup keluarga kami lebih tepatnya, berubah seusai Ayah meninggal. Semuanya lebih sulit, bernafas lebih berat, dan kesedihan tak sudah-sudah. Tapi ajaibnya, kami melalui semuanya dengan baik. Agak tersengal memang, tapi tetap baik kan. Aku bisa kuliah sambal bekerja part time, uangku jadi agak banyak. Dompetku bisa sedikit sombong sekarang. Aku merasa diberkati karena kuliahku lancar dan lulus tepat waktu. Oh, pasti ini karena Ayah mendoakanku dari langit sana, doanya lebih cepat sampai kepada Tuhan, tidak perlu menembus lapisan ozon dulu atau setengah terbakar di stratosfer.
Baca juga: Ayah Pergi Menyalakan Lampu
***
Hampir sembilan tahun berlalu sejak hari kelam itu, aku benar-benar menjadi lawyer. Wah, hebat betul harapan ayahku, terkabul. Aku mendengar seruan dari langit di hari pertamaku kerja, “Apa Ayah bilang! Kamu pasti jadi lawyer!” Ah, suara ayahku terdengar bersemangat. Aku pun begitu, berseri-seri dan yakin akan menjalani hari dengan baik. Semuanya menyenangkan, sampai badai itu datang.
Badai kecemasan yang menyerbu dengan tiba-tiba, terburu-buru, disertai rasa takut yang tak kulihat ujungnya. Aku bingung, aku kehilangan arah. Temanku bilang, aku hanya sedang masuk di quarter life crisis dan semuanya akan berlalu. Aku lupa bertanya, akan lama tidak perasaan aneh ini terjadi? Aku kira perasaan negatif begini hanya dirasakan orang dewasa. Aku pura-pura lupa kalo usiaku bukan belasan lagi, aku juga sedang tumbuh dewasa. Aku sebenarnya takut, takut gila.
“Ayah, kenapa kerjaanku sering salah? Kenapa aku sekarang menjadi pemurung dan suka sendiri? Kenapa aku merasa takut hanya sekedar mengobrol dengan teman-temanku? Aku kenapa ya, Yah? Kenapa cemas ini makin menjadi-jadi?”
Aku mulai ragu tentang apa yang kujalani ini tepat. Biasanya, setiap kali aku sedih dan ragu pada hal yang aku kerjakan, aku mencari kehadiran ayah di langit-langit kamarku. Kok gitu? Iya, karena Ayah sekarang bisa melayang, jadi engga selalu duduk di sampingku seperti dulu.
Ayah biasa kutemui malam sebelum tidur, tersenyum, menanyakan hariku, tanpa bicara. Aku bisa menjawab tanpa suara, tapi Ayah biasanya mengerti. Hebat sekali, kan? Eh atau sebenarnya aku sering salah menjawab? Yang pasti, saat aku kelihatan tidak sedang baik-baik saja, Ayah akan mendongeng untukku. Kemudian aku akan makan setelahnya.
Tapi aneh, akhir-akhir ini tidak kujumpai bayangan ayah di langit-langit kamar. Aku memanggil dalam hati, berulang-ulang. Aku panggil dengan suara akhirnya.
“Kenapa ayah tidak hadir ya? Apa karena kamarku sedang mati AC-nya jadi terlalu gerah untuk Ayah di sini?” Aku pandangi langit-langit kamarku setiap malam, berharap ayah melambaikan tangan seperti biasa. Minta maaf, tidak bisa datang karena sibuk mengoreksi ujian mahasiswa-mahasiswanya di langit.
Ah, apakah aku baik-baik saja?
“Ayah, jadi orang dewasa itu emang enggak enak ya? Ayah, dengar tidak pertanyaanku? Ayah kenapa enggak muncul sih?”
Aku mulai tersedu, sendiri.