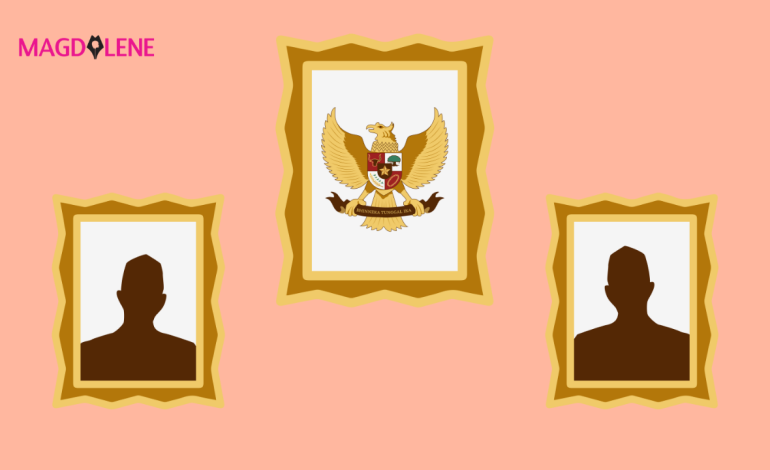Di kampungku, seseorang tak bisa dilabeli sukses jika belum jadi PNS atau dosen. Namun, tagar #JanganJadiDosen yang belakangan viral setelah Podcast The Conversation rilis, bikin saya harus memikirkan ulang parameter kesuksesan orang-orang di kampung.
Tagar itu sendiri turut menguak wajah dan suara pendidik yang berjuang di jalan sunyi. Tak hanya dosen, tapi juga para guru di sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengajar di pesantren, ramai-ramai mengeluhkan ketidakmerdekaan mereka dalam urusan finansial. Ini memang lagu lama, tapi sayangnya selalu tenggelam karena romantisasi yang terus dilanggengkan.
Buat saya sendiri, meski sudah ngos-ngosan menyiapkan lesson plan, memberikan assessment, menghadapi murid tantrum, menangani bullying, dicecar orang tua, disalahkan atasan, itu tak lantas jadi jalan pintas untuk mundur sebagai guru. Selain masalah passion, seperti dilema guru lainnya, tak banyak pilihan yang tersisa untuk orang-orang seperti kami.
Baca juga: Kekerasan Seksual di Kandang Kiai: Lima Alternatif Solusi
Keluar dari satu institusi pendidikan, lalu nyemplung ke tempat lain, akan terus berakhir sama selama frasa “pengabdian”, “mencerdaskan generasi Islam”, “ikhlas beramal” itu terus diglorifikasi. Padahal buat saya, itu cuma alasan institusi pendidikan untuk tak menghargai kami, termasuk tak memberi upah layak.
Di saat bersamaan, dampak glorifikasi ini juga membuat orang terdoktrin bahwa kamu belum naik status sosialnya di mata keluarga dan tetangga, jika tak bisa berprofesi sebagai tenaga pengajar. Saya sudah meyaksikan sendiri, rekan-rekan dosen non-ASN yang harus berjibaku demi mendapat pekerjaan. Jika tak punya orang dalam atau privilese lain, susah sekali masuk ke kawah candradimuka ini. Belum lagi, ini diperparah dengan karakter feodalistik dari beberapa institusi pendidikan. Harus permisi dulu sama senior, misalnya.
Enggak heran jika di beberapa tempat, rekan-rekan pengajar saya sering dicap tukang ngamen. Sebab, mereka harus mengajar di berbagai institusi untuk mencukupi kebutuhannya. Banyak job hustle yang dilakoni pengajar, entah menjajalkan bisnisnya, mengisi talkshow, influencer, dan lainnya.
Antara dosen dan guru, termasuk guru pesantren pun tak jauh berbeda realitasnya. Bahkan bisa jadi lebih parah. Sebagai tenaga pengajar di salah satu pondok pesantren dan tutor daring, saya tak mendapat privilese status sosial yang bisa dipamerkan saat Lebaran di kampung. Tak cuma status sosial, upah guru pun selalu kecil. Apalagi di pondok pesantren di mana banyak yang dibayar berkah atau jabat tangan.
Baca juga: Beramal Itu Banyak Caranya, Termasuk Jadi Dosen Honorer
Saya sendiri terkadang gamang dengan label ikhlas beramal yang kerap dikoar-koarkan institusi pesantren. Tak sedikit saya temukan beberapa teman pengajar di berbagai wilayah yang harus mengeluskan dada karena bekerja secara pro bono, apalagi jika tak memiliki safety net yang baik atau latar belakang keluarga mapan. Tak heran, guru masih sering absen dan tidak mindful ketika mengajar sebab keletihan dengan pekerjaan sampingan, atau buru-buru ingin meninggalkan kelas karena hanya mengejar poin kehadiran di hari tersebut.
Belum lagi wacana pemakaian anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dipaksakan untuk dialihkan jadi program makan siang gratis yang digagas oleh Paslon 02. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), pun menolak kebijakan ini karena mempertimbangkan gaji guru. Jika dilakukan, maka sama halnya memberikan makanan gratis dari hasil jatah makanan gurunya.
Maka benarlah sebuah pepatah: “There’s no such things a free lunch”. Anggaran negara saja belum bisa sepenuhnya menyejahterahkan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memajukan kualitas pendidikan, eh ini dana yang kerap jadi “penyelamat” kami justru disunat demi ambisi tak masuk akal dari politisi.
Nestapa guru pondok pesantren tak berakhir di situ. Selain mengajar di kelas dan mendampingi santri di asrama, mereka tetap harus dituntut ikhlas meski 24/7 harus degdegan dengan tingkah santrinya yang bisa saja memicu protes orang tua. Atau, ketika salah seorang rekan harus merangkap menjadi admin dan mengerjakan pengisian data beberapa guru yang baru getol dan rajin absensi ketika informasi insentif mulai beredar di grup WhatsApp.
Baca juga: Kuliah Online di Masa Pandemi Ternyata Lebih Menguras Energi
Padahal, metriks keikhlasan tak bisa diukur dari penolakan atau penerimaan seseorang terhadap sebuah upah. Jika hal ini yang menjadi tolok ukur, maka semua pekerja tak akan sukses mendapat predikat ikhlas dalam hidupnya.
Jika ini dibiarkan, maka masalah pendidikan masih terus berputar di ranah yang sama. Semoga segala jerih payah pendidik tidak diromantisasi oleh kata berkah, dan iming-iming ikhlas beramal.
Mufidatunnisa, seorang guru biasa di Sulawesi Selatan. Penulis bisa dihubungi melalui email: [email protected].