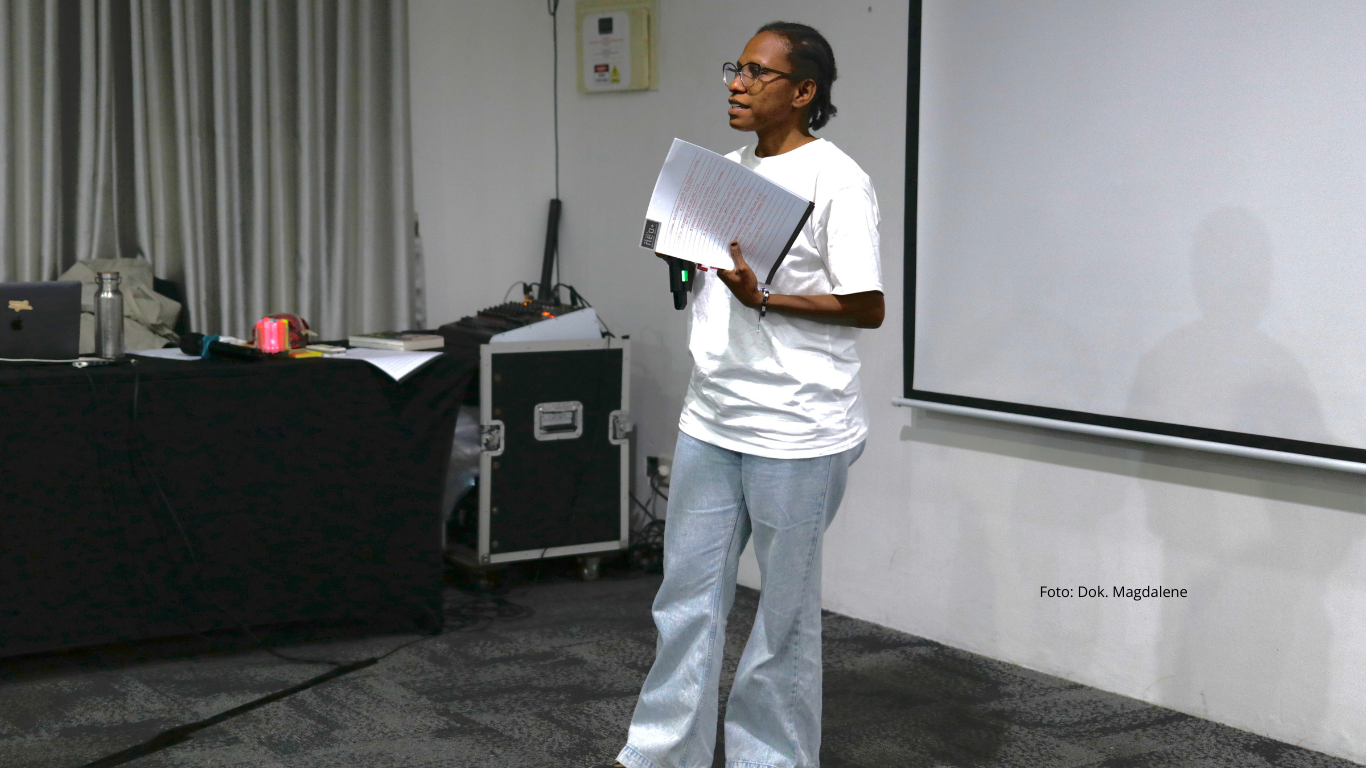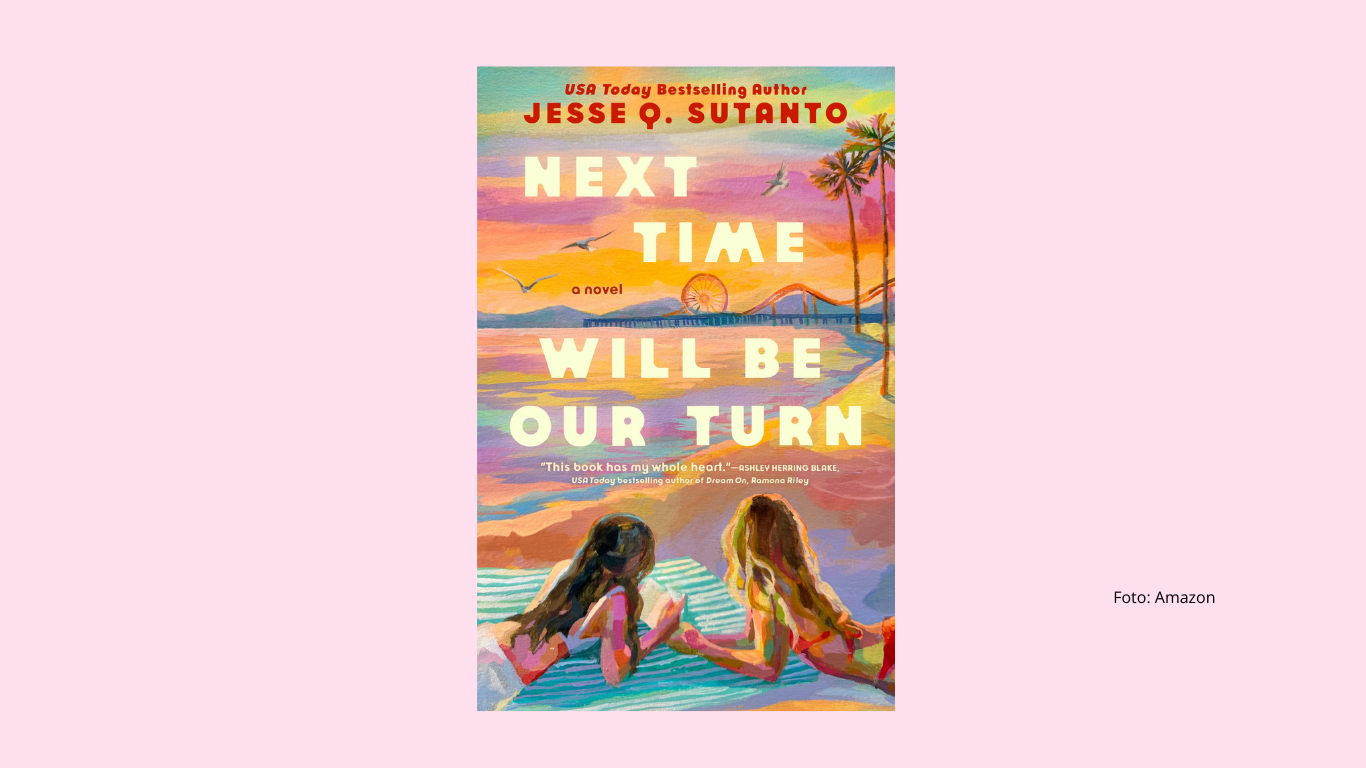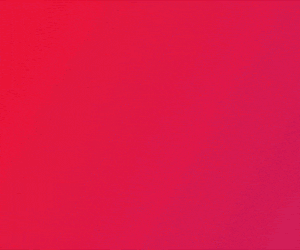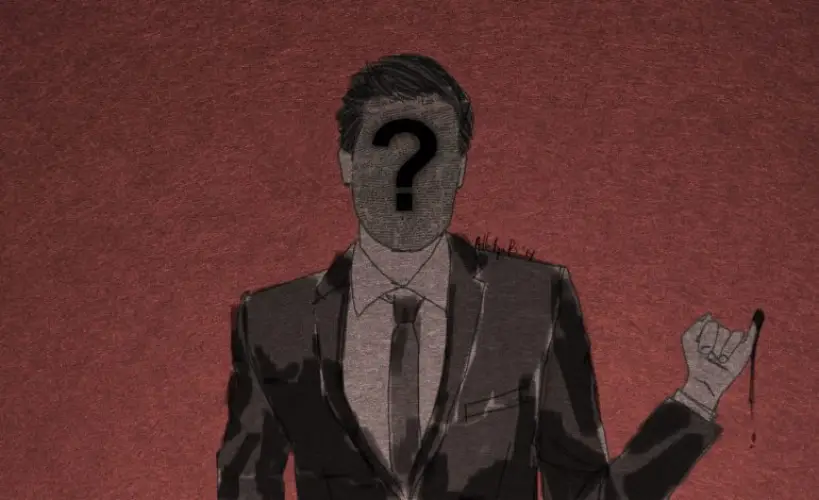Kontrasepsi: Alat Pembebasan atau Beban yang Tak Adil bagi Perempuan?

Ketika membicarakan kontrasepsi, kita sering memulainya dari narasi kebebasan: bahwa perempuan kini bisa mengatur kehamilan, menentukan waktu menjadi ibu, bahkan membangun karier sebelum membentuk keluarga. Namun, narasi ini seringkali mengabaikan satu fakta penting: hampir seluruh beban kontrasepsi, baik fisik, mental, sosial, masih ditanggung oleh perempuan.
Dari pil, suntik, implan, IUD, hingga sterilisasi, hampir semua metode kontrasepsi yang tersedia saat ini diperuntukkan bagi tubuh perempuan. Padahal, dalam relasi seksual yang melibatkan dua orang, mengapa hanya satu pihak yang diposisikan sebagai pengguna tetap?
Efek sampingnya pun tidak ringan. Kontrasepsi hormonal dapat memicu naik-turunnya berat badan, perubahan mood, depresi, tekanan darah tinggi, bahkan risiko pembekuan darah. IUD, meski efektif, dapat menyebabkan kram hebat, perdarahan berat, hingga risiko perforasi rahim. Sementara metode permanen seperti tubektomi (sterilisasi perempuan) lebih berisiko dibanding vasektomi (sterilisasi pria), namun tetap lebih umum dilakukan.
Ini bukan semata pilihan personal, melainkan hasil dari sejarah panjang kontrol sosial terhadap tubuh perempuan.
Baca juga: KB Adil Gender, Bisakah Lelaki Lebih Banyak Pakai Kontrasepsi?
Sejarah yang Menyisakan Beban
Kontrasepsi modern lahir dari perjuangan panjang perempuan untuk mengklaim kembali kendali atas tubuh dan masa depan mereka. Di Amerika Serikat, Margaret Sanger mendirikan klinik keluarga berencana pertama pada 1916. Ia dipenjara, ditentang hukum, tetapi tak menyerah. Bersama Dr. Gregory Pincus dan aktivis perempuan Katharine McCormick, ia meletakkan dasar bagi pengembangan pil KB yang akhirnya dilegalkan pada 1965 untuk perempuan menikah, dan secara umum pada 1972.
Kontrasepsi kemudian menyebar ke berbagai negara sebagai bagian dari upaya pengendalian penduduk. Di Indonesia, alat kontrasepsi diadopsi dalam program Keluarga Berencana (KB), dengan misi membentuk keluarga kecil dan sejahtera. Namun, meskipun tujuannya terdengar netral, realisasinya tetap menjadikan perempuan sebagai sasaran utama.
Tak bisa dipungkiri, kontrasepsi memberi perempuan ruang untuk sekolah lebih tinggi, bekerja lebih lama, atau menunda kehamilan sesuai kehendaknya. Data menunjukkan bahwa akses kontrasepsi berkorelasi dengan peningkatan upah dan peluang kerja. Ia menjadi alat emansipasi, membuka pintu bagi kemandirian finansial dan kesetaraan peran di ruang publik.
Tapi di balik pencapaian itu, tubuh perempuan tetap menjadi medan eksperimen utama. Laki-laki hampir tak pernah diminta memikul tanggung jawab kontrasepsi. Metode untuk mereka masih minim dan tidak dikembangkan serius, karena ada anggapan bahwa pria tidak akan mau menanggung efek samping hormonal seperti penurunan libido, mood swing, atau perubahan fisik, padahal semua itu sudah lama dihadapi perempuan. Tidak hanya itu, metode kontrasepsi permanen seperti sterilisasi cenderung lebih sering dilakukan oleh perempuan, meskipun prosedurnya lebih berisiko dibandingkan vasektomi pada pria.
Baca juga: Kata Islam tentang Kondom dan Kontrasepsi Lainnya: Tak Membunuh Makhluk Hidup
Mengapa bebannya selalu di perempuan?
Ada dua sebab utama. Pertama, kontrol sosial dan politik. Sejak awal, kontrasepsi dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur populasi, terutama di kalangan miskin dan minoritas. Karena kehamilan dianggap sebagai “urusan perempuan”, maka pencegahannya juga dibebankan kepada mereka. Pemerintah dan institusi medis jarang menawarkan opsi kontrasepsi untuk pria sebagai bentuk kesetaraan, melainkan tetap menjadikan tubuh perempuan sebagai sasaran intervensi.
Kedua, alasan medis. Penelitian kontrasepsi sejak awal hanya berfokus pada perempuan. Karena perempuanlah yang hamil, maka pencegahan kehamilan juga diarahkan ke tubuh mereka. Penelitian tentang kontrasepsi pria masih tertinggal jauh, baik karena resistensi sosial maupun karena asumsi bahwa laki-laki tak akan menerima efek samping yang mengganggu produktivitas mereka.
Konsep ini tidak lepas dari warisan patriarki. Dalam buku The Second Sex, Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa masyarakat memosisikan perempuan sebagai pihak pasif, tunduk, dan tak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Reproduksi menjadi “takdir biologis” yang melekat dan tak bisa ditawar, seolah-olah kodrat alami.
Akibatnya, tanggung jawab menghindari kehamilan menjadi bagian dari konstruksi sosial yang menindas. Kontrasepsi, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, juga menjadi simbol beban yang dipikul secara tidak seimbang oleh perempuan.
Laki-laki tak hanya luput dari beban biologis, tetapi juga dari tanggung jawab moral. Mereka tidak didorong untuk menggunakan kontrasepsi, tidak menjadi target kampanye, dan jarang dimintai peran aktif dalam perencanaan kehamilan. Kontrasepsi pria pun jarang disediakan secara luas, apalagi digratiskan atau disubsidi.
Menuju kontrasepsi yang setara, perubahan perlu dimulai dari dua arah. Pertama, dorong keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab kontrasepsi. Investasi serius dalam pengembangan kontrasepsi pria bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keadilan. Ketika pria juga turut serta, beban perempuan dapat dikurangi, dan hubungan pun lebih setara.
Baca juga: Berhenti Bilang Pakai Kondom Enggak Enak, Kontrasepsi Juga Urusan Laki-laki
Kedua, perempuan harus diberdayakan untuk tidak lagi menerima beban ini sebagai keniscayaan. Kesadaran kritis perlu dibangun untuk memahami bahwa peran pasif dalam reproduksi bukanlah kodrat, melainkan konstruksi yang bisa dan harus dibongkar.
Kontrasepsi bisa tetap menjadi simbol kebebasan. Tapi untuk mewujudkannya, kita harus mencabut akar ketimpangan yang membuatnya hanya menjadi beban sepihak. Karena kendali atas tubuh, dan masa depan, seharusnya adalah hak setiap individu, bukan beban satu gender saja.
Firda Amalia Putri adalah asisten peneliti di Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta and asisten editor Jurnal Studia Islamika.