KUHAP Baru: Ketika Hukum Acara Masih Tinggalkan Perempuan dan Anak
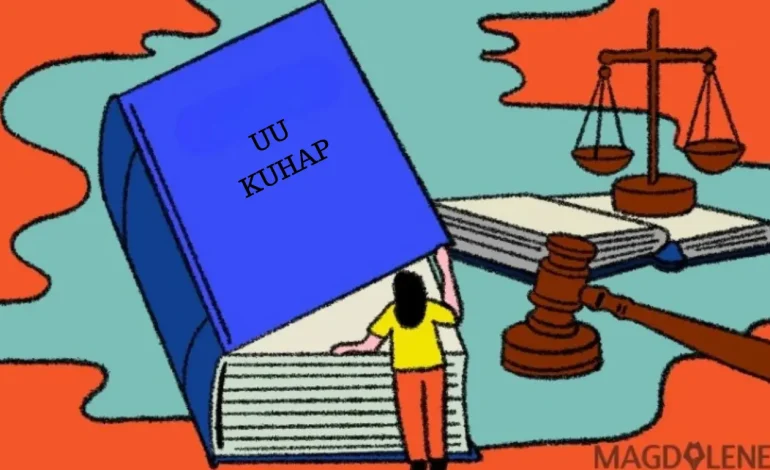
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kerap dipromosikan sebagai langkah modernisasi sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, alih-alih menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi warga negara, KUHAP baru justru memunculkan kegelisahan, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Dari sudut pandang korban, hukum acara pidana kita masih terasa dingin, berjarak, dan lebih sibuk mengatur prosedur ketimbang memulihkan luka.
Pengalaman di lapangan menunjukkan jurang yang lebar antara klaim keadilan substantif dan kenyataan. Pada November 2023, Institut Sarinah bersama organisasi Jala PRT mendampingi seorang pekerja rumah tangga bernama Rizky, korban penyiksaan di Jakarta Timur. Kasus ini bahkan sempat dibawa ke Kantor Staf Presiden dan dipertemukan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian, didampingi Kepala KSP Jenderal Moeldoko. Berita menyebar luas, perhatian publik sempat muncul. Namun hingga hari ini, penanganan perkara di Polres Jakarta Timur mandek tanpa kejelasan.
Kasus Rizky bukan pengecualian. Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2024 mencatat ratusan kasus kekerasan seksual yang diproses menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga berakhir di jalan buntu. Dalam konteks ini, pemberlakuan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada awal 2026 justru memicu kekhawatiran baru. Sistem hukum yang seharusnya melindungi korban berpotensi makin menyulitkan mereka, baik perempuan maupun laki-laki.
Dari perspektif Feminisme Pancasila, masalah KUHAP bukan semata soal teknis prosedural. Yang dipertaruhkan adalah mandat konstitusional Pancasila itu sendiri: kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Jika hukum acara gagal melindungi mereka yang paling rentan, maka ada yang keliru secara mendasar.
Baca juga: #SemuaBisaKena: Diwarnai Kritik Publik, DPR Tetap Sahkan Revisi KUHAP
Ketika KUHAP lebih ramah pada pelaku
Secara formal, KUHAP menjadi pedoman proses penyidikan, penuntutan, penahanan, hingga eksekusi putusan. Namun kritik paling mendasar terhadap KUHAP baru adalah orientasinya yang masih offender-centred. Fokus utamanya tetap pada hak-hak pelaku, sementara korban ditempatkan sebagai pihak pinggiran yang suaranya nyaris tak terdengar.
Ruang partisipasi korban dalam proses peradilan sangat terbatas. Hak untuk didengar pada tahap penyidikan dan penuntutan belum menjadi norma yang kuat. Perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perdagangan orang, masih minim. Akses bantuan hukum yang terbatas membuat perempuan miskin semakin terjepit, menghadapi sistem yang tidak dirancang untuk memahami pengalaman mereka.
Penempatan korban semata sebagai objek pemeriksaan jelas bertentangan dengan prinsip perikemanusiaan. Korban seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang bermartabat, bukan sekadar alat bukti. Dalam praktiknya, KUHAP masih memproduksi hierarki warga. Bagaimana mereka yang punya sumber daya bisa bertahan, sementara korban dari kelompok miskin dan rentan tersingkir.
Masalah lain yang krusial adalah standar pembuktian yang kaku dan tidak sensitif gender. KUHAP masih sangat mengandalkan bukti fisik, visum, dan saksi langsung. Pendekatan ini problematik dalam kasus kekerasan seksual, di mana luka fisik sering tidak tampak, dan pelaporan kerap tertunda karena trauma. Relasi kuasa, baik antara suami dan istri, atasan dan bawahan, aparat dan warga, juga sangat memengaruhi keberanian korban untuk melapor.
Feminisme Pancasila melihat kekosongan ini sebagai warisan formalitas legal kolonial, yang menempatkan prosedur di atas realitas sosial. Padahal, hukum acara pidana seharusnya mengakui bukti psikologis, kesaksian ahli trauma, pola kekerasan berulang, serta relasi kuasa sebagai bagian sah dari pembuktian. Tanpa itu, tujuan UU TPKS untuk memberi keadilan substantif akan selalu kandas.
KUHAP baru seharusnya bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran cara pandang. Dari hukum yang memeriksa tubuh perempuan, menuju hukum yang memahami pengalaman perempuan.
Baca juga: Saat Kepemilikan Buku Jadi Bukti Kejahatan
Negara kuat, tapi siapa yang dilindungi
Kontroversi lain dalam KUHAP adalah penguatan kewenangan penyidik melalui aturan upaya paksa—penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Secara teori, semua ini memerlukan kontrol yudisial sebagai jaminan due process of law. Namun KUHAP baru justru dinilai memberi ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat, melemahkan praperadilan, dan tidak memperkuat mekanisme akuntabilitas.
Dalam praktik, kondisi ini berbahaya bagi perempuan, korban kekerasan, aktivis, dan kelompok rentan lainnya. Diskresi tanpa pengawasan berpotensi melahirkan kriminalisasi korban, intimidasi pelapor, hingga penahanan sewenang-wenang terhadap perempuan miskin. Dalam kerangka Feminisme Pancasila, negara memang harus kuat, tetapi kekuatan itu wajib dibatasi oleh moralitas Pancasila, bukan dilepaskan tanpa kendali.
Masalah kian serius karena minimnya kontrol publik dan akses bantuan hukum. Banyak perempuan menjalani proses hukum tanpa pendampingan memadai. Advokat bantuan hukum tidak merata, layanan psikososial minim, dan anggaran bantuan hukum di daerah sering tidak pasti. Padahal, sila Keadilan Sosial secara tegas mengamanatkan akses terhadap keadilan bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang mampu.
Dari perspektif Feminisme Pancasila, pengujian KUHAP tidak cukup dilakukan dengan pendekatan legal-positivistik. Pancasila harus dipahami sebagai konstitusi moral yang berhak mengoreksi hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi harapan penting.
Sedikitnya ada lima agenda reformasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, memperkuat hak partisipasi korban di setiap tahap peradilan. Kedua, mengadopsi standar pembuktian berbasis trauma dan sensitif gender. Ketiga, mereformasi mekanisme upaya paksa agar prinsip checks and balances benar-benar dijalankan. Keempat, memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan miskin dan kelompok rentan. Kelima, mewajibkan prosedur ramah penyintas di seluruh sistem peradilan.
Kelima agenda ini harus dipahami sebagai reformasi struktural, bukan sekadar tambal sulam kosmetik. Tujuannya bukan hanya efisiensi peradilan, tetapi pemulihan martabat manusia sebagai pusat hukum acara pidana.
Kontroversi KUHAP bukan soal pasal semata. Ia menyangkut cara negara memperlakukan warganya, terutama mereka yang paling rentan. Hukum acara pidana yang berkeadilan gender dan sosial bukan bonus tambahan. Ia adalah mandat konstitusional sekaligus kompas moral bangsa. Dan di situlah, sayangnya, KUHAP kita hari ini masih tertinggal.
Ilustrasi oleh Karina Tungari






















