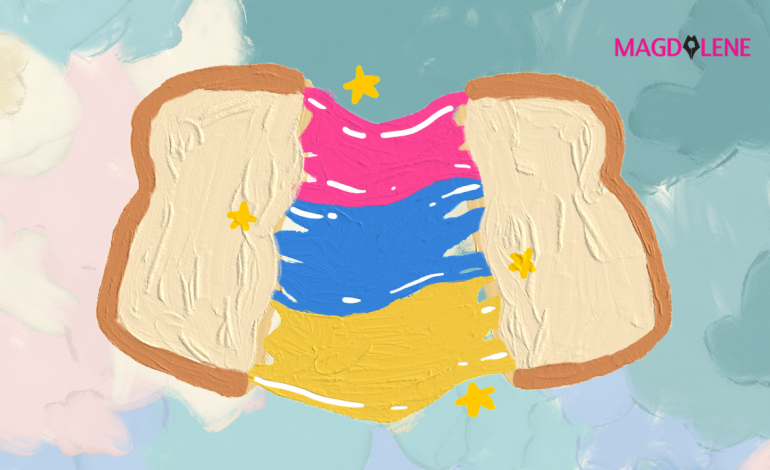Matinya Kepakaran: Kenapa Ilmuwan Kalah Pamor dari Influencer?

Di era digital ini, orang-orang lebih suka mendengarkan dan mengikuti influencers ketimbang para pakar. Meski kerap tanpa dukungan latar belakang keilmuan yang memadai, para influencer mampu mendominasi percakapan publik dan memengaruhi perilaku masyarakat.
Sebuah survei misalnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai influencer keuangan ketimbang ekonom profesional dalam persoalan finansial.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, namun juga di negara maju seperti Amerika Serikat. Masyarakat Amerika cenderung lebih percaya pada influencers kesehatan daripada tenaga kesehatan di komunitas masing-masing. Riset membuktikan bahwa sebanyak 20 persen orang Amerika mencari saran tentang masalah kesehatan di Tiktok terlebih dahulu, sebelum pergi ke dokter.
Studi lainnya menemukan bahwa 57 persen Gen Z dan 44 persen generasi milenial di AS tertarik mencoba suatu produk setelah melihat unggahan influencer.
Baca juga: Hidup Gen Z dan Milenial: “Cukup Saja Sudah Mewah, Dua-Tiga Pekerjaan Enggak Cukup”
Fakta-fakta ini memperkuat diskursus tentang “matinya kepakaran”. Orang-orang lebih percaya dengan influencer alih-alih mencari para pakar. Apakah benar kepercayaan terhadap para pakar telah ‘mati’?
Matinya Kepakaran
Fenomena “matinya kepakaran” pernah dibahas oleh penulis asal Amerika Serikat, Tom Nichols, dalam bukunya “The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters” yang terbit pada 2017 silam.
Nichols menyoroti fenomena banyaknya orang yang merasa berpengetahuan setara dengan para ahli, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi atau pengetahuan yang sama. Hal ini terjadi berkat akses informasi yang mudah melalui teknologi dan internet. Misalnya hanya dengan mengetik beberapa kata di Google atau menonton video pendek di TikTok, orang-orang sudah merasa tahu segalanya. Influencers pun bermunculan menjadi ‘pakar-pakar dadakan’.
“Teknologi telah menciptakan dunia di mana kita semua seperti Cliff Clavin,” tulis Nichols.
Nichols menggambarkan orang-orang itu seperti Cliff Calvin-karakter fiksi dari sitkom Amerika “Cheers”, yang tayang dari tahun 1982 hingga 1993. Cliff yang diperankan oleh aktor John Ratzenberger, adalah seorang tukang pos yang dikenal sebagai salah satu pelanggan tetap bar Cheers.
Baca Juga: Generasi Z: Rumah Tak Terbeli Bukan karena Kebanyakan ‘Ngopi’
Cliff sering duduk di bar itu, membual penuh percaya diri seolah tahu segalanya saat berbincang dengan teman-temannya. Padahal, ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan sebagian besar informasi yang ia sampaikan hanya bualan belaka. Sialnya, orang-orang terus mendengarkannya.
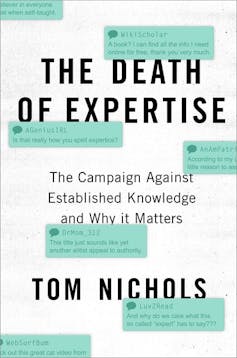
Di dunia maya, kondisi ini diperkeruh dengan algoritma platform sosial media yang menyesuaikan konten dengan preferensi dan bias kita. Akibatnya banyak orang cenderung hanya melihat informasi yang memperkuat pandangan dan preferensinya saja. Kondisi ini tidak hanya memperkuat echo chamber, tetapi juga membuat teori konspirasi dan berita palsu lebih cepat menyebar. Kemampuan berpikir kritis masyarakat justru menurun di tengah terpaan tsunami informasi. Akibatnya adalah degradasi debat publik. Alih-alih berdiskusi secara konstruktif, kita lebih sering terjebak dalam pertengkaran verbal atau hinaan.
Lalu, bagaimana para pakar harus merespons situasi ini, apakah kita harus marah atau justru mengoreksi diri?
Menghidupkan Kembali Kepakaran di Era Digital
Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa di era teknologi ini, sumber utama pengetahuan masyarakat berasal dari platform digital. Oleh karena itu, para pakar harus beradaptasi dan merangsek ke ruang digital.
Jika para ilmuwan tidak hadir di ruang ini, suara mereka akan tenggelam di tengah derasnya arus informasi, termasuk hoaks, teori konspirasi, dan opini yang tidak berbasis data.
Kita tidak bisa membiarkan publik terjebak dalam informasi yang tidak benar di era post-truth ini. Apalagi, sudah ada survei di Indonesia yang menyebutkan bahwa kurang dari 50% responden tidak mampu mengidentifikasi sumber informasi sebelum mereka bagikan di media sosial. Kemudian survei terbaru juga mengungkap sebagian besar influencer dan kreator konten tidak melakukan verifikasi fakta sebelum mengunggah konten mereka ke media sosial.
Fakta ini sangat miris tapi harus diterima. Tak ada jalan lain, pakar harus masuk ke dunia digital dan menjadi rujukan di media sosial. Berikut adalah beberapa rekomendasi agar pakar tidak kalah pamor dengan influencer;
1. Perbaiki Gaya Komunikasi
Transformasi cara komunikasi menjadi kunci keberlanjutan pengaruh pakar. Miskomunikasi antara ilmuwan dan masyarakat kerap terjadi karena para pakar lebih suka menjabarkan fakta-fakta ilmiah rumit dengan tulisan dan perkataan yang tak kalah rumit. Sementara di sisi lain, masyarakat lebih tertarik pada manfaat penelitian tersebut pada kehidupan sehari-hari.
Para ilmuwan juga sering menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Sedangkan para influencer menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti.
Ke depan, para ilmuwan perlu menggunakan pendekatan komunikasi berbasis cerita (storytelling) atau penggunaan bahasa visual seperti infografik agar pesan yang disampaikan lebih menarik.
Para pakar mungkin bisa belajar dari ahli yang sukses memiliki banyak pengikut di media sosial. Di Amerika Serikat misalnya, ada Dr Sanjay Gupta, seorang dokter bedah saraf dan koresponden medis untuk CNN. Ia kerap memberikan penjelasan mengenai isu kesehatan yang banyak terjadi di publik menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
Kemudian, ada juga Roy Casagranda, pakar ilmu politik, sejarah, dan filsafat yang sering membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat. Roy memiliki banyak pengikut di Instagram dan Tiktok serta sering mengisi siniar populer di Youtube. Selain itu, juga ada peneliti kecerdasan buatan (AI) Lex Fridman serta sejarawan dan filosof modern Yuval Noah Harari, yang siniar sains populer mereka sangat viral, dan kerap viral di Tiktok maupun Instagram.
Sementara itu, di Indonesia, ada pakar bioteknologi Riza Arief Putranto yang sering membagikan informasi sains populer di media sosial dengan menggunakan framework ViVaSo (Vision, Value, Soul) dalam komunikasi sainsnya. Kemudian, ada juga dosen Teknik Geologi ITB Dasapta Erwin yang sering membagikan ilustrasi atau gambar mengenai sains populer di media sosial.
Sudah banyak suksesi para pakar nasional maupun internasional yang mencoba unjuk gigi di ranah dunia maya dan telah menjadi rujukan di media sosial. Tidak ada salahnya bagi ilmuwan lain untuk mereplikasi metode mereka dalam komunikasi publik.
2. Aktif di media sosial dan membangun kredibilitas online
Untuk bisa menjangkau audiens yang lebih luas, ilmuwan harus mau berinteraksi di media sosial. Para pakar bisa membangun kredibilitas online sesuai bidang keahlian masing-masing dengan konsisten menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas, maupun berinteraksi dengan audiens.
Pesan yang disampaikan harus dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang sedang trending di media sosial maupun mesin pencarian.
Pengembangan konten juga harus disesuaikan dengan audiens. Jika mayoritas yang disasar adalah generasi Z dan alfa yang lebih cenderung aktif di media sosial berbasis audio-visual seperti Tiktok dan Instagram, maka kita tidak boleh “one way ticket lecturing” atau ceramah panjang satu arah seperti perkuliahan. Gaya seperti itu cenderung menjemukan, bahkan dalam praktik perkuliahan offline sekalipun.
Baca juga: Ragukan Guru Besar hingga Ahli di ‘Dirty Vote’, Warga +62 Harus Berhenti Menyangkal Pakar
Hindari membuat video sains popular terlalu panjang, kurang dari lima menit sudah cukup. Pakar bisa memberikan rujukan ke referensi yang terkait jika audiens ingin tahu lebih banyak.
Jika memiliki sumber daya yang cukup, pengembangan konten media sosial mungkin bisa dibantu tim produksi. Untuk pemula atau amatir, mungkin belum memerlukan tim produksi profesional, cukup memulai dengan meminta bantuan teman atau keluarga.
3. Kolaborasi dengan Influencer
Alih-alih melihat influencers sebagai ancaman, pakar dapat berkolaborasi dengan mereka untuk menyebarkan informasi kredibel. Influencers atau kreator konten yang punya minat di bidang sains bisa menjadi jembatan antara pakar dan masyarakat dalam membumikan ilmu pengetahuan.
Intensifikasi lintas platform media sosial juga patut dicoba. Di Indonesia, misalnya ada kampanye #infokesehatan kolaborasi antara platform Halodoc dan Tiktok, yang merupakan sebuah inisiasi inovatif nan menarik dalam melawan hoaks isu kesehatan.
Para ilmuwan juga bisa terlibat dalam aktivisme digital untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. KawalCOVID19 merupakan salah satu contoh nyata dari aktivisme digital yang melibatkan ahli dalam melawan infodemik atau misinformasi pada masa Covid-19. Advokasi KawalCOVID19 menyumbang masukan kepada pembuat kebijakan terkait masalah pandemi, dengan mengembangkan peta risiko atau indeks kewaspadaan risiko Covid-19.
Setelah melihat fakta yang ada, menurut saya, pakar tidak akan pernah ‘mati’ di era post-truth ini. Keahlian para ilmuwan akan selalu dibutuhkan, tetapi mereka suka tidak suka harus mau beradaptasi dengan zaman jika tidak ingin ditinggalkan.
Arli Aditya Parikesit, Professor of Bioinformatics, Indonesia International Institute for Life Sciences, Indonesia International Institute for Life Sciences
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.