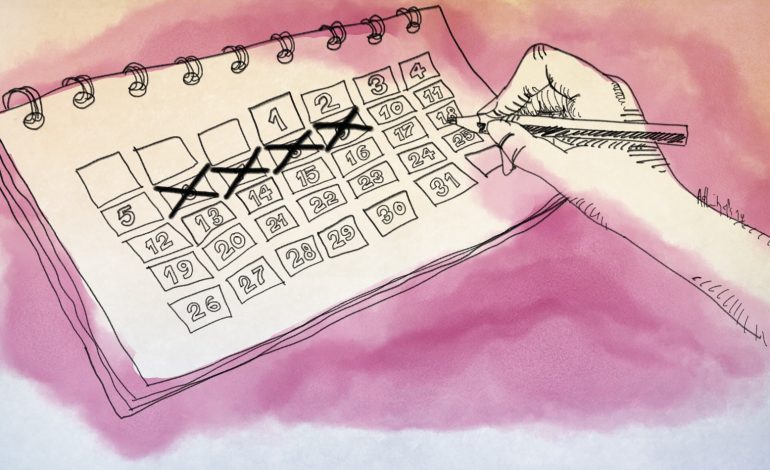Menjadi Feminis, Bukan ‘Femonasionalis’
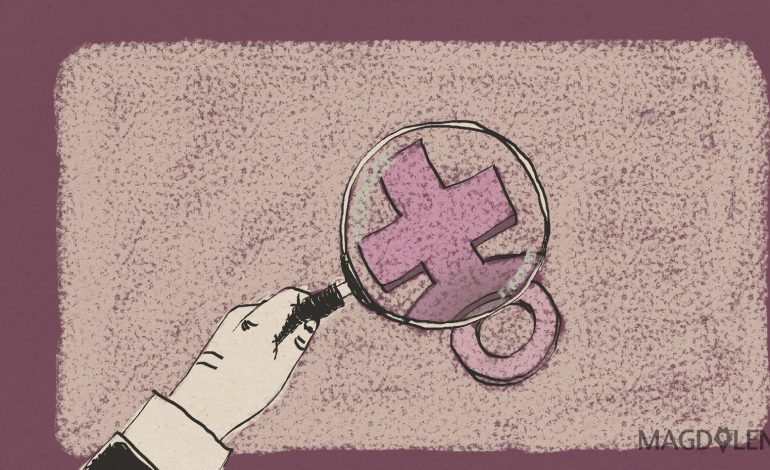
Sudah lama saya ingin menuliskan autokritik terhadap feminisme di Indonesia.
Dorongan pertama untuk tulisan ini bermula dari situasi setelah beberapa serangan teroris terbaru di Indonesia (Markas Komando Brimob di Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, dll) yang menghasilkan banyak dukungan untuk mengalienasi mereka yang mengenakan niqab. Saya akhirnya memutuskan untuk menuliskan autokritik pada hari ini setelah membaca banyak komentar bernada Islamofobik pada laman Indonesia Feminis terkait dengan unggahan-unggahan yang mendukung eksistensi feminisme Islam di Indonesia.
Sebagai sebuah ideologi dan gerakan sosial-politik, religius, dan kebudayaan, feminisme bersifat inklusif dan pluralis. Ini berarti bahwa ideologi dan gerakan ini dapat dimiliki oleh siapa pun dari lini pemikiran apa pun. Dengan demikian, feminisme yang berbasis keagamaan, seperti feminisme Islam dan feminisme Kristiani, maupun feminisme yang berbasis sekuler, seperti feminisme sosialis, merupakan hal yang wajar adanya. Sikap eksklusif dan elitis adalah racun bagi feminisme karena keduanya merupakan ekspresi wajah kekerasan yang berasal dari struktur patriarki itu sendiri.
Karena karakteristiknya yang terbuka, tentunya banyak posisi politis-ideologis yang mengklaim diri sebagai bagian dari feminisme, walaupun sesungguhnya mereka membunuh feminisme secara pelan-pelan. Dengan risiko ini, salah satu keharusan lainnya dalam feminisme adalah kewajiban autokritik (mengkritik diri sendiri) yang harus dilakukan para feminis secara berkala untuk menyaring elemen-elemen anti-feminis yang menyaru sebagai klaim feminisme tersebut.
Salah satu posisi ideologis anti-feminis yang mengklaim diri sebagai bagian dari feminisme ini adalah apa yang oleh Profesor Sara Farris dari University of London sebagai ‘femonasionalisme’ dan ‘homonasionalisme’ oleh Profesor Jasbir Puar dari Rutgers University.
Femonasionalisme dalam pemahaman sempitnya merupakan ideologi ekstrem kanan di negara-negara Barat yang mengadopsi agenda feminisme, terutama agenda pemberdayaan perempuan, sebagai alat untuk membuat posisi anti-Islam dan anti-imigrasi mereka lebih dapat diterima publik. Sementara homonasionalisme adalah pengadopsian agenda advokasi LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) oleh ideologi ekstrem kanan, pun sebagai alat pemasaran bagi posisi fasis mereka.
Dalam konteks feminisme, femonasionalisme dan homonasionalisme sebenarnya merupakan bentuk-bentuk terbaru dari “feminisme kulit putih kolonial” yang bertujuan untuk mengeliminasi bentuk-bentuk representasi feminis lainnya yang dipandang sebagai liyan dari sudut pandang Orientalis. Ini berarti bahwa dalam pandangan femonasionalis dan homonasionalis, agensi dan kedirian perempuan hanya bisa diperoleh melalui ideologi imperialis Barat yang bersifat neoliberal. Pun, pembebasan bagi kelompok-kelompok minoritas gender dan seksual hanya bisa didapatkan dari hegemoni Barat.
Pada tataran epistemologis, femonasionalis dan homonasionalis berpandangan bahwa kebenaran sejati hanya dapat diperoleh melalui kerangka epistemologi ilmiah yang rasional, yang lagi-lagi tidak lebih dari penghambaan terhadap perspektif epistemologis Barat. Segala sesuatu yang berasal dari kerangka epistemologi lainnya dianggap sebagai hal yang tak penting untuk dihiraukan. Aspek ini juga merupakan alasan mengapa perspektif ini menjadi konteks yang sangat ramah bagi gerakan-gerakan supremasi Barat, seperti Ateisme Baru.
Dengan demikian, feminisme yang berasal dari kerangka femonasionalisme dan homonasionalisme merupakan feminisme timpang yang berpandangan bahwa kebebasan perempuan dan kelompok marginal lainnya hanya bisa diekspresikan melalui agensi dan independensi neoliberal.
Feminisme ini mengesampingkan keberagaman narasi kehidupan perempuan dan kelompok marginal lainnya yang seharusnya merupakan inti sari dari gerakan feminisme apa pun. Bagi mereka, agensi ditentukan oleh tampilan luar semata. Dalam posisi ini, seorang perempuan yang mengekspresikan seksualitas dan ketubuhannya secara lebih terbuka merupakan perempuan yang lebih “terbebaskan” daripada mereka yang mengekspresikan seksualitas dan ketubuhan secara lebih tertutup.
Berbagai paradigma ekstrem kanan mengadopsi posisi femonasionalis dan homonasionalis untuk mendukung mitos “Barat yang Tercerahkan”. Posisi yang dikonstruksi untuk menjamin hegemoni imperial Barat terhadap Dunia Ketiga ini tentunya membutuhkan liyan yang dapat dijadikan landasan bagi klasifikasi Barat dan Non-Barat. Di sinilah peran Islam, muslim, dan imigran non-kulit putih muncul.
Sebagai liyan, ketiga kategori tersebut dipandang sebagai lawan dari apa pun yang direpresentasikan oleh Barat. Peradaban, kehormatan, dan independensi perempuan, rasionalitas, keilmiahan, kebebasan, dan kemajuan, dipersepsikan sebagai hal-hal yang hanya bisa diperoleh di dan inheren dalam masyarakat Barat. Sementara kehidupan primitif, perempuan submisif, perspektif irasional, terkekangnya kehidupan, dan kemunduran, dianggap sebagai hal-hal yang inheren dalam masyarakat non-Barat, terutama mereka yang muslim.
Sayangnya, mitos supremasi Barat ini tidak hanya dikonsumsi dan dibela oleh masyarakat kulit putih Barat saja, melainkan juga oleh sebagian masyarakat di “Dunia Ketiga”. Pada titik inilah terletak permasalahan dalam narasi-narasi feminisme anti-niqab, anti-Islam, dan anti feminisme keagamaan lainnya, yang sebagian contohnya dapat dilihat dari banyak komentar di laman Indonesia Feminis.
Karena bentuk klaim kebenarannya yang absolut (ironis karena mereka umumnya membenci kerangka agama karena faktor klaim kebenaran absolutnya), pendukung femonasionalis dan homonasionalis menutup pintu dialog melalui narasi-narasinya.
Narasi-narasi yang menempatkan ajaran Islam dan perspektif keagamaan secara umum sebagai sumber bagi opresi perempuan tersebut merupakan contoh jelas dari racun femonasionalisme dalam tubuh gerakan feminisme di Indonesia. Paling tidak, terdapat tiga faktor utama yang menempatkan narasi-narasi tersebut sebagai paradigma anti-feminis (walaupun mereka yang mendukungnya mengklaim bahwa perspektif mereka adalah bagian dari feminisme).
Pertama, narasi-narasi tersebut menafikan bentuk-bentuk pengalaman keperempuanan lainnya melalui klaim anti-Islam dan anti-keagamaan mereka. Dalam konteks ini, feminisme dipersempit lingkup ekspresinya karena yang dilegitimasi sebagai bagian dari feminisme hanya bentuk-bentuk agensi yang berlandaskan individualitas. Inilah mengapa hijab dan niqab tetap dipandang sebagai bagian dari patriarki secara keseluruhan, terlepas dari apa pun narasi pribadi pemakainya.
Kedua, narasi-narasi tersebut mengandung ketidakadilan pemikiran/ketidakadilan epistemologi melalui loyalitasnya terhadap epistemologi Barat. Bagi pendukung femonasionalis dan homonasionalis, kebenaran terletak pada sabda-sabda Richard Dawkins, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders, Bill Maher, para aktivis FEMEN, dll.
Sungguh ironis sebenarnya, karena pendewaan figur-figur tersebut merupakan bentuk lain dari irasionalitas yang mereka klaim sebagai sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Dari posisi ini, karena kebenaran hanyalah milik kerangka Orientalis-Imperialis Barat, maka figur-figur seperti Nabi Muhammad hanya bisa dipandang sebagai pelaku penyelewengan seksual yang patriarkal, tanpa adanya upaya kontekstualisasi mendasar dari sisi kesejarahannya.
Ketiga, karena bentuk klaim kebenarannya yang absolut (ironi lainnya, karena mereka yang mengajukan narasi-narasi femonasionalis dan homonasionalis umumnya juga membenci kerangka agama karena faktor klaim kebenaran absolutnya), pendukung femonasionalis dan homonasionalis menutup pintu dialog melalui narasi-narasinya. Hal ini menghadirkan polusi ideologis bagi gerakan feminisme yang bersemangat inklusif dan pluralis. Melalui narasi-narasi mereka, para femonasionalis dan homonasionalis sesungguhnya telah menghapuskan ruang-ruang pembebasan non-Imperialis bagi kaum marginal dan perempuan, yang mereka anggap sedang mereka bela eksistensinya.
Pada akhirnya, jika saya harus menggariskan satu prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seluruh feminis, maka prinsip itu adalah prinsip kemanusiaan. Ini bermakna bahwa kita harus menelanjangi asumsi-asumsi dan klaim-klaim feminis kita dan melihatnya dari konteks implikasi apa yang dihasilkan oleh asumsi-asumsi dan klaim-klaim tersebut.
Apalah artinya mengaku sebagai feminis jika ternyata posisi ideologis kita kembali mengorbankan para imigran di Eropa dan Amerika? Apalah artinya berteriak-teriak tentang pembebasan perempuan jika sejatinya klaim pembebasan kita hanya berarti pembebasan bagi perempuan kulit putih di Barat dan bermakna opresif bagi para perempuan di wilayah perdesaan Indonesia? Apalah artinya mengaku diri sebagai orang yang tercerahkan jika ternyata kita hanya menjadi budak pemikiran patriarkal dalam bentuk pendewaan rasionalitas?
Baca tentang penolakan terhadap Hari Hijab Sedunia.
Lailatul Fitriyah adalah mahasiswi doktoral Program Studi Agama-agama Dunia dan Gereja Global di University of Notre Dame, AS.