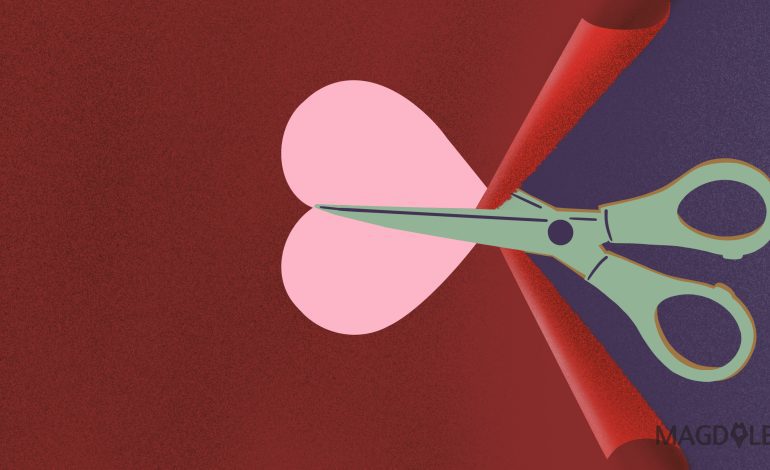Mental Kuat, Siap Hadapi Aparat: Menjadi Pendamping Penyintas Kekerasan

Peringatan pemicu: Gambaran kekerasan fisik, psikis, dan seksual
Sudah hampir 13 tahun Lisa Oktavia menjadi pendamping korban-korban kekerasan, sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai konselor hukum di Rifka Annisa, sebuah lembaga pemberdayaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berlokasi di Yogyakarta. Tugas yang tidak mudah, dan Lisa sering kali masih terkejut dan terpukul dengan tingkat kekejian yang dihadapi para penyintas.
Salah satunya yang paling membekas adalah kekerasan pada istri dan anak-anak yang dilakukan oleh ayahnya dengan berbagai bentuk, mulai dari fisik, psikis, hingga seksual.
“Pelaku tidak hanya melakukan kekerasan pada istri, tapi juga pada dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Mereka mengalami kekerasan seksual dari usia sekolah dasar selama bertahun-tahun, bayangkan!” ujar Lisa dengan nada sedih kepada Magdalene (20/6).
Sang istri kemudian mengalami depresi berat, sementara anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut trauma sampai kesulitan berkomunikasi.
“Waktu pertama kali saya datang ke sana, ibunya bahkan sudah sulit membedakan pakaian, diajak komunikasi pun enggak begitu nyambung. Anak-anaknya dititip di rumah neneknya yang miskin tidak layak huni. Kepedihan mereka bisa saya rasakan dan sangat membekas,” ujar Lisa.
Beratnya beban sebagai pendamping penyintas kekerasan turut dirasakan oleh Rahmi Meri Yenti, Direktur Nurani Perempuan Women Crisis Center (WCC) di Padang, Sumatra Barat. Rahmi sudah sembilan tahun menjadi pendamping, dan perasaannya sering tidak karuan setiap mendampingi penyintas dengan kasus kekerasan berat.
Kasus yang paling membekas baginya adalah ketika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami sekaligus ayah.
“Suaminya itu polisi, mereka sudah menikah 20 tahun namun pernikahannya penuh kekerasan fisik dan psikis. Baru menikah saja sudah sering berkata kasar. Semua kebutuhannya harus dilayani, sepatu aja dibukain, kakinya dibersihkan. Ketika si ibu ini hamil, suaminya membawa ke suatu daerah, ibunya dipaksa aborsi sampai dua kali,” ujar Rahmi.
Faktor ekonomi membuat istrinya enggan melapor, ia yang bekerja sebagai guru honorer takut tak bisa hidup mandiri dan membesarkan anak-anaknya. Anak perempuannya, yang tidak kuat melihat ibunya disiksa dan juga menemukan ayahnya berselingkuh, kemudian melaporkan sang ayah ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
“Ketika ayahnya tahu dirinya dilaporkan ke polisi, dia marah dan mengancam akan membunuh. Bahkan dia sampai nekat memanjat balkon karena mereka bersembunyi di lantai dua. Anak istrinya itu berteriak sampai akhirnya ada Pak RT yang menyelamatkan,” ujar Rahmi.
Baca juga: Mimpi Buruk Baru: Mengurus Perceraian di Tengah Pandemi
“Banyak trauma dan kekejaman yang harus kami dengarkan sebagai pendamping. Tidak mudah bagi mereka, tapi bagi kami juga berat. Belum lagi saat proses hukum penyintas harus menyampaikan kesaksian, saya harus terus mendorong supaya penyintas berani bicara,” tambahnya.
Penegak hukum bias gender
Pendamping penyintas kekerasan tidak hanya harus bermental kuat, ujar Rahmi, tapi juga harus bisa mendorong para penyintas agar bisa berdaya di atas kakinya sendiri karena kebanyakan dari mereka bertahan dalam rantai kekerasan akibat ketergantungan ekonomi. Menyediakan tempat aman sementara serta mengakomodasi kebutuhan penyintas adalah salah satu cara untuk menguatkan penyintas secara perlahan agar mereka bisa berdaya.
“Dalam kasus tadi, ibu dan anaknya menetap untuk sementara di rumah aman selama dua bulan, semua kebutuhannya kita akomodir. Setelah pelaku dihukum dua bulan penjara dan dipindahkan ke provinsi lain, akhirnya si Ibu mulai mau membuka les privat untuk membantu ekonomi,” ujar Rahmi.
Mental kuat sebagai pendamping juga harus disiapkan untuk menghadapi proses hukum yang terkadang penuh liku. Koordinator Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Uli Pangaribuan mengatakan, aparat hukum yang bias dan tidak paham perspektif gender menjadi tantangan besar dalam memberikan keadilan bagi penyintas.
“Pertanyaan-pertanyaan menyudutkan kepada korban sering banget muncul dari penegak hukum. Sampai pernah ada yang nanya tentang riwayat seksual korban, kan enggak nyambung ya. Ada juga yang dicecar karena menceritakan kronologi enggak runut, terus disuruh adegan ulang. Mereka sudah trauma jadi korban kekerasan masa harus diulang lagi,” ujar Uli.
Penyalahan semacam itu yang membuat penyintas sering kali enggan membawa kasus kekerasannya ke meja hijau. Di sini, tugas pendamping menjadi sangat krusial untuk meyakinkan penyintas bahwa kasus kekerasan hanya bisa diputus jika korbannya sendiri yang melapor.
“Padahal kekerasan itu siklus yang terus berputar, kalau enggak diputus enggak akan berhenti. LBH APIK mendorong untuk kasus-kasus agar bisa diproses lewat meja hijau, jangan hanya dibungkam saja,” ujar Uli.
“Tapi ya itu, kasih pengertiannya yang kadang susah sekali sebagai pendamping, apalagi kalau lingkungan penyintasnya juga kurang mendukung,” ia menambahkan.
Uli pernah mendengar sendiri aparat yang malah membela pelaku. Pernyataan seperti, “Coba kalau kamu nurut suami, pasti enggak akan disiksa” masih sering keluar dari mulut aparat yang seharusnya berada di pihak korban. Kacamata patriarkal yang memandang suami harus dituruti masih terus ditemui Uli selama 16 tahun menjadi pendamping penyintas.
Baca juga: Perlindungan Saksi dan Korban KDRT Terhambat Aturan PSBB dan WFH
Lisa dari Rifka Annisa mengatakan, pihaknya mengantisipasi hal itu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada aparat untuk memberikan pengetahuan dasar bagaimana sebaiknya bertindak ketika menghadapi kasus kekerasan fisik, seksual, maupun psikis.
“Memang harus ada kerja sama antara dua pihak ya. Kalau memang (aparat penegak hukum) enggak tahu bagaimana menangani kasus kekerasan, ya harus mau belajar. Mendengarkan itu yang paling penting,” ujarnya.
Ancaman UU ITE
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah lama diperdebatkan karena pasal-pasal karet yang dapat berbalik menuntut korban, seperti yang terjadi pada Baiq Nuril dan dalam kasus yang melibatkan petinggi BPJS. Dalam kedua kasus itu korban sama-sama dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik, sedangkan pelaku tidak mendapat hukuman apa-apa, malah sekarang ini dikabarkan naik jabatan. Karenanya, pendamping penyintas harus siap dengan ancaman-ancaman pelaku yang tidak terima ketika mereka diseret ke meja hijau.
“Korban berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka malah dikriminalisasi UU ITE atau pasal lain. Contohnya, ada ustaz yang dilaporkan ke polisi karena melecehkan muridnya. Ketika kasus berjalan, istri si ustaz malah melaporkan korban atas pasal perzinaan. Korban akhirnya jadi takut untuk terus melanjutkan kasus,” kata Uli dari LBH APIK.
Ia menambahkan, hal lain yang kadang luput dari perhatian tetapi sangat berdampak pada pendampingan penyintas adalah bahasa media yang masih seksis, dan juga kultur membeberkan segala sesuatu di media sosial.
“Media di Indonesia memang belum cukup ramah dalam perspektif korban. Bahasa-bahasa seksis masih sering kali muncul, dan belum lagi identitas korban yang terus menerus dicari-cari bukannya dilindungi,” ujarnya.
“Budaya spill up di media sosial juga seharusnya dikurangi ya karena nanti kalau viral pelaku malah balik menuntut,” ujar Uli.
Artikel ini didukung oleh hibah Splice Lights On Fund dari Splice Media.
Jika memerlukan bantuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan hubungi Komnas Perempuan (021-3903963, [email protected]); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH APIK (021-87797289, WA: 0813-8882-2669, [email protected]). Klik daftar lengkap lembaga penyedia layanan di sini.