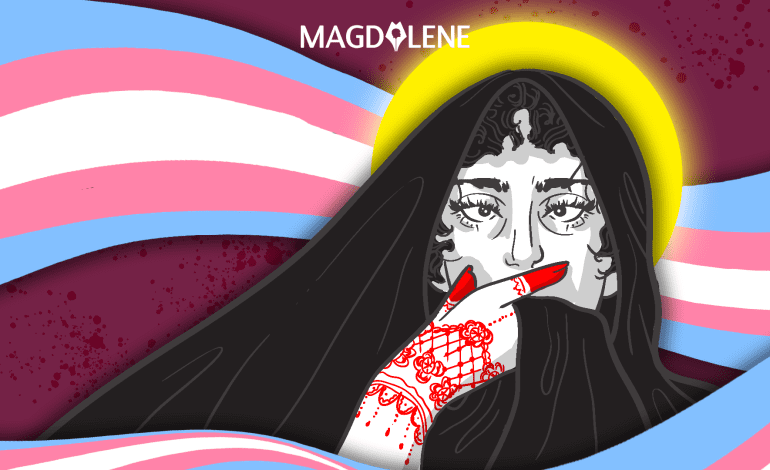Merekonstruksi Cara Keliru Merayakan Pemikiran Kartini

Perjuangan dan pergerakan perempuan setidaknya dikenang orang-orang Indonesia pada dua hari spesial: Hari Kartini dan Hari Ibu. Topik-topik tentang kesetaraan biasanya akan ramai dibahas.
Meski sudah ada kepedulian tentang sejarah dan gerakan perempuan, masalahnya debat yang muncul sering kali berputar-putar dan tak berguna. Khas patriarki memandang perempuan, dan sejarah perjuangannya.
Patriarki tak pernah melihat perempuan sebagai agen perubahan sosial, melainkan sekadar sebagai objek reproduksi manusia. Sehingga sulit sekali mendeskripsikan perempuan tanpa menyebutkan parasnya, tubuhnya, hubungan romansanya, dan anak-anaknya ketika melakukan rekonstruksi.
Diskusi terkait Kartini—simbol gerakan perempuan Indonesia—juga berputar-putar dalam sosok Kartini sebagai objek, alih-alih melihatnya sebagai subjek. Hal ini tercermin dalam berita-berita atau kontroversi yang muncul setiap Hari Kartini, yang isinya objektifikasi: menjadikan tanggal lahirnya potongan diskon, gambar di poster, membandingkan hidupnya, mengagumi wajahnya, melacak keturunannya, atau merekonstruksi pakaiannya.
Kartini sudah lama dijadikan objek oleh beberapa rezim pemerintahan dan kita harus melawan narasi serta pola diskusi yang memuakan ini. Pemikiran Kartini tak boleh dikerdilkan. Lewat gagasan dan tulisan-tulisannya, kita bisa belajar tentang kegelisahan perempuan pada masa itu yang menginginkan dunia lebih aman dan adil.
Menurut saya, cara yang paling tepat merayakan Hari Kartini adalah dengan menegakkan kembali sosoknya sebagai subjek. Kita harus membuka diskusi lebih luas dalam ilmu sejarah dan feminisme.
Kita bahkan bisa menelusuri pemikiran Kartini lebih jauh dari batasan geografis nusantara. Misalnya, mencoba membaca bagaimana kegelisahan Kartini masa itu bisa selaras dengan perempuan feminis revolusioner sezamannya.
Bagaimana mereka bisa menyuarakan kegelishan yang sama—meski terpisah jarak ruang dan sama sekali tak mengenal satu sama lain?
Baca juga: Kartini Sebagai Kakak Perempuan Panutan
Digerakan Semangat Melawan Penindasan
Perjuangan perempuan di belahan bumi mana pun memiliki pola yang sama. Menolak untuk dijadikan objek. Entah sebagai simbol seksual atau heroik, perempuan revolusioner menuntut untuk dilihat sebagai manusia seutuhnya. Penindasan lewat budaya patriarki itu lalu berkelindan dengan perasaan tertindas karena praktik kolonialisme bangsa Eropa.
Kolonialisme yang marak pada abad ke-17 telah membuat segregasi kelas sosial dipisahkan berdasarkan warna kulit. Secara berangsur-angsur, tradisi penjualan budak memisahkan antara warga negara dan non-warga negara. Warga negara yang memiliki hak di masyarakat dicirikan dengan kebangsaan Eropa dengan warna kulit putih porselen, murni, lelaki dan bekerja untuk pemerintahan. Selain ketiga identitas tersebut, maka tidak memiliki hak untuk hidup atau berpartisipasi di masyarakat dalam bentuk hak pilih.
Periode akhir abad ke-19 menjadi titik-titik api politik yang bergejolak di seluruh dunia, tidak hanya di Hindia Belanda. Industrialisasi dan kebangkitan liberalisme pada abad sebelumnya telah melahirkan kelompok-kelompok atas yang mengembara dari benua Eropa ke benua-benua lainnya seperti Amerika, Afrika, termasuk ke Asia Tenggara.
Pengembaraan tersebut juga melahirkan migrasi. Tidak hanya migrasi perpindahan manusia dan barang, tapi juga migrasi pikiran dan pengetahuan.
Baca juga: Kobarkan Kembali Api Kartini
Keresahan Kartini dan Susan B. Anthony
Migrasi pikiran dan pengetahuan terjadi pada Kartini dan Susan B. Anthony, perempuan revolusioner dari Amerika Serikat yang hidup di era yang sama dengan Kartini. Meski terpisah benua dan mungkin tidak kenal satu sama lain, mereka berbagi keresahan yang sama. Keresahan mereka adalah diskriminasi yang menjadikan perempuan dan orang-orang kulit berwarna sekadar objek.
Susan dilahirkan pada 20 Februari 1820 di Massachusets. Ia berasal dari keluarga Quaker yang memiliki bisnis penggilingan kapas. Pengalamannya berhadapan langsung dengan diskriminasi berdasarkan gender dan warna kulit ia dapat ketika ia menggantikan pekerja yang sakit di pabrik ayahnya, Daniel Anthony. Kala itu ia dibimbing oleh Sally An Hyatt, seorang perempuan pekerja yang sangat terampil.
Susan bertanya pada Ayahnya mengapa Sally An Hyatt yang begitu terampil tidak dijadikan supervisor, sementara pengawas penggilingan lelaki bekerja tidak seterampil pekerja perempuan. Ayahnya menjawab, “Supervisor harus seorang lelaki, Susan. Tidak akan pernah ada pengawas penggilingan perempuan.”
Mendengar jawaban ayahnya, ia terkejut dan marah. Dalam diarinya, ia menuliskan bahwa ia marah dengan ketidakadilan dalam pembagian kerja dan pengupahan terhadap perempuan.
Dalam salah satu pidatonya ia menolak sistem yang meletakan perempuan dan kulit berwarna sebagai objek dan bukan seorang subjek merdeka, “Memangnya bagaimana perempuan pertama kali tunduk pada pria, seperti sekarang di seluruh dunia? Apakah menurut perangainya, jenis kelaminnya, orang kulit hitam (dan perempuan itu hinggga) akhir zaman akan selalu lebih rendah dari ras kulit putih? Dan oleh karena itu, ditakdirkan untuk tunduk?”
Baca juga: Kartini, Nasionalis yang Terlupakan
Kesedihan dan kemarahan juga dirasakan oleh Kartini dalam surat-suratnya. Kartini yang dilahirkan sejaman dengan Susan mengalami diskriminasi berdasarkan gender dan ras yang diwujudkan dalam bentuk feodalisme dan kolonialisme.
Dalam suratnya pada tahun 1888, ia menulis, “Peradaban adalah berkah tetapi juga memiliki sisi gelap. Dorongan untuk meniru melekat pada manusia, itu yang saya percaya. (Kelas sosial membuat) orang-orang meniru kebiasaan kelas di atasnya, kemudian kelas-kelas tersebut meniru kelas yang tertinggi – kelas orang Eropa.”
Dengan membaca secara saksama diari Susan B. Anthony maupun surat-surat Kartini, kita dapat menangkap nuansa yang sama.
Kemarahan atas sistem patriarki dan kolonialisme yang menciptakan segregasi di masyarakat berdasarkan warna kulitnya. Kita belajar, bahwa pengalaman diskriminasi terhadap perempuan dan kulit berwarna walau terpisah ruang dan waktu, tetap relevan untuk diperjuangkan.
Membaca perjuangan Kartini dan Susan juga membawa kita pada gambaran lebih luas tentang penindasan yang dialami perempuan di sepenjuru dunia. Nuansa yang kita perlukan untuk tak lagi merayakan pemikiran-pemikiran perempuan revolusioner seperti mereka, pakai kacamata patriarki yang suka mengobjektifikasi.