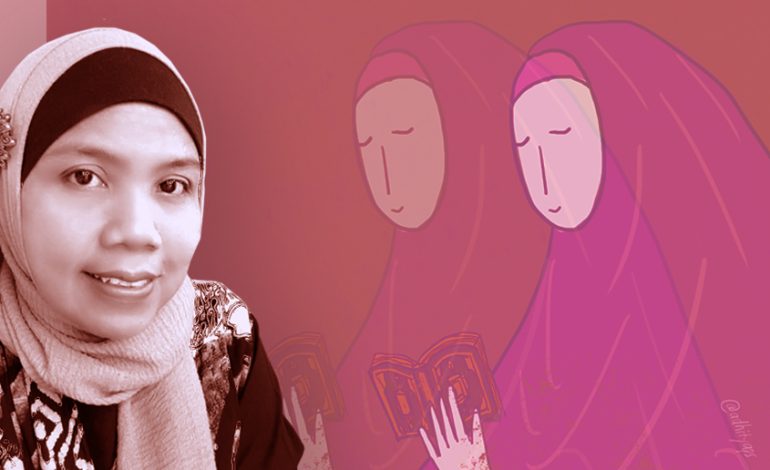Pak Bahlil, Perempuan Sudah Lebih Dulu Gantikan Anda dengan Robot

“Semakin hari, dunia berubah, suatu saat pekerja perempuan mungkin nanti tidak laku, diganti robot. Hati-hati kalian perempuan, ini tidak bisa dihindari, tenaga kerja sekarang banyak digantikan oleh teknologi,” ujar Bahlil Lahadilia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pernyataan tersebut tidak lagi membuat saya kaget. Sepanjang 24 tahun hidup saya di Indonesia, saya sangat terbiasa dengan pejabat-pejabat pemerintahan yang misoginis dan seksis. Jari tangan dan kaki saya tidak cukup untuk menyebutkan siapa-siapa saja mereka.
Meski tidak mengherankan, pernyataan Bahlil sangat keliru dan perlu dikritik dalam beberapa level. Pertama, dia melihat perempuan sebagai warga negara kelas dua yang dibayar dengan upah rendah. Kedua, pemahamannya sempit terkait perkembangan teknologi dan ketakutan terhadap teknologi akan mengambil alih kerja manusia. Ketiga, dia pikir investasi melalui modal asing dapat membuat penduduk Indonesia sejahtera.
Ucapan Bahlil sungguh ironis, sebab jika dia menyatakan semakin hari dunia berubah, mengapa isi kepalanya yang misoginis tidak berkembang sesuai dengan perubahan zaman? Reformasi 1998 yang digembar-gemborkan membawa perubahan bagi rakyat Indonesia berbalik arah 20 tahun kemudian seperti zaman Orde Baru.
Lebih dari setengah abad lalu, saat Soeharto menaiki tampuk pemerintahan, aturan yang pertama kali diresmikannya adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967. Ini adalah tonggak awal akumulasi kapitalisme global dan dimulainya pengisapan habis-habisan sumber daya alam Indonesia yang dilakukan oleh asing dan dibantu oleh warganya sendiri di posisi elite.
Baca juga: Apa Itu Omnibus Law dan Mengapa Kita Harus Waspada
Dan kini, Presiden Joko Widodo, yang digadang-gadang sebagai pemimpin yang membawa perubahan, malah melanjutkan eksploitasi sumber daya alam dengan mengutamakan ekspor industri ekstraktif seperti pertambangan dan pendirian pabrik-pabrik multinasional. Kebijakan ini ditopang dengan penciptaan budaya pendidikan yang membuat warga negara Indonesia sekadar menjadi jongos, melakukan kerja produksi yang nilai akumulasi modalnya dinikmati oleh negara-negara asing di belahan dunia utara sana.
Eksploitasi pekerja perempuan berkedok pemberdayaan
Indonesia menjadi target penanam modal sebagai negara dunia ketiga dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan banyak, serta memiliki angka angkatan kerja yang cukup tinggi. Pada 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk angkatan kerja di perkotaan dan pedesaan mencapai 133 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 67,49 persen.
Sayangnya, data mentah seperti ini memang tidak bisa bicara banyak, hanya menunjukkan angka-angka. Angka partisipasi angkatan kerja yang disajikan tidak mengelaborasi jenis pekerjaan bidang informal seperti pekerja rumah tangga, pedagang asongan dan kaki lima, warung makan yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, definisi kerja kita juga sangat terbatas pada kerja produktif dan formal.
Nyatanya, perempuan pekerja banyak diserap sektor informal dengan menjadi asisten rumah tangga, dalam bisnis katering, atau tukang cuci-setrika. Sedangkan yang dimaksud dalam ucapan misoginis pejabat penanaman modal adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh upahan rendah.
Ketika teknologi semakin maju dan seharusnya membebaskan semua manusia termasuk perempuan, pemerintah Indonesia malah mengancam perempuan dengan teknologi.
Perempuan kelas menengah ke bawah yang bekerja biasanya terperangkap dalam nilai-nilai patriarki sehingga mereka diikat dalam kewajiban mengurus rumah, menjadikan mereka sebagai tenaga kerja sampingan, bukan bekerja penuh. Dengan statusnya sebagai pekerja rumah tangga dan hanya membantu perekonomian dengan bekerja upahan, perempuan rentan dieksploitasi dengan kedok pemberdayaan. Lihat bagaimana katadata.co.id menyajikan data rendahnya serapan perempuan pekerja formal menurut Bank Dunia, dan bagaimana perempuan mengharapkan jam kerja fleksibel supaya bisa fokus mengurus rumah tangga.
Tanggung jawab tunggal perempuan terhadap domestik rumah tangga membuat mereka tidak dilihat sebagai pekerja utama. Berbagai jenis sistem kerja perempuan dibuat supaya mereka dapat diperas tenaganya dengan beberapa sistem kerja: kerja sesuai target dan perhitungan pembayaran sejumlah produksi, bukan jam kerja yang digunakan dalam memproduksi barang; memperkerjakan perempuan di rumah atau pekerja rumahan dengan alasan supaya perempuan lebih fleksibel mengatur waktu mengurus rumah; serta semakin pendeknya kontrak kerja bagi perempuan dan keengganan memperpanjang kontrak jika pekerja ketahuan hamil. Pikiran misoginis Bahlil tidak bisa melihat kenyataan kondisi pekerja perempuan negerinya yang dieksploitasi demi modal asing.
Ketakutan terhadap teknologi
Level kedua kesalahan argumen Bahlil adalah ketakutan dia terhadap teknologi. Bukan barang baru bahwa pemerintah yang tua-tua nan patriarki itu lamban dan tidak mampu menanggapi perkembangan teknologi. Peneliti di Koperasi Riset Purusha dan Editor Jurnal IndoProgress, Hizkia Yosie Polimpung, sudah memprediksi ketakutan pemerintah terhadap otomasi 4.0 ini sebab pekerjaan formal di Indonesia didominasi oleh kerja-kerja buruh dengan upah rendah dan sifatnya teknis.
Di sisi lain, kemajuan teknologi yang dipikirkan (dan disponsori) oleh pejabat pemerintah neoliberal adalah teknologi dalam bidang industri. Lihat bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronisk 2008 (UU ITE) dibuat untuk mengakomodasi kehadiran e-commerce yang modal rintisannya dimiliki oleh Tiongkok.
Baca juga: Perempuan Pekerja Rumahan: Terabaikan dan Tak Diakui Haknya
Perempuan sudah lama berusaha mengganti kerja-kerja domestik yang membebaninya dengan teknologi. Teknologi tidak selalu menjadi musuh perempuan, tergantung ke arah mana perkembangan teknologi dilakukan. Alat kontrasepsi seperti morning after pill atau IUD misalnya, adalah bentuk kemajuan teknologi supaya perempuan tidak khawatir hamil dan mampu menikmati hubungan seks.
Perkembangan teknologi juga mengurangi beban perempuan dalam kerja-kerja rumah tangga seperti mesin cuci dan pengering, robot pembersih lantai, mesin cuci piring, dan sebagainya. Bahkan kami sudah lama mengganti laki-laki dalam memenuhi kebutuhan seksual dengan vibrator dan dildo.
Terakhir, investasi dan modal asing tidak akan menyelesaikan permasalahan kerja dan ledakan angkatan kerja sepuluh tahun ke depan. Ditambah dengan adanya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cilaka, yang hanya memperparah kerusakan lingkungan sebab izin mendirikan pabrik dan pertambangan akan menjadi semakin mudah. Dampaknya adalah bencana lingkungan beberapa tahun ke depan, saat sumber daya alam diserap habis-habisan dan sumber daya manusia dimiskinkan secara struktural, sebab semua akumulasi keuntungan, akan lari ke luar negeri.
Kita tidak bisa diam jika pemerintah yang seksis, misoginis, dan buta teknologi hendak menjual sumber daya alam dan memiskinkan warganya secara struktural. Semua kelompok, tidak hanya perempuan, harus marah dan berlomba-lomba protes pada pemerintahan yang terlalu pro-modal assing. Ketika teknologi semakin maju dan harusnya membebaskan semua manusia termasuk perempuan, pemerintah Indonesia malah mengancam perempuan dengan teknologi.