Pandemi Zaman Kolonial Hingga Kini, Kesehatan Ibu dan Anak Tetap Rentan
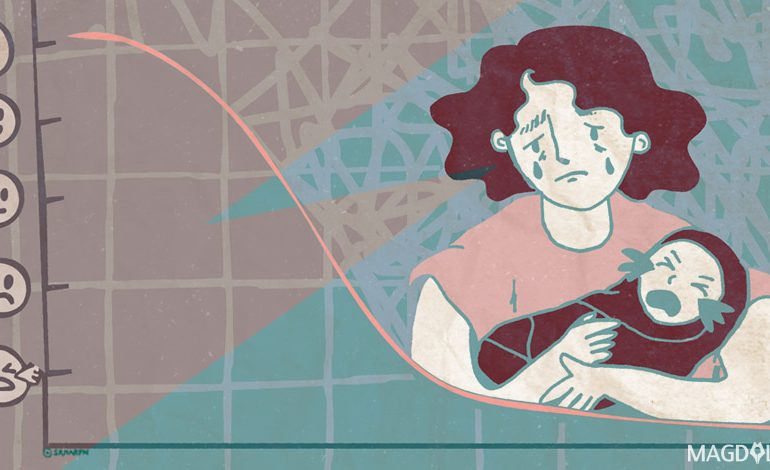
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap perempuan, termasuk semakin terabaikannya layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR) serta layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) semakin tersisihkan.
Implikasi serius dari terbatasnya layanan KSR dapat terlihat dari peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan selama pandemi ini berlangsung. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi akan ada tambahan 370.000-500.000 kelahiran pada medio awal 2021.
Selain itu, ibu hamil biasanya memiliki sistem imunitas tubuh yang lebih rendah, sehingga lebih rentan untuk terinfeksi virus corona, berisiko melahirkan secara prematur, serta berpotensi mengalami gejala penyakit yang lebih parah hingga meninggal dunia.
Terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak akibat pandemi seperti sekarang ini bukan kali pertama terjadi, menurut para sejarawan. Dalam catatan sejarah, sejak masa kolonial Hindia-Belanda, setidaknya ada lima pandemi yang mematikan dan berdampak serius di Nusantara: wabah malaria (1733-1738), pes pada awal abad 19, kolera (1820-1822), flu Spanyol (1918-1919) dan cacar (1920-an).
Kelima pandemi ini berdampak pada kematian perempuan usia produktif, terutama ibu hamil, serta anak.
Angka Kematian Ibu dan Anak Tinggi Akibat Pandemi
Sejarawan dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Martina Safitry mengatakan, flu Spanyol yang juga menyerang pernapasan seperti COVID-19, sepanjang tahun 1918 menewaskan banyak perempuan usia 15-49 tahun. Jumlah kematian tersebut mencapai 600 kali lipat total angka kematian selama empat tahun sebelum wabah terjadi. Angka tersebut juga diperburuk oleh peningkatan kematian bayi yang baru lahir.
Wabah cacar yang menyerang sejak abad ke-17 pun rentan menyerang bayi yang daya tahan tubuhnya masih rendah, ujar Martina.
Baca juga: Menengok Dampak Jangka Panjang Kehamilan Tak Direncanakan Selama Pandemi
“Kerentanan perempuan hamil ini mungkin disebabkan oleh perubahan sirkulasi darah, berkurangnya kapasitas fungsional paru-paru, dan imunosupresi, atau kadang-kadang disebut sebagai sindrom imunodefisiensi terkait kehamilan (PAIDS)) yang juga membuat perempuan lebih rentan terhadap infeksi,” ujar Martina dalam webinar Antara Harapan dan Kenyataan: Sejarah Kesehatan Ibu dan Anak di Tengah Pandemi yang diadakan oleh Komunitas Sejarawan Perempuan (16/1).
Ia menambahkan, wabah flu Asia pada 1957 yang menimpa wilayah Asia, mengakibatkan separuh kematian perempuan usia subur dan cenderung menjangkiti perempuan hamil.
Jika ibu hamil terpapar flu tersebut pada trimester pertama dan kedua kehamilan, maka hal itu akan meningkatkan risiko kelahiran prematur dan kematian setelah melahirkan, ujarnya. Demikian rentannya kondisi ibu hamil pada pandemi saat itu, sampai banyak ibu memilih untuk melahirkan bayi lebih awal untuk mengurangi risiko terpapar influenza, ujar Martina.
Angka kematian ibu dan anak yang tinggi akibat pandemi juga ditemukan oleh sejarawan dari Universitas Airlangga, Moordiati, dalam penelitiannya tentang kesehatan perempuan dan anak pada masa tanam paksa (1830-1870).
Moordiati mengatakan, selain kurangnya asupan gizi dan kelelahan bekerja, ada pola kematian yang lebih tinggi dalam periode sejarah tertentu akibat wabah penyakit, mulai dari tipus, cacar, sampai dengan kolera.
“Selain karena pandemi, sebagian besar kematian ibu dan anak karena tersita waktunya di perkebunan, sehingga mereka enggak punya waktu untuk mengurus asupan gizi saat sedang hamil,” ujar Moordiati di acara yang sama.
Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Pemerintah Kolonial
Tantri Swastika dari Youth Engagement Officer Unala, organisasi yang berfokus pada pelayanan kesehatan reproduksi remaja, mengatakan adanya berbagai wabah yang juga menyerang banyak orang Belanda membuat pemerintah kolonial memperbaiki sektor kesehatan di Hindia Belanda.
Baca juga: Pandemi Hambat Program Penapisan Kanker Serviks di Indonesia
Sejak wabah malaria, pemerintah kolonial terus mengirimkan dokter dari Belanda untuk membantu menangani wabah. Selain itu, sejak 1851, mereka juga membuka sekolah bidan di Batavia, yang berfokus mengadakan pelatihan kebidanan untuk dukun beranak.
“Jumlah dokter keturunan Eropa pada saat itu ada 177 orang, sementara dokter bumiputra ada 150 orang. Sedangkan jumlah perawat berdiploma dari kalangan bumiputra lebih banyak empat kali lipat dibandingkan perawat Eropa, yakni sebesar 1.210 orang sedangkan perawat Eropa 316 orang,” ujar Tantri, yang juga alumni Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada.
Selain tenaga medis yang terus bertambah, kemajuan dunia kesehatan juga ditandai oleh banyaknya jumlah pembangunan rumah sakit oleh pihak swasta. Pada 1910 misalnya, ada lima orang lulusan pendidikan kebidanan pertama dari Rumah Sakit Petronella, Yogyakarta. Baru pada tahun 1937 ada desentralisasi layanan kuratif ke provinsi, kota praja, kabupaten, dan sektor swasta oleh pemerintah kolonial. Sejak saat itu, pelayanan kebidanan makin berkembang, begitu pun layanan kesehatan anak dan ibu.
“Di Surabaya misalnya, pada 1930-an berdiri sebuah perhimpunan yang bertujuan mencegah tingginya kematian bayi (Vereeniging voor Kinderzorg). Mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah perempuan yang sedang hamil dan mengedukasi perawatan kesehatan ibu hamil dan bayi dengan tenaga profesional,” ujar Tantri.
Pemerintah kolonial melalui Dinas Kesehatan Rakyat juga turut mengadakan program Pendidikan Kesehatan Rakyat (Medisch-Hygienische), di mana kegiatan itu menekankan cara-cara edukatif dalam menumbuhkan kesadaran hidup bersih dan sehat.
“Pusat higiene itu memiliki layanan konsultasi menyangkut kehamilan, pertolongan persalinan, sampai perawatan selama masa nifas,” ujar Tantri.
Baca juga: 32 Tahun Posyandu: Miskin Dana, Perspektif Gender, dan Regenerasi
Vaksin yang Tidak Mudah Diterima
Meski secara perlahan pelayanan kesehatan ibu dan anak semakin berkembang dan masyarakat mulai menerima ilmu pengetahuan medis, namun, menurut Tantri, vaksin tidak serta merta langsung diterima. Layaknya sekarang ini, di mana banyak pihak menolak vaksin, hal serupa juga terjadi pada masa kolonial.
“Awalnya tidak mudah diterima masyarakat, banyak yang beranggapan kalau itu politik kolonial untuk menghegemoni mereka dan pengobatan tradisional semakin dikerdilkan. Ada juga isu agama, banyak yang percaya kalau air susu ibu itu vaksin alami,” ujar Tantri.
Setelah Indonesia merdeka, kepedulian akan kesehatan ibu dan menjadi perhatian utama pemerintah, karena angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Pada dekade 1950-an didirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKAI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui BKAI dan IBU, pemerintah terus menggalakkan program imunisasi dan vaksinasi yang berlangsung hingga sekarang.
Walaupun berkaca pada sejarah penanganan kesehatan ibu dan anak saat pandemi penting dilakukan, Martina mengatakan, masih minimnya historiografi yang membahas mengenai hal itu membuat permasalahan ini seolah tidak dianggap serius. Padahal, jika semua pihak mau belajar pada penanganan kesehatan ibu dan anak saat masa krisis dalam sejarah, bukan tidak mungkin bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Apalagi angka kematian ibu masih tinggi sampai sekarang, mencapai 305 per 1.000 kelahiran hidup pada 2018/2019, menurut data Kementerian Kesehatan.
“Mengetahui riwayat pelayanan kesehatan ibu dan anak pada saat pandemi di masa lalu akan memberikan pelajaran dan pertimbangan untuk mempersiapkan diri dalam situasi serupa yang terjadi di masa akan datang. Merawat kesehatan ibu dan anak menjadi penting untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa,” ujar Martina.






















