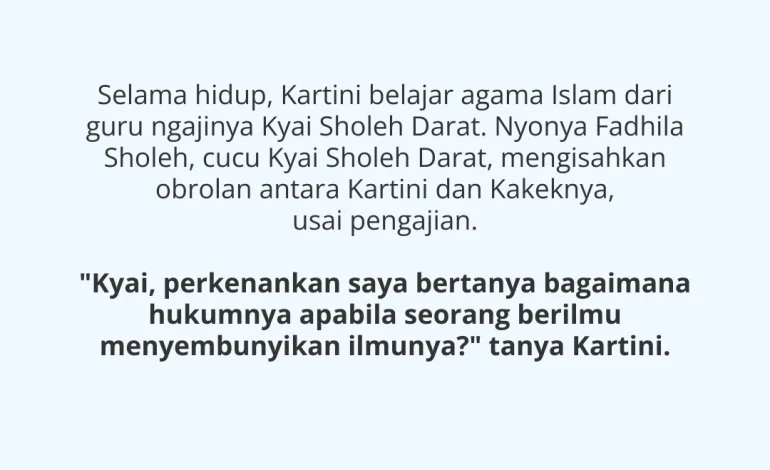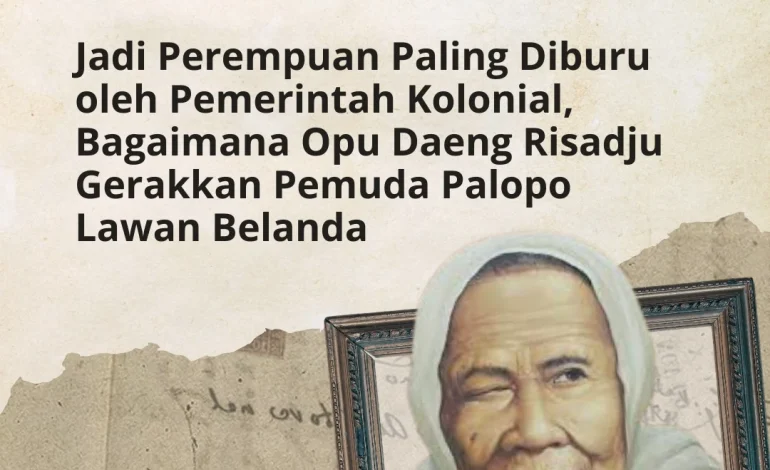“Rina” sedih bukan kepalang begitu tahu artikelnya di jurnal internasional diplagiasi dengan kemiripan 83 persen. Pelakunya adalah dosen lain di perguruan tinggi swasta di Jogja pada akhir 2022 silam. Sebagai dosen yang dikenal pintar dan memegang teguh etika akademis sejak berstatus mahasiswa, hal ini membuatnya kaget.
“Aku dikasih tahu sama mahasiswaku. Dia bilang, ‘Mbak, tahu enggak kalau ada artikel jurnal yang mirip banget sama punya Mbak.’ Langsung aku cek. Deg-degan aku pas buka karena ini pertama kalinya aku ngalamin ini. Dan kupikir bakal beda gitu datanya, ternyata persis sama,” kenang Rina.
Rina bukan satu-satunya korban plagiasi. Beberapa tahun belakangan, dugaan pelanggaran serupa marak dilaporkan terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Misalnya kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe, Aceh; Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah; dan Universitas Sumatra Utara, Medan, Sumatra Utara.
Selama 6 bulan, The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Majalah Tempo dan Jaring.id, media nirlaba independen yang didirikan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), melakukan reportase mendalam untuk membongkar praktik pelanggaran akademis yang terjadi di Indonesia.
Hasil pengamatan mendalam kami berhasil memetakan tren pelanggaran akademis, dampaknya bagi publik dan mengapa ini makin marak.
Baca juga: ‘Calo Publikasi’: Jalan Pintas Dosen di Tengah Tuntutan Menulis
Tren Pelanggaran Akademis di Indonesia
Data dari Retraction Watch Database, website yang melaporkan pencabutan makalah ilmiah, menunjukkan jumlah artikel penulis Indonesia yang diretraksi (dicabut) meningkat. Per 2023, misalnya, ada 18 artikel yang diretraksi. Sementara, per Maret 2024 jumlahnya sudah mencapai 27 artikel.
Retraksi dilakukan apabila dalam artikel terdapat indikasi pemalsuan data, plagiarisme, klaim kepenulisan yang tidak benar, pengiriman artikel berulang kali, atau ada kesalahan umum terkait kode etik profesi.
Naiknya jumlah artikel ilmiah bermasalah memperburuk reputasi Indonesia di mata internasional.
Awal 2024 ini, Peru, yang sedang menggodok undang-undang untuk menghukum peneliti yang terlibat dalam praktik penerbitan palsu, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan banyak peneliti yang “mencurigakan”.
Indonesia juga menempati ranking dua setelah Kazakhstan untuk jumlah publikasi di jurnal predator, yaitu jurnal internasional yang proses penerbitannya tidak melalui proses peninjauan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Gaji Secuil, Lingkungan Toksik: Potret Buram Kesejahteraan Dosen Indonesia
Dampak Pelanggaran Akademis pada Publik
1. Dampak keuangan negara
Meski pelanggaran akademis termasuk pelanggaran etik, tapi dampaknya dapat menjalar ke kerugian keuangan negara.
Pemerintah melalui universitas mengalokasikan sebagian anggaran negara untuk tunjangan profesi dosen. Tunjangan diberikan setiap bulan sebagai bentuk penghargaan dan stimulus agar dosen terus meningkatkan kinerja, termasuk menerbitkan artikel ilmiah di jurnal bereputasi internasional.
Ini belum termasuk dana dari universitas negeri dan swasta sebagai insentif kepada dosen yang berhasil menerbitkan artikel di jurnal bereputasi. Jumlahnya berkisar Rp4 juta – Rp40 juta per artikel.
Dana insentif ini bisa diambil dari uang kuliah mahasiswa, bisa juga dari anggaran negara.
Analisis profesor Ekonomi dari Universitas Padjajaran sekaligus Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia periode 2021-2023, Arief Anshory Yusuf, menemukan seribu lebih artikel yang terbit di jurnal-jurnal bermasalah pada 2021. Jika per artikel mendapatkan insentif setidaknya Rp5 juta, maka tahun itu publik sudah merugi Rp5 miliar.
Selain insentif publikasi jurnal, pembiayaan riset sendiri juga bisa berasal dari dana internal universitas yang salah satu sumbernya adalah uang pangkal mahasiswa baru. Ini biasanya diterapkan oleh perguruan tinggi swasta.
Sementara, pembiayaan riset di perguruan tinggi negeri berasal dari keuangan negara.
“Mereka (kampus negeri) dibayar kita (rakyat),” tegas Arief.
Dia turut menekankan pentingnya kampus negeri mempertanggungjawabkan alokasi anggaran riset dan penerbitan jurnal ilmiah kepada publik apalagi ketika prosesnya terbukti bermasalah.
2. Dampak kredibilitas ilmu
Kampus adalah pusat ilmu pengetahuan dan sains. Kedua hal ini, menurut Arief, memerlukan kejujuran untuk berkembang. Produksi pengetahuan lembaga yang dibuat secara ala kadarnya—bahkan bermasalah secara etika—akan berdampak negatif pada publik.
“Tidak hanya publik menjadi apatis dengan ilmu pengetahuan, hasil-hasil riset tidak akan lagi bisa dipercaya,” ujar Arief.
Jika dosen ataupun peneliti di kampus tidak menulis artikel ilmiah dengan benar, jurnal hanya akan memuat artikel-artikel tidak bermutu. Ini memperbesar peluang replikasi pengetahuan yang salah.
Apabila pelanggaran akademis dibiarkan, database penelitian akan dipenuhi karya-karya ilmiah yang meragukan.
“Yang lebih makro, ini akan merusak ekosistem riset kita,” tegas Arief.
Mahasiswa doktoral di Ludwig Maximillian Universität (LMU) München, Jerman, Ilham Akhsanu Ridlo, mengatakan banyaknya artikel ilmiah yang meragukan memaksa dia bolak-balik memeriksa kebenaran riset yang menjadi rujukan penelitiannya. Sebab, saat melihat data Retraction Watch Database, Ilham justru mendapati banyak riset bidang kesehatan di Indonesia, termasuk tentang COVID-19, yang bermasalah. Riset doktoral Ilham berhubungan dengan pagebluk.
Dia menganggap pelanggaran akademis tidak bisa dibiarkan. Selain menambah lapis pemeriksaan dalam riset, pembiaran akan membuat publik, termasuk mahasiswa, kehilangan kepercayaan pada dosen.
“Ketika penelitian sudah bohong, rusaklah sudah. Kredensial yang dipunyai akan menjadi sekadar kredensial palsu,” tegas Arief.
Baca juga: Mempertanyakan Konsep ‘Kampus Merdeka’ di Indonesia: Siapkah Mahasiswa Kita?
Mengapa itu Marak?
Wawancara kami dengan beberapa sumber mengindikasikan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang mendorong maraknya praktik pelanggaran akademis dalam lima tahun terakhir.
1. Neoliberalisme dan otoritarianisme dalam pendidikan tinggi
Masduki, guru besar Media dan Jurnalisme dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang juga seorang aktivis pro kebebasan akademis, menjelaskan dalam wawancara dengan The Conversation Indonesia bahwa fenomena pelanggaran akademis ini disebabkan oleh tarik menarik antara neoliberalisme, otoritarianisme, dan demokratisasi pendidikan tinggi di Indonesia.
“Kita ini hybrid. Istilahnya, state control capitalism. Pemerintah ikut campur terlalu banyak, termasuk dalam hal pola karir dosen,” tuturnya.
Ikut campur negara ini dapat dilihat dalam bentuk penentuan angka kredit (penilaian) untuk mendapatkan promosi ke jenjang karier akademis atau jabatan keahlian fungsional tertentu. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 untuk dosen negeri. Ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen untuk dosen swasta.
Untuk memenuhi angka kredit tersebut, dosen harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat, termasuk menerbitkan publikasi di jurnal ilmiah.
Target publikasi ilmiah turut menjadi indikator capaian untuk menjadi universitas kelas dunia (World Class University). Banyaknya kampus yang berlomba-lomba mengejar status tersebut, kian menambah tekanan sehingga para dosen mudah tergelincir dalam praktik pelanggaran akademis.
2. Masih belajar
Arief mengemukakan bahwa maraknya pelanggaran akademis turut berhulu dari mental akademisi Indonesia yang belum siap dengan budaya penerbitan jurnal. Padahal, sistem pendidikan tinggi yang diciptakan pemerintah menuntut adanya publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional.
“Budaya menulis dan menerbitkan di jurnal ini baru banget, masih merangkak istilahnya, kita baru tahun 2000-an sadarnya. Dulu penelitian ya cuma terhenti di rak-rak,” ungkap dia.
Selain itu, menurut Arief, maraknya pelanggaran akademis di Indonesia, khususnya penerbitan di jurnal abal-abal juga disebabkan oleh sistem yang kurang baik. Target program hibah penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), misalnya, mengharuskan publikasi riset di tahun yang sama, sehingga banyak dosen menyiasatinya.
Ilham mengamini pendapat Arief.
“Pengajuan penelitian dibuka Januari…hasilnya butuh 3-4 bulan untuk pengumuman dapat (hibah) atau enggak, anggaran turun bulan keenam, itupun tidak 100 persen…untuk memenuhi 100 persen harus berupaya biar segera terbit, jadi akhirnya diakali atau ditalangi dulu,” jelasnya.
“Kalau prosesnya benar, dalam setahun bisa terbit dua atau satu artikel di jurnal ilmiah saja sudah bagus banget,” tegas Ilham, yang juga dosen di Universitas Airlangga, Jawa Timur.
Jika melampaui angka tersebut, dunia akademik akan kehilangan hal terpenting tentang sains, yaitu ketelitian ilmiah, karena risetnya dilakukan secara terburu-buru.
Sayangnya, hingga artikel ini terbit, pihak Dikti tidak memberikan komentar terkait hal ini meski sudah dihubungi berulang kali. Pesan WhatsApp kami kepada Nizam pada 13 Maret 2024 (saat itu masih menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) yang berisi daftar pertanyaan wawancara tidak berbalas.
Kami juga mengajukan permintaan wawancara melalui surat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang baru, Abdul Haris. Namun, hingga berita ini ditulis, keduanya tidak menanggapi.
3. Absennya ekosistem pendukung
Idhamsyah Eka Putra, dosen Universitas Persada Indonesia dan Anggota Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menuturkan, ekosistem akademis di Indonesia (semisal dukungan dari komunitas ilmiah) kurang mendukung iklim penelitian dan penulisan. Sebagian besar universitas di Indonesia lebih berorientasi pada kegiatan pengajaran.
Motif menerbitkan jurnal, kata dia, lebih dimotivasi oleh hal-hal praktis seperti kenaikan pangkat, atau insentif yang besarnya bisa mencapai Rp40 juta.
“Dalam hal ini, fakultas juga diuntungkan dengan adanya banyak publikasi karena meningkatkan reputasi,” tambah Ilham.
Baca juga: Beramal Itu Banyak Caranya, Termasuk Jadi Dosen Honorer
Bertumpu pada Dosen-dosen Jujur
Saat ditanya terkait usaha untuk menghentikan praktik pelanggaran akademis, Sigit Riyanto, guru besar bidang hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang juga bagian tim pengkaji untuk International Association of Law Schools (IALS) perwakilan kawasan Asia-Pasifik, menekankan pentingnya komitmen dari universitas dan kementerian.
“Universitas, fakultas, Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi), dan inspektorat jenderal (yang menyelidiki kasus-kasus pelanggaran akademis) harus lebih tegas, lebih punya komitmen. Inspektorat jendral juga sangat mungkin membawa (kasus-kasus pelanggaran akademis) ke ranah hukum. Tapi seringnya, timnya ‘masuk angin’ (tidak konsisten memproses),” tuturnya.
Jadi kita tinggal berharap pada dosen-dosen jujur seperti Rina, meskipun, Sigit menganggap di tengah ekosistem begini jumlahnya tidak banyak.
“Coba bayangin, orang kalau jadi profesor di Indonesia itu kan “iya prof, iya prof” (menghormati) … batinku lha kamu jadi profesornya aja, well, we all know menjadi profesornya dengan beragam ketidakjujuran, jadi sebel aku lihatnya, tapi kejadian di manapun,“ pungkas Rina.
Hayu Rahmitasari, Education & Culture Editor, The Conversation dan Ika Krismantari, Chief Editor/Content Director, The Conversation.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.