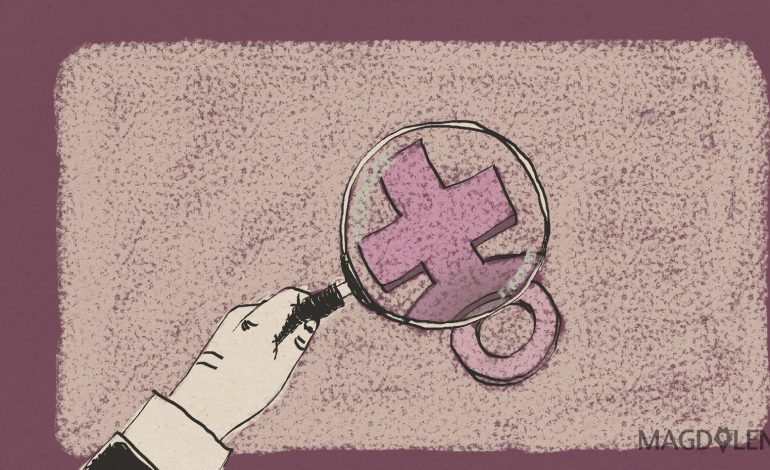Peran Vital Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan dalam Aktivisme Lingkungan

Saat ini, kita mengenal Greta Thunberg, remaja Swedia yang menggerakkan jutaan orang untuk protes terkait perubahan iklim, hingga Jane Fonda, artis senior asal Amerika Serikat yang bolak-balik masuk penjara karena aksinya memperjuangkan keadilan iklim. Sementara di Indonesia, ada Aleta Baun, perempuan asal Nusa Tenggara Timur, yang memprotes pembukaan lahan di daerahnya untuk tambang dengan menenun di depan pintu lokasi tambang. Tokoh-tokoh tersebut mematahkan anggapan umum bahwa perempuan tidak mampu memainkan peran penting dalam gerakan-gerakan sosial bagi pelestarian lingkungan.
Riset kami soal politik lingkungan dan sumber daya alam juga menemukan bahwa perempuan dengan latar belakang ibu rumah tangga dan petani justru memiliki peran vital dalam pergerakan lingkungan di Indonesia.
Mereka berada di garis depan perlawanan, terutama dalam melawan penyerobotan lahan dan perusakan alam. Mereka pun menjadi penyeimbang dalam relasi politik antara masyarakat dengan negara dan korporasi.
Hal ini merupakan harapan baru bagi agenda advokasi perlindungan lingkungan, terutama di tengah melemahnya gerakan masyarakat sipil di Indonesia belakangan ini.
Bersama dengan tim dari Universitas Diponegoro, Semarang, dengan dana riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya melakukan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dan observasi terkait kebijakan sumber daya alam di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Kami menggali pengalaman, pemahaman, dan argumentasi dari masyarakat akar rumput yang menolak kebijakan tambang dan eksploitasi sumber daya alam. Sejak 2018 hingga 2020, kami melakukan penelitian di Rembang dan Pati di Jawa Tengah, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung, dan Balikpapan di Kalimantan Timur.
Baca juga: Ekofeminisme: Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Mematahkan stereotip
Tahun 2015, Sukinah, salah satu perempuan pejuang Kendeng, di Rembang, Jawa Tengah, mendatangi beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, lalu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Jawa Tengah. Sukinah dan teman-teman aktivis kala itu gencar melakukan serangkaian demonstrasi menolak aktivitas pabrik semen di desa mereka. Ia menantang para akademisi yang menunjukkan keberpihakan terhadap perusakan lingkungan.
Itu kali pertama para peneliti, termasuk saya, bertemu Sukinah dan melihat begitu kerasnya protes yang disampaikan bersama teman-teman aktivis lainnya.
Ketika kami mendatanginya tiga tahun kemudian, ia mengulangi pesan yang sama.
“Kita ingin menyampaikan bahwa orang-orang pinter di kampus itu mbok yang bener. Jangan karena kepinterannya itu, dibuat untuk merusak alam dengan memberi dukungan pada perusahaan-perusahaan macam semen gini-gini,” ujarnya.
Ia geram dengan adanya akademisi kampus yang justru mendukung pendirian PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.
Tidak hanya aktif melakukan demo di kampus-kampus, Sukinah juga turut dalam aksi menyemen kaki di depan istana.
Di Kalimantan Tengah, Mariana, perempuan suku Dayak di Desa Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, menolak pembukaan hutan adat mereka untuk lahan perkebunan sawit pada 2012. Dalam wawancara untuk riset kami, Mariana tegas mengatakan bahwa perjuangan mereka dilandasi oleh nasib anak dan cucu mereka di masa depan, bukan semata-mata menumpuk kekayaan bagi diri mereka sendiri.
Dari kedua perempuan tersebut, kita bisa mengambil pesan moral bahwa memperjuangkan suatu gerakan atau nilai-nilai luhur tidak terjebak dalam gelar akademis, status pekerjaan, atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Baca juga: Perempuan Bali Mimpi Terlibat Aktif dalam Gerakan Lingkungan Hidup
Pergerakan Sukinah dan Mariana tidak abstrak atau sebatas teori, tapi tumbuh langsung dari masyarakat (grassroot movement) dan didasarkan dari kehidupan keseharian mereka. Mereka membuat gerakan sosial menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan agenda dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Kehadiran mereka berdua, beserta perempuan-perempuan daerah lainnya, mematahkan stereotip sosial bahwa perempuan, terutama yang tinggal di pedesaan, adalah makhluk lemah, penurut, gampang ditundukkan, dan bodoh.
Penulis buku Women Activists: Challenging the Abuse of Power, Anne Witte Garland mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif perempuan, seperti Sukinah dan Mariana, dalam perlawanan tambang dan ahli fungsi lahan mengempaskan narasi bahwa perempuan tidak berdaya. Kedua sosok tersebut, sebaliknya, menjadi contoh konkret bagaimana perempuan desa, berprofesi sebagai petani, dan tidak mengenyam pendidikan, mampu mengekspresikan kritik dan melakukan perlawanan terhadap strategi pembangunan yang eksploitatif.
Aktivisme lingkungan yang efektif
Setidaknya, ada dua hal yang dapat membuat gerakan aktivis lingkungan perempuan efektif. Pertama, jejaring yang mereka miliki. Kedua, kreativitas dalam mengekspresikan kritik dan perlawanan mereka terhadap pembangunan.
Jejaring sosial kaum perempuan adalah potensi yang besar bagi suatu gerakan. Aktivis lingkungan hidup di Indonesia, terutama perempuan, tidak wajib memiliki karier di ranah publik untuk aktif di organisasi. Mereka justru tumbuh dari organisasi-organisasi seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), hingga kelompok pengajian atau kegiatan religius yang lain.
Dalam organisasi-organisasi ini, perempuan yang mayoritas ibu rumah tangga mengadakan kegiatan dasar terkait perlindungan lingkungan, mulai dari daur ulang plastik, pembuatan kompos organik, tata kelola sampah, hingga cara menanam.
Baca juga: Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan
Organisasi semacam ini menjadi awal berkembangnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap perusakan lingkungan yang radikal. Contohnya, Sukinah beserta rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok pengajian di Rembang melawan pendirian pabrik semen. Ini membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan religius seperti pengajian yang diikuti ibu-ibu secara teratur selama bertahun-tahun dapat menjadi wadah konsolidasi gerakan yang strategis dan penting.
Aktivisme perempuan sering kali memiliki cara-cara perlawanan sekaligus pemberdayaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Aleta Baun, aktivis lingkungan asal Mollo, Nusa Tenggara Timur dan pemenang Goldman Environmental Prize (penghargaan prestigius bagi para aktivis lingkungan) tahun 2013, melakukan protes menenun di tengah area pertambangan marmer pada 1995. Ia bersama ibu-ibu lainnya melakukan aksi menenun selama setahun sebelum perusahaan marmer menyerah dan meninggalkan daerah tersebut.
Sementara, Sukinah dan ibu-ibu Kendeng melakukan protes dengan menyemen kaki mereka di depan istana kepresidenan di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan kepada publik tentang isi perlawanan mereka.
Para perempuan ini mengusung isu-isu yang konkret dan sehari-hari. Mereka berbicara tentang hilangnya sumber daya air mereka untuk kehidupan sehari-hari akibat tambang, rusaknya lahan mereka untuk bercocok tanam dan hutan yang menjadi sumber penghidupan.
Perjuangan mereka selalu berasal dari kebutuhan untuk masa depan keluarga mereka ketimbang kepentingan diri sendiri. Hal ini sangat penting dalam advokasi kebijakan dan kritik pembangunan.
Lebih lanjut, keterhubungan antarperempuan juga penting untuk membangun solidaritas lintas daerah, etnis, dan kepercayaan guna menjadi amunisi bagi gerakan kolektif yang lebih besar.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.