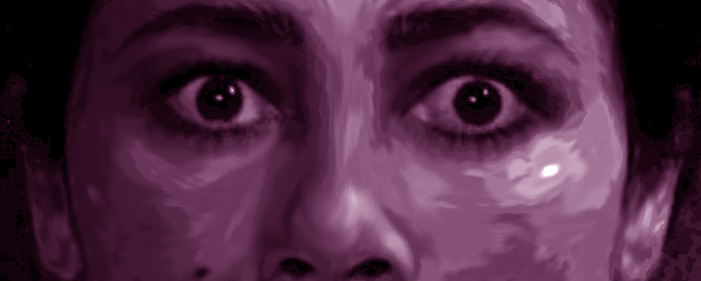Perempuan, Kreativitas, dan Ruang Pribadi

“Saya harus merawat anak kecil saya sambil mencari waktu luang menulis,” ujar seorang teman via telepon saat itu.
“Suamiku sedikit patriarkal, sih. Untung saja dia tidak bodoh, karena kalau bodoh, bayangkan!” timpalnya kembali.
Obrolan dengan teman ini sontak membawa ingatan saya pada sebuah diktum masyhur Virigina Woolf dalam A Room of One’s Own, “a woman must have money and a room of her own if she to write fiction”.
Dulu, saya kurang begitu paham maksud diktum ruang dan uang tersebut. Apa kaitan keduanya dalam kehidupan konkret seorang perempuan? Saya mungkin mudah membayangkan fungsi uang dan bagaimana ia begitu jemawa dalam harkat hidup kita ini, tapi tidak dengan ruang. Bagi saya, kala itu, ruang hanyalah hal sepele yang mungkin saja tak perlu dirisaukan. Pendeknya, dengan sadar saya ragu diktum tersebut.
Saya berpendapat ruang bisa saja diakali dan itu tergantung bagaimana cara seorang membuat manajemen hidup yang ketat, dengan mengelolah waktu dan membikin agenda yang efektif misalnya. Kemudian, sebagaimana ucapan ala para motivator itu, cukup memilah yang primer dan sekunder, serta mungkin ditambah mengatur hal-hal kecil, sampai tak ada lagi celah dan ruang pun tercipta. Mudah, bukan?
Kenyataannya, tak sesederhana itu. Saya mulai memikirkan hal ini pada saat saya benar-benar kehilangan ruang. Tentu saja tetap dengan catatan, dalam kebudayaan kita ini, menjadi laki-laki seperti saya sudah sangat banyak mendapat hak istimewa ketimbang perempuan pada umumnya. Artinya, apa yang saya alami mungkin tak seberapa.
Baru-baru ini, saya pindah tempat tinggal setelah garansi sebagai mahasiswa habis. Di Yogyakarta, saya punya kamar pribadi. Memang jauh dari kata menarik, bahkan cenderung kumuh. Tapi, tetap saja kamar itu adalah ruang saya.
Di kamar itu saya membuatnya jadi sebuah dunia bagi saya. Saya menata koleksi buku pribadi, misalnya dengan meletakkan jenis buku yang akan atau tengah saya baca di atas papan kecil; sementara buku teori yang tebal-tebal itu saya taruh di sebuah kardus. Sisanya, buku yang nyaris tak pernah saya sentuh lagi sudah saya rapatkan di kardus lain. Di tembok juga menempel papan dari styrofoam tempat saya mencanangkan ide atau agenda atau keinginan untuk melakukan satu atau lain hal.
Baca juga: Okky Madasari dan Buku yang Membentuk Pola Pikir Kritis Anak
Dunia kecil yang kumuh itu adalah tempat saya menumpahkan ekspresi, tempat proses kreatif saya menulis juga berlangsung di situ.
Ditambah lagi saat di Yogya, saya punya lingkaran pertemanan, mobilitas, juga akses. Semua itu tentu memperluas ruang saya. Pada lingkaran pertemanan, saya sering memperbincangkan atau berbagi satu atau dua ide sebelum benar-benar menggarapnya. Begitu pula dengan mobilitas dan akses yang begitu membuat saya terdorong menulis dan menemukan data yang saya butuhkan.
Singkat cerita, saya pulang ke rumah dan saya kehilangan itu semua. Saya kehilangan ruang saya; dunia kumuh kecil yang menyokong proses kreatif saya, serta lingkaran-lingkaran yang juga ikut lenyap begitu saja.
Kesadaran itu terpantik pada saat tengah menulis. Di rumah, saya tidak memiliki kamar khusus, hal itu menyulitkan karena saya tidak punya lagi dunia kecil saya itu. Saat mencari buku untuk menulis umpamanya, saya tidak lagi mendapati keluwesan meletakkan buku-buku dan mengambilnya saat butuh.
Hal yang sama terjadi saat saya tidak lagi mendapat papan untuk oret-oretan ide atau rencana atau apa saja yang menurut saya perlu. Dan yang lebih parah lagi, saya tidak mendapat teman diskusi serius untuk satu atau lain hal. Belum lagi suasana yang gaduh dan tak kondusif di rumah. Pendeknya, ruang ekspresi saya tidak baik-baik saja.
Pengalaman itu membuat saya merasa saya dan teman saya kehilangan ruang pribadi. Saya kembali membayangkan bagaimana ruang bagi teman saya saat ini? Saya–sebetulnya, jika boleh dikatakan– hanya kehilangan sebagaian dari ruang fisik saja, tapi tidak bagi teman saya. Dia tidak semata-mata kehilangan ruang fisik, tetapi juga ruang lain seperti pikiran tempatnya berdialog dengan dirinya. Dia memiliki relasi lebih kompleks, sebuah keluarga kecil, lengkap dengan beban domestik yang mesti ditanggungnya karena budaya kita.
Baca juga: Menjadi Perempuan Penulis Muda di Jakarta
Penyair Sofyan RH. Zaid pernah menulis “Fenomena Penyair Perempuan Indonesia” yang menyoroti kepenyairan perempuan yang meredup karena, salah satunya, beban domestik. Dalam kehidupan berumah tangga, perempuan memang tidak lagi memiliki dirinya secara utuh. Tulisan tersebut secara khusus menekankan pentingnya ruang pribadi untuk mencapai–apa yang dipinjamnya dari Lorens Bagus sebagai “perasaan estetis”, yaitu berupa tanggapan atas keadaan emosional akibat gejala kemanusiaan.
Tapi, ruang pribadi menjadi begitu pelik dan menjadi sebuah kemewahan tersendiri bagi seorang perempuan. Tanpa hal tersebut, dia tidak lagi memiliki tempat berpikir secara mandiri, membaca, menulis, mengoreksi apa yang ditulisnya dan juga berdiskusi.
Saya menyadari betul bahwa kehilangan ruang fisik membuat saya gagap melakukan proses kreatif. Di situ, saya mudah membayangkan perempuan dengan beban domestik akan membuatnya tidak hanya kehilangan ruang dalam artian fisik. Lebih jauh lagi, juga ruang dalam artian retoris.
Saya membayangkan teman saya membagi waktu untuk mengurusi anak, memasak, membersihkan rumah, dan sekaligus membagi pikiran untuk mengelola ini dan itu. Saya membayangkan di sela-sela itu, dia akan mencuri-curi waktu untuk mengambil laptopnya, kemudian menulis, dan saat mulai mengerjakan tulisannya, tiba-tiba anaknya menangis.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga adalah sebuah kesalahan, lebih-lebih jika tanpa ada dialog yang emansipatif di dalamnya. Pada kenyataannya, ruang pribadi tempat seorang perempuan berpikir untuk dirinya memang nyaris tak pernah ada. Dan bila begitu, bagaimana dia menemukan “perasaan estetis” dan kemudian menuliskannya?
“Saya harus merawat anak kecil saya sambil mencari waktu luang menulis,” ucapan teman saya kembali terngiang. Dia mungkin satu dari sedikit perempuan yang, katakanlah, masih bersikeras melakukan proses kreatif dalam ruang pribadi yang minim.
Tapi, mari sama-sama membayangkan, berapa banyak perempuan yang meninggalkan proses kreatifnya karena beban domestik tersebut. Saya kira penulis Perancis Stendhal memang benar, “all geniuses who were born women were lost to the public good”.