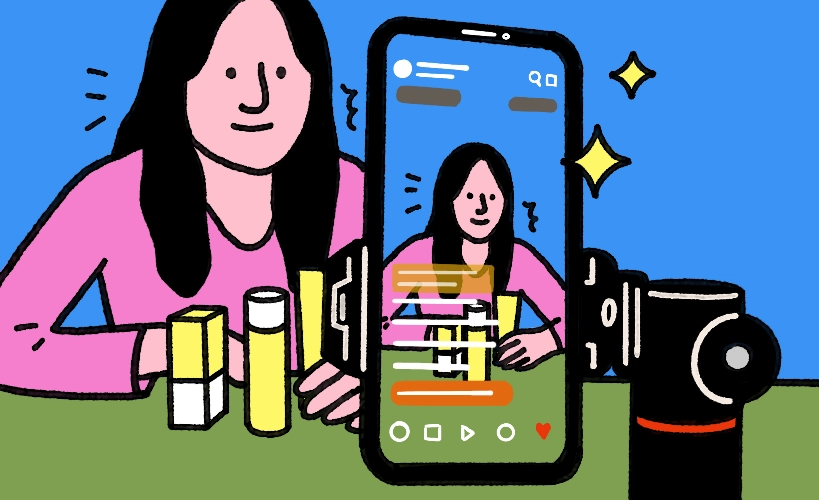Terjepit Panas dan Lapar di Lumbung Pangan: Beban Perempuan Petani Indramayu

Indramayu telah memasuki musim penghujan sejak akhir 2025. Namun itu tak otomatis menghapus dampak panas ekstrem yang lebih dulu menghantam wilayah ini bertahun-tahun sebelumnya. Bagi petani di kawasan pesisir utara Indramayu, terutama yang minim tutupan vegetasi, seperti Patrol, Sukra, Losarang, Kandanghaur, hingga Krangkeng, panas berkepanjangan tetap meninggalkan sejumlah kerusakan.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan wilayah Indramayu, mengalami peningkatan suhu maksimum harian dan malam hari dalam satu dekade terakhir. Lonjakan tertinggi dirasakan pada periode El Niño 2015–2016 dan kembali menguat pada 2023–2024. Saat puncak kemarau 2024-2025, suhu di sejumlah titik Indramayu berkisar 35 hingga mendekati 40 derajat Celsius. Kondisi ini memperpanjang tekanan ekologis di wilayah pesisir yang secara historis bergantung pada pertanian sawah dan ketersediaan air.
Tak hanya itu, sawah pun menjelma ruang kerja yang berisiko, terutama bagi perempuan. Darsini, 54, buruh tani di Desa Mekarsari, Kecamatan Sukra, masih mengingat bagaimana ia bertaruh nyawa di bawah matahari yang ia gambarkan seperti “geni” atau api.

Saat masih hamil sembilan bulan, Darsini tetap memaksakan diri membungkuk untuk menanam padi di sawah. Panas dan kelelahan fisik membuatnya mengalami pendarahan tak lama berselang. Sang bayi selamat, tetapi pengalaman itu meninggalkan trauma di ingatannya hingga sekarang.
Satiah, 54, petani perempuan Mekarsari lainnya, juga menghadapi situasi serupa. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian sekitar Rp100 ribu. Saat panas ekstrem datang, pekerjaan tanam dan penyiangan terasa jauh lebih berat. Meski tubuh sering sakit dan kepala pusing, ia tetap bertahan di sawah.
“Kalau enggak kerja ya enggak makan,” ungkapnya pada saya, 26 Desember 2025 saat ditemui di sekretariat Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (JATAYU), Mekarsari, Sukra, Indramayu.
Celakanya, beban perempuan tidak berhenti di sawah. Setelah bekerja dari pagi hingga sore, pekerjaan domestik menunggu mereka, dari memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anggota keluarga. Panas ekstrem telah meningkatkan risiko kelelahan dan gangguan kesehatan. Namun di saat bersamaan, juga tak memberi ruang bagi perempuan untuk berhenti bekerja.
Kisah Darsini dan Satiah bukan pengecualian. Mereka adalah bagian dari realitas luas di Kabupaten Indramayu—wilayah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 Indramayu memproduksi sekitar 1,39 juta ton gabah kering panen dari lebih dari 125 ribu hektare lahan sawah. Angka ini kerap dikutip sebagai indikator keberhasilan kebijakan pangan.
Ironisnya, di balik produksi tinggi, panas ekstrem justru memperbesar risiko gagal panen, meningkatkan kebutuhan air dan biaya produksi, serta menggerus pendapatan rumah tangga petani. Di titik inilah kerja perempuan menjadi semakin berat. Sementara, perlindungan terhadap tubuh, kesehatan, dan penghidupan mereka justru kian rapuh.

Baca juga: Walhi: Risiko Banjir dan Longsor Jabar Bisa Lebih Parah dari Sumatera
Produksi Padi Tinggi, Kenapa Ekonomi Petani Stagnan?
Persoalan stagnasi ekonomi petani di Indramayu terbentuk dari sejumlah faktor yang saling berkelindan dan bekerja bersamaan di tingkat tapak. Data ekonomi, kebijakan tata ruang, keberadaan proyek strategis nasional, serta perubahan kondisi produksi memunculkan tekanan berlapis yang dirasakan berbeda di setiap kecamatan, namun menghasilkan pola dampak yang serupa di tingkat rumah tangga petani.
Pertama, indikator kesejahteraan petani menunjukkan pergerakan yang sangat terbatas. Policy Brief Edisi Pertanian yang diterbitkan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Kampus Putih pada 2025 mencatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) Indramayu pada Desember 2024 hanya naik 0,02 persen. Indikator ini mengukur perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani dalam periode yang sama.
Akmal, Ketua DEMA Kampus Putih sekaligus penyusun policy brief tersebut, mengatakan kenaikan tipis ini berkaitan langsung dengan struktur biaya produksi.
“Kenaikan harga gabah ketutup biaya pupuk, pestisida, sewa alat, sama tenaga kerja. Petani tetap kerja, tapi selisihnya kecil,” kata Akmal kepada saya, 24 Desember 2025.
Menurutnya, kondisi ini membuat petani tidak memiliki ruang aman ketika terjadi gangguan produksi. Satu kali tanam ulang atau penurunan hasil panen langsung berdampak pada kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan harian. “Sekali musim bermasalah, ekonomi keluarga langsung goyah,” imbuhnya.
Kedua, penyempitan akses lahan terjadi seiring perubahan tata ruang dan masuknya proyek strategis nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 menetapkan sekitar 20.835 hektare lahan untuk kawasan industri sebagai bagian dari pengembangan kawasan Rebana. Kawasan ini terhubung dengan jaringan industri dan infrastruktur regional yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Masih dari sumber yang sama, policy brief ini merinci alokasi kawasan industri yang tersebar di Kecamatan Patrol seluas 4.144 hektare, Kecamatan Losarang 6.710 hektare, dan Kecamatan Tukdana 563 hektare. Wilayah-wilayah ini merupakan kawasan pertanian aktif dan lokasi kerja buruh tani.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Indramayu, Try Utomo, menjelaskan perubahan fungsi ruang tersebut mengubah struktur penguasaan tanah petani. “Petani yang jual tanah itu uangnya enggak cukup buat beli lahan lagi. Akhirnya kerja sebagai buruh atau nyewa ke perusahaan,” kata Try kepada saya, 24 Desember 2025.
Try menyebut pola pembebasan lahan kerap dimulai dari petak sawah yang memiliki akses jalan dan irigasi. Setelah kawasan industri berdiri, akses ke petak di bagian belakang tertutup. “Tanah yang di belakang pabrik nilainya turun. Lama-lama ditawar murah,” tuturnya.
Data pertanahan daerah mencatat pada 2023 terdapat sekitar 111.000 petani gurem di Indramayu, atau petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare. Kelompok ini sebagian besar menggantungkan hidup dari kerja sebagai buruh tani atau penggarap sewaan, tanpa kepastian pendapatan.
Selain kawasan industri Rebana, tekanan ruang hidup petani juga muncul dari proyek energi yang masuk kategori PSN. Di Kecamatan Sukra, Desa Mekarsari, tempat Darsini dan Satiah tinggal, berdiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu yang mulai beroperasi pada 2011. Kawasan ini menjadi salah satu titik konsentrasi konflik agraria dan lingkungan yang memengaruhi aktivitas pertanian warga.
Sementara itu, Tarmudi, Koordinator Lapangan JATAYU menjelaskan perubahan kondisi produksi mulai terasa setelah proyek energi tersebut beroperasi.
“Dulu musim tanam kedua justru paling bagus. Sekarang justru paling berisiko,” kata Tarmudi kepada saya, 26 Desember 2025.
Ketiga, keberadaan proyek industri dan energi berkelindan dengan krisis iklim dan memperbesar ongkos produksi di lapangan. Petani muda dari Kecamatan Losarang, Bengbeng bilang, petani di sekitarnya bergantung pada Sungai Kalijangga sebagai sumber irigasi utama. Sungai yang sama juga menjadi sumber air bagi industri kimia dan tekstil yang berkembang sejak 1990-an dan terhubung dengan kawasan industri regional.
“Kalau kemarau, petani harus pompa air sendiri. Biayanya sekitar Rp500 ribu seminggu buat satu jalur,” kata Bengbeng kepada saya, 26 Desember 2025.
Biaya tersebut ditanggung kelompok tani di luar ongkos pupuk, benih, dan tenaga kerja. Bengbeng mengatakan keterbatasan modal membuat sebagian petani tidak mampu melanjutkan musim tanam berikutnya.

“Kalau modal habis di awal, musim berikutnya enggak jalan. Lahannya akhirnya diserahin,” ujarnya.
Di Sukra, perhitungan ongkos produksi dan risiko kerugian dijelaskan oleh Tarmudi. Modal awal produksi satu hektare sawah dalam kondisi normal mencapai sekitar Rp20 juta per musim tanam. Ketika tanaman mati pada fase awal akibat panas ekstrem dan kondisi lingkungan, petani harus melakukan tanam ulang.
“Tanaman mati di umur satu bulan. Tanam ulang, obat nambah, waktu tanam molor,” ungkap Tarmudi.
Perpanjangan masa tanam dari empat menjadi enam bulan menambah biaya konsumsi rumah tangga sekitar Rp6 juta. Biaya pemulihan lahan dan penanaman ulang mencapai sekitar Rp8 juta.
“Totalnya bisa Rp34 sampai Rp40 juta satu hektare satu musim,” ujarnya.
Dalam kondisi gagal panen sebagian, hasil panen yang diperoleh hanya dua hingga tiga kuintal gabah. Pendapatan bersih yang diterima petani berkisar Rp2–3 juta per hektare.
“Kerugiannya bisa Rp30 juta lebih,” ucap Tarmudi.
Meski bentuk tekanannya berbeda, baik masalah harga, alih fungsi lahan akibat PSN, kompetisi air di Losarang, serta risiko gagal tanam, mayoritas petani yang saya wawancara menggambarkan pola yang sama di tingkat rumah tangga. Pendapatan bersih menyempit, ongkos produksi meningkat, dan utang menjadi mekanisme bertahan yang terus berulang dari satu musim ke musim berikutnya.

Baca juga: Ketika Banjir Melanda: Krisis Iklim dan Beban Ganda bagi Perempuan
Ketika Utang Jadi Pilihan Bertahan
Stagnasi ekonomi di sawah mendorong rumah tangga petani Indramayu mencari sumber penghidupan di luar pertanian. Ketika hasil panen tidak lagi cukup menutup biaya produksi dan kebutuhan harian, perempuan jadi kelompok yang paling cepat terdorong keluar dari desa. Entah mereka bekerja sebagai buruh migran, pekerja informal, atau pun lewat skema utang yang berputar dari satu sumber ke sumber lain.
Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan Indramayu konsisten menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Jawa Barat. Pada 2023, BP2MI mencatat lebih dari 17.000 pekerja migran asal Indramayu diberangkatkan ke luar negeri. Sekitar 70 persen di antaranya perempuan, dengan tujuan utama Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Arab Saudi. Mayoritas bekerja di sektor domestik dan perawatan.
Hanna Adriani Savitri, peneliti sekaligus aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, mengatakan migrasi perempuan dari keluarga petani tidak bisa dilepaskan dari krisis struktural di pedesaan.
“Perempuan jadi penyangga terakhir ekonomi keluarga. Ketika sawah tidak lagi menghasilkan, perempuan yang didorong keluar untuk menutup kebutuhan rumah tangga,” ujar Hanna kepada saya, 24 Desember 2025.
Menurut Hanna, wilayah dengan tekanan konflik agraria, proyek energi, dan kawasan industri—seperti Sukra, Losarang, Patrol, dan Tukdana—menunjukkan pola migrasi perempuan yang lebih tinggi.
“Ini bukan pilihan individual, tapi respons terhadap tekanan berlapis,” ujarnya.
Sementara itu di Kecamatan Losarang, Bengbeng melihat tren berutang ini juga berlangsung di lingkar terdekatnya.

“Di desa saya, yang berangkat ke luar negeri kebanyakan perempuan. Ibu-ibu, anak perempuan,” kata Bengbeng kepada saya, 26 Desember 2025.
Ia menyebut keputusan itu kerap diambil setelah beberapa musim tanam gagal atau hasil panen tidak cukup menutup utang.
Bengbeng mengingat satu peristiwa yang menggambarkan rapuhnya ekonomi petani kecil. Suatu hari, ketika tidak ada uang tunai di rumah dan kebutuhan anak mendesak, ia menjual kaus satu-satunya yang sedang ia pakai.
“Saya jual kaus di badan ke teman Rp20 ribu. Buat beli susu sama pampers eceran,” katanya. “Saya pulang tanpa baju.”
Bagi keluarga yang tidak memilih migrasi, utang menjadi mekanisme bertahan yang paling umum. Di Indramayu, utang petani berasal dari berbagai sumber, dari perbankan formal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi simpan pinjam, hingga lembaga keuangan informal seperti bank keliling, bank emok, dan skema pinjaman berbasis kelompok perempuan.
BPS pernah mencatat utang sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan di Indramayu pada 2024 yang mencapai sekitar Rp1,49 triliun. Namun Hanna menegaskan angka tersebut hanya mencerminkan utang formal yang tercatat.
“Yang tidak kelihatan justru utang informal. Bank emok, bank keliling, pinjaman harian. Itu tidak masuk statistik, tapi paling banyak dipakai perempuan,” tutur Hanna.
Di tingkat tapak, pola utang sering kali bersifat berulang. Petani menutup cicilan lama dengan pinjaman baru, atau membayar utang konsumsi menggunakan gabah hasil panen. Ketika panen gagal, utang bergeser ke musim berikutnya.
“Ini praktik gali lubang tutup lubang,” ujar Hanna. “Dan yang mengelola utang rumah tangga biasanya perempuan.”

Dalam kondisi ekstrem, ketika utang dan merantau ke luar negeri tak bisa jadi pegangan, Bengbeng menyebut sebagian perempuan akhirnya bekerja di sektor hiburan malam dan prostitusi di kota-kota besar.
“Ada yang bekerja ke Kopi Lendot, pusat prostitusi di Mangga Besar. Itu cerita dari tetangga-tetangga sendiri,” katanya.
Untuk menelusuri praktik utang informal, saya mencoba menghubungi sejumlah grup Facebook yang berisi koperasi simpan pinjam dan kelompok bank emok komunitas warga Indramayu. Beberapa pesan saya kirim ke pengelola grup dan akun yang aktif menawarkan pinjaman. Namun hingga akhir Desember 2025, tidak ada satu pun respons yang diberikan.
Di Tukdana, Kartini, 50, petani perempuan yang pernah menjadi buruh migran di Arab Saudi dan Brunei bilang, jadi buruh migran bukan solusi jangka panjang. Dari hasil kerja di luar negeri, ia membeli sawah yang kini digarap bersama suaminya. Namun tekanan biaya produksi membuat kondisi kembali rapuh.
“Kalau sekarang, enggak kerja ke luar negeri pun tetap utang. Modal tanam pinjam, panen buat nutup cicilan,” kata Kartini kepada saya.
Ia menyebut perempuan di desanya berada di antara dua pilihan sempit: Pergi bekerja ke luar daerah atau bertahan dengan utang yang terus berputar.

Baca juga: Kerja Sama Agama dan Gender Membantu Adaptasi Iklim Warga Pantura
“Kalau enggak jadi TKW, ya utang terus. Mau berhenti tanam juga enggak bisa,” ucapnya.
Karena alasan-alasan inilah, Bengbeng melihat pertanian sebaiknya memang jangan diperlakukan sebagai sumber penghidupan, melainkan sekadar ikhtiar mempertahankan tradisi.
“Bertani sekarang itu cuma kayak nguri-nguri budaya,” kata Bengbeng kepada saya, 26 Desember 2025.
Ia menyebut kerusakan ekosistem, minimnya infrastruktur irigasi, serta absennya perlindungan negara membuat kerja di sawah tidak menghasilkan kepastian ekonomi. Petani tetap menanam, bukan karena ada keuntungan yang bisa dihitung, melainkan karena sawah merupakan satu-satunya ruang hidup yang tersisa di desa.
Dalam situasi itu, imbuhnya, bertahan jadi petani justru mendorong rumah tangga petani masuk ke lingkar kemiskinan.
“Kalau dihitung, hasilnya enggak nutup. Yang ada malah nambah utang,” ujarnya.
Tanpa dukungan kebijakan yang memperbaiki ekosistem produksi dan akses dasar petani, ia menilai kerja menanam hari ini hanya berujung pada kerugian berulang.
“Menanam sekarang enggak menghasilkan apa-apa selain kemelaratan. Sementara satu-satunya yang dikuasai oleh pemerintah kita cuma ‘mengganggu kemiskinan’ orang miskin seperti kita,” pungkas Bengbeng.
Tulisan ini merupakan bagian dari seri liputan yang mendapatkan fellowship dari Global Climate Resilience for All.