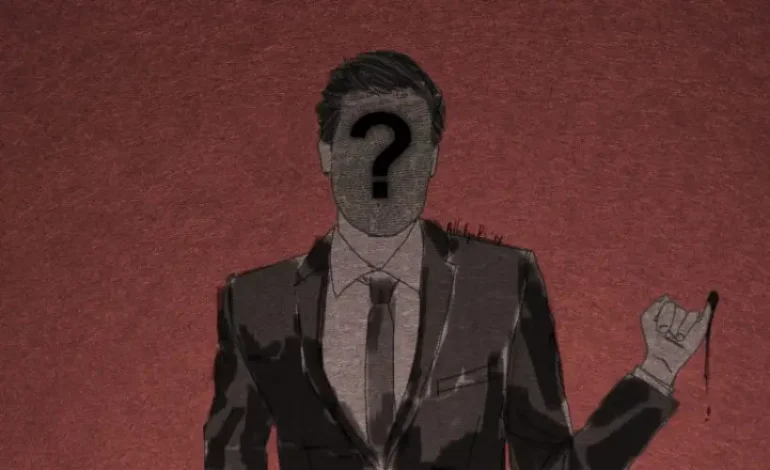Politisi yang Tidak Biasa

Sekitar tengah malam pada Maret lalu, anggota legislatif Eva Kusuma Sundari duduk di tenda darurat di pelosok pedesaan Jawa Timur, menonton pertunjukan ludruk yang dia adakan sebagai bagian dari kampanye untuk kembali terpilih sebagai anggota DPR.
Ketika saya bergabung dengan rombongannya di Blitar beberapa jam sebelumnya, saya mengira dia akan seperti pejabat tinggi lain dengan tampil basa-basi, menghadiri upacara pembukaan, berpidato dan menonton selama 30 menit. Tetapi tiga jam telah berlalu sejak kami tiba, dan tidak ada tanda-tanda kami akan segera meninggalkan tempat. Meski sudah terjaga sejak pukul 5 pagi, dia tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Bersama 200an penonton lainnya, dia tertawa menikmati humor pertunjukan tersebut. Sesekali dia terlihat sibuk dengan telepon genggamnya, mengecek dan membalas pesan singkat, serta mengirium ciutan di twitter, dan sesekali terlibat pembicaraan serius dengan kader-kader setempat.
Tampaknya ini akan menjadi hari yang panjang bagi kami, dan yang terlihat paling khawatir adalah suaminya Jose Amorim Dias, Dutabesar Timor Leste untuk Malaysia, yang datang berkunjung untuk menghabiskan akhir minggu bersama sang istri dalam kegiatan kampanye.
Dalam satu jam terakhir, dia terus mengingatkan Eva untuk pergi, mengingatkan bahwa mereka masih harus menghabiskan waktu dua jam perjalanan naik mobiluntuk tiba di rumah orangtuanya. Mereka berencana menginap di sana sebelum berpisah di pagi hari. Jose juga harus kembali ke Kuala Lumpur dengan pesawat pagi dari Surabaya.Tetapi Eva berkeras untuk tetap tinggal. Dia mensponsori pertunjukan yang bertujuan menghidupkan kembali kelompok ludruk di sana, yang seperti seni tradisional itu sendiri, juga sudah hampir mati. Jadi, paling tidak dia merasa harus memperlihatkan penghargaannya.
Sebagai salah satu politisi perempuan terkemuka di PDI-P, Eva sudah berlaga di pemilihan legislatif sebanyak tiga kali, sejak yang pertama pada 2004.Sayangnya, dia kalah dalam pemilihan umum tahun ini.
Dalam dua hari yang saya bersamanya, dia mengunjungi derah pemilihannya di Kediri, Blitar dan Tulungagung. Di sana dia bertemu dengan berbagai anggota masyarakat dari petani, mantan pekerja migran sampai masyarakat Katolik dan Kristen.
Banyak anggota legislatif inkumben lain yang jarang bertemu dengan warga daerah pemilih secara langsung.
Mereka menyerahkan tugas kampanye ke timpemenangan yang memiliki sumber dana besar. Namun Eva mengunjungi desa-desa terpencil dan berpidato mengenai pendidikan politik dan memberi suara, serta masalah-masalah penting lainnya. Dia memiliki tim relawan di kota-kota itu, tetapi lebih sering dia turun langsung dengan satu kendaraan bersama seorang sopir, asisten dan manajer kampanye daerah. Mereka kerap berhenti dan menginap di mobil atau pun di mesjid.
“Banyak faktor yang menyebabkan saya kalah,” kata Eva baru-baru ini setelah hasil resmi mengkonfirmasi kekalahannya
“Pertama, saya tidak memberi uang kepada pemilih sebelum hari pencoblosan. Dan ketika kertas suara dihitung, saya tidak membayar petugas TPS, saksi dan komite pengawas untuk memastikan saya aman,” ujarnya merujuk pada praktek membeli suara setelah hari pemilihan.
Eva mengakui bahwa dalam tiga pemilihan legislatif yang dia ikuti, semakin sulit bagi politisi profesional seperti dirinya untuk menang dengan jujur. Pada 2004, kompetisi terjadi antar partai-partai politik karena sistemnya memungkinkan pemberian suara bagi partai politik dibagikan ke caleg berdasarkan nomor urut mereka. Perubahan sistem pada 2009 mengubah kompetisi menjadi antar kader partai, mendorong para caleg menyogok pemilih dan meningkatkan iklim politik uang.
“Tahun 2004 saya menghabiskan dana Rp 225 juta dan mendapat 28 ribu suara. Lima tahun kemudian dana yang saya keluarkan berlipat empat kali hingga Rp 1 miliar, dan saya hanya mendapat 38 ribu suara.”
“Itu adalah pengalaman mengejutkan karena para pemilih tiba-tiba berorientasi uang. Mereka tahu semua caleg saling bersaing, bahkan di dalam satu partai sendiri.”
Belajar dari pengalaman ini, setelah terpilih kembali pada 2009 dia terus mempertahankan komunikasi aktif dengan daerah pemilihannya di Malang untuk menggalang pendukung yang loyal. Dia mengunjungi mereka secara rutin setiap dua minggu sekali atau ketika DPR sedang reses. Dalam kunjungan itu Eva memberi pupuk kepada para petani, menghidupkan kembali masyarakat seni setempat dan membantu menengahi perebutan tanah. Namun, setahun sebelum pemilu daerah pemilihannya dipindah ke lokasi sekarang sehingga dia harus memulai dari nol.
Tahun ini partai politik peserta pemilu juga turun dari 24 pada 2009 menjadi 12, yang mengharuskan Eva setidaknya mendapatkan 80 ribu suara untuk bisa memenangkan kursi di DPR. Dan setelah menghabiskan dana Rp 1,5 miliar rupiah untuk biaya kampanye, dia hanya mendapatkan suara setengah dari yang diperlukan.
Tidak terpilihnya Eva merupakan “kerugian” bagi Indonesia. Tidak seperti anggota legislatif perempuan lain, yang kebanyakan terpilih karena koneksi keluarga atau karena mereka selebriti terkenal dan jarang berkiprah selama di DPR, Eva secara aktif mendorong sejumlah inisiatif penting. Diantaranya adalan pendirian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR untuk mengatasi korupsi di DPR, menerapkan sistem nilai dan mengatur masalah-masalah yang sebelumnya masih terhitung “abu-abu” seperti gratifikasi.
Tetapi, prestasi yang paling mengagumkan adalah penolakan keras atas diskriminasi berdasarkan agama terhadap perempuan dan juga agama minoritas, satu konsistensi yang membuat kelompok-kelompok Islamis marah.
Eva juga selalu kritis terhadap para pemimpin pemerintah dan politik karena tidak mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok anarkis yang menggunakan dengan kekerasan terhadap agama minoritas. Dia juga mengkritik pemerintah karena membiarkan pemerintah daerah memberlakukan peraturan berdasarkan syariah Islam seperti menghukum perempuan karena keluar di malam hari atau mengenakan pakaian yang dianggap tidak Islami.
“Kita tidak memiliki sistem federal, jadi Presiden seharusnya bisa mencabut peraturan daerah itu dengan dasar tidak sesuai UUD. Tahun 2004, Kementrian Dalam Negeri mencabut peraturan daerah yang tidak mendukung investasi, mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama dengan peraturan yang tidak mendukung kaum perempuan?” ujarnya. Semua itu tergantung pada keinginan politik, tambahnya.
Politik Pribadi
Sebelum menjadi anggota legislatif Eva adalah seorang dosen di Universitas Airlangga Surabaya dan konsultan bidang gender untuk satu badan pembangunan, namun ia sudah terlibat aktif dalam politik sejak masih duduk di bangku kuliah. Tetapi dia mengakui jika bukan karena kuota 30 persen untuk caleg perempuan yang diterapkan tahun 2004, dia tidak akan terjun ke dunia politik.
“Saya tidak pernah terpikir untuk bergabung dalam satu partai, meskipun waktu muda saya aktif di gerakan pemuda GMNI, yang secara ideologis dekat dengan PDI-P,” katanya.
“Tetapi saya seorang profesional; sekali saya setuju untuk melakukan sesuatu, saya harus melakukannya dengan serius. Jadi saya melakukan apa yang dilakukan oleh seorang politisi serius, seperti rutin mengunjungi daerah pemilihan untuk mendengarkan masalah warga, dan saya harus mengorbankan privasi saya karena harus siap ditelpon 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, bahkan juga untuk wartawan,” jelasnya.
Ketika ditanya berapa dari sekitar 100 anggota DPR yang memiliki etos kerja yang sama dengan dia, Eva hanya mengangkat bahu.
“Mungkin hanya sekitar tujuh persen dari anggota parlemen perempuan yang berkualitas, artinya kerja mereka memiliki dampak. Banyak politisi perempuan terkenal karena politik tingkat tinggi, seperti kedekatan mereka dengan pemimpin partai, bukan karena hasil kerja mereka,” kata Eva.
Kemudian ada juga keterbatasan pribadi yang menghalangi kaum perempuan untuk terjun penuh di bidang pelayanan publik.
“Ketika seorang perempuan berpikir dia harus mengikuti ekspektasi masyarakat, seperti menuruti kata suami atau menjadi isteri dan ibu yang baik, maka politik pribadinya telah mengalahkan aspirasi politiknya,” ujar Eva.
“Dia tidak akan pernah terjun ke politik publik karena konsep menjadi perempuan yang baik menjadi beban, karena anggapan bahwa kaum perempuan harus menangani urusan dapur.”
Banyak kaum perempuan Indonesia yang memiliki jabatan tinggi yang mungkin memiliki pandangan yang sama, tetapi sebagaian besar tidak berani mengemukakan pendapat mereka segamblang Eva.
Ketika ditanya oleh penguna Facebook apakah dia masih punya waktu untuk memasak diantara jadwalnya yang padat, Eva menjawab dengan pedas: “Saya sudah melawan FPI dan anda masih bertanya apa saya ada waktu untuk menggoreng tempe? Jika saya punya pembantu, kenapa saya harus menambah kesibukan dengan memasak di dapur? Suami saya saja tidak pernah mengeluh.”
Dan dia memang memiliki perkawinan yang tidak konvensional. Eva bertemu suaminya ketika sama-sama belajar untuk meraih gelar S2 di Belanda, ketika Timor Leste masih menjadi provinsi Indonesia. Mereka menikah tahun 1993 dan setahun kemudian memiliki anak bernama Maria. Setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia tahun 1999, pasangan ini bercerai karena tidak bisa memutuskan masa depan yang sama bagi keluarga mereka. Jose memilih pulang ke tanah airnya dan bekerja di kementrian luar negeri, sementara Eva tinggal di Indonesia bersama putrinya.
Beberapa tahun kemudian keduanya bertemu kembali ketika Jose ditempatkan di Belgia dan melamar Eva. Keduanya menikah lagi dan Danny lahir pada 2004. Sejak itu merekamelanjutkan hubungan jarak jauhnya. Maria tinggal bersama ibunya di Jakarta dan dibesarkan sebagai Muslim, dan Danny beragama Katolik di Kuala Lumpur bersama ayahnya. Tetapi, agama tidak pernah menjadi masalah di rumah tangga mereka.
“Sebagai orangtua, kami hanya menemani anak-anak kami di jalan mereka, tetapi kami sepakat jika mereka berusia 18 tahun, mereka bebas memilih keyakinan masing-masing,” katanya.
Perkawinan yang tidak lazim ini tidak bisa diterima oleh sejumlah pengkritiknya, yang meragukan patriotisme Eva karena kewarganegaraan suami, tetapi dia tidak mengindahkan pandangan itu.
“Saya tidak mau mengikuti logika mereka. Saya perlihatkan pencapaian saya. Saya minta mereka untuk menunjukkan prestasi mereka. Suami saya memang orang asing, tetapi perlihatkan: apa saya pernah korupsi? Pernahkah saya tidak bolos kerja? Apakah saya pernah tidak konsisten dalam pekerjaan saya? Karena pada akhirnya, itulah yang penting.”
Lalu apa kegiatannya setelah tidak menjadi anggota DPR?
“Saya belum ada waktu untuk memikirkan itu, tetapi sekarang saya sudah kembali bekerja di DPR dan saya ingin menyelesaikan masa jabatan saya dengan baik.”
Namun melihat keterlibatannya dalam kampanye capres PDI-P Joko Widodo, saya rasa kita masih akan mendengar kiprah Eva di masa depan.
Ikuti @dasmaran di Twitter
Diterjemahkan oleh Yoko Sari dari artikel “An Uncoventional Politician.”