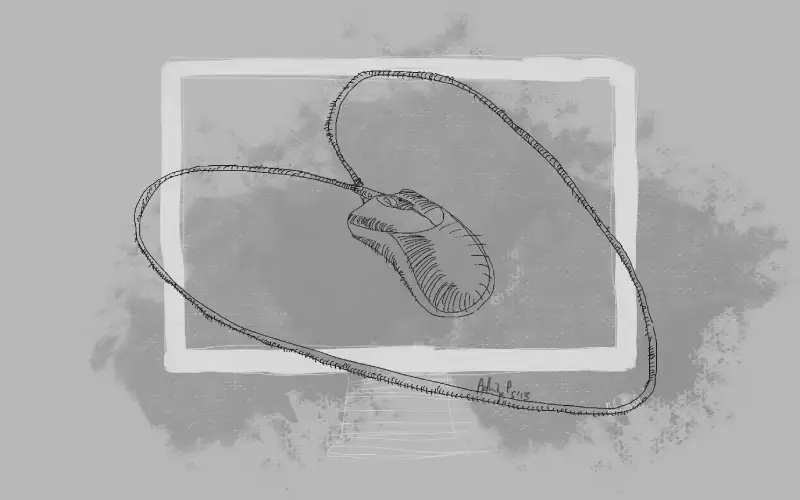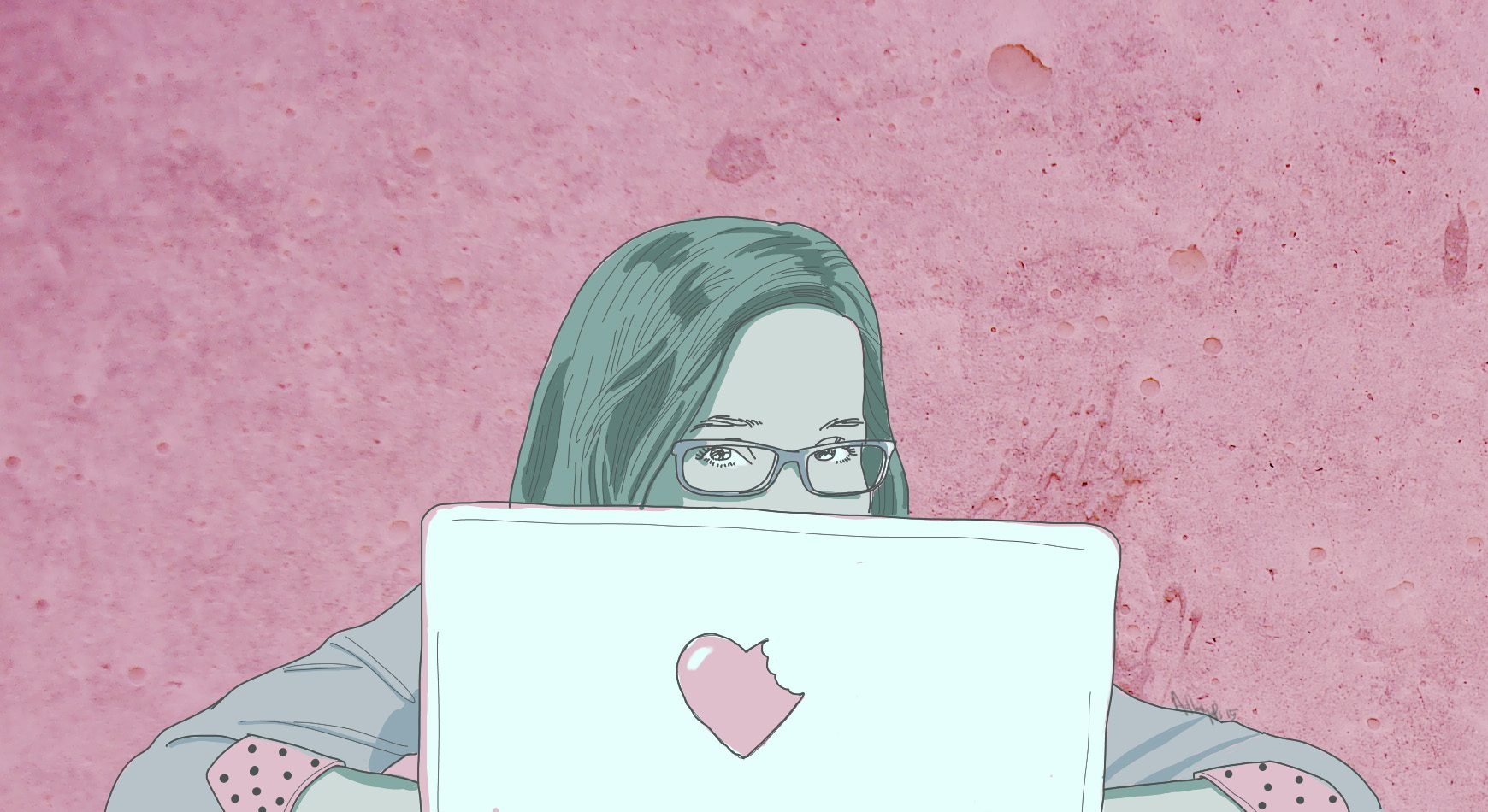Ketika Pria Gay Menikahi Perempuan: Egoisme yang Patut Dihindari

Di atas ranjang, saya merengkuh tubuh Sam yang sudah bercelana pendek meskipun belum menanggalkan kemeja kantornya. Pintu kamarnya telah saya kunci rapat-rapat sesuai permintaannya saat kami mulai berintim ria. Takut orang rumah tiba-tiba masuk, begitu alasannya. Saya menghargai dan mengikuti kehendaknya.
Malam itu adalah ketiga kalinya saya menginap di rumah keluarga Sam. Sesungguhnya saya tidak pernah membayangkan hubungan saya dan Sam akan berjalan sejauh ini, apalagi sampai di satu titik di mana saya betulan jatuh hati kepadanya.
Kedekatan saya dengan Sam memang dimulai tak lama setelah mantan pasangan saya memutuskan hubungan kami secara sepihak. Sam sendiri belum lama mengakhiri hubungan serius pertamanya dengan laki-laki. Bahwa saya dan Sam sedang menjadi rekan kerja pada saat itu tentu sangat membantu proses pendekatan kami.
Di sisi lain, hubungan saya dan sang mantan yang cukup serius–ditambah dengan kesadaran yang semakin tinggi akan pertambahan usia dan pengurangan masa hidup–mendorong saya untuk berpikir bahwa saya tidak lagi ingin menjalin hubungan dengan kredo ‘yang penting jalani saja dulu’ atau dengan pendekatan kasual, hanya ingin bersenang-senang.
Saya meminta Sam untuk bertemu malam itu setelah di akhir pekan sebelumnya kami bersitegang perihal status hubungan. Pada awalnya, Sam kelihatan tertarik untuk menjalin hubungan dengan saya. Prospek itu rasanya sirna ketika beberapa malam sebelumnya, di saat kami sedang saling berbicara dari hati ke hati dan mengenal lebih dalam, tiba-tiba Sam berseloroh, “Kita enggak pacaran kan ya?”
Saya tercekat.
“Mungkin belum. Tapi kan lama-lama bisa jadi pacaran,” jawab saya, setengah berkelakar, setengah serius. Saya gemar berdiplomasi lewat humor dan biasanya cara ini ampuh.
Namun tidak kali itu. Berbagai argumen dan penjelasan saya tidak digubris oleh Sam. Saya paham pentingnya sebuah hubungan untuk melalui sebuah proses, apalagi mengingat saya dan Sam sama-sama baru mengakhiri hubungan jangka panjang.
“Kamu akan menemukan orang lain,” ucap Sam, seolah-olah bermaksud menghibur saya.
“Loh, aku sudah menemukan kamu. Kenapa harus sama yang lain?” sanggah saya.
“Aku ingin coba pacaran sama cewek,” akhirnya Sam mengaku.
Baca juga: Kisah Teman-teman Saya, Pria Gay yang Menikah dengan Perempuan
Rupanya, meskipun ide pasangan sesama jenis menikah dan berkeluarga sudah semakin lazim, Sam beranggapan bahwa sebuah keluarga selayaknya memiliki sepasang ayah dan ibu. Seperti saya, Sam tumbuh tanpa sosok bapak. Tidak seperti saya, Sam mendambakan menjadi sosok tersebut bagi anak biologisnya di masa depan. Saran saya untuk menjadi sosok tersebut bagi dirinya sendiri terlebih dahulu ditepisnya. Sam bahkan pernah meniduri perempuan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi sosok laki-laki yang paripurna, meskipun juga mengakui bahwa dirinya tidak terlalu menikmati hal tersebut.
Saya tidak pernah lagi bermalam di kamar Sam setelah itu. Semakin saya jatuh hati padanya, semakin Sam menutup diri dan berhenti mengontak saya. Seakan mendapatkan amunisi baru, setelah itu saya semakin gencar berkencan sana-sini, termasuk dengan seorang teman lama, Dani. Saya yang ateis kerap bergurau bahwa mungkin saya akan lebih beruntung dengan seseorang yang non-muslim atau bukan sama-sama eks-Muslim seperti saya.
Sayangnya, lagi-lagi saya harus menelan rasa kecewa ketika berbicara panjang lebar dengan Dani dan mendengarnya mengutarakan niat yang serupa dengan Sam: menikah secara heteroseksual dan menghasilkan keturunan, dengan tujuan membahagiakan orang tua.
Pantang menyerah, saya kembali mencoba memberikan pengertian kepada Dani bahwa ada banyak sekali cara untuk membahagiakan orang tua tanpa harus mengorbankan jati diri. Terlebih, overpopulasi adalah sebuah masalah yang riil, besar, dan global. Sebagai bagian dari generasi Milenial yang hidup di tahun 2019, di mana efek bahaya laten pemanasan global dan kapitalisme semakin terasa di berbagai sendi kehidupan, rasanya naif sekali untuk melanggengkan hal-hal yang terbukti berkontribusi besar terhadap berbagai masalah yang kita hadapi dewasa ini.
Saat saya membaca artikel lama yang dibagikan ulang oleh Magdalene ini, saya kembali tercekat membaca kutipan artikelnya, “Jangan salahkan pria homoseksual yang menikahi perempuan heteroseksual.” Mungkin tidak sepenuhnya adil menyalahkan para individunya satu per satu ketimbang menyalahkan sistem dan norma yang berlaku luas dalam masyarakat Indonesia: hidup secara relijius, heteroseksual dan cisgender, serta menjunjung tinggi semangat guyub.
Baca juga: Prasangka: Sebuah Cerita Pendek
Saya sempat berasumsi bahwa artikel tersebut ditulis oleh seseorang dari generasi di atas saya, yang mungkin memiliki pola pikir dan mentalitas tertentu serta tumbuh di era di mana wacana terkait orientasi seksual atau ekspresi dan identitas gender belum banyak didengungkan di media, apalagi menjadi topik arus utama seperti halnya bagi generasi saya dan seterusnya. Tapi bagaimana mungkin orang-orang seperti Sam dan Dani, yang bukan hanya berasal dari generasi yang sama dengan saya, tapi juga mengenyam pendidikan di luar negeri dan bekerja di perusahaan multinasional, ternyata memutuskan untuk mempertahankan pandangan usang terkait konsep kedirian dan kekeluargaan?
Satu-satunya jawaban yang saya temukan dari pertanyaan tersebut adalah bahwa tingkat pendidikan atau pekerjaan seseorang, atau sejauh mana dia mampu melanglang buana, memang pada akhirnya bukan tolok ukur yang pas untuk menentukan kualitas pemikiran atau tindakannya. Laki-laki cenderung mendapatkan akses dan kuasa yang lebih dalam bersikap dan bertindak, apalagi ketika mampu melancarkan trik-trik yang diperlukan atau diharapkan darinya. Dalam konteks ini, selama Sam dan Dani mampu melakukan hal-hal tertentu, berpenampilan tertentu, atau memenuhi standar tertentu yang membuat mereka dianggap fungsional sebagai laki-laki dalam masyarakat Indonesia, niscaya mereka akan terus menikmati keamanan dan kenyamanan dalam hidup. Meskipun itu artinya membohongi banyak pihak, terutama perempuan yang dipersuntingnya, dan bertanggung jawab akan munculnya manusia-manusia baru di dunia ini. Padahal, semua itu sebenarnya bisa dihindari seandainya saja mereka cukup sadar bahwa pilihan untuk hidup secara jujur dan bertanggung jawab tanpa perlu melibatkan atau bahkan menciptakan pihak-pihak lain sebenarnya ada dan bisa digunakan.
Dalam narasi perjalanan melela seorang pria homoseksual, ada banyak sekali perempuan yang terpaksa menanggung beban malu, amarah, bahkan penyakit sebagai efek domino dari pilihan hidup yang dibuat oleh si pria. Tidak dibiasakan secara struktural untuk memiliki kesadaran diri atau merefleksikan tindak-tanduknya membuat banyak pria, terlepas dari orientasi seksualnya, merasa berhak untuk mengambil jalan pintas dan membuat keputusan-keputusan hidup yang tidak bijaksana dan merugikan dirinya sendiri sekaligus orang-orang di sekitarnya—sebelum kemudian mencari pembenaran atas motivasinya melakukan semua itu. Padahal, sebagai kelompok masyarakat yang dianggap liyan, menurut saya sudah sepatutnya LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) secara umum, terutama pria homoseksual, menggugat kebiasaan tersebut, alih-alih turut serta di dalamnya.
Baca juga: Kultur Misogini dalam Kelompok LGBT
Saya berpikir, bagaimana jadinya apabila Sam atau Dani kemudian mencapai tujuan mereka untuk menikah dan berkeluarga. Apakah benar itu akan menjamin kebahagiaan orang tua mereka? Bagaimana dengan kebahagiaan mereka sendiri? Istri dan anak mereka? Artikel tulisan Jeffry tersebut menggunakan peribahasa yang pas untuk menggambarkan situasi ini — sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga.
Dalam perjalanan hidup mereka, Sam atau Dani kemungkinan besar akan tetap memenuhi dorongan naluriah mereka terhadap sesama jenis dan mengerahkan berbagai cara untuk menutupi hal tersebut, semua atas nama menjaga posisi dan fungsionalitas mereka dalam masyarakat. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki saja: pengakuan terbaru dari Robyn Crawford, mantan kekasih mendiang Whitney Houston, menjadi satu lagi bukti nahas akan betapa budaya yang homofobik dapat menggerogoti psikis seseorang sedemikian rupanya, karena orang tersebut tidak mampu mengaktualisasikan dirinya secara utuh dan jujur. Ini biasanya berujung pada hidup dengan setumpuk kebohongan, sebelum tumpukan tersebut kemudian meledak dan membunuhnya.
Terkadang, saya membayangkan bagaimana jika Sam bersedia memberikan hubungan kami kesempatan yang sama untuk berkembang seperti jika dia berhubungan dengan seorang perempuan. Saya membayangkan menyambutnya ketika dia baru pulang kerja seperti malam itu atau menemaninya bersiap-siap beraktivitas kembali seperti di pagi keesokan harinya. Saya membayangkan mengenal ibunya lebih jauh dan mendengar pengalamannya membesarkan Sam sebagai orang tua tunggal, seperti halnya ibu saya. Mungkin ibu-ibu kami dapat saling bertemu. Mungkin saja mereka akan bahagia dengan sendirinya melihat putra-putra mereka saling menyayangi dan membahagiakan satu sama lain.