L. Ayu Saraswati dan Soal Cantik yang Tak Harus Putih
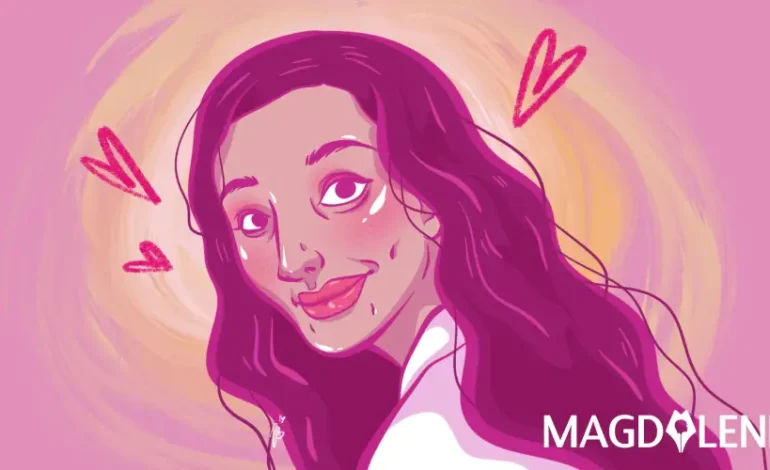
Kamu masih berpikir standar cantik harus berwajah putih? Atau jangan-jangan kamu terobsesi mengubah warna kulit jadi lebih cerah agar sesuai standar publik?
Tahun lalu Magdalene menyurvei 725 responden lintas usia, mulai dari generasi X (1965 – 1980), Y (1981 – 1994), hingga Z (1995 – 2010). Dalam survei itu, ditemukan sebanyak 56 responden mendefinisikan cantik berarti punya kulit putih. Sementara, 254 orang lainnya memilih kulit glowing sebagai perluasan makna kulit cerah.
Cantik yang berarti putih atau cerah juga terlihat dari 188 responden, yang memutuskan memakai filter untuk menaikkan warna atau tone kulit. Tak cuma pakai filter, standar kulit putih ini juga berhubungan dengan tingginya minat produk pemutih instan yang dijual bebas di pasaran.
Dalam liputan sebelumnya, saya menyitir data Compas.co.id, perusahaan teknologi yang fokus pada business intelligence tools (2021) mengenai penjualan serum wajah di dua e-commerce Indonesia, Tokopedia dan Shopee.
Dalam periode dua bulan, menurut catatan Compas.co.id, ada penjualan cukup tinggi pada dua produk andalan Scarlett Whitening, yaitu Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum (151.492 transaksi) dan Scarlett Whitening Acne Serum (80.106 transaksi). Dua-duanya adalah produk pemutih.
Selanjutnya, di urutan ketiga dan keempat ialah produk dari Erto’s, yaitu Erto’s Niacinamide Serum (19.106 transaksi) dan Erto’s Serum Kinclong (5.429 transaksi) dengan total nilai penjualan sebesar Rp2.666.851.832. Pada urutan kelima, Garnier Sakura White Booster Serum 30 ml yang tercatat memiliki 3.166 transaksi dengan nilai penjualan Rp361.012.630.
L. Ayu Saraswati, profesor di Departemen Kajian Perempuan, Gender, dan Seksualitas Universitas Hawaii, seperti banyak perempuan di Indonesia, juga sempat termakan paham bahwa cantik harus berkulit putih. Walau tidak seekstrem melakukan berbagai perawatan memutihkan kulit, pemahaman ini sempat membuat Ayu benci diri sendiri karena kulitnya yang sawo matang.
“Saya dulu punya masalah sama body image. Saya sering di-bully, ‘Ih kok hidungnya pesek, kok kulitnya item.’ Bahkan di lingkaran keluarga atau kenalan sendiri saya dibilang manis, karena kata mereka cantik itu berarti harus punya kulit putih. Sedangkan saya enggak. Saya jalannya jadi bongkok, itu saking malunya sama diri saya sendiri,” kata Ayu kepada Magdalene, (16/8).
Standar cantik kulit putih, imbuh Ayu, juga banyak terlihat dalam karya sastra di Indonesia. Bahkan dalam karya sastrawan berpengaruh Pramoedya Ananta Toer. Meski cukup feminis dan lantang menyuarakan ketidakadilan perempuan, ia kerap kali menggambarkan kecantikan lewat kulit putih atau cerah. Kata Pram, perempuan cantik adalah mereka yang berasal dari blasteran Belanda dan Indonesia atau perempuan pribumi yang berkulit kuning langsat. Misalnya tampak di buku “Jejak Langkah” dan “Gadis Pantai”.
Baca juga: Mpu Uteun: Kelompok Perempuan Pelindung Hutan Aceh yang Melawan Patriarki
Dari pengalaman membaca karya sastra dan perundungan demi perundungan itulah, Ayu menjadi pribadi yang resah. Ia berusaha menggugat standar cantik kulit putih lewat tulisan.
“Saya ingin mengakhiri warnaisme rasisme di indonesia dengan menulis disertasi pada 2013, kemudian dijadikan buku berjudul ‘Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional’. Saya pingin gadis-gadis kecil yang kulitnya hitam punya rasa percaya diri, enggak malu. Karena kata malu itu selalu muncul dari bibir mereka setiap berbicara tentang kepemilikan warna kulit selain putih dan cerah,” jelas Ayu.
Selama menulis buku, ia jadi tahu obsesi kulit putih berasal dari sejarah pra kolonial dan berlanjut saat era kolonialisme. Dari hasil wawancara, analisis teks puisi epos (puisi naratif panjang yang biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh pahlawan dalam hubungannya dengan dewa atau kekuatan super lain), serta mengaji berbagai iklan dan rubrik di media massa, ia memperoleh kesimpulan.
Metafora kecantikan dan keindahan di zaman Jawa prakolonial digambarkan lewat bulan purnama yang terang dan cerah, sedangkan kegelapan sebagai sesuatu yang menakutkan atau perlu dihindari.
“Ketika kolonialisme masuk, putih sebagai sesuatu yang lebih superior pun jadi mudah diterima. Lebih makes sense, karena memang sebelumnya yang cerah dan putih lebih didambakan,” jelas Ayu kepada Magdalene.
Belanda mengenalkan definisi cantik perempuan lewat representasi ras kulit putihnya, sedangkan Jepang dengan putih Asianya. Standar tersebut terus dilanggengkan lewat majalah-majalah perempuan dengan iklan produk kecantikan yang konon bisa memutihkan kulit. Salah satunya iklan bedak Club pada 1944 di Djawa Baroe yang mempertontonkan model perempuan Jepang berkulit sangat terang, tengah memulas bedak ke pipinya.

Baca juga: Rambu Dai Mami, Pemimpin Perempuan dari Tanah Sumba
Memutus Mata Rantai
Sadar standar cantik ini telah hidup ratusan tahun, Ayu mengakui proses untuk mendobrak atau memutus rantainya bakal sulit. Saat singgah ke Indonesia, ia masih menemukan mal-mal bergengsi yang menjual produk whitening. Belum lagi masih digandrunginya kontes kecantikan di tengah masyarakat.
“Yang beda itu bentuk pakaiannya saja. Bentuk tubuh dan feature wajah bahkan tone kulitnya masih sama: Putih atau cerah. Di sini kita melihat gimana ideologi putih terus bermain, bersamaan dengan patriarki dan kapitalisme. Makanya perubahan sulit sekali terjadi,” tutur Ayu.
Kendati demikian, bukan berarti kita tak punya cara lain untuk memutus mata rantai yang menindas ini. Dalam hemat Ayu, perubahan tetap bisa terjadi dan bisa dimulai dari hal-hal kecil.
Ia mengutip isi buku Introduction to women’s, gender and sexuality studies: interdisciplinary and intersectional approaches (2018), yang mengajak pembaca untuk melatih jujur pada emosinya sendiri. Ayu meminta pembaca untuk melihat pantulan diri dalam cermin. Ketika merasa diri tidak cantik atau malu, pembaca diminta untuk berefleksi dan bertanya kenapa kita merasa demikian.
Baca juga: Santi Warastuti dan Legalisasi Ganja Medis: Saya Takkan Berhenti
“Kita harus bisa talk about our feelings. Itu adalah titik awal untuk menggugat serta menentang nilai-nilai atau ideologi yang kita internalisasi sejak kecil,” ucap dia.
Selain itu berefleksi pada diri sendiri, menurut Ayu penting buat kita untuk memulai perubahan lewat kegiatan kita sehari-hari, termasuk lewat media sosial. Kita harus mulai awas dalam pemilihan kata-kata serta pembagian unggahan.
“Apakah unggahan kita memperkuat patriarki atau social justice itu harus kita amati baik-baik. Kita masih melontarkan candaan ke orang-orang berkulit gelap tidak? Kalau masih ya itu harus diperbaiki,” kata Ayu.
Selain kedua hal ini, kita harus sepakat standar atau ideologi yang sudah berakar kuat, harus dilawan lewat institusi yang lebih besar bernama pemerintah.“Negara bisa melarang ada (produk) pemutih kulit, karena pelarangan pemakaian nama saja saja kan terbukti tidak ampuh ya. Justru ada permainan kata mencerahkan sebagai gantinya. Bisa juga dengan membuat kebijakan-kebijakan yang secara eksplisit mencantumkan bahwa warnaisme dan rasisme itu ilegal. Ini karena ideologi putih sendiri berakar dari anti-blackness jadi perlu ada kebijakan tegas,” tutup Ayu.






















