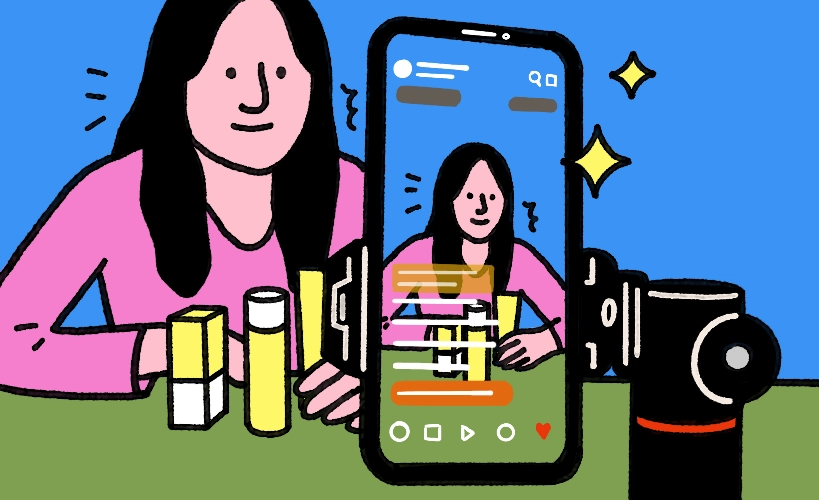Cangkul di Tangan Kanan, Buku di Tangan Kiri: Siasat Petani Indramayu Hadapi Cuaca Ekstrem

Saya tiba di rumah Yusuf di Desa Bangun II, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, sekitar pukul delapan pagi, tepat di Hari Natal 2025. Rumahnya sederhana dengan cat berkelir hijau menyala, senada dengan warna batang padi di seberang jalan. Ia menyambut saya hangat dengan kopi dan kudapan. Tak lama, ia mengajak saya bertolak ke sawahnya yang hanya berjarak beberapa langkah di depan rumah.
Di pematang sawah, ia berhenti di dekat batang kayu dengan tinggi 150 sentimeter. Di bagian atasnya terpasang tabung silinder dari kaleng bekas. “Ini namanya omplong, Mbak, fungsinya mengukur curah hujan harian,” ujarnya pada saya saat itu.
Yusuf mengeluarkan penggaris kayu kecil dari sela-sela buku, mengukur tinggi air di dalam tabung, lalu mencatatnya di buku. Saya memerhatikan dengan saksama. Di dalam buku Yusuf, tergambar sebuah tabel dengan beberapa kolom, curah hujan cuma salah satunya. Ada kolom umar semai/ tanam, sifat hujan, hingga dampaknya.
Rutinitas mencatat hujan ini rutin dilakukan Yusuf saban pagi, antara pukul 06.30 hingga 08.00. Menurutnya ini waktu ideal karena hujan yang tercatat terkumpul dari malam hingga, sebelum terjadi evaporasi (penguapan). Jika turun hujan lagi setelah pencatatan maksimal di jam 8 pagi, ia baru akan mencatatnya esok.
“Curah hujan itu penting sekali,” tandas Yusuf. Dari angka-angka tersebut, ia belajar tentang pola hujan, menghubungkannya dengan ketinggian air, pertumbuhan tanaman, hingga peluang kemunculan serangan hama. Ini semua merupakan bagian dari Agrometerologi, agar enggak lagi sepenuhnya berspekulasi pada musim, dilansir dari BBC Indonesia.
Dicap Petani Gila karena Bawa Buku ke Sawah
Nyatanya buat Yusuf, rutinitas ini tak mudah dilakukan. Ia dan beberapa petani lain yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim (P2TPI) mengaku sempat jadi bahan olok-olok tetangga dan petani lainnya.
“Dibilang petani gila, petani sinting, bawa-bawa buku ke sawah,” ujar Tarsono, Ketua P2TPI, mengingat masa-masa awal mereka mencatat hujan setiap hari.
Mulanya, pencatatan ini dipandang tak ada gunanya. Petani sudah cukup dipusingkan oleh harga pupuk dan pestisida yang naik, biaya sewa lahan, serta harga gabah yang tak menentu. Menambah pekerjaan dengan mengukur hujan dianggap membuang waktu.
Namun perubahan cuaca membuat kebiasaan lama tak lagi bisa diandalkan. Sejak 2019, Indramayu mengalami pola cuaca yang semakin sulit diprediksi: Kemarau panjang, kemarau basah, hujan turun di musim yang seharusnya kering, diselingi panas ekstrem. Pada periode 2020–2022, kondisi ini memicu ledakan hama, terutama tikus.
Dalam situasi normal, tikus bermigrasi saat kemarau karena kekurangan air dan makanan. Namun kemarau basah membuat air dan tanaman tetap tersedia. Tikus tidak bermigrasi dan berkembang biak di lahan yang sama. Yusuf mengaku dalam satu musim bisa menangkap 700 hingga 800 ekor tikus, jumlah yang tak sebanding dengan kecepatan reproduksinya.
Dampaknya langsung terasa pada biaya produksi. Sebelum mengenal pencatatan iklim, Yusuf dan Tarsono menyemprot sawah hingga 12–13 kali per musim tanam. Setiap kali semprot membutuhkan sedikitnya tiga jenis pestisida. Biaya pestisida saja bisa mencapai Rp3,6 juta hingga Rp10,8 juta per hektare, belum termasuk upah tenaga semprot, ongkos traktor, tanam, perawatan galengan, dan bawon panen. Total biaya produksi bisa menembus Rp12–15 juta per hektare per musim.
Dalam kondisi panen normal, hasil padi di Indramayu berkisar 7–8 ton per hektare. Setelah dipotong bawon (bagi upah dengan buruh), petani menerima sekitar 5,5–6 ton gabah bersih. Dengan harga gabah 2024–2025 di kisaran Rp6.500–Rp7.000 per kilogram, pendapatan kotor berada di rentang Rp35–40 juta per hektare—angka yang langsung tergerus biaya produksi dan sewa lahan.
Ketika panen terganggu cuaca atau hama, defisit tak terhindarkan. Sejumlah petani mengaku terpaksa berutang untuk menutup biaya tanam berikutnya. Dalam kondisi inilah, pencatatan iklim mulai dilihat bukan sebagai tambahan kerja, melainkan sebagai upaya mengurangi risiko.
Belajar Iklim dari Sawah Sendiri
Upaya pencatatan curah hujan tak lahir tiba-tiba. Menurut Prof. Yunita T. Winarto, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, pendekatan petani-peneliti iklim berangkat dari kritik terhadap pendidikan pertanian yang bersifat proyek dan jangka pendek.
“Petaninya belum betul-betul menginternalisasi pengetahuan itu. Proyeknya selesai, belajarnya juga selesai,” ungkap Yunita dalam wawancara via Zoom pada 24 Desember 2025.
Berangkat dari pengamatannya sejak 1990-an terhadap sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Yunita mengembangkan pendekatan yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembelajaran. Konsep ini mulai diperkenalkan lebih sistematis pada 2008, ketika ia berjejaring dengan komunitas Farmer Field School di bawah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Pendekatan tersebut masuk ke Indramayu sekitar 2009–2010. Komunitas petani sempat berhenti, lalu bergerak kembali hingga bertahan sampai 2025. Awalnya, sekitar 50 petani terlibat, tersebar di berbagai ekosistem. Sebut daja dari lahan irigasi teknis, setengah irigasi, tadah hujan, pesisir, hingga wilayah lebih tinggi.
“Kenapa tersebar? Karena ekosistem Indramayu itu sangat beragam. Kalau mau belajar iklim, tidak bisa hanya dari satu tipe lahan,” ujar Yunita.
Dalam skema ini, setiap petani mengukur curah hujan di lahannya sendiri, mencatatnya harian, lalu mengevaluasi bersama dalam pertemuan bulanan. Dari situ, mereka belajar membaca hubungan antara hujan, kondisi agroekosistem, hama, dan hasil panen.
“Yang kami perkenalkan bukan transfer teknologi, tapi transmisi cara belajar,” kata Yunita. “Pengetahuan lokal petani tidak ditinggalkan, justru diperkaya.”
Petani juga mempelajari dinamika El Niño dan La Niña, serta menyusun strategi tanam berbasis skenario iklim tiga bulanan. Manfaatnya tidak selalu berupa peningkatan pendapatan, melainkan pengurangan risiko. “Kalau petani lain gagal panen, paling tidak mereka tidak 100 persen gagal panen,” ujarnya.
Perempuan Terlibat Aktif
Pendekatan ini melibatkan rumah tangga petani secara utuh. “Pengambilan keputusan itu tidak hanya suami. Harus ada kesepakatan bersama,” tutur Yunita. Di Indramayu, keterlibatan perempuan berkembang secara organik. Mulai dari menemani pertemuan, ikut mencatat, hingga terlibat dalam diskusi evaluasi.
Nunung, 54, salah satu perempuan petani, mengingat bagaimana awalnya ia hanya ikut menemani suami. “Dari situ akhirnya kita ikut mengamati,” katanya. Lama-kelamaan, ia memahami apa yang dicatat dan mengapa tidak semua hama harus dibasmi dengan pestisida.
“Saya itu bertanya-tanya, kenapa tetangga-tetangga beli obat semprot, sementara kita tidak,” ujarnya. Jawabannya ditemukan di sawah mereka sendiri. Sawah yang tampak “panur”—tidak bersih karena tidak disemprot—justru bertahan ketika sawah tetangga terserang hama. Dari situ, pertanyaan dan rasa ingin tahu mulai sering muncul.
Keterlibatan perempuan ini berdampak langsung pada pengelolaan biaya rumah tangga pertanian. Pengurangan semprot berarti penghematan. Dalam situasi cuaca ekstrem dan biaya produksi yang terus naik, keputusan-keputusan kecil berbasis pengamatan ini menjadi penyangga keberlanjutan.
Kini, komunitas petani-peneliti iklim Indramayu mengumpulkan data hingga 13–16 tahun. Jumlah anggota aktif menyusut menjadi sekitar 25 orang karena keterbatasan pendanaan, namun praktik mereka menarik perhatian petani dari daerah lain. Sejumlah anggota pernah diminta berbagi pengalaman hingga ke luar Jawa.
Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, praktik ini tidak menjanjikan panen selalu berhasil. Namun bagi Yusuf dan rekan-rekannya, catatan hujan, buku lusuh di tangan, dan diskusi bulanan memberi sesuatu yang lebih penting: Kendali atas keputusan bertani mereka sendiri. Bukan menunggu musim datang, tetapi belajar membacanya, langsung dari sawah di depan rumah.
Tulisan ini merupakan bagian dari seri liputan yang mendapatkan fellowship dari Global Climate Resilience for All.