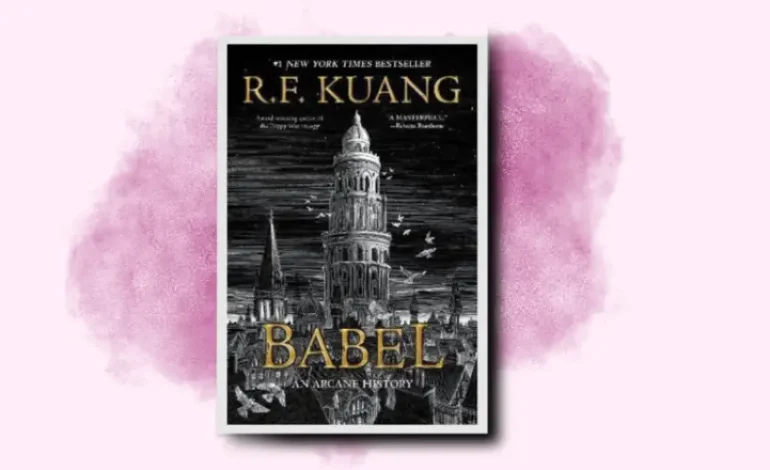Ruang Aman hayVee, Cara Scott Alfaz Lawan Stigma ODHIV

Bak tersambar petir di siang bolong, mungkin ini analogi yang pas untuk menggambarkan pengalaman Scott Alfaz saat pertama divonis HIV positif. Saat itu, 2012, Alfaz masih jadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Info tentang status HIV ini peroleh usai memutuskan untuk mendonorkan darah melalui Unit Kegiatan Mahasiswa pada akhir 2011. Beberapa bulan pasca-donor darah, ia dikabari pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Yogyakarta untuk melakukan tes darah ulang ke Puskesmas Gedongtengen.
Tiga puluh menit kemudian, hasil tes darah Alfaz keluar. Ia dinyatakan positif HIV. Dunia Alfaz runtuh seketika begitu tahu ia adalah bagian Orang Dengan HIV (ODHIV). Minimnya informasi mengenai HIV yang dapat ia peroleh kala itu, membuat dirinya terpuruk. Pikiran untuk mengakhiri hidup nyaris tiap hari muncul.
“Karena akses informasinya enggak ada, ya aku dulu mikirnya benar-benar kayak masyarakat awam yang barangkali enggak tahu meninggalnya kapan, bisa saja bulan depan. Aku enggak tahu bisa punya anak atau enggak, bisa nikah atau enggak, bisa sampai bertahun-tahun hidup atau enggak. Jangankan bertahun-tahun, setahun aja aku enggak bisa bayangin ketika itu,” ceritanya pada Magdalene,(10/1).
Di masa sulit ini, cuma sahabat-sahabat terdekat yang tahu kondisinya. Ia lantas menjalani seluruh pengobatan seorang diri. Butuh waktu tujuh tahun, tepatnya pada 2019 sampai Aflaz berani bercerita pada keluarga besar. Bukan takut bakal diusir atau tidak diakui, tapi ia enggan melihat air mata di tengah keluarga. Apalagi Alfaz dan keluarga masih belum selesai berduka akibat kematian ibu.
“Aku enggak takut bakal diusir, sih, karena aku yakin mereka tetap akan support aku. Aku hanya belum siap ngelihat ayah, adik, atau mas aku, mereka harus sedih. Belum siap aja liat mereka sedih karena virus aku, atau mungkin terus mereka tahu masa lalu aku, tapi ya tetap mereka harus tahu. Dan beneran, memang ketika mereka tahu, nangis semua,” jelasnya.
Setelah hampir dua belas tahun hidup berdampingan dengan HIV, Alfaz akhirnya mampu bangkit dan menghadapi kenyataan. Dengan tekad melawan stigma ODHIV, Alfaz tak hanya berhasil lulus sarjana. Ia juga berhasil menyelesaikan studi S-2 di Universitas Groningen, Belanda dan merintis HayVee. Itu adalah platform digital kesehatan mental dan seksual didirikan bersama dengan teman-teman yang punya perhatian sama terkait HIV/AIDS.
Bersama Magdalene, Alfaz lebih lanjut membagikan ceritanya tentang ceritanya sebagai ODHIV dan tekadnya melawan stigma seputar HIV/AIDS. Berikut adalah kutipan wawancaranya:
Magdalene: Boleh enggak, sih, Kak diceritain kenapa memutuskan untuk mendirikan hayVee?
HayVee itu sebenarnya berdiri karena pastinya aku punya kepedulian tentang isu HIV/AIDS. Aku sendiri ODHIV, tapi ternyata teman-teman di sekitar aku juga punya concern yang sama walau mereka bukan ADHIV. Akhirnya kita kita bikin platform atau wadah bareng-bareng berbentuk komunitas. Lalu pada 2021 lambat laun ini menjadi badan hukum berbentuk yayasan. Sesuai hastag-nya #JadiRuangAman, hayVee kami dedikasikan sebagai safe space bagi teman-teman yang punya isu dengan kesehatan seksual maupun kesehatan mental terkait HIV/AIDS ini.
Dari yang awalnya cuma pengen mengedukasi aja, bikin akun Instagram untuk buat konten-konten, lama kelamaan kami juga membuat program. Misalnya pas COVID masih tinggi-tingginya dan kita masih belum bisa tatap muka, akhirnya bikin online counseling sama dokter dan psikolog gratis bagi teman-teman yang HIV positif atau teman-teman yang ada di populasi kunci (perempuan pekerja seks, transpuan, lelaki seks dengan lelaki (LSL), dan pengguna napza suntik (penasun), ibu hamil, dan pasien TBC).
Selain itu, agar bisa se-relate mungkin dengan generasi muda yang berarti generasi Z dan milenial, campaign yang dilakukan itu seperti bikin short movie. Bahkan kami sempat kolaborasi juga dengan salah satu teater pertunjukan dan bikin lagu.
Baca Juga: Hidupkan Palestina Lewat Cerita, Wawancara Eksklusif dengan Maya Abu Al Hayyat
Berbicara soal ruang aman, apakah hayVee hanya eksklusif untuk teman-teman ODHIV saja atau untuk semua?
Kami punya harapan, bersama hayVee semoga banyak ruang aman yang tercipta, ruang-ruang aman di berbagai institusi, di berbagai tempat yang tercipta. Sesimpel dalam pertemanan, semoga mereka semua bisa jadi ruang aman dengan sesamanya. Pun, begitu di institusi pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Itu, sih, harapannya.
Yang paling menyedihkan, kadang institusi keluarga yang seharusnya nomor satu menjadi ruang aman, tapi justru belum bisa memberikan rasa aman bagi anggota keluarga mereka. Tidak sedikit teman-teman HIV positif yang sampai harus ngekos, harus diusir, harus pindah ke luar kota, keluar pulau.
Puji Tuhan selama berproses bersama hayVee, banyak yang bukan ODHIV justru mendapatkan ruang aman ini. Mereka ini caretaker atau caregiver. Banyak yang biasanya datang ke kami itu istri, suami, adik, atau kakaknya yang positif HIV. Mereka ini engage sama kita. Ikut kelompok dukungan sebaya juga secara virtual sama programnya hayVee untuk lebih banyak tau tentang gimana caranya bisa menjadi caregiver bagi teman-teman positif HIV. Dari situ merasa empowered, merasa tidak sendiri, sih. Itu yang paling utama.
Karena banyak banget teman-teman ini yang merasa sendiri, kayak aku harus kemana, aku enggak tahu harus bagaimana sebagai caregiver. Jadi mereka berusaha kami kumpulin juga, kami buatkan peer group support. Di situ mereka saling berbagi. Karena aku sendiri bahkan kalau enggak HIV positif juga enggak mungkin sepaham ini ngomong tentang undetectable untransmitable misalnya. Enggak jarang juga berpendidikan pun enggak paham tentang HIV 100 persen, buktinya masih banyak orang berpendidikan yang tertulang HIV. Makanya ruang aman ini perlu buat semua.
Kakak tadi bilang kalau hayVee juga fokus pada isu kesehatan mental ya, tapi memang apa, sih korelasinya kesehatan mental dan HIV/ADIS?
Dari riset yang kami baca atau riset pribadi yang hayVee lakukan gitu, kesehatan mental penting bagi teman-teman HIV positif. Sebab, penerimaan diri akan berpengaruh ke adherence atau kepatuhan mengonsumsi ARV (Antiretroviral). Semakin tinggi level penerimaan dirinya, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan untuk mengonsumsi ARV. Sebaliknya, ketika level penerimaan dirinya rendah, maka kepatuhannya juga akan rendah. Ketika kepatuhannya rendah, berarti nanti kesehatannya akan rendah juga.
Jadi sangat berpengaruh kondisi kesehatan mental teman-teman HIV positif terhadap kesehatan. Enggak jarang ketika mereka belum bisa menerima diri mereka, akhirnya ada internalisasi stigma di diri mereka. Mereka yang menstigma diri mereka sendiri.
“Oh, gue sampah.”
“Oh, gue malu-maluin.”
“Oh, gue emang beban. Buktinya gue dikasih azab HIV ini.”
Itu sempat juga aku alami, internalized stigma tadi karena masyarakat sendiri menganggap HIV se-negatif itu. Akhirnya aku ketika awal-awal juga ikut menganggap HIV se-negatif itu, diri aku pun senegatif itu, sejelek itu. Angka internalized stigma masih cukup tinggi juga di teman-teman HIV positif, ini yang mesti diubah.
Ada enggak kendala selama berproses bersama heyVee?
Tujuan awal hayVee adalah untuk teman-teman HIV positif, jadi ruang untuk saling support. Itu kenapa namanya hayVee. Tapi setelah kami coba mengulik feedback dan coba nanya-nanya ke audiens, baik di social media, atau yang pernah ikutan program, (mereka) mulai melakukan perubahan. Ternyata sebelum akhirnya engage sama kami, baik di media sosial, atau di program, mereka nyatanya masih punya ketakutan.
Ketika mereka follow, like, comment konten heyVee mereka takut bakal diasosiasikan sebagai HIV positif. Itu yang jadi kendala kami awal berdirinya heyVee, that’s why kami berusaha rebranding. HayVee jadinya bukan cuma ruang aman bagi temen-temen HIV positif tetapi juga bagi teman-teman yang concern dengan isu kesehatan seksual dan mental. Ini kami lakukan biar lebih inklusif dan bisa dikatakan rebranding cukup berhasil karena responsnya lebih positif.
Selain itu kalau berbicara soal kendala ada juga kasus di mana kami sempat punya program. Program ini sebenarnya cukup general ya untuk ibu dan anak, tetapi karena isu yang kami bawa, pihak yang mau kami ajak kerja sama akhirnya mundur. Menurut mereka risikonya cukup tinggi being associated sama sama HIV.
Kalau begitu berarti stigma terhadap ODHIV masih cukup kuat ya seperti yang Kakak bilang sebelumnya juga?
Aku melihat masih ya. Buktinya teman-teman HIV positif enggak bisa segampang itu kan cerita kayak kita kena COVID terus update di story (Instagram). Padahal kan sama-sama virus itu, tapi enggak ada itu ceritanya teman-teman baru tes positif, dia langsung upload ke situ. Bisa support aku enggak? Kan tidak sesimpel itu, ternyata. Berarti pada tahap ini memang masih ada stigmanya. Memang di lapangan banyak teman-teman di lingkungan pendidikan yang aku tahu bahkan dekanat (kampus) sampai manggil dia.
Walaupun Alhamdulillah enggak sampai dikeluarkan karena memang enggak ada dasar buat mengeluarkan dia dari kampus, tapi kan tetap dengan dia udah disidang sama dekanat, jadi indikasi apa sebenarnya yang jadi privasi disebarkan ke satu fakultas atau mungkin satu kampus. Yang di lingkungan kerja juga. Walaupun dari segi peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan enggak bisa dipecat oleh si pemberi kerja, tapi stigma ini bekerja dengan dia dibikin enggak nyaman sama lingkungan kerjanya. Dia bisa aja dimutasi berkali-kali, sampai dia resign.
Yang paling menyedihkan, kadang institusi keluarga yang seharusnya nomor satu menjadi ruang aman, tapi justru belum bisa memberikan rasa aman bagi anggota keluarga mereka. Tidak sedikit teman-teman HIV positif yang sampai harus ngekos, harus diusir, harus pindah ke luar kota, keluar pulau.
Lalu, kenapa stigma ini masih langgeng? Apakah informasi yang serba gampang diakses sekarang enggak begitu berkontribusi untuk meruntuhkan stigma ini?
Informasi memang semakin gampang diperoleh, tapi kan masih belum bisa menyasar ke semua orang. Bahkan kalau kita lihat dari riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Indonesia, pemahaman komprehensif masyarakat kita isu kesehatan seksual dan reproduksi masih di angka 1 persen. Karena rendahnya edukasi, akhirnya mereka enggak paham kalau ternyata HIV itu tidak segampang itu menular, bahkan lebih gampang menular COVID-19 dan tuberkulosis. Terus, kenapa stigmanya masih tetap tinggi?
Dari yang aku lihat selain rendahnya edukasi, masyarakat belum bisa memisahkan HIV ini dengan latar belakang dan masa lalu teman-teman yang ada di populasi kunci tadi. Mostly orang-orang dari populasi kunci ini bertentangan banget sama moral kompas masyarakat kita in general. Mereka ini kan pekerja seks, laki-laki seks sama laki laki, pengguna jarum suntik yang pastinya dianggap tidak baik sama mereka. Jadinya terlepas orang-orang dari populasi kunci ini sangat berkontribusi bagi masyarakat, masa lalunya itu tetap membayang-bayangi.
Bahkan yang dia sebenarnya adalah korban, bisa aja dia ibu rumah tangga, atau yang lagi lebih menyedihkan, dia ada anak dengan HIV AIDS, stigma itu tetap kena juga ke mereka. Perkataan, ‘Ya lu sih punya laki-laki kayak gitu, makanya dijaga,’ tetap terlontar. Perempuan jadi serba salah, padahal dia sebagai istri misalnya enggak tahu apa-apa. Suaminya yang jajan di luar yang menularkan, tapi stigma kan tetap bermain. Kalau berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kesehatan di laporan 2023 saja, angka penyumbang infeksi adalah dari ibu-ibu hamil. Saya rasa perempuan hamil yang terinfeksi ini bisa jadi kena dari suaminya selain misalnya dari gaya hidup seksual berisiko.
Dari pengalaman aku pribadi di social media, mau se-positif dan se-informatif apapun konten yang aku sampaikan, tetap aja ada netizen yang berkomentar. “(Kamu) kena HIV karena apa dulu? Kok kalian support-support aja, kok kalian setuju-setuju aja sama pendapatnya?”.
Korelasinya dengan masa lalu aku enggak ada. Memang karena aku HIV positif lantas jadi menegasikan edukasi yang aku sampaikan? Kan enggak juga, edukasinya tetap benar. Tapi ya realitasnya masih saja masyarakat banyak melihat HIV karena faktor risikonya yang bertentangan dengan kompas moral masyarakat. Itulah sebabnya aku pun tetap berusaha hadir di sosial media, menunjukkan sepositif mungkin, biar enggak menambah stigma. Ya walaupun kadang capek juga sih menjadi positif yang terlalu dipaksakan.
Mengingat stigma soal HIV/AIDS ini masih juga tinggi, selain dari kerja-kerja edukasi hayVee atau organisasi masyarakat lain, apa sih harapan Kakak ke pemerintah?
Kalau berbicara soal harapan ke pemerintah sulit juga ya karena bahkan aku masih belum melihat standing yang sangat crystal clear. Sebagai contoh, ketika ada materi edukasi di sekolah seperti di SD yang sudah jelas-jelas materi kesehatan reproduksi dan menjadi diskursus negatif di media sosial, pemerintah kita enggak sejelas itu ngasih standing, enggak berani ambil suara. “Ini edukasi lho. Yang kami lakukan sudah benar”. Mereka kan enggak melakukan ini.
Jadi aku merasa mereka masih belum hadir menurut aku, pemerintah masih belum hadir bahkan sesederhana membantu meluruskan edukasinya. Jadi dengan didiamkan aja, akhirnya (diskursus) ini semakin melebar dan semakin melanggengkan stigma juga. Akhirnya ketika anak-anaknya mereka sudah menginjak dewasa, menginjak remaja ada resiko besar mengalami kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) atau bahkan ekstremnya kena HIV kayak aku.
Ini kan aku korban dari edukasi kesehatan reproduksi dan seksual yang tidak optimal. Jadi ya PR-nya banyak, sih. Perbaikannya pun masih besar, masih jauh dari kata sempurna. Tapi harapannya masalah ini semoga bisa cepat ditangani.