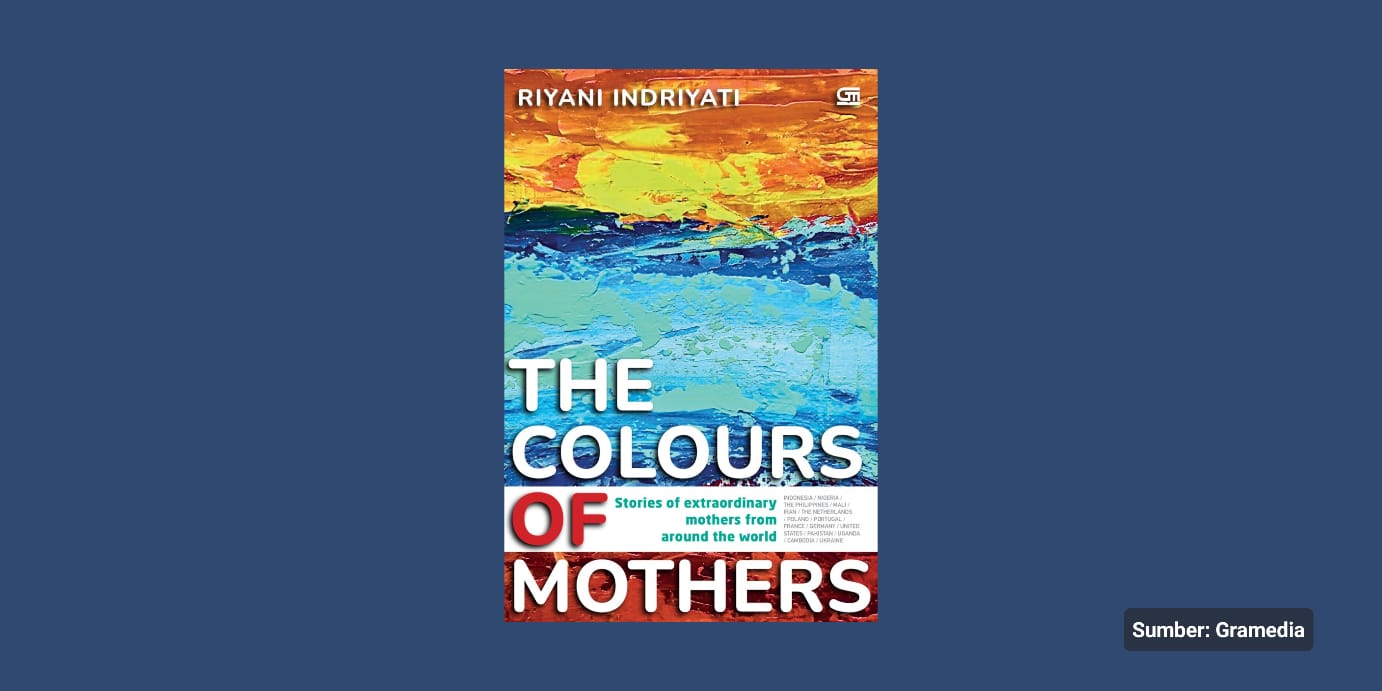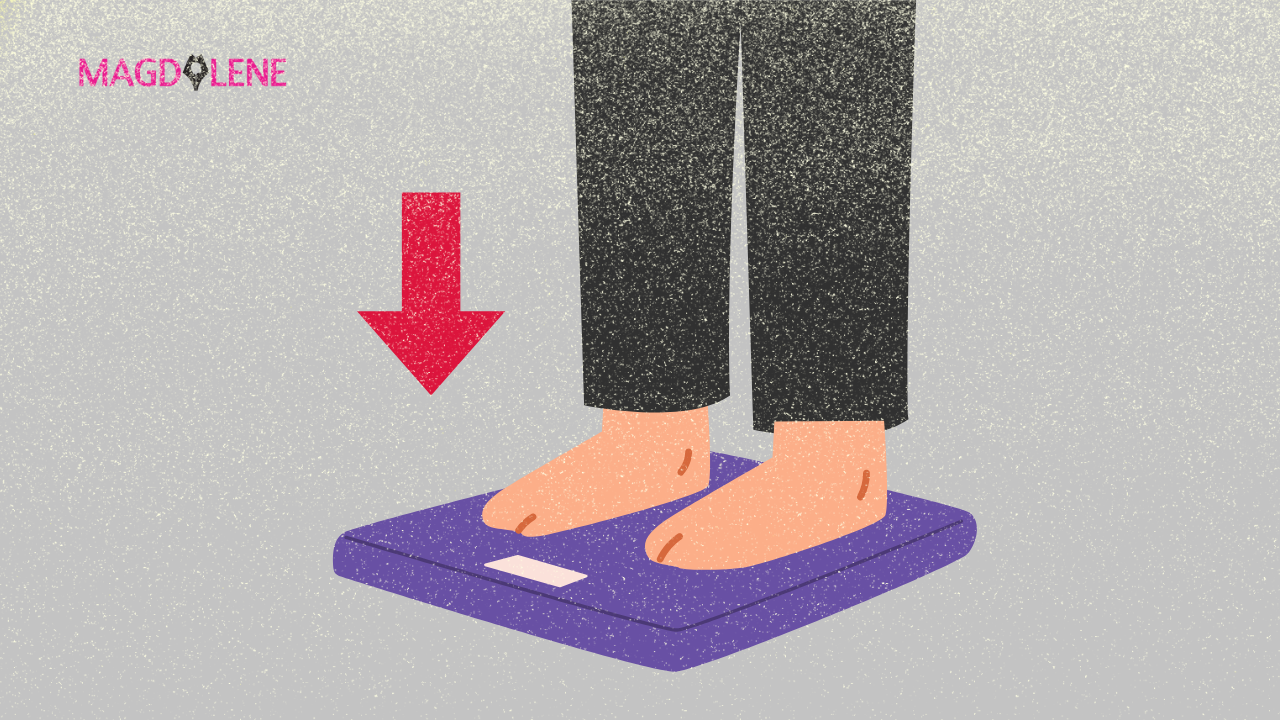Di Balik Konten Viral, ‘Cancel Culture’, dan Perlunya ‘Mindful’ di Medsos: Wawancara Eksklusif Wregas Bhanuteja
Wregas Bhanuteja menceritakan alasannya mengisahkan guru perempuan dalam karakter utama ‘Budi Pekerti’, dampak ‘cancel culture’, dan upaya menyampaikan isu sosial lewat karya.

Di tengah larisnya film horor Indonesia—yang hampir setiap Kamis tayang—Budi Pekerti (2023) muncul dengan premis yang melekat dengan pengguna medsos: seorang guru Bimbingan Konseling (BK) kena cancel culture, karena omongannya yang diplesetkan viral di medsos. Ini merupakan film panjang kedua garapan Wregas Bhanuteja, yang kembali bertemakan isu sosial. Sebelumnya, Wregas mengangkat tentang kekerasan seksual dalam Penyalin Cahaya (2021).
Usai menyaksikan filmnya di Jakarta Film Week akhir Oktober lalu, ada satu hal yang saya sadari. Budi Pekerti bisa menjadi medium berefleksi bagi penonton yang senang berselancar di medsos. Sayang, belum tentu banyak penonton Indonesia menyukai genre drama keluarga dan menampilkan isu sosial—mengingat film yang tembus satu juta penonton pada paruh pertama 2023 didominasi genre horor, berdasarkan laporan Katadata.
Konsistensi Wregas dalam menciptakan karya yang idealis, membuat saya ingin mengobrol seputar film teranyarnya. Terutama tentang cancel culture yang menginspirasi Wregas memproduksi Budi Pekerti, pilihannya menetapkan perempuan sebagai karakter utama dalam film, serta ambisi Wregas dalam berkarya.
Bersama Koordinator Media Sosial Magdalene Siti Parhani, saya menemui Wregas di XXI Baywalk Pluit pada (10/11). Di tengah kesibukannya promosi film, siang itu Wregas ada jadwal cinema visit, bersama para siswa sebuah SMA swasta di Jakarta. Berikut kutipan obrolan kami.

Kak Wregas, selamat ya untuk Budi Pekerti, dapat 17 nominasi di FFI (Festival Film Indonesia). Bagaimana perasaannya melihat antusiasme dan respons penonton?
Bersyukur sekali tentunya. Film ini pertama tayang justru di Toronto International Film Festival (TIFF), dan cerita yang diangkat dari kejadian sehari-hari di Indonesia. Ketika di Toronto, awalnya saya punya kekhawatiran, apakah akan relate dengan penonton di luar Indonesia? Ternyata responsnya positif. Mereka juga relate dengan berbagai peristiwa keviralan, dan bagaimana guru juga sering dikritik oleh berbagai pihak.
Saat tayang di Indonesia, ternyata publik lebih relate lagi dengan berbagai kejadian di film ini. Yang paling menyentuh buat saya adalah, banyak sekali (penonton) yang terharu, atau menangis melihat ending filmnya. (Melihat) kehangatan dan kisah perjuangan keluarga Bu Prani (Sha Ine Febriyanti), yang disajikan dari awal sampai akhir.
Baca Juga: Obrolan Candid dengan Gina S. Noer, Sutradara ‘Like & Share’: “I Walk the Talk”
Di sejumlah wawancara sebelumnya kak Wregas cerita, film ini terinspirasi dari masa pandemi, sewaktu ada video ibu-ibu marah yang viral di medsos. Lalu dijadikan konten komedi, dan di-bully netizen yang juga menuntut permintaan maaf. Selain itu, ada konten viral soal hukuman guru terhadap murid, yang dipermasalahkan netizen. Dari banyaknya peristiwa cancel culture di medsos, kenapa memilih fokus ke dua hal ini untuk storyline?
Pertama, banyak sosok viral, karena tertangkap sedang marah atau mengumpat (dalam) video 15 detik. Lalu netizen menghakimi, kelakuannya itu tidak baik dan tidak mencoba mencari tahu latar belakang, atau apa yang terjadi dengan sosok tersebut di baliknya.
Kedua, banyak sekali peristiwa guru yang tiba-tiba viral, ketika memberikan hukuman pada siswanya. Jadi sewaktu ditangkap kamera, lalu dipublikasikan di media sosial, berbagai orang ikut nge-judge kelakuan sang guru. Tanpa tahu latar belakang atau konteks guru tersebut memberikan hukuman pada siswa, maupun aturan sekolahnya seperti apa.
Nah, kedua peristiwa ini enggak hanya terjadi bullying-nya di media sosial, tapi ke kehidupan nyata mereka juga. Ada yang tiba-tiba enggak nyaman untuk pulang ke rumah. Ada juga yang di tempat kerjanya pun dipermasalahkan, sampai sanak saudara yang lain ikut terkena imbas bullying.
Jadi saya merasa, peristiwa ini dirangkum dalam sosok karakter utama guru BK (Bimbingan dan Konseling). Guru BK dikenal sebagai orang yang memberikan konseling di sekolah, dan mengajarkan soal perilaku, pendewasaan tentang bersosialisasi.
Ketika video Bu Prani sebagai guru BK ini viral saat mengumpat, ada kontras yang dinilai netizen dalam cerita ini enggak sesuai dengan yang diajarakan tentang tata krama, dan bagaimana bersosialisasi. Lalu netizen nge-judge, kok yang kamu ajarkan enggak sesuai, dengan perilakumu di kehidupan sehari-hari? Makanya, guru BK menjadi karakter utama yang ditampilkan.
Dalam riset dan menulis skenario, ada interaksi dengan guru yang terdampak langsung oleh cancel culture?
Riset yang dilakukan lebih mengumpulkan sosok-sosok, yang tiba-tiba viral. Bukan seorang guru, tapi berbagai macam orang yang viral karena mengumpat, marah, atau gestur tubuhnya itu enggak sopan.
Saya mengumpulkan 10 video (sosok yang viral karena marah-marah), dari berbagai media sosial. Dan saya mengikuti perkembangan kehidupan mereka, perkembangan peristiwa itu. Biasanya orang-orang ini klarifikasi dulu, alasan dia marah dan yang ada di video itu enggak benar. Lalu, netizen menyerang balik lagi, katanya ada bukti dan bilang marahnya enggak beralasan. Setelah itu netizen menuntut permintaan maaf, dan sosok ini mau melakukan klarifikasi permintaan maaf. Jadi ada pola seperti itu.
Di akhir, biasanya sosok-sosok ini curhat. Sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi kehidupan pribadinya masih terdampak. Mereka enggak nyaman untuk tinggal di rumah dan bersosialiasi. Nah, semua kisah itu saya kumpulkan, dan dirajut menjadi skenario.
Tentang guru-guru ini juga sama, proses risetnya itu mengumpulkan keviralan guru yang pernah terjadi. Misalnya memotong rambut siswa yang poninya terlalu panjang, menyita sepatu, atau meminta siswa memakai baju lain karena salah seragam—yang netizen anggap baju itu malah mempermalukan siswa.
Kejadian-kejadian itu dan nasib para guru saya kumpulkan. Ada guru yang sampai dituntut ke pengadilan oleh orang tua murid, karena hukumannya dinilai enggak layak dan guru-guru lain membela. Ada juga video orang tua murid datang ke sekolah membawa handphone, mendatangi guru tersebut sambil marah-marah. Jadi dibandingkan berbicara satu-satu, tatap muka, handphone itu berada di depan muka terlebih dahulu sebelum bertemu. Handphone-nya dijadikan senjata. Setelah video-video itu dikumpulkan, saya masukan data.
Terakhir, saya lakukan riset terhadap guru BK sewaktu SMP. Saya juga ke psikolog, dan beberapa guru BK lain. Mereka cerita, di tengah pandemi itu konflik antara siswa dan orang tua semakin meningkat. Soalnya siswa belajar dari rumah, dan waktu di rumah semakin banyak.
Pada saat itu, guru-guru BK berusaha menerapkan kedisiplinan. Meskipun belajar online, interaksinya lebih mudah terpapar karena orang tua pun bisa melihat, apa yang dikerjakan dan diajarkan guru lewat webinar. Makanya banyak sekali orang tua murid yang komplain dan protes, terhadap metode pengajaran.
Kalau saya amati sekarang, dari cerita para guru, mereka jadi agak khawatir dalam memberikan pendidikan. Keberadaan handphone dan segala sesuatu yang mudah diviralkan, bikin netizen mudah menghakimi metode pendidikan. Tanpa tahu misi atau fakta kebenarannya.

Menurutku, cancel culture dan kesehatan mental itu berkelindan, karena bullying oleh netizen bisa mengguncang seseorang. Bagaimana proses menulisnya, supaya penonton bisa relate dan merasakan dampaknya?
Mungkin proses menulisnya saya mengutip dari berbagai peristiwa yang udah ada, respons apa yang biasanya netizen berikan pada sosok yang diviralkan. Di film ini, kami menampilkan adanya transformasi dalam bentuk video, yang sifatnya memparodikan si sosok. Bukan (berupa) meme atau video remix, tapi animasi.
Kalau dalam film, dibandingkan komentar atau tanggapan langsung oleh netizen, (bullying-nya) lebih banyak berbentuk video parodi sehingga mudah sekali disebarluaskan. Dan video itu lebih mudah viral, dibandingkan komentar-komentar yang bersifat opini. Akhirnya lebih banyak orang yang tahu soal kemarahannya Bu Prani. Jadi hal yang dianggap lucu, mudah disebarluaskan, dan mudah sekali disimpan, justru dampaknya lebih besar ke seseorang. Akibatnya sosok ini enggak nyaman dalam menjalani hidup.
Baca Juga: ‘Penyalin Cahaya’ Soroti Sulitnya Korban Kekerasan Seksual Cari Keadilan
Aku lihat di salah satu wawancara, kak Wregas bilang, dalam proses reading itu melibatkan aktor untuk mengevaluasi dan rewrite skenario. Apakah proses ini begitu penting, misalnya untuk mendalami peran ibu, sehingga harus tahu langsung dari Mbak Ine Febriyanti?
Sangat penting. Waktu bertemu para aktor, saya bilang, butuh dua setengah bulan untuk reading karena skenario yang ditulis sekarang belum utuh. Saya butuh sudut pandangnya teman-teman.
Misalnya untuk Bu Prani. Saya minta pendapat Mbak Ine ketika reading, soal cara berbicara ke Muklas (Angga Yunanda) dan Tita (Prilly Latuconsina). Saya konsultasi, Tita ini anak pertama, kalau di rumah, gimana Mbak Ine berkomunikasi ke anak pertama yang usianya 25 tahun? Oh begini, terus saya revisi. Lalu (berkomunikasi) ke anak bungsu yang usianya 23 tahun gimana? Kemudian dia menyampaikan.
Kadang-kadang, Mbak Ine punya pengalaman tersebut. Dia punya tiga anak, dan saya mencoba membuat karakter Bu Prani ini seperti karakter Mbak Ine dalam mendidik, atau berbicara pada anak-anaknya. Meskipun banyak sekali ya cara berkomunikasi, tapi mungkin salah satunya yang diadaptasikan itu cara Mbak Ine.
Lalu bersama Pak Didit (Dwi Sasono). Sebagai seorang bapak, karena Mas Dwi adalah bapak tiga anak, pernah enggak merasakan bisnis itu gagal? Apa yang dirasakan? Atau ketika rencana pekerjaan tidak semulus biasanya, bagaimana reaksinya? Lalu Mas Dwi cerita pengalamannya.
Satu per satu itu saya sesuaikan, untuk mengganti (skenario sebelumnya) yang sifatnya cuma asumsi pendapat saya. Karakter ini dilengkapi dengan respons-respons mereka.
Kalau dari perspektif Angga dan Prilly, seperti apa penyesuaiannya?
Kehidupan mereka berbeda sekali dengan karakter dalam film ya. Muklas itu kreator konten media sosial, dan Tita seorang penjual baju bekas sekaligus musisi. Jadi diskusinya bukan lebih ke profesi. Misalnya Prilly, saya tanya, “Pril, di sini kan sosok Bu Prani dilukai oleh media, yang mana (orang-orang di baliknya) itu teman-temanmu. Ketika media menuliskan berita yang enggak benar, dan itu teman-temanmu, biasanya kamu merespons gimana?” Lalu Prilly menyampaikan.
Kalau Muklas, “Sebagai Angga Yunanda, banyak sekali brand yang meng-endorse kamu. Lalu banyak sekali bikin konten yang mempromosikan brand itu. Kalau suatu saat, katakanlah bapak atau adikmu membuat konten yang berpotensi mencederai dirimu dan brand, kira-kira bagaimana kamu akan ngomong ke mereka? Marahkah?”
Saya pengen minta sudut pandang Angga, emosinya sebesar apa? Dan risiko ketika brand itu hilang, karena ada satu reaksi dari keluargamu yang berpotensi menggagalkan itu, kamu bagaimana?

Jadi proses ini penting untuk kak Wregas, sebagai sutradara laki-laki, terutama dalam memahami karakter perempuan?
Iya, sangat penting karena kolaborasi ini. Ditambah saya juga ada produser, Ibu Willawati. Dari awal menulis skenario, banyak sekali konsultasi adegan-adegannya, untuk melengkapi supaya jangan sampai yang saya tulis ini sifatnya asumsi.
Statement apa yang mau disampaikan dari cancel culture di Budi Pekerti?
Budi Pekerti sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Budi artinya kesadaran, pekerti adalah perilaku. Jadi budi pekerti itu, perilaku manusia yang disertai kesadaran. Atau dalam bahasa sekarang lebih populer dikenal dengan mindfulness.
Yang saya perhatikan, banyak sekali keviralan di medsos atau komentar-komentar netizen, yang saya rasa enggak disertai dengan kesadaran. Komen-komen atau mengunggah ulang berbagai postingan itu lebih bersifat reaktif. Reaktif karena dia sedang ikutan marah, sedih, atau sedang pengen bercanda sehingga headline yang ditampilkan itu enggak ditelaah dulu isinya. Jadinya makin banyak duplikasi postingan tersebut yang dilakukan netizen. Dan semakin besar juga opini dunia terhadap orang yang viral.
Saya cuma berpikir, kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk menggunakan kesadaran, meluangkan waktu lima menit sebelum bereaksi atau menekan tombol like atau repost, mungkin kita memiliki argumen berbeda terhadap apa yang terjadi di lini masa. Mungkin menarik napas sejenak, mencoba menelaah, apa yang terjadi di belakang sosok ini—bukan spontan nge-judge seseorang hanya dari video vertikal 15 detik, dan enggak mengerti latar belakangnya.
Saya rasa ketika kita bisa meluangkan waktu untuk memperlambat diri sejenak, kita tidak melukai dan membuat hidup seseorang menjadi hancur dan buruk.
Jadi salah satu tujuan film ini supaya penonton berefleksi?
Ketika membuat film, yang saya paparkan mungkin adalah pengamatan, observasi saya terhadap apa yang terjadi di dunia. Tapi, saya biasanya jarang untuk memberikan panduan agar penonton merasakan hal ini. Atau penonton harus berpikiran sama seperti ini. Jadi film ini saya bikin untuk menjadi paparan, observasi saya terhadap apa yang terjadi di media sosial. Jika penonton memang ada waktu untuk merefleksikan filmnya, saya akan sangat bersyukur.
Kalau kita membicarakan karakter utama, di kedua film panjang kak Wregas, karakter utamanya perempuan. Kenapa memilih menarasikan dari pengalaman perempuan?
Hmm…balik lagi, film yang dibikin itu berdasarkan observasi. Mengapa Bu Prani dan guru BK, itu karena sosok yang saya riset adalah perempuan. Dari seorang ibu yang marah dan viral, sama seorang guru yang viral karena memberikan hukuman. Mungkin saya berangkat dari apa yang pernah terjadi, supaya ada data atau pengalamannya. Lalu diterapkan di karakter.
Karakter Suryani di Penyalin Cahaya (2021) dan Bu Prani disorot dari perspektif medsos, seolah karakternya terpenjara oleh ekspektasi publik. Apakah ini cara kak Wregas untuk relatable dengan generasi sekarang, sambil menyisipkan isu sosial?
Kalau itu dianggap sebagai suatu cara atau pilihan directing, rasanya enggak. Tapi lebih kebetulan, dua film tersebut diproduksi di tengah era media sosial yang sangat marak. Kalau misalnya film ini diproduksi saat saya SMA, tahun 2007, mungkin enggak semua orang handphone-nya bisa mengakses media sosial. Hanya ada fitur SMS. Maka peristiwa atau konflik-konfliknya pasti akan berbeda.
Kebetulan karena saya membuat kedua film ini pada 2020 dan 2022, di mana semua orang menatap media sosial, maka saya menggunakan realita yang ada di sekitar. Ketika seseorang mudah sekali dipandang, atau dilihat kepribadiannya, dan dinilai perilakunya dari kacamata media sosial.
Apakah 10 atau 15 tahun lagi akan berubah? Bisa jadi, karena kita enggak pernah tahu yang terjadi ke depannya. Katakanlah 10 tahun kemudian, malah bisa jadi medsos enggak ada karena semua manusia, misalnya, bersama-sama memutuskan enggak main medsos. Kita akan kembali ke zaman di mana handphone belum ada. Jadi saya membuat film sebagai respons akan kondisi masyarakat, yang sedang terjadi saat film itu dibuat.

Kalau kulihat, karya-karyanya kak Wregas cukup idealis dan menampilkan karakter perempuan tanpa male gaze. Tapi, enggak semua filmmaker bisa melakukan itu. Gimana cara kak Wregas menciptakan karya yang idealis dan tetap punya nuance?
Tentu saja riset dan diskusi dengan banyak pihak. Sepertinya memang dalam proses penulisan skenario itu diperlukan banyak input, data, referensi, dan komentar. Setiap draf skenario pertama jadi, kami melakukan big reading. Di sini semua produser terlibat. Ada Adi Ekatama, Ibu Willawati, Iman Usman, Ridla An-Nuur, dan Nurita (Tata) Anandia. Kami punya beragam perspektif. Bu Willa, Ridla, dan Tata perempuan, sedangkan Adi, Iman, dan saya laki-laki.
Kami pengen mendengar dari semua sudut pandang dan latar belakang keluarga yang berbeda, dalam menilai skenario ini. Di tengah scene A misalnya, ada yang berkomentar, “Sepertinya kalau Bu Prani mengalami peristiwa, misalnya diejek temannya, respons dia enggak mungkin langsung melawan atau marah. Dia akan diam dulu.” Kemudian kami sepakat dan revisi.
Atau misalnya, pas adegan Tita dikeluarkan dari band, apa yang akan dia lakukan? Apakah langsung berargumen? Mendebat? Membuat postingan yang (meluapkan) amarah, atau justru merelakan?
Nah itu dari opini kami masing-masing sebagai tim. Termasuk para pemain ya, Prilly, Mbak Ine, dan HOD (Head of Department) termasuk makeup, wardrobe, art director, dan sinematografer. Saat big reading, semuanya bebas memberikan input.
Selain lewat big reading, ada referensi film atau sutradara yang kak Wregas jadikan contoh untuk menghadirkan nuance?
Dulu di kekaryaan film pendek saya, pasti harus ada referensi ya karena belajar, nyari referensi. Di titik mulai berkarya ke film panjang, ketika mencoba meletakkan referensi, ngikutin seorang sutradara, sering kali saya menemukan ceritanya jadi terarahkan gara-gara berusaha mengakomodir referensi sutradara tersebut.
Katakanlah sutradara A, style (directing)-nya enggak begini. Masa saya buat keputusan karakternya berdasarkan (style directing sutradara) itu? Terus saya berpikir, kok jadi terbatas ya, terhambat ya, ketika referensi sutradara itu datang duluan, dibanding kita menyajikan skenario.
Akhirnya saya enggak memakai referensi sutradara, yang saya fokuskan adalah, apa yang ingin dirasakan penonton saat adegan ini. Misalnya, di adegan Bu Prani, Tita, dan Muklas berdebat di rumah. Seandainya saya mengikuti style sinematografi Alejandro Iñárritu, karena saya menyukai dia, adegan (berdebat) itu akan diambil dalam satu shot utuh.
Terus saya berpikir, ketika dilakukan, apakah secara emosi akan sampai ke penonton? Saya rasa enggak, karena penonton membutuhkan kecepatan tempo editing, raut wajah yang menuturkan kemarahan, dan lain-lain. Jadinya ya sudah, ngapain saya menggunakan referensi sutradara itu? Saya lebih fokus saja ke apa yang kira-kira, penonton ingin rasakan di adegan ini. Kemudian saya tampilkan melalui pilihan angle kamera, warna, sound, dan editing.

Baca Juga: Nia Dinata Review Unearthing Muarajambi Temples
Belakangan ini mulai banyak filmmaker yang membahas isu sosial, tetapi belum tentu bisa menangkap nuance dalam film. Gimana kak Wregas men-challenge diri supaya tetap memiliki perspektif itu?
Mungkin yang pertama di umur yang ke-31, saya banyak sekali melihat kejadian atau peristiwa dalam hidup, dan bertemu banyak orang. Mungkin kalau dibandingkan seseorang yang umurnya 50 atau 60 tahun, pengalaman yang saya temui masih jauh.
Membuat film itu menjadi tempat saya untuk belajar. Jadi saya memposisikan diri untuk mengetahui berbagai macam perspektif manusia. Manusia punya pandangan A, keyakinan B, dan prinsip C. Semuanya memiliki perbedaan dan latar belakang yang juga berbeda. Saya merasa, memahami dan menghargai berbagai macam sudut pandang itu, adalah cara saya untuk belajar.
Jadi yang pertama dilakukan ketika membuat film, adalah mendapatkan perspektif sebanyak-banyaknya. Lalu sebagai pembuat film, saya enggak memberikan suatu “statement”, tapi memberikan observasi saya.
Tapi seperti apa sih kak Wregas dibesarkan, sehingga mampu melibatkan sensitivitas terhadap isu sosial dan perspektif perempuan dalam berkarya?
Saya tumbuh besar di Yogyakarta. Tinggal bersama ibu, bapak, dan adik laki-laki. Ibu saya dosen ekonomi, bapak seorang karyawan swasta. Tapi, keluarga besar saya di Yogyakarta itu rata-rata pengajar.
Ibu saya empat bersaudara, semuanya perempuan. Sering kali kami tinggal di rumah kakek dan nenek, di mana saya pasti bertemu dengan tante-tante saya. Ketiga adiknya ibu juga pengajar. Yang pertama guru musik, kedua dosen kedokteran gigi, dan yang ketiga dosen psikologi.
Kakek saya dosen teknik sipil, sementara nenek ibu rumah tangga yang aktif di berbagai kegiatan—seperti Dharma Wanita, ikatan istri insinyur, dan kegiatan sosial lainnya.
Mungkin saya tumbuh dengan berbagai macam sudut pandang keluarga saya, ketika kami makan malam bersama atau merayakan tahun baru di Kaliurang. Bisa dibilang secara rasio, saya lebih banyak mendengarkan ibu dan tante-tante. Soalnya bapak bekerja, sering di luar kota atau dipindahkan ke kantor cabang lain. Om-om saya juga jarang di rumah, paling malam aja, karena bekerja juga.
Jadi saya tumbuh dengan interaksi dominan dengan ibu, para tante, dan nenek. Apalagi tante yang paling kecil itu, jarak umurnya dengan saya cuma sembilan tahun, lebih seperti kakak. Mungkin itu sedikit berpengaruh ya.
Memang di keluarga didominasi perempuan ya.
Bisa dibilang gitu, apalagi sosok ibu. Ibuku tuh dosen ekonomi dan doktor, S-3. Dia yang mengantarku ke sekolah waktu SD, sering nyetir dari Semarang ke Yogyakarta untuk (berkunjung) ke rumah keluarga. Ibu yang ngajarin saya bikin materi presentasi, sampai sekarang kubawa untuk cerita, disertakan dengan slideshow dan presentasi. Lalu ibu ngajarin menulis dan berpuisi. Dan ibu juga yang ngajarin untuk enggak menyerah saat menemukan kegagalan.
Akhirnya ya, ibu juga yang mengizinkan untuk kuliah film. Dia yang nganterin waktu pendaftaran kuliah di IKJ (Institut Kesenian Jakarta), sambil nunggu di suatu kafe. Jadi ibu sangat banyak memengaruhi pola pikir dan pikiran kreatifku.
Selanjutnya aku mau bahas sedikit tentang Penyalin Cahaya. Film ini banyak diapresiasi penonton, dan sempat backlash karena kasus kekerasan seksual. Apakah kasus itu sempat jadi turn back kak Wregas, untuk membahas isu perempuan dalam film?
Mungkin jawabannya belum tahu, karena ketika memilih isu film berikutnya, bukan berasal dari gendernya dulu. Tapi berfokus pada peristiwanya, apa yang mau diobservasi. Jadi, apakah film ketiga dan keempat udah tahu ceritanya seperti apa? Bisa dibilang belum tahu, karena saya baru akan mulai riset setelah film ini (Budi Pekerti) tayang.
Nanti film ketiga dan keempat, observasinya berdasarkan yang paling meresahkan saya. Biasanya itu yang dipilih sebagai dasar pembuatan film. Jadi saya enggak spesifik atau khusus membahas satu tema, terhadap satu isu.
Ada trauma untuk mengangkat isu perempuan?
Sepertinya ya yang terpenting, saya rasa film itu bisa memberikan sumbangsihnya pada perkembangan kehidupan manusia. Enggak hanya sekadar menjadi produk audiovisual. Dan ketika saya memahami dan bisa menuturkan observasi itu dengan baik, maka akan saya lakukan. Tapi, kalau misalnya saya enggak tahu, enggak cukup memahami apa yang akan diobservasi di karya berikutnya, sepertinya tidak akan diceritakan dalam film.
Soalnya ketika riset atau penelitian saya belum komplit untuk disebarkan ke masyarakat, maka akan kurang optimal dalam memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kemanusiaan.
Yang utama bagi saya, ketika yang diceritakan besok adalah sesuatu yang riset dan sudut pandangnya lengkap, kuat, dan bisa disampaikan ke penonton, serta memberikan sumbangsih yang besar pada kemanusiaan, akan saya lakukan.
Berkaca dari kasus kekerasan seksual kemarin, apakah proses produksi Budi Pekerti menerapkan SOP kekerasan seksual?
Iya, kami menerapkan SOP yang dibentuk APROFI (Asosiasi Produser Film Indonesia). Dari awal sampai akhir proses selalu menerapkan.
Kedua film panjang kak Wregas dapat banyak penghargaan maupun nominasi dari FFI. Sebagai filmmaker yang membuat film tentang isu sosial, apakah penggambaran isu sosial dalam film udah mulai diapresiasi di industri?
Kalau kita berbicara tentang seberapa besar penonton, jumlah dan rasio penonton di industri, mungkin penonton tertinggi adalah (film) horor. Yang kedua mungkin komedi. Apakah (film tentang isu sosial) sudah mulai diapresiasi? Ya mungkin ada. Tapi, masih sangat jauh, kalau dibandingkan dengan rasio penikmat horor.
Memang menjadi diskusi bersama, bagaimana agar penonton pun, ketika ada film seperti ini (Budi Pekerti) yang membicarakan berbagai macam kejadian sosial, juga tertarik untuk menonton di bioskop.
Diperlukan promosi, metode publikasi, dan berbagai pendekatan untuk menyentuh penonton, bahwa ini adalah film yang baik, yang bagus. Dan penonton pun berkenan.

Sebagai filmmaker baru yang mengangkat isu sosial ke layar lebar, menurut kak Wregas, ke depannya apakah akan ada ruang untuk film tentang isu sosial sehingga lebih banyak diminati dan diproduksi?
Saya rasa ada. Dan PR bersama bagi sutradara sebagai pencerita, meluangkan waktu lebih khusus untuk mengasah skenario dan style directing kami, agar penonton pun bisa menikmati filmnya. Ketika penonton menikmati film, tersentuh, dan tergerak, pastinya isu-isu yang disampaikan enggak hanya sampai direnungkan di rumah. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari pun akan melakukan, jika mereka betul-betul tergerak.
Saya rasa hal itu disebut empati. Ketika penonton bisa berempati terhadap film, film-film yang membawa berbagai macam pengamatan sosial pun akan mendapatkan tempat. Tugas siapa untuk bisa menimbulkan empati terhadap cerita? Tak lain tak bukan ya sutradara.
Ketika sutradara punya ilmu, atau cara penulisan yang bisa (membuat) penonton mengidentifikasikan diri terhadap tokoh, saya rasa beragam film pun bisa dibuat, dan mendapatkan tempatnya di penonton.
Film-film pendek kak Wregas juga masuk nominasi, dan ditayangkan di berbagai festival di luar negeri. Sementara kedua film panjangnya juga mendapatkan penghargaan, dan masuk nominasi FFI. Apakah kak Wregas punya ambisi tersendiri saat membuat film?
Kalau festival enggak, bukan ambisi. Lebih dilihat sebagai bentuk untuk menyebarluaskan (film) demi market yang lebih besar, atau penonton yang lebih banyak. Festival itu berfungsi agar filmnya bisa ketemu penonton di luar Indonesia, dan membuka peluang supaya filmnya didistribusikan ke negara-negara lain. Semakin banyak penonton yang menyaksikan film kami, apa yang ingin diungkapkan di film akan semakin tersebar luas. Saya rasa sesimpel itu.
Ketika ada nominasi dan award, itu suatu apresiasi aja bagi saya. Tapi tidak mendapatkan itu pun, bagi saya apresiasi tertinggi adalah penonton yang berkomentar secara jujur terhadap film kami. Penonton yang tergerak dan tersentuh dengan film kami, adalah penghargaan tertinggi.